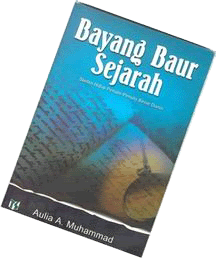...tera di sesela gegas-gesa
Friday, September 15, 2006
Gibran, dan Moralitas Orang Tua
Anakmu bukanlah anakmu. Mereka adalah putra kerinduan diri Sang Hidup. Melaluimu mereka ada, namun bukan darimu. Meskipun bersamamu, mereka bukan milikmu.
 Five V sesenggukan. Air matanya menggerus make-up di sisi hidungnya. Di depannya, di atas meja yang rapi tertata , terpajang tart dengan lilin menyala. "Untuk anakku, di mana pun kamu berada... selamat ulang tahun, ya..." Tangisnya kembali pecah.
Five V sesenggukan. Air matanya menggerus make-up di sisi hidungnya. Di depannya, di atas meja yang rapi tertata , terpajang tart dengan lilin menyala. "Untuk anakku, di mana pun kamu berada... selamat ulang tahun, ya..." Tangisnya kembali pecah.
Ya, Five V merayakan hari ulang tahun anaknya, Bilkis Emeliski. Namun, tak ada raut Bilkis di antara kerumunan itu. Mantan suami Five V, Iwan, membawa Bilkis usai perceraian mereka, dan tak pernah membolehkan artis cantik itu untuk menemuinya. Five V bahkan tak tahu di mana Bilkis berada. Padahal, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memberi hal pada Five V untuk mengasuh Bilkis. "Ternyata, lewat hukum pun, dia tak merespon baik," tutur Five V di "Otista". "Ini sungguh nggak fair. Kayak dia yang ngelahirin aja," geramnya.
Five V tidak sendiri. Zarima dan Jane Shalimar pun mengalami hal yang sama. Usai perceraian, anak mereka dijadikan sandera oleh mantan suami. Seperti Five V, Jane dan Zarima juga sudah berusaha sekuat tenaga untuk dapat memeluk buah hatinya. Apa daya, hanya tangis yang akhirnya mereka dapat. Kedua suami mereka merasa lebih berhak untuk mendidik sang anak.
Uniknya, nasib ketiga wanita ini berbanding terbalik dengan Tamara Bleszinsky. Tamara justru merasa lebih berhak untuk mengasuh Rassya, buah cintanya dengan Rafly. Delapan bulan dia menghaki Rassya sendiri, dan membiarkan Rafly menempuh semua cara. Sampai akhirnya, di ujung bulan lalu Tamara "menyerah", dan bersedia berbagi asuh dengan Rafly, di kantor polisi, dengan berbagai kompensasi. Rafly lega, Rassya juga. "Yang terpenting sekarang membuat Rassya senang. Saya ingin mengembalikan delapan bulan yang hilang," ucapnya, sebagaimana tayang di "Insert" TransTV.
Seteru pikir
Berikan kasih sayangmu, tapi jangan paksakan pikiranmu. Sebab mereka berbekal pikiran sendiri. Berikan rumah untuk raganya, bukan jiwanya. Jiwa mereka adalah penghuni masa depan. Yang tak dapat kau gapai, meski dalam impian.
Berbeda dari kasus di atas --anak dianggap sebagai milik--, kasus Kiki Fatmala dengan Fatma Farida, Jonathan Frizy dengan mamanya, dan Dhani Ahmad dengan Eddy Manaf, lebih mencerminkan konflik antara orang tua dan anak. Tak heran, cap durhaka pun mampir kepada Kiki, Jonathan, dan Dhani. Meski, kalau mau dilihat dari perspektif lain, "orang tua" durhaka pun layak dicapkan untuk kasus ini. Fatma Farida yang menyumpahi Kiki, bahkan berikrar untuk tak rela dimandikan dan dikafani jika dia menjadi mayat nanti, dan mengungkapkan semua "keburukan" anaknya ke media, sulit untuk diterima dengan simpati. Demikian ibu Jonathan, yang ternyata tak membantah telah "lupa" atas diri anaknya, membuat pemirsa mulai ragu tentang mitos kasih seorang ibu. Perseteruan Dhani dan Eddy apalagi. Keduanya memakai bahasa yang sama, untuk mengungkapkan kemarahan mereka. Tapi, lebih daripada persoalan "siapa mendurhakai siapa", untuk kasus Dhani dan Eddy, kita dapat menilainya dengan kacamata yang lebih jernih, menisik akar persoalan.
Masalah Dhani-Eddy bermula dari kabar kawin siri. Eddy tidak setuju dengan hal itu. Di tayangan awal kasus itu, dengan santai pria tua ini berkata, "Saya sayang sama tiga cucu saya, pintar-pintar dan tampan-tampan. Bagi saya, hanya Maia itu menantu saya. Jadi, saya tidak akan merestui jika Dhani mau kawin lagi." Barangkali, akar masalah ini yang tidak "diinvestigasi", "diinsert", "disilet" oleh media teve, ketidaksetujuan Eddy jika Dhani sampai kawin lagi. Dan, sikap "politik" itu yang kemudian memicu pertengkaran antara keduanya, setelah Dhani mengirim SMS, "Urus saja kepentingan Papa sendiri..."
Akar masalahnya di situ, perbedaan pandangan. Dhani, di "Lepas Malam" TransTV dengan santai berkata, "Yang penting jangan berzinah, jangan memfitnah." Dan satu lagi, seperti Eddy, media pun tak dapat "membaca" Maia, istri Dhani, yang tenang, diam, dan tertawa, ketika diimpit gosip itu. Dan di sinilah kita dapat melihat, Eddy masih menganggap Dhani adalah miliknya saja, bukan milik Maia, atau Joice, istrinya. Dhani adalah anaknya, kepunyaannya. Dan sebagai milik, anak harus dapat dikendalikan, diarahkan, dijaga, karena selalu dianggap belum dewasa. Ini pandangan yang umum, dan masih menjadi "arus utama moralitas" masyarakat kita. Karena itu juga, media pun bersikap sama. Tak heran jika akhirnya, "pertengkaran pikiran" itu dimaknai sebagai kedurhakaan. Stigma yang terlalu terburu dan kejam.
Moral tua
Engkau dapat menjadi seperti mereka. Tapi jangan buat mereka menjadi seperti kamu. Sebab kehidupan tidak surut, dan tiada tinggal bersama kemarin. Engkaulah busur, dam mereka anak panah yang meluncur.
 Dari ragam peristiwa di atas, kita dapat melihat bagaimana "ambiguitas moral" media, terutama televisi. Dapat dikatakan, untuk tiap acara, teve punya ukuran moral yang berbeda. TransTV misalnya, memakai "moralitas longgar" untuk tayangan "Fenomena" atau "Penjaga Pantai" , dan "moralitas ketat" untuk tayangan "Cerita Sore". Karena itulah, di "Fenomena", seks bebas dan segala variasinya, dianggap sebagai gaya hidup metropolitan. Ditayangkan tanpa sinisme, kecaman, atau makian. Presenter berada di tapal netral, dan terkadang memaklumkan. Di "Cerita Sore" sebaliknya. Tak ada tapal netral. Semua jelas, hitam atau putih, dosa dan pahala. Anehnya, untuk "infotainmen" semua teve memakai moralitas yang sama, keketatan atau "moralitas orang tua".
Dari ragam peristiwa di atas, kita dapat melihat bagaimana "ambiguitas moral" media, terutama televisi. Dapat dikatakan, untuk tiap acara, teve punya ukuran moral yang berbeda. TransTV misalnya, memakai "moralitas longgar" untuk tayangan "Fenomena" atau "Penjaga Pantai" , dan "moralitas ketat" untuk tayangan "Cerita Sore". Karena itulah, di "Fenomena", seks bebas dan segala variasinya, dianggap sebagai gaya hidup metropolitan. Ditayangkan tanpa sinisme, kecaman, atau makian. Presenter berada di tapal netral, dan terkadang memaklumkan. Di "Cerita Sore" sebaliknya. Tak ada tapal netral. Semua jelas, hitam atau putih, dosa dan pahala. Anehnya, untuk "infotainmen" semua teve memakai moralitas yang sama, keketatan atau "moralitas orang tua".
Yang dimaksud dengan "moralitas orang tua" adalah ukuran nilai yang telah mapan dan terus dimapankan, sebagai model yang dipercayai menjadi jaminan untuk mendapatkan kepastian di dalam hidup. Karena itu juga, nilai ini dianut oleh banyak orang, dimitoskan, diwariskan, dan dijaga. Nyaris menjadi sebuah kemustahilan untuk mengevaluasi moralitas tua ini. Anak sebagai milik adalah salah satunya. Ucapan untuk bayi yang baru lahir, "semoga menjadi anak yang berbakti pada orang tua, bangsa, negara..." menegaskan hal itu. Bahkan sebelum hak untuk dibesarkan dalam kasih sayang dinikmati si anak, "kewajiban" baginya telah diikatkan. Anak dan orang tua tak dapat dipisahkan. Dalam moralitas ini, orang tua yang justru menjadi beban bagi anak, membebani si anak. Contohnya, tampak di "Dorce Show", yang menampilkan anak-anak Krisdayanti, Ruth Sahanaya, dan Ikang Fauzi-Marisa Haque. Di akhir acara, Dorce "menguji" mereka, apakah dapat bernyanyi seperti orang tuanya. Anak Uthe bernyanyi gemilang, demikian juga anak KD, dan Ikang. Penonton bertepuk tangan. Tapi, lihatlah, apa yang mereka tampilkan hanyalah kemampuan teknis bernyanyi, bukan ekspresi diri. Bukan sebagai ekspresi, di panggung itu, mereka pasti tersiksa.
Moralitas orang tua memang menghilangkan suara anak. Itu juga yang terjadi pada Rassya, anak Tamara. Suaranya tak pernah didengar. Kalau pun didengar, dianggap tak ada. Kalau pun ada, dianggap tak punya harga. Rassya, bagi Tamara, adalah miliknya. "Dalam kasus ini, sudah waktunya kami mendengar suara anak. Kami tanya pada Rassya, dia mau ikut siapa? Dia memilih di sini, bersama ayahnya. Ini menunjukkan, fundamen pergaulan Rassya dan Rafly cukup kuat. Meski sudah 8 bulan tidak bertemu, sehari bersama, dia sudah memiliki lagi ikatan bersama ayahnya," kata Iqbal Anshori dari Komnas HAM anak, di "Insert" (4/9), yang mencoba mendengar keinginan Rassya. Berapa banyak infotainmen yang berpikir untuk ikut "menyuarakan" suara Rassya? "Mempercayai" juga suara Dhani, Della Puspita, dan Kiki Fatmala? Dan tidak hanya menggemakan suara serta kesakitan orang tua, dan membuat gaung suara itu sebagai "kebenaran"? Kita tahu jawabnya, karena infotainmen sebenarnya manisfestasi dari kecemasan orang tua. Tak heran, di tayangan itu, kita acap lihat orang tua yang merasa jera dengan kelakuan anaknya, dan melabelinya dengan kata durhaka.
Padahal, "Setiap anak," kata Tagore, "selalu membawa pesan bahwa Tuhan belum jera dengan manusia." Padahal, "Tuhan mengasihi anak yang panah yang melesat," ucap Gibran, "juga mengasihi busur panah yang mantap." Tapi kenapa, akhir-akhir ini, sebagai orang tua, kita seperti melupakannya....
[Artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 17 September 2006]
 Five V sesenggukan. Air matanya menggerus make-up di sisi hidungnya. Di depannya, di atas meja yang rapi tertata , terpajang tart dengan lilin menyala. "Untuk anakku, di mana pun kamu berada... selamat ulang tahun, ya..." Tangisnya kembali pecah.
Five V sesenggukan. Air matanya menggerus make-up di sisi hidungnya. Di depannya, di atas meja yang rapi tertata , terpajang tart dengan lilin menyala. "Untuk anakku, di mana pun kamu berada... selamat ulang tahun, ya..." Tangisnya kembali pecah.Ya, Five V merayakan hari ulang tahun anaknya, Bilkis Emeliski. Namun, tak ada raut Bilkis di antara kerumunan itu. Mantan suami Five V, Iwan, membawa Bilkis usai perceraian mereka, dan tak pernah membolehkan artis cantik itu untuk menemuinya. Five V bahkan tak tahu di mana Bilkis berada. Padahal, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memberi hal pada Five V untuk mengasuh Bilkis. "Ternyata, lewat hukum pun, dia tak merespon baik," tutur Five V di "Otista". "Ini sungguh nggak fair. Kayak dia yang ngelahirin aja," geramnya.
Five V tidak sendiri. Zarima dan Jane Shalimar pun mengalami hal yang sama. Usai perceraian, anak mereka dijadikan sandera oleh mantan suami. Seperti Five V, Jane dan Zarima juga sudah berusaha sekuat tenaga untuk dapat memeluk buah hatinya. Apa daya, hanya tangis yang akhirnya mereka dapat. Kedua suami mereka merasa lebih berhak untuk mendidik sang anak.
Uniknya, nasib ketiga wanita ini berbanding terbalik dengan Tamara Bleszinsky. Tamara justru merasa lebih berhak untuk mengasuh Rassya, buah cintanya dengan Rafly. Delapan bulan dia menghaki Rassya sendiri, dan membiarkan Rafly menempuh semua cara. Sampai akhirnya, di ujung bulan lalu Tamara "menyerah", dan bersedia berbagi asuh dengan Rafly, di kantor polisi, dengan berbagai kompensasi. Rafly lega, Rassya juga. "Yang terpenting sekarang membuat Rassya senang. Saya ingin mengembalikan delapan bulan yang hilang," ucapnya, sebagaimana tayang di "Insert" TransTV.
Seteru pikir
Berikan kasih sayangmu, tapi jangan paksakan pikiranmu. Sebab mereka berbekal pikiran sendiri. Berikan rumah untuk raganya, bukan jiwanya. Jiwa mereka adalah penghuni masa depan. Yang tak dapat kau gapai, meski dalam impian.
Berbeda dari kasus di atas --anak dianggap sebagai milik--, kasus Kiki Fatmala dengan Fatma Farida, Jonathan Frizy dengan mamanya, dan Dhani Ahmad dengan Eddy Manaf, lebih mencerminkan konflik antara orang tua dan anak. Tak heran, cap durhaka pun mampir kepada Kiki, Jonathan, dan Dhani. Meski, kalau mau dilihat dari perspektif lain, "orang tua" durhaka pun layak dicapkan untuk kasus ini. Fatma Farida yang menyumpahi Kiki, bahkan berikrar untuk tak rela dimandikan dan dikafani jika dia menjadi mayat nanti, dan mengungkapkan semua "keburukan" anaknya ke media, sulit untuk diterima dengan simpati. Demikian ibu Jonathan, yang ternyata tak membantah telah "lupa" atas diri anaknya, membuat pemirsa mulai ragu tentang mitos kasih seorang ibu. Perseteruan Dhani dan Eddy apalagi. Keduanya memakai bahasa yang sama, untuk mengungkapkan kemarahan mereka. Tapi, lebih daripada persoalan "siapa mendurhakai siapa", untuk kasus Dhani dan Eddy, kita dapat menilainya dengan kacamata yang lebih jernih, menisik akar persoalan.
Masalah Dhani-Eddy bermula dari kabar kawin siri. Eddy tidak setuju dengan hal itu. Di tayangan awal kasus itu, dengan santai pria tua ini berkata, "Saya sayang sama tiga cucu saya, pintar-pintar dan tampan-tampan. Bagi saya, hanya Maia itu menantu saya. Jadi, saya tidak akan merestui jika Dhani mau kawin lagi." Barangkali, akar masalah ini yang tidak "diinvestigasi", "diinsert", "disilet" oleh media teve, ketidaksetujuan Eddy jika Dhani sampai kawin lagi. Dan, sikap "politik" itu yang kemudian memicu pertengkaran antara keduanya, setelah Dhani mengirim SMS, "Urus saja kepentingan Papa sendiri..."
Akar masalahnya di situ, perbedaan pandangan. Dhani, di "Lepas Malam" TransTV dengan santai berkata, "Yang penting jangan berzinah, jangan memfitnah." Dan satu lagi, seperti Eddy, media pun tak dapat "membaca" Maia, istri Dhani, yang tenang, diam, dan tertawa, ketika diimpit gosip itu. Dan di sinilah kita dapat melihat, Eddy masih menganggap Dhani adalah miliknya saja, bukan milik Maia, atau Joice, istrinya. Dhani adalah anaknya, kepunyaannya. Dan sebagai milik, anak harus dapat dikendalikan, diarahkan, dijaga, karena selalu dianggap belum dewasa. Ini pandangan yang umum, dan masih menjadi "arus utama moralitas" masyarakat kita. Karena itu juga, media pun bersikap sama. Tak heran jika akhirnya, "pertengkaran pikiran" itu dimaknai sebagai kedurhakaan. Stigma yang terlalu terburu dan kejam.
Moral tua
Engkau dapat menjadi seperti mereka. Tapi jangan buat mereka menjadi seperti kamu. Sebab kehidupan tidak surut, dan tiada tinggal bersama kemarin. Engkaulah busur, dam mereka anak panah yang meluncur.
 Dari ragam peristiwa di atas, kita dapat melihat bagaimana "ambiguitas moral" media, terutama televisi. Dapat dikatakan, untuk tiap acara, teve punya ukuran moral yang berbeda. TransTV misalnya, memakai "moralitas longgar" untuk tayangan "Fenomena" atau "Penjaga Pantai" , dan "moralitas ketat" untuk tayangan "Cerita Sore". Karena itulah, di "Fenomena", seks bebas dan segala variasinya, dianggap sebagai gaya hidup metropolitan. Ditayangkan tanpa sinisme, kecaman, atau makian. Presenter berada di tapal netral, dan terkadang memaklumkan. Di "Cerita Sore" sebaliknya. Tak ada tapal netral. Semua jelas, hitam atau putih, dosa dan pahala. Anehnya, untuk "infotainmen" semua teve memakai moralitas yang sama, keketatan atau "moralitas orang tua".
Dari ragam peristiwa di atas, kita dapat melihat bagaimana "ambiguitas moral" media, terutama televisi. Dapat dikatakan, untuk tiap acara, teve punya ukuran moral yang berbeda. TransTV misalnya, memakai "moralitas longgar" untuk tayangan "Fenomena" atau "Penjaga Pantai" , dan "moralitas ketat" untuk tayangan "Cerita Sore". Karena itulah, di "Fenomena", seks bebas dan segala variasinya, dianggap sebagai gaya hidup metropolitan. Ditayangkan tanpa sinisme, kecaman, atau makian. Presenter berada di tapal netral, dan terkadang memaklumkan. Di "Cerita Sore" sebaliknya. Tak ada tapal netral. Semua jelas, hitam atau putih, dosa dan pahala. Anehnya, untuk "infotainmen" semua teve memakai moralitas yang sama, keketatan atau "moralitas orang tua".Yang dimaksud dengan "moralitas orang tua" adalah ukuran nilai yang telah mapan dan terus dimapankan, sebagai model yang dipercayai menjadi jaminan untuk mendapatkan kepastian di dalam hidup. Karena itu juga, nilai ini dianut oleh banyak orang, dimitoskan, diwariskan, dan dijaga. Nyaris menjadi sebuah kemustahilan untuk mengevaluasi moralitas tua ini. Anak sebagai milik adalah salah satunya. Ucapan untuk bayi yang baru lahir, "semoga menjadi anak yang berbakti pada orang tua, bangsa, negara..." menegaskan hal itu. Bahkan sebelum hak untuk dibesarkan dalam kasih sayang dinikmati si anak, "kewajiban" baginya telah diikatkan. Anak dan orang tua tak dapat dipisahkan. Dalam moralitas ini, orang tua yang justru menjadi beban bagi anak, membebani si anak. Contohnya, tampak di "Dorce Show", yang menampilkan anak-anak Krisdayanti, Ruth Sahanaya, dan Ikang Fauzi-Marisa Haque. Di akhir acara, Dorce "menguji" mereka, apakah dapat bernyanyi seperti orang tuanya. Anak Uthe bernyanyi gemilang, demikian juga anak KD, dan Ikang. Penonton bertepuk tangan. Tapi, lihatlah, apa yang mereka tampilkan hanyalah kemampuan teknis bernyanyi, bukan ekspresi diri. Bukan sebagai ekspresi, di panggung itu, mereka pasti tersiksa.
Moralitas orang tua memang menghilangkan suara anak. Itu juga yang terjadi pada Rassya, anak Tamara. Suaranya tak pernah didengar. Kalau pun didengar, dianggap tak ada. Kalau pun ada, dianggap tak punya harga. Rassya, bagi Tamara, adalah miliknya. "Dalam kasus ini, sudah waktunya kami mendengar suara anak. Kami tanya pada Rassya, dia mau ikut siapa? Dia memilih di sini, bersama ayahnya. Ini menunjukkan, fundamen pergaulan Rassya dan Rafly cukup kuat. Meski sudah 8 bulan tidak bertemu, sehari bersama, dia sudah memiliki lagi ikatan bersama ayahnya," kata Iqbal Anshori dari Komnas HAM anak, di "Insert" (4/9), yang mencoba mendengar keinginan Rassya. Berapa banyak infotainmen yang berpikir untuk ikut "menyuarakan" suara Rassya? "Mempercayai" juga suara Dhani, Della Puspita, dan Kiki Fatmala? Dan tidak hanya menggemakan suara serta kesakitan orang tua, dan membuat gaung suara itu sebagai "kebenaran"? Kita tahu jawabnya, karena infotainmen sebenarnya manisfestasi dari kecemasan orang tua. Tak heran, di tayangan itu, kita acap lihat orang tua yang merasa jera dengan kelakuan anaknya, dan melabelinya dengan kata durhaka.
Padahal, "Setiap anak," kata Tagore, "selalu membawa pesan bahwa Tuhan belum jera dengan manusia." Padahal, "Tuhan mengasihi anak yang panah yang melesat," ucap Gibran, "juga mengasihi busur panah yang mantap." Tapi kenapa, akhir-akhir ini, sebagai orang tua, kita seperti melupakannya....
[Artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 17 September 2006]