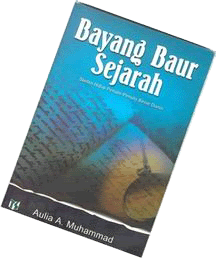...tera di sesela gegas-gesa
Thursday, March 27, 2008
Biarkan Saja Anak Berlagu Cinta
"Anak-anak harus dijauhkan dari lagu-lagu dewasa dan cinta," kata banyak orang. Bah! Omongan apa itu?!
 "YA, saya prihatin. Memang tidak pantas anak-anak menyanyikan lagu dewasa atau lagu cinta," jawab Adi Bing Slamet ketika ditanya Ulfa, dalam acara "Gebyar BCA" di Indosiar, Sabtu seminggu lalu. "Miris aku. Bayangkan saja, anak-anak zaman sekarang lebih kenal lagu-lagu milik Peterpan, Matta, Samsons, dibandingkan lagu anak-anak sendiri. Padahal lagu-lagu itu bukan konsumsi mereka. Jadi akan sangat mengganggu pertumbuhan mereka," tambah Andy /rif, dengan mimik bergidik.
"YA, saya prihatin. Memang tidak pantas anak-anak menyanyikan lagu dewasa atau lagu cinta," jawab Adi Bing Slamet ketika ditanya Ulfa, dalam acara "Gebyar BCA" di Indosiar, Sabtu seminggu lalu. "Miris aku. Bayangkan saja, anak-anak zaman sekarang lebih kenal lagu-lagu milik Peterpan, Matta, Samsons, dibandingkan lagu anak-anak sendiri. Padahal lagu-lagu itu bukan konsumsi mereka. Jadi akan sangat mengganggu pertumbuhan mereka," tambah Andy /rif, dengan mimik bergidik.
"Itu namanya pelanggaran hak anak untuk menikmati masa kecilnya dengan lagu-lagu anak yang bisa membuat mereka ceria," ungkap Kak Seto. "Lagu anak-anak zaman dulu tuh masih layak dinyanyikan, bahkan tak lekang oleh waktu. Seperti `Naik Gunung`, `Naik Delman`"," tambahnya.
Ya, semua memang prihatin. Dan akar keprihatinan itu dipicu oleh acara "Idola Cilik" yang tayang setiap hari di RCTI. Di ajang reality show pencarian bakat untuk anak-anak itu, lagu-lagu cinta "milik" kaum dewasa acap tampil. Peserta, anak-anak 12 tahun ke bawah itu, lebih sering menyanyikan lagu-lagu kasmaran dan atau perselingkuhan. "Kekasih Gelap" milik Ungu, "Ketahuan" dan "Playboy" Matta Band, "Aku Mencintaimu Apa Adanya" Once, atau "Munajat Cinta" The Rock, tampil dalam keceriaan dan lengking kanak-kanak. Kadang dengan ekspresi yang tidak klop, namun acap juga sangat mengena, seperti penampilan Kiki atau Siti. Ekpresi yang kena inilah yang barangkali membuat Kak Seto takut, "Anak-anak akan menjadi lebih cepat dewasa karena perkembangan psikoseksualnya menjadi lebih cepat."
Alasan Ideologis
Semua pendapat di atas, termasuk komentar Tompi di "Insert", menempatkan acara "Idola Cilik" sebagai ajang yang salah, tidak tepat, dan eksploitatif. Dan televisi yang paling kerap menyuarakan opini eksploitasi ini adalah Indosiar. Tentu, selain sebagai wujud keprihatinan, opini itu juga dibangun dalam perspektif kepentingan bisnis, persaingan acara yang nyaris sama, reality show anak-anak. RCTI memang mencuri start, memotong rencana Indosiar yang tengah mempersiapkan "AFI Junior". Jadi, para aktris pemberi opini di atas barangkali tidak menyadari, pendapat mereka didukung bukan karena akan "menyelamatkan" anak-anak, melainkan dijadikan sebagai "peluru" untuk menembak kepentingan lawan bisnis. Karena, sebenarnya, anak-anak memang tak perlu dicemaskan dan atau diselamatkan.
"Idola Cilik" adalah ajang pencarian bakat untuk menjadi penyanyi. Yang jadi ukuran utama diacara ini adalah suara. Dan untuk mendapatkan gambaran suara yang baik, unik, konstan, mampu menjangkau nada-nada tinggi, dan tidak getar di suara rendah, penyanyi butuh lagu yang tepat. Dan harus diakui, lagu anak-anak tidak mampu secara eksploitatif menunjukkan hal tersebut. Lagu "Naik Delman", "Naik Kereta Api", "Lihat Balonku", "Potong Bebek Angsa", atau "Pelangi", harus diakui, bermain dalam nada-nada yang sederhana, bahkan cenderung sama. Keunikan suara seorang anak tidak akan tereksplorasi secara sempurna jika menyanyikan lagu di atas. Itu terutama karena lagu anak-anak tadi lebih diniatkan sebagai lagu dolanan, yang lebih mementingkan aspek bermain dan belajar. Beberapa episode "Idola Cilik" yang menampilkan lagu anak-anak seperti di atas --setelah kritik yang bertubi-tubi-- menunjukkan dengan jelas hal ini, kedataran vokal, dan keunikan yang hilang. Anak-anak jadi tampak memiliki kemampuan yang seragam dan seimbang.
Lagu dewasa jelas berbeda. Dalam suasana kompetitif, lagu-lagu ini mampu menunjukkan secara langsung kualitas vokal peserta. Suara Kiki misalnya, jadi tereksplorasi sempurna ketika menyanyikan "Mengejar Matahari" Ari Laso, dengan jangkauan nada tinggi yang stabil. Dalam lagu itu, suara Kiki menemukan rumahnya. Atau Itamar ketika menyanyikan "Terpesona" Glenn Fredly dan "Reflection" Christina Aquilera, vokalnya sungguh teraksentuasi dengan maksimal. Penyanyi merasa puas, komentator menjadi gampang menilai, penonton langsung tahu siapa yang layak untuk terus maju. Dengan kata lain, lagu-lagu dewasa justru membuat anak-anak tadi mendapatkan keadilan penilaian atas kualitas suaranya.
Yang juga harus diingat, "Idola Cilik" sarat dengan suasana kompetitif. Dan untuk memenangkan kompetisi menyanyi, selain suara, situasi panggung, dukungan penggemar, sampai aspek personalitas pun harus dimanfaatkan secara maksimal. Penyanyi harus mampu menjalin relasi dan ikatan emosi dengan penonton. Relasi dan jalinan emosi itu hanya akan tumbuh jika penyanyi berada dalam suasana, iklim, ekosistem, dunia, yang sama dengan penonton. Dan harus diakui, dunia penonton --baik itu anak-anak dan orang tua--, adalah lingkungan yang dihidupi oleh lagu-lagu orang dewasa, berlirik cinta dan perselingkuhan. Penyanyi harus masuk dalam suasana itu, dan tidak boleh menafikannya. Karena kalau penyanyi kehilangan relasi, keterhubungan dengan penonton, otomatis dia kehilangan panggung, dan juga suara. Apalagi, untuk kompetisi yang bersandar pada SMS, yang lebih banyak dikirimkan oleh orang dewasa. Jadi, memilih dan menyanyikan lagu cinta adalah persoalan mekanis semata, untuk meraih simpati dan juara. Tak ada alasan ideologis di belakangnya.
Makna Privat
Kekhawatiran Kak Seto, Tompi, Andi /rif, atau Joshua, berangkat dari paradigma bahwa anak-anak harus berada dalam iklim yang steril dari cengkraman "dunia" dewasa. Namun, kelemahan argumentasi mereka justru terletak dari hal yang paling dasar, menempatkan anak-anak dalam satu sudut pandang saja. Kak Seto dan Andi/rif khawatir lirik cinta akan memengaruhi emosi si anak. Di sini sebenarnya telah terjadi sebuah pengandaian bahwa "anak-anak mengerti dengan lirik tersebut", dan karena itu "berbahaya" bagi jiwa mereka. Masalahnya adalah apakah "pengertian" anak-anak itu sama dengan "pengertian" yang orang dewasa, Kak Seto dan Andi/rif? Jangan-jangan, "pengertian" yang dipahami Kak Seto dan atau orang dewasa lainnya itulah yang dijadikan ukuran "pengertian" anak-anak. Dengan kata lain, opini di atas, kekhawatiran itu, berangkat dari "pengertian" orang dewasa yang diatasnamakan "pengertian" anak-anak. "Pengertian" anak-anak sendiri tidak pernah termanifestasikan. Dengan "pengertian" semacam itu, anak-anak justru telah "didewasakan".
Ya, itulah persoalannya, orangtua yang selalu merasa tahu alam pikir anak-anak. Orang dewasa yang merasa paling tahu apa yang pantas dan tidak bagi anak-anak. Sebuah anggapan bahwa anank-anak adalah makhluk yang gampang retak, mudah tercemari, dan karena itu butuh pertolongan. Padahal, orangtualah yang seharusnya lebih butuh diselamatkan. Proteksi mereka, kecemasan mereka, sebenarnya adalah kekhawatiran pada diri sendiri akan sebuah "masa depan" anak-anak. Padahal, masa depan anak-anak itu, kelak menjadi milik mereka sendirim, bukan milik orang dewasa atau orangtuanya, dan karena itu tidak bisa diarahkan, didesain, apalagi dalam kultur kecemasan.
Anak-anak adalah anak-anak. Orang dewasa harus melihat anak-anak sebagai anak-anak. Ketika Kiki menyanyi "Aku Mencintaimu Apa Adanya" Once, yang tersaji adalah ungkapan seorang anak pada orangtuanya yang memilik keterbatasan, cacat fisik tapi bukan cacat cinta. "Pengertian" Kiki bukanlah "pengertian" Once atau Kak Seto. Ekspresi Kiki tidak sebangun dengan luahan rasa Once. Lagu itu dipilih Kiki sebagai "rumah" untuk menampung semua pengalaman pribadinya bersangkutan dengan ayahnya, juga penyataan dia tentang bagaimana mencintai seseorang yang memilik keterbatasan. Dan pengalaman pribadi Kiki tidak sama dengan Once atau Dewiq yang menciptakan lagu tersebut. Dan ketika Kiki bernyanyi, tak ada sebersit ingatan pun yang memperhubungkannya dengan "pengertian" dewasa itu. Lagu dewasa itu, justru sempurna dalam ungkapan kekanakan Kiki. Lagu itu tidak membuat Kiki jadi dewasa. Tak ada yang berbahaya di sini.
Jadi, Kak Seto, Andi/rif, hakikatnya, lagu seperti puisi. Dia menyentuhmu dalam pengalaman personalmu, dalam "pengertian" privatmu. Pengertian itu multak milikmu, berada dalam duniamu. Baik kamu dewasa atau anak-anak. Dan haram hukumnya "pengertian" personalmu itu kamu paksakan jadi "pengertian" orang lain. Karena, jika kamu tetap memaksakan pengertian itu, sungguh kamulah yang tidak dewasa, dan engkaulah yang patut dicemaskan, lebih layak diselamatkan, daripada anak-anak yang bernyanyi cinta dalam pengertian dan dunia kanaknya....
[Telah di Harian Suara Merdeka, Minggu 30 Maret 2008]
( t.i.l.i.k ! )
 "YA, saya prihatin. Memang tidak pantas anak-anak menyanyikan lagu dewasa atau lagu cinta," jawab Adi Bing Slamet ketika ditanya Ulfa, dalam acara "Gebyar BCA" di Indosiar, Sabtu seminggu lalu. "Miris aku. Bayangkan saja, anak-anak zaman sekarang lebih kenal lagu-lagu milik Peterpan, Matta, Samsons, dibandingkan lagu anak-anak sendiri. Padahal lagu-lagu itu bukan konsumsi mereka. Jadi akan sangat mengganggu pertumbuhan mereka," tambah Andy /rif, dengan mimik bergidik.
"YA, saya prihatin. Memang tidak pantas anak-anak menyanyikan lagu dewasa atau lagu cinta," jawab Adi Bing Slamet ketika ditanya Ulfa, dalam acara "Gebyar BCA" di Indosiar, Sabtu seminggu lalu. "Miris aku. Bayangkan saja, anak-anak zaman sekarang lebih kenal lagu-lagu milik Peterpan, Matta, Samsons, dibandingkan lagu anak-anak sendiri. Padahal lagu-lagu itu bukan konsumsi mereka. Jadi akan sangat mengganggu pertumbuhan mereka," tambah Andy /rif, dengan mimik bergidik."Itu namanya pelanggaran hak anak untuk menikmati masa kecilnya dengan lagu-lagu anak yang bisa membuat mereka ceria," ungkap Kak Seto. "Lagu anak-anak zaman dulu tuh masih layak dinyanyikan, bahkan tak lekang oleh waktu. Seperti `Naik Gunung`, `Naik Delman`"," tambahnya.
Ya, semua memang prihatin. Dan akar keprihatinan itu dipicu oleh acara "Idola Cilik" yang tayang setiap hari di RCTI. Di ajang reality show pencarian bakat untuk anak-anak itu, lagu-lagu cinta "milik" kaum dewasa acap tampil. Peserta, anak-anak 12 tahun ke bawah itu, lebih sering menyanyikan lagu-lagu kasmaran dan atau perselingkuhan. "Kekasih Gelap" milik Ungu, "Ketahuan" dan "Playboy" Matta Band, "Aku Mencintaimu Apa Adanya" Once, atau "Munajat Cinta" The Rock, tampil dalam keceriaan dan lengking kanak-kanak. Kadang dengan ekspresi yang tidak klop, namun acap juga sangat mengena, seperti penampilan Kiki atau Siti. Ekpresi yang kena inilah yang barangkali membuat Kak Seto takut, "Anak-anak akan menjadi lebih cepat dewasa karena perkembangan psikoseksualnya menjadi lebih cepat."
Alasan Ideologis
Semua pendapat di atas, termasuk komentar Tompi di "Insert", menempatkan acara "Idola Cilik" sebagai ajang yang salah, tidak tepat, dan eksploitatif. Dan televisi yang paling kerap menyuarakan opini eksploitasi ini adalah Indosiar. Tentu, selain sebagai wujud keprihatinan, opini itu juga dibangun dalam perspektif kepentingan bisnis, persaingan acara yang nyaris sama, reality show anak-anak. RCTI memang mencuri start, memotong rencana Indosiar yang tengah mempersiapkan "AFI Junior". Jadi, para aktris pemberi opini di atas barangkali tidak menyadari, pendapat mereka didukung bukan karena akan "menyelamatkan" anak-anak, melainkan dijadikan sebagai "peluru" untuk menembak kepentingan lawan bisnis. Karena, sebenarnya, anak-anak memang tak perlu dicemaskan dan atau diselamatkan.
"Idola Cilik" adalah ajang pencarian bakat untuk menjadi penyanyi. Yang jadi ukuran utama diacara ini adalah suara. Dan untuk mendapatkan gambaran suara yang baik, unik, konstan, mampu menjangkau nada-nada tinggi, dan tidak getar di suara rendah, penyanyi butuh lagu yang tepat. Dan harus diakui, lagu anak-anak tidak mampu secara eksploitatif menunjukkan hal tersebut. Lagu "Naik Delman", "Naik Kereta Api", "Lihat Balonku", "Potong Bebek Angsa", atau "Pelangi", harus diakui, bermain dalam nada-nada yang sederhana, bahkan cenderung sama. Keunikan suara seorang anak tidak akan tereksplorasi secara sempurna jika menyanyikan lagu di atas. Itu terutama karena lagu anak-anak tadi lebih diniatkan sebagai lagu dolanan, yang lebih mementingkan aspek bermain dan belajar. Beberapa episode "Idola Cilik" yang menampilkan lagu anak-anak seperti di atas --setelah kritik yang bertubi-tubi-- menunjukkan dengan jelas hal ini, kedataran vokal, dan keunikan yang hilang. Anak-anak jadi tampak memiliki kemampuan yang seragam dan seimbang.
Lagu dewasa jelas berbeda. Dalam suasana kompetitif, lagu-lagu ini mampu menunjukkan secara langsung kualitas vokal peserta. Suara Kiki misalnya, jadi tereksplorasi sempurna ketika menyanyikan "Mengejar Matahari" Ari Laso, dengan jangkauan nada tinggi yang stabil. Dalam lagu itu, suara Kiki menemukan rumahnya. Atau Itamar ketika menyanyikan "Terpesona" Glenn Fredly dan "Reflection" Christina Aquilera, vokalnya sungguh teraksentuasi dengan maksimal. Penyanyi merasa puas, komentator menjadi gampang menilai, penonton langsung tahu siapa yang layak untuk terus maju. Dengan kata lain, lagu-lagu dewasa justru membuat anak-anak tadi mendapatkan keadilan penilaian atas kualitas suaranya.
Yang juga harus diingat, "Idola Cilik" sarat dengan suasana kompetitif. Dan untuk memenangkan kompetisi menyanyi, selain suara, situasi panggung, dukungan penggemar, sampai aspek personalitas pun harus dimanfaatkan secara maksimal. Penyanyi harus mampu menjalin relasi dan ikatan emosi dengan penonton. Relasi dan jalinan emosi itu hanya akan tumbuh jika penyanyi berada dalam suasana, iklim, ekosistem, dunia, yang sama dengan penonton. Dan harus diakui, dunia penonton --baik itu anak-anak dan orang tua--, adalah lingkungan yang dihidupi oleh lagu-lagu orang dewasa, berlirik cinta dan perselingkuhan. Penyanyi harus masuk dalam suasana itu, dan tidak boleh menafikannya. Karena kalau penyanyi kehilangan relasi, keterhubungan dengan penonton, otomatis dia kehilangan panggung, dan juga suara. Apalagi, untuk kompetisi yang bersandar pada SMS, yang lebih banyak dikirimkan oleh orang dewasa. Jadi, memilih dan menyanyikan lagu cinta adalah persoalan mekanis semata, untuk meraih simpati dan juara. Tak ada alasan ideologis di belakangnya.
Makna Privat
Kekhawatiran Kak Seto, Tompi, Andi /rif, atau Joshua, berangkat dari paradigma bahwa anak-anak harus berada dalam iklim yang steril dari cengkraman "dunia" dewasa. Namun, kelemahan argumentasi mereka justru terletak dari hal yang paling dasar, menempatkan anak-anak dalam satu sudut pandang saja. Kak Seto dan Andi/rif khawatir lirik cinta akan memengaruhi emosi si anak. Di sini sebenarnya telah terjadi sebuah pengandaian bahwa "anak-anak mengerti dengan lirik tersebut", dan karena itu "berbahaya" bagi jiwa mereka. Masalahnya adalah apakah "pengertian" anak-anak itu sama dengan "pengertian" yang orang dewasa, Kak Seto dan Andi/rif? Jangan-jangan, "pengertian" yang dipahami Kak Seto dan atau orang dewasa lainnya itulah yang dijadikan ukuran "pengertian" anak-anak. Dengan kata lain, opini di atas, kekhawatiran itu, berangkat dari "pengertian" orang dewasa yang diatasnamakan "pengertian" anak-anak. "Pengertian" anak-anak sendiri tidak pernah termanifestasikan. Dengan "pengertian" semacam itu, anak-anak justru telah "didewasakan".
Ya, itulah persoalannya, orangtua yang selalu merasa tahu alam pikir anak-anak. Orang dewasa yang merasa paling tahu apa yang pantas dan tidak bagi anak-anak. Sebuah anggapan bahwa anank-anak adalah makhluk yang gampang retak, mudah tercemari, dan karena itu butuh pertolongan. Padahal, orangtualah yang seharusnya lebih butuh diselamatkan. Proteksi mereka, kecemasan mereka, sebenarnya adalah kekhawatiran pada diri sendiri akan sebuah "masa depan" anak-anak. Padahal, masa depan anak-anak itu, kelak menjadi milik mereka sendirim, bukan milik orang dewasa atau orangtuanya, dan karena itu tidak bisa diarahkan, didesain, apalagi dalam kultur kecemasan.
Anak-anak adalah anak-anak. Orang dewasa harus melihat anak-anak sebagai anak-anak. Ketika Kiki menyanyi "Aku Mencintaimu Apa Adanya" Once, yang tersaji adalah ungkapan seorang anak pada orangtuanya yang memilik keterbatasan, cacat fisik tapi bukan cacat cinta. "Pengertian" Kiki bukanlah "pengertian" Once atau Kak Seto. Ekspresi Kiki tidak sebangun dengan luahan rasa Once. Lagu itu dipilih Kiki sebagai "rumah" untuk menampung semua pengalaman pribadinya bersangkutan dengan ayahnya, juga penyataan dia tentang bagaimana mencintai seseorang yang memilik keterbatasan. Dan pengalaman pribadi Kiki tidak sama dengan Once atau Dewiq yang menciptakan lagu tersebut. Dan ketika Kiki bernyanyi, tak ada sebersit ingatan pun yang memperhubungkannya dengan "pengertian" dewasa itu. Lagu dewasa itu, justru sempurna dalam ungkapan kekanakan Kiki. Lagu itu tidak membuat Kiki jadi dewasa. Tak ada yang berbahaya di sini.
Jadi, Kak Seto, Andi/rif, hakikatnya, lagu seperti puisi. Dia menyentuhmu dalam pengalaman personalmu, dalam "pengertian" privatmu. Pengertian itu multak milikmu, berada dalam duniamu. Baik kamu dewasa atau anak-anak. Dan haram hukumnya "pengertian" personalmu itu kamu paksakan jadi "pengertian" orang lain. Karena, jika kamu tetap memaksakan pengertian itu, sungguh kamulah yang tidak dewasa, dan engkaulah yang patut dicemaskan, lebih layak diselamatkan, daripada anak-anak yang bernyanyi cinta dalam pengertian dan dunia kanaknya....
[Telah di Harian Suara Merdeka, Minggu 30 Maret 2008]
( t.i.l.i.k ! )
Wednesday, March 12, 2008
Ayo Rayakan Keamatiran!

BULLETIN, majalah yang telah menjadi "otak" warga Australia, akhirnya padam juga. Scott Lorson, pemimpin majalah itu, dengan sedikit terbata, mengumumkan edisi "Why We Love Australia" sebagai cetakan terakhir, di awal Februari lalu. Padahal, kata Lorson, "The Bulletin has been an institution in Australian publishing and has provided... the best quality, in-depth news and current affairs analysis in the country.
"The Bulletin has often set the political agenda, broken many important stories and won many award for journalism over the years."
Apa yang membuat majalah dengan sejarah 128 tahun itu tumbang? Harold Mitchell, analis media, punya jawaban. "Bulletin tidak menemukan jalan untuk menjadi bagian dari Australia yang modern, dan bagian dari kehidupan kami," ucapnya. "Bulletin gagal memodernisasi diri dan bersaing dengan internet."
Majalah yang modern, bagi Mitchell, adalah yang menjadikan internet bukan semata "corong baru" untuk perluasan pasar, melainkan "telinga" untuk mendengar suara warga, dan kanal untuk saling bertukar kuasa produksi-distribusi berita. Itulah yang disebut Mitchell, "Bagian dari kehidupan kami."
Internet. Suara warga. Bertukar kuasa produksi dan distribusi berita. Semua kosa kata tadi mengacu pada satu hal: citizen journalism atau jurnalisme warga, sebuah "gerakan" yang muncul sebagai wujud "ketidakpuasan" pada jurnalisme mainstream. Dalam citizen journalism, warga adalah konsumen sekaligus produsen berita. Tugas editor, yang biasanya melakukan penyelarasan berita untuk pembaca yang dituju, ditampik. Dalam jurnalisme warga, subjektivitas dibiarkan, kaidah baku penulisan ditanggalkan, sudut pandang boleh bercecabang, opini dan hasutan kadang berkelindan. Semua "dibolehkan" karena citizen journalism adalah warga yang menulis, bukan wartawan, warga yang bercerita, karena berita adalah percakapan.
Dan karena citizen journalism merayakan kebebasan warga untuk membuat berita, di sini, istilah itu pun cepat meraih gempita. Warga kini punya kuasa, punya justifikasi untuk melakukan hal yang sama dengan wartawan. Ucapan sejumlah pakar disiarkan, Jay Rossen menjadi nabi baru, Tim Porter sebagai khalifah, dan ohmynews didudukkan sebagai surga yang dituju. Pesta Blogger 2007 pun mengklaim sebagai suara baru Indonesia, dan media mewartakannya sebagai "ajang berkumpulnya pewarta warga". Tak ada yang salah memang, karena sebagai istilah, citizen journalism memang susah ditentukan, batasnya, juga arahnya. 11 kategori yang dijabarkan Steve Outing dalam "The 11 Layers of Citizen Journalism" kian menegaskan luasnya ranah --sekaligus tidak jelasnya-- istilah ini. Jay Rosen yang menolak mendefenisikan, kian membuat siapa pun warga yang menulis dapat mengklaim diri menjadi bagian dari kegempitaan ini.
Lalu, sebenarnya, siapakah mereka yang dapat disebut sebagai pewarta warga? Apakah blog-blog yang berisi curahan hati dan atau resep masakan? Atau blog berisi puluhan tips, kutipan bijak dari berbagai buku, ratusan opini berupa kritik terhadap "penguasa"? Dan manakah situs yang sungguh menjalankan "prinsip" citizen journalism?
Aceh, akhir 2004. Tak ada yang mengira tsunami akan menerakakan negeri Serambi Mekah ini. Luluh-lantak. Aceh lebur, tapi media tak bisa mewartakannya. Wartawan sibuk menyelamatkan diri dan atau mencari keluarganya yang hilang. Tak ada gambaran yang jernih bagaimana sebenarnya muasal penderitaan akibat tsunami itu. Media, karena keterbatasan data, sibuk menduga, berspekulasi, dan hanya bercerita tentang korban. Awal kejadian, tak tergambarkan.
Lalu, muncullah video dokumenter itu. Jelaslah kini semuanya: bumi yang mendapat getaran pertama, wajah-wajah yang pias-cemas, gerak air pasang, terjangan gelombang, jeritan, doa, pekikan Allahuakbar! Selebihnya adalah tangis.
Cut Putri yang berada di belakang kamera itu. Dia bukan wartawan, cuma warga, yang ingin merekam sejak getar pertama dirasakan keluarganya. Dia semula tak menyangka gempa itu akan menjadi neraka, dan merekam tanpa maksud untuk disiarkan. Karena itu, berkali-kali kameranya goyang, membuat sudut pandang bercecabang. Suara yang terekam pun, bukan nada-nada yang enak didengarkan. Cut Putri jelas amatir. Tapi yang amatir ini, yang merekam suasana apa yang ingin dia lihat, dan bukan apa yang dia bayangkan penonton ingin lihat, meniadakan jarak. Rimbun air mata, lolongan putus asa, demikian jelasnya. Putri tanpa sadar, telah membuat pengalaman personalnya menjadi pengalaman publik. Publik melalui "kacamatanya" mendapatkan sesuatu yang murni, tanpa "frame", tanpa tendensi, juga bunga kata. Sudut-sudut yang ditangkap kameranya adalah jejak yang tak biasa, yang pasti tak akan mendapat tempat dalam kamera jurnalisme biasa; papan yang hanyut, gerak air meninggi, patahan pelepah kelapa, kata-kata cemas dan juga desis harap, kronologi yang semula tak mungkin tampil di televisi karena alasan durasi. Kamera putri adalah mata orang yang terlibat, yang tak berjarak dengan peristiwa. Dia mengalami dan bukan sekadar melaporkan.
Tapi, sampai kini, siapa yang "mengikuti" jejak Putri? Ada berapa banyak pewarta warga yang mampu melihat dan menjadikan "pengalaman personal menjadi milik publik"? Atau sebaliknya, pengetahuan publik menjadi pengalaman personal, sebagaimana yang dilakukan warga Kanada, ketika merekam polisi yang memerasnya di Bali? Pemerasan, pungli yang dilakukan polisi adalah rahasia umum, tapi sampai kini, "rahasia" itu tidak menyentuh, tidak menggerakkan karena tidak "dikelola" menjadi situasi yang personal. Citizen Journalism, karena dari warga, seharusnya menangkap secara utuh denyut urat nadi warga, yang mampu membangun jalinan emosi, dan kalau bisa, menggerakkan warga.
Putri juga menunjukkan satu aspek yang sangat penting, lokalitas. Yang tampil adalah wajah orang-orang terdekatnya, lingkungan sekitar rumahnya, kecemasan dan dengung Allahuakbar ninikmamaknya. Lokalitas, subjektivitas, ketakberjarakan. Itulah yang coba ditampik jurnalis "tulen", dan mendapat tempat di pewarta warga. Tapi, manakah situs atau media yang secara ketat mengadopsi tiga hal itu?
Di mana video Cut Putri ditayangkan? Di MetroTV. Media mana yang memuat video pungli yang dilakukan polisi Bali? Youtube, dan kemudian dikutip detik.com, dan juga Suara Merdeka. Situs yang mengusung khusus kredo citizen jornalisme, berapa hitnya atau cepatkah up-date-nya? Lebih banyak mana hit dan kecepatan beritanya, di bandingkan dengan "citizen journalism" yang juga dikelola media umum seperti kompas.com dan Suara Merdeka Cybernews? Darimana sumber pembiayaan mereka? Sudahkah dilirik pengiklan? Apakah "percakapan" terjadi secara alamiah, dengan keterlibatan yang intens? Benarkah pewarta berada dalam kelokalan yang sama?
Di Australia, Majalah Bulletin yang berusia 128 tahun memang runtuh, karena gagal beradaptasi dengan internet, tidak berbagi kuasa dalam pendistribusian berita, yang seperti kata Mitchell, "Bagian dari kehidupan kami." Dan di sini harus kita akui, internet justru belum menjadi bagian dari kehidupan kita. Karena itu, citizen journalisme belum akan menjadi ancaman bagi media mainstream. Kita mungkin lebih baik untuk menyetiainya, mengembangkannya, merayakannya, karena warga memang punya kuasa atas produksi dan distribusi berita. Karena kita percaya, warga memang bisa.
[Pokok pikiran dalam seminar "Citizen Journalisme: Ancaman bagi Media Massa" di UNS, Solo, 29 Februari 2008]
( t.i.l.i.k ! )
Tuesday, March 04, 2008
Tangis Kemenangan Indra Brugman

INDRA Brugman kalah juga. Berkali dia mengucek, menahan cairan hangat itu jatuh, namun ketika di sudut kanan, matanya menangkap isakan Mama Mimi, tangisannya pun pecah.
Ya, Indra kalah, melawan kenangan pedih ketika melihat Mama Mimi berjualan gorengan untuk membiayai keluarga mereka. Dia tahu betul bagaimana pengorbanan Mama Mimi saat itu, tapi Indra tak kuasa membantu. Itulah sebabnya, ketika di Jakarta, setiap ada penjual gorengan, Indra selalu membelinya, kalau bisa menghabiskannya. "Karena saya selalu berdoa, di sana, di rumah, ada juga yang membeli gorengan Mama, dan menghabiskannya..."
Selasa malam itu (26/2), panggung grandfinal "Supermama Seleb Concert" jadi milik Indra. Semua penonton seperti terhisap pada kenangan masa lalunya, yang demikian pedih. Tak ada lagi akting. Indra luruh, dan mengisak, tangisan anak yang demikian sakit karena merasa dalam salah satu episode hidupnya, pernah membuat sang mama berkorban terlalu besar. Dia peluk Mama Mimi, dia abai pada ingus yang jatuh dari hidungnya. "Terimakasih Mama, terimakasih..." bisiknya.
Di belakang mereka, Eko Patrio menangis.
Di sisi kiri, di jajaran peserta, Mama Lutfia, terisak. Tangannya digenggam Adly, putranya, seakan memberikan kekuatan, untuk tak larut dalam kesedihan.
Ruben Onsu, yang selalu bercanda gila, seperti kehilangan suara. Ivan Gunawan, yang meminta Indra bercerita, memandang dengan mata berkaca. Dia juga menahan sedan. Panggung "pesta" itu senyap. Isakan, suara tangis, menjadi orkestra yang demikian indah, musik yang bercerita kasih anak dan orang tua.
Dan Eko kemudian memberi nilai yang lebih dalam lagi. Sehabis melap matanya, dengan suara yang belum bebas dari tangis, dia berkata, "Yang penting dari kita adalah bukan di posisi mana saat ini, melainkan bagaimana cara kita bisa meraih posisi itu."
Ya, Eko benar. Yang menggetarkan dari pengamanan Indra Brugman bukanlah posisinya sekarang sebagai aktor terkenal, melainkan perjuangannya meraih itu semua. Dengan kata lain, Indra meraih semua posisi itu dengan tidak menggadaikan kehormatannya, harga dirinya. Indra membayar pantas, tanpa jalan pintas.
Apa yang dilakukan Indra, dengan demikian, nyaris jadi anomali dalam dunia industri. Ketika semua orang ingin cepat populer, yang patuh pada proses, sering terlindas. Yang cepat, dapat. Jalan pintas, wajar dan benar. Industri membuat semua orang lebih menghitung posisi. Berada dalam satu status, terutama selebritis, adalah segalanya. Apa pun boleh dikorbankan untuk meraih itu.
Kita tahu berbagai rumor seram dalam hal itu, mulai membayar juri, "menjual" keperawanan, sampai menjadi istri simpanan, hanya untuk meraih sebuah peran. Dan banyak artis yang mengakuinya, kemudian. Mereka seakan mengatakan bahwa hal itu adalah harga dari sebuah popularitas, sebuah tujuan. Moral orang kebanyakan jadi tidak cocok sebagai ukuran. "Gue terpaksa melakukan itu," kata Cut Memey, ketika statusnya sebagai istri simpanan Jakcson terungkap. Alm Alda Risma pun punya "sejarah" yang sama, juga Mayangsari, tentunya. Dan yang tak terbantahkan, "si kembar" Sarah dan Rahma Azhari.
Maka, terasa ajaib, ketika di tengah tangis panggung "Supermama seleb Consert" itu, Eko menegaskan bahwa posisi tak terlalu berarti. Barangkali Eko tahu, sangat sedikit artis kini, yang meraih posisinya dengan meneteskan airmata, dan terus berjuang, tetap sebagai manusia. Eko mengerti, karena seperti Indra, dia pun melakukannya. Mereka bermimpi dan mewujudkan mimpi itu dengan sempurna, sebagai buah usaha dan doa. Tangis malam itu, adalah isakan mereka yang bahagia, tetap memilih menjadi manusia, di jalan yang menjadi binatang pun akan dianggap biasa. Tangis itu adalah perayaan kemenangan mereka....
[Telah dimuat sebagai "Tajuk" dalam Tabloid Cempaka, Kamis 6 Maret 2008]
( t.i.l.i.k ! )