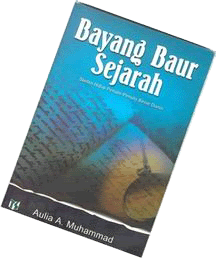...tera di sesela gegas-gesa
Monday, April 28, 2008
Cara Terhormat Melawan Dewi
Bagi Dewi Persik, panggung bukanlah ajang pamer suara, melainkan olah-senggama. Orgasme tujuannya.
 Wajah Dewi Persik memerah. Duduk di samping Hj Endah Murnalita, penasihat hukumnya, dia tak dapat lagi menahan marah. "Kata-kata Dewi Persik telah merusak moral, itu yang saya tidak bisa terima," ketusnya seperti terlihat di "Selebrita" Global TV (23/4). "Saya sedih karena semua ini dibuat untuk kepentingan politik!" tambahnya.
Wajah Dewi Persik memerah. Duduk di samping Hj Endah Murnalita, penasihat hukumnya, dia tak dapat lagi menahan marah. "Kata-kata Dewi Persik telah merusak moral, itu yang saya tidak bisa terima," ketusnya seperti terlihat di "Selebrita" Global TV (23/4). "Saya sedih karena semua ini dibuat untuk kepentingan politik!" tambahnya.
Dewi memang tengah gundah. Walikota Tangerang, Wahidin Halim, melarang dia bergoyang. Walikota Bandung, Dada Rosana, juga melakukan hal yang sama. "Coba saja dia minta izin, pasti tidak saya izinkan. Kecuali dia mau mengubah goyangan dan penampilannya," ucap Dada. Namun Dewi dan penasihat hukumnya yakin, larangan itu hanya upaya untuk menarik simpati warga. Kedua walikota itu ternyata tengah bersiap ikut pilkada, dan mencalonkan diri untuk kali kedua.
"Memang kami tidak ingin ini jadi politis. Makanya, kamu tidak mau menanggapi lagi. Tujuannya pilkada," terang Murnalita.
Dada Rosada jelas membantah motif politik itu. "Saya cuma memenuhi permintaan warga," katanya sebagaimana ramai dikutip media.
Warga, masyarakat, memang acap dijadikan alat atau alasan untuk bertindak. Forum Pembela Islam pun, atas nama keresahan umat, membakar kaset dan CD Dewi Persik. Forum itu bahkan siap membubarkan panggung Dewi jika mantan istri Saipul Jamil itu tak juga mau berubah. Tapi, apakah yang dimaksud dengan warga, masyarakat atau umat, sebenarnya?
Ubah Persepsi
Goyang Dewi Persik memang sensual. Bahkan dalam beberapa penampilan, seperti yang acap ditunjukkan ragam infotainmen, sangat erotis. Dewi tak cukup hanya menggoyangkan pinggul seperti Nita Thalia, atau memutar pantat seperti Inul, tapi menggelepar-gelepar di panggung, kadang bergaya seolah bersanggama. Eskpresinya pun bukan seperti orang yang tengah bernyanyi, melainkan raut yang sedang bercinta. Bagi Dewi, panggung adalah arena dia untuk berolahasmara, dan dia selalu memperoleh orgasme karenanya. Yang ditampilkan Dewi pada intinya bukanlah pertunjukan suara tapi olah kamasutra. Karena itulah, tak terdengar suara yang mendukung Dewi ketika terjadi pelarangan dan pencekalan di Bandung dan Tangerang, atau pembakaran oleh Forum Umat Islam. Warga, umat, masyarakat, seperti berada di seberang dirinya. Dalam hal inilah, Dewi berbeda dari Inul.
Inul juga pernah seperti Dewi, dilarang dan dikecam, bahkan oleh pemilik "otoritas" Dangdut, Rhoma Irama. Tapi apa yang terjadi kemudian, Inul justru tak pernah merasa sendirian. Selalu ada bagian dari warga, umat, atau masyarakat, yang berdiri di sisinya, membelanya. Sebabnya, Inul bertindak lebih cerdas daripada Dewi.
Ketika larangan dan kecaman datang, Inul tidak mencoba melawan sendirian. Dia minta bantuan dan sowan ke berbagai banyak orang. Inul tahu, "fatwa" Rhoma bukanlah kebenaran satu-satunya. Dia ke Gus Dur, dan teryakinkah untuk tak boleh mundur. Inul memberi "agenda" bahwa yang dia perjuangkan bukanlah soal goyangan semata, melainkan haknya sebagai seorang wanita untuk mencari makan. Inul mengubah persepsi larangan itu jadi pencekalan atas keinginannya untuk menjadi tulang punggung keluarga, hak anak untuk membuat orangtuanya bahagia. "Saya hanya mencari makan dengan bergoyang. Apakah saya salah?" tanyanya.
Publik pun terbelah. Sebagian bahkan jadi berubah arah, mencoba memaklumi. Apalagi, media pun menaruh simpati pada istri Adam Suseno ini, dan memblow-up hal itu menjadi isu feminisme. Dangdut bahkan mendapat gugatan, moralitas, juga agama. Emha Ainun Najib sampai menulis "Pantat Inul adalah Wajah Kita Semua", dan KH Musthofa Bisri pun menjadikan Inul sebagai tema lukisan. Inul menjadi "gelombang" justru karena dia bisa mengajak orang untuk berpikir bahwa apa yang dia perjuangkan bukan semata soal goyang.
Dewi Persik tak mampu mengubah itu. Dewi terlalu angkuh untuk meminta bantuan dan melawan sendirian. Dia bahkan menantang, melawan, tanpa meminjam mulut orang. Dewi jadi terkesan arogan. Dewi tak mencitrakan diri sebagai sosok yang lemah dan terhina. Dan karena itulah, pembelaan pun tak datang dari "ibu semua artis", Titiek Puspa.
Secara sadar, Dewi Persik justru mencitrakan diri sebagai perempuan yang bebas menjual sensualitas. "Siapa yang tidak mau? Sudah enak, dapat duit lagi," katanya, ketika ditanya mengapa mau beradegan intim dalam film Tali Pocong Perawan. Dewi membuat orang tahu, bahwa sensualitas, goyangan syawat dan mimik orgasme itu, adalah pilihan sadarnya untuk mencari uang. Dewi melakukannya dengan riang.
Inul sebaliknya, mencitrakan diri sebagai perempuan yang terpaksa. "Hanya bernyanyi itu yang aku bisa," katanya dulu. Inul membuat orang berpikir bahwa dia, dengan latar belakang religiusitas keluarga, pun tak bangga menjual goyangannya. Untuk orang yang terpaksa, warga, masyarakat, umat, pasti gampang memberi maaf.
Uji Pasar
Dewi memang secara sadar menjual sensualitas goyangnya. Dia memang tak perlu dibela, dan tentu, tak usah juga dicekal atau dilarang. Pelarangan, pencekalan, atau pembubaran dan pembakaran, bagaimanapun adalah wujud dari sikap yang tidak dewasa. Dewi seharusnya dibiarkan saja. Masyarakat, warga, atau umat, harus terbiasa untuk terbuka pada perbedaan, keanekaragaman. Goyangan Dewi Persik bahkan penting untuk membuat beda antara mutiara dan sampah.
Dewi Persik adalah produk yang lahir dari mekanisme pasar. Dia tumbuh dan berkembang --lihatlah modifikasi goyang Dewi-- karena memenuhi hukum permintaan. Harus diakui, di luar umat atau warga yang menentang, ada juga warga dan umat yang lain justru memuja Dewi. Sebagian warga, umat, atau penonton, yang tidak suka harus bisa melihat Dewi bukan "bagian dari kita", bukan milik "kita", melainkan produk dan hak warga yang lain. Dan sangat tidak benar, apa pun alasannya, untuk melarang, atau menghakimi, sesuatu yang bukan menjadi bagian dari milik sendiri. Sebagai bagian dari "mereka", Dewi bebas melakukan hak-haknya. Dengan cara itulah warga jadi dewasa, menghargai heterogenitasnya.
Lalu pemerintah? Pemerintah harus berada di antara warga. Pemerintah atau pemda, harus menjamin warga menikmati kesetujuan dan ketidaksetujuannya, dan tidak menjadi "beking" salah satu di antaranya. Negara harus menjadi wasit, agar tidak terjadi pemaksaan selera dari satu warga kepada warga lainnya. Negara harus berdiri di tengah, agar antara warga yang berbeda tidak bertindak sendiri, menjauhkan anarki. Dengan kata lain, negara atau pemerintah, harus membiarkan proses pasar.
Dewi adalah produk pasar dan harus dilawan di pasar. Jika sebagian warga takut goyangan Dewi merusak moral, lawanlah hal itu dengan membuat dan memasuki pasar dengan produk yang berbeda. Juallah Dewi yang berbeda, yang tidak merusak sendi moral dan agama, Dewi dangdut yang tidak bergoyang erotis di panggungnya. Penganjur moral harus mulai dewasa untuk tidak melakukan larangan atau kecaman saja, melainkan membuat dan memasarkan produk yang memenuhi tuntunan moralitasnya. Biarkan pasar yang mengujinya.
Kini saatnya untuk belajar dari Ayat-ayat Cinta, bahwa kebaikan, bahkan "film khotbah" pun memiliki pasar jika dikemas dan dimanajemen secara benar. Bahwa pasar bukan saja menerima hantu, pocong atau perselingkuhan, tapi juga "malaikat" dalam bentuk Fahri, dan cinta dalam wajah poligami. Dan Dewi, bukankah tidak sendiri? Telah ada Ustad Jeffry yang berdangdut dalam barzanzi, melayani, melawan "pasar" Dewi. Dan itulah perlawanan terhormat dalam era liberalisasi.
[Artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 27 April 2008]
 Wajah Dewi Persik memerah. Duduk di samping Hj Endah Murnalita, penasihat hukumnya, dia tak dapat lagi menahan marah. "Kata-kata Dewi Persik telah merusak moral, itu yang saya tidak bisa terima," ketusnya seperti terlihat di "Selebrita" Global TV (23/4). "Saya sedih karena semua ini dibuat untuk kepentingan politik!" tambahnya.
Wajah Dewi Persik memerah. Duduk di samping Hj Endah Murnalita, penasihat hukumnya, dia tak dapat lagi menahan marah. "Kata-kata Dewi Persik telah merusak moral, itu yang saya tidak bisa terima," ketusnya seperti terlihat di "Selebrita" Global TV (23/4). "Saya sedih karena semua ini dibuat untuk kepentingan politik!" tambahnya.Dewi memang tengah gundah. Walikota Tangerang, Wahidin Halim, melarang dia bergoyang. Walikota Bandung, Dada Rosana, juga melakukan hal yang sama. "Coba saja dia minta izin, pasti tidak saya izinkan. Kecuali dia mau mengubah goyangan dan penampilannya," ucap Dada. Namun Dewi dan penasihat hukumnya yakin, larangan itu hanya upaya untuk menarik simpati warga. Kedua walikota itu ternyata tengah bersiap ikut pilkada, dan mencalonkan diri untuk kali kedua.
"Memang kami tidak ingin ini jadi politis. Makanya, kamu tidak mau menanggapi lagi. Tujuannya pilkada," terang Murnalita.
Dada Rosada jelas membantah motif politik itu. "Saya cuma memenuhi permintaan warga," katanya sebagaimana ramai dikutip media.
Warga, masyarakat, memang acap dijadikan alat atau alasan untuk bertindak. Forum Pembela Islam pun, atas nama keresahan umat, membakar kaset dan CD Dewi Persik. Forum itu bahkan siap membubarkan panggung Dewi jika mantan istri Saipul Jamil itu tak juga mau berubah. Tapi, apakah yang dimaksud dengan warga, masyarakat atau umat, sebenarnya?
Ubah Persepsi
Goyang Dewi Persik memang sensual. Bahkan dalam beberapa penampilan, seperti yang acap ditunjukkan ragam infotainmen, sangat erotis. Dewi tak cukup hanya menggoyangkan pinggul seperti Nita Thalia, atau memutar pantat seperti Inul, tapi menggelepar-gelepar di panggung, kadang bergaya seolah bersanggama. Eskpresinya pun bukan seperti orang yang tengah bernyanyi, melainkan raut yang sedang bercinta. Bagi Dewi, panggung adalah arena dia untuk berolahasmara, dan dia selalu memperoleh orgasme karenanya. Yang ditampilkan Dewi pada intinya bukanlah pertunjukan suara tapi olah kamasutra. Karena itulah, tak terdengar suara yang mendukung Dewi ketika terjadi pelarangan dan pencekalan di Bandung dan Tangerang, atau pembakaran oleh Forum Umat Islam. Warga, umat, masyarakat, seperti berada di seberang dirinya. Dalam hal inilah, Dewi berbeda dari Inul.
Inul juga pernah seperti Dewi, dilarang dan dikecam, bahkan oleh pemilik "otoritas" Dangdut, Rhoma Irama. Tapi apa yang terjadi kemudian, Inul justru tak pernah merasa sendirian. Selalu ada bagian dari warga, umat, atau masyarakat, yang berdiri di sisinya, membelanya. Sebabnya, Inul bertindak lebih cerdas daripada Dewi.
Ketika larangan dan kecaman datang, Inul tidak mencoba melawan sendirian. Dia minta bantuan dan sowan ke berbagai banyak orang. Inul tahu, "fatwa" Rhoma bukanlah kebenaran satu-satunya. Dia ke Gus Dur, dan teryakinkah untuk tak boleh mundur. Inul memberi "agenda" bahwa yang dia perjuangkan bukanlah soal goyangan semata, melainkan haknya sebagai seorang wanita untuk mencari makan. Inul mengubah persepsi larangan itu jadi pencekalan atas keinginannya untuk menjadi tulang punggung keluarga, hak anak untuk membuat orangtuanya bahagia. "Saya hanya mencari makan dengan bergoyang. Apakah saya salah?" tanyanya.
Publik pun terbelah. Sebagian bahkan jadi berubah arah, mencoba memaklumi. Apalagi, media pun menaruh simpati pada istri Adam Suseno ini, dan memblow-up hal itu menjadi isu feminisme. Dangdut bahkan mendapat gugatan, moralitas, juga agama. Emha Ainun Najib sampai menulis "Pantat Inul adalah Wajah Kita Semua", dan KH Musthofa Bisri pun menjadikan Inul sebagai tema lukisan. Inul menjadi "gelombang" justru karena dia bisa mengajak orang untuk berpikir bahwa apa yang dia perjuangkan bukan semata soal goyang.
Dewi Persik tak mampu mengubah itu. Dewi terlalu angkuh untuk meminta bantuan dan melawan sendirian. Dia bahkan menantang, melawan, tanpa meminjam mulut orang. Dewi jadi terkesan arogan. Dewi tak mencitrakan diri sebagai sosok yang lemah dan terhina. Dan karena itulah, pembelaan pun tak datang dari "ibu semua artis", Titiek Puspa.
Secara sadar, Dewi Persik justru mencitrakan diri sebagai perempuan yang bebas menjual sensualitas. "Siapa yang tidak mau? Sudah enak, dapat duit lagi," katanya, ketika ditanya mengapa mau beradegan intim dalam film Tali Pocong Perawan. Dewi membuat orang tahu, bahwa sensualitas, goyangan syawat dan mimik orgasme itu, adalah pilihan sadarnya untuk mencari uang. Dewi melakukannya dengan riang.
Inul sebaliknya, mencitrakan diri sebagai perempuan yang terpaksa. "Hanya bernyanyi itu yang aku bisa," katanya dulu. Inul membuat orang berpikir bahwa dia, dengan latar belakang religiusitas keluarga, pun tak bangga menjual goyangannya. Untuk orang yang terpaksa, warga, masyarakat, umat, pasti gampang memberi maaf.
Uji Pasar
Dewi memang secara sadar menjual sensualitas goyangnya. Dia memang tak perlu dibela, dan tentu, tak usah juga dicekal atau dilarang. Pelarangan, pencekalan, atau pembubaran dan pembakaran, bagaimanapun adalah wujud dari sikap yang tidak dewasa. Dewi seharusnya dibiarkan saja. Masyarakat, warga, atau umat, harus terbiasa untuk terbuka pada perbedaan, keanekaragaman. Goyangan Dewi Persik bahkan penting untuk membuat beda antara mutiara dan sampah.
Dewi Persik adalah produk yang lahir dari mekanisme pasar. Dia tumbuh dan berkembang --lihatlah modifikasi goyang Dewi-- karena memenuhi hukum permintaan. Harus diakui, di luar umat atau warga yang menentang, ada juga warga dan umat yang lain justru memuja Dewi. Sebagian warga, umat, atau penonton, yang tidak suka harus bisa melihat Dewi bukan "bagian dari kita", bukan milik "kita", melainkan produk dan hak warga yang lain. Dan sangat tidak benar, apa pun alasannya, untuk melarang, atau menghakimi, sesuatu yang bukan menjadi bagian dari milik sendiri. Sebagai bagian dari "mereka", Dewi bebas melakukan hak-haknya. Dengan cara itulah warga jadi dewasa, menghargai heterogenitasnya.
Lalu pemerintah? Pemerintah harus berada di antara warga. Pemerintah atau pemda, harus menjamin warga menikmati kesetujuan dan ketidaksetujuannya, dan tidak menjadi "beking" salah satu di antaranya. Negara harus menjadi wasit, agar tidak terjadi pemaksaan selera dari satu warga kepada warga lainnya. Negara harus berdiri di tengah, agar antara warga yang berbeda tidak bertindak sendiri, menjauhkan anarki. Dengan kata lain, negara atau pemerintah, harus membiarkan proses pasar.
Dewi adalah produk pasar dan harus dilawan di pasar. Jika sebagian warga takut goyangan Dewi merusak moral, lawanlah hal itu dengan membuat dan memasuki pasar dengan produk yang berbeda. Juallah Dewi yang berbeda, yang tidak merusak sendi moral dan agama, Dewi dangdut yang tidak bergoyang erotis di panggungnya. Penganjur moral harus mulai dewasa untuk tidak melakukan larangan atau kecaman saja, melainkan membuat dan memasarkan produk yang memenuhi tuntunan moralitasnya. Biarkan pasar yang mengujinya.
Kini saatnya untuk belajar dari Ayat-ayat Cinta, bahwa kebaikan, bahkan "film khotbah" pun memiliki pasar jika dikemas dan dimanajemen secara benar. Bahwa pasar bukan saja menerima hantu, pocong atau perselingkuhan, tapi juga "malaikat" dalam bentuk Fahri, dan cinta dalam wajah poligami. Dan Dewi, bukankah tidak sendiri? Telah ada Ustad Jeffry yang berdangdut dalam barzanzi, melayani, melawan "pasar" Dewi. Dan itulah perlawanan terhormat dalam era liberalisasi.
[Artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 27 April 2008]