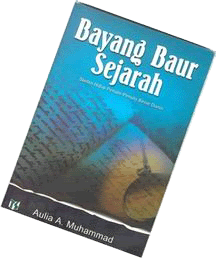...tera di sesela gegas-gesa
Monday, January 21, 2008
Mereka yang Menasehati Diri Sendiri
Banyak orang yang tak menyadari, nasehat yang mereka berikan sebenarnya lebih cocok untuk diri mereka sendiri.
 Di "Silat Lidah", komentator bebas bicara apa pun, tanpa basa basi. Tapi, sebebasnya Julia Perez, dia pasti tak akan diperbolehkan bicara sambil makan atau berkumur, atau tidur telentang di atas panggung. "Silat Lidah", bagaimanapun, masih bebas terbatas, bebas terkendali. Itupun telah membuat acara ini berisik sekali. Jadi bayangkanlah betapa riuh dan "berasak"nya "Supermama Seleb Show", ketika semua komentator dan peserta bebas melakukan apa saja.
Di "Silat Lidah", komentator bebas bicara apa pun, tanpa basa basi. Tapi, sebebasnya Julia Perez, dia pasti tak akan diperbolehkan bicara sambil makan atau berkumur, atau tidur telentang di atas panggung. "Silat Lidah", bagaimanapun, masih bebas terbatas, bebas terkendali. Itupun telah membuat acara ini berisik sekali. Jadi bayangkanlah betapa riuh dan "berasak"nya "Supermama Seleb Show", ketika semua komentator dan peserta bebas melakukan apa saja.
Ivan Gunawan, komentator tetap di acara itu, misalnya, sering disapa Ruben Onsu dengan panggilan "Banteng", "Sapi", "Banci", sampai "Setengah Lelaki". Dan Ivan, meskipun berpura-pura marah, harus bisa menerima panggilan itu dengan riang, dan membalasnya kemudian. Baku hina antara kedua orang inilah yang selalu tertayang panjang di "Supermama Seleb Show", dan memancing riuh tawa penonton.
Acara itu sepertinya dibebaskan Indosiar berjalan apa adanya, termasuk soal waktu. Dimulai lepas maghrib, "Supermama Seleb Show" mungkin selesai pukul 22.30, namun acap lebih dari 23.30. Ivan bebas mengangkat kaki, bicara sambil nyanyi, berada di lingkaran penonton, bahkan menari dan berlarian di atas panggung. Tak ada yang melarang. Peserta juga tak dikenai aturan. Bedu misalnya, tiba-tiba menghilang ketika aksinya tengah dikomentari Hetty Koes Endang, dan ketika ditangkap kamera, tengah makan nasi bungkus berlauk sate. "Acara kelamaan, gue kelaperan," ucapnya ketika ditegur Eko Patrio. Apakah Eko menariknya ke atas panggung? Tidak. Dia ikut menemani Bedu dan makan bersama. Dan Dorce lalu melompat dari kursinya, menyusul Eko, mengambil sate dan mengunyahnya sambil tidur telungkup di panggung. Ulfa tak mau ketinggalan, dia pun telentang berebutan sate. Ketiganya seperti abai pada acara, ngerumpi rasa sate, dan tersadar ketika diteriaki Ruben untuk meneruskan acara. Penonton tertawa.
Tidak ada yang boleh jaim, jaga image, di acara ini. Maka komentator seperti Tri Utami, atau juga Maia, acap mati gaya, dan tak bisa bicara lama. Ruben terkadang harus bertanya dan bertanya agar Maia bisa bicara panjang dan "membual" sesukanya. Dan tetap gagal. Tri Utami lebih sering tertawa dan kehilangan konsentrasi karena penilaiannya selalu terpotong celotehan Ivan dan Ruben atau tingkah Eko di panggung. Inilah acara yang aksi peserta mungkin hanya 5 menit tapi dikomentari nyaris satu jam! Inilah acara yang setiap peserta harus rela ibunya dipermainkan dijadikan bahan lawakan, ditertawakan. Bedu misalnya, di penampilan awal pernah berkernyit dahi ketika ibunya, Mama Sri, dijadikan bahan lelucon oleh Eko. Namun, ketika nilai ibunya lebih tinggi dan membantunya untuk tetap bertahan, Bedu sepertinya mengikhlaskan keluguan Mama Sri dijadikan bahan tertawaaan.
Cinta tanpa Kalkulasi
Acara yang berisik sepertinya telah jadi magnet baru di televisi. Rating acara super berisik ini ajaibnya justru tinggi sekali. Cikal-bakalnya, barangkali, dimulai oleh "Ceriwis" di TransTV. Duet MC Indi Barens-Indra Bekti jadi warna baru dengan celotehan yang "kacau", penuh hahahihi. Namun, keberisikan itu masih normal dibandingkan "Silat Lidah" Anteve, dan kini "Supermama Seleb Show" Indosiar.
Nah, di tengah magnet berisik itu, TransTV justru menayangkan acara yang tenang, tak memicu konflik, dan naratif. Tayangan non-argumentatif itu diwakili oleh "Atas Nama Cinta" dan "Andai Aku Menjadi...". "Atas Nama Cinta" berisi paparan kisah nyata narasumber tentang cinta yang tak tergadai ketika bencana dan malapetaka datang. Cinta yang tetap tinggal di hati seorang istri ketika suaminya justru tengah menghadapi hukuman mati. Atau cinta istri yang tetap membara meski tubuh suami telah tak sempurna, dirusakkan nyala api. Acara itu dengan lembut menunjukkan manusia yang mencinta tanpa memakai kalkulator, ketika penilaian mata tunduk oleh suara hati. Manusia yang mencinta untuk, mengutip filsuf Gabriel Marcel, "dia yang hadir bagi saya dan kepadanyalah saya setia, kendati kematian telah memisahkan kami".
"Andai Aku Menjadi..." bercerita lebih nyata lagi, tentang kehidupan orang-orang kecil yang selama ini mungkin dipanglingi televisi. Kisah tukang sampah, nelayan, pengangon kambing, pemecah batu, diceritakan dengan wajar, tanpa hiperbola yang berlebihan. Kisah mereka diberi impresi kepada penonton dengan menghadirkan seorang peserta yang bersedia menjalani profesi dan memahami kehidupan mereka. Maka terbentanglah di layar kaca kamar yang sempit tanpa jendela, kasur bertumpuk, dan si nelayan yang berjaga sepanjang malam mengusiri nyamuk dari tubuh mungil anaknya. Atau peserta yang muntah tak tahan bau sampah, menangis karena menyaksikan anak yang merengek minta susu, atau melihat seorang ibu yang tak punya jawaban ketika anaknya meminta uang sekolah. Di layar itu, penonton melihat orang-orang kecil yang menjalani hidup tanpa keluh, yang menjawab kekurangan dengan doa. Manusia-manusia yang berusaha menampik kesulitan namun tak lari ketiga menemukan jalan buntu. Sosok-sosok yang menjalani hidup dengan sikap, seperti kata filsuf Nietzshe, amorfati, menerima apa pun yang diberi nasib dengan sepenuh rasa cinta. Mereka, tidak seperti di "Supermama Seleb Show", sehari-harinya pasti jarang tertawa. Karena tertawa, barangkali, menghapus sebagian tenaga mereka untuk mengais rejeki.
Menasehati Diri
"Supermama Seleb Show" dan "Andai Aku Menjadi" memang dua acara yang berbeda sekali. Namun, persamaan yang cukup kental dalam dua acara itu yakni penilaian komentator pada peserta. Bedanya, di "Supermama" penilaian kepada peserta terjadi hanya berdasarkan pandangan mata terhadap suara, busana, dan cara berkomunikasi. Ivan, Hetty Koes Endang, dan Pongky misalnya, menilai Bedu dengan liar dan bebas. "Kamu cukup jadi pelawak saja," kata Pongky, seakan Bedu memang sungguhan ingin menjadi penyanyi. Atau kritik Ivan yang acap menilai busana para mama dengan sinis, tak modis, kampungan, memberi efek gemuk, atau tabrak warna. Hetty apalagi, selalu memberi contoh dengan nada-nada tinggi, karena itulah cara bernyanyi yang dia sukai. Ketiga komentator itu menjadi pengamat, dan karena itu mereka berjarak dari para peserta. Jarak memang menisbatkan objektivitas. Tapi jarak juga membuat setiap objek pengamatan berada dalam rentang yang tak selalu dikuasai. Jarak juga membuat pengamat menjadi bersandar pada mungkin.
Dalam "Andai Aku Menjadi...", jarak itu yang coba ditampik. Pengamat masuk ke dalam kehidupan objek, merasakan apa pun yang dialami dan dilakukan objek. Anita, penyiar radio, misalnya, ikut masuk lumpur untuk membersihkan empang, memikul air, sampai tidur bersarung di karpet apak, dengan kamar yang tak sepenuhnya terhindar dari angin malam. Ruri, mahasiswi, ikut menjala, berjualan tahu campur, dan merasakan kesakitan seorang suami yang terpaksa membiarkan istrinya terbaring sakit, karena tak mampu mengirim ke rumah sakit. Ruri menjadi "anak" selama dua hari, akhirnya menangis dan menyatakan tak kuat melihat penderitaan tersebut.
Ketakberjarakan inilah yang membuat mereka kemudian sesenggukan ketika bercerita. Anita dan Ruri mengalami kejutan-kejutan batin ketika seluruh indranya merasakan hidup yang selama ini cuma dia lihat dan bayangkan. Anita berkaca-kaca karena tak pernah menyangka ada manusia yang tetap menjadi manusia di tengah segala himpitan yang nyaris tak masuk di akal. Manusia yang berusaha hidup dengan segala kehormatannya. Penilaian "komentator" di "Andai Aku Menjadi..." adalah objektivitas yang "aku alami", sedangkan di "Supermama" adalah penilaian yang "aku amati". Yang hilang di "Supermama" adalah keterlibatan diri, rasa empati dari kesakitan yang sama.
Jika, cara manusia memandang dunia adalah cara dia melihat dirinya sendiri," kata Cristoph Wulf dalam artikelnya "The Temporality of Word-Views and Self-Images", dan cara ia memahami dirinya sendiri adalah cara dia menilai dunia, maka kita jadi tahu "nilai" komentator di atas. Komentator di "Supermama..." sebenarnya mengomentari dan menilai diri mereka sendiri. Yang mereka lihat dari para peserta adalah kenaifan diri mereka sendiri. Dan semua komentar dan nasihat itu sesungguhnya untuk diri mereka sendiri juga. Jadi, wajahlah jika acara itu lucu dan lama sekali. Karena sudah watak manusia, tak pernah puas dan cukup waktu, untuk mematut diri, menjadi narsistik sejati.
[Artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 27 Januari 2008]
 Di "Silat Lidah", komentator bebas bicara apa pun, tanpa basa basi. Tapi, sebebasnya Julia Perez, dia pasti tak akan diperbolehkan bicara sambil makan atau berkumur, atau tidur telentang di atas panggung. "Silat Lidah", bagaimanapun, masih bebas terbatas, bebas terkendali. Itupun telah membuat acara ini berisik sekali. Jadi bayangkanlah betapa riuh dan "berasak"nya "Supermama Seleb Show", ketika semua komentator dan peserta bebas melakukan apa saja.
Di "Silat Lidah", komentator bebas bicara apa pun, tanpa basa basi. Tapi, sebebasnya Julia Perez, dia pasti tak akan diperbolehkan bicara sambil makan atau berkumur, atau tidur telentang di atas panggung. "Silat Lidah", bagaimanapun, masih bebas terbatas, bebas terkendali. Itupun telah membuat acara ini berisik sekali. Jadi bayangkanlah betapa riuh dan "berasak"nya "Supermama Seleb Show", ketika semua komentator dan peserta bebas melakukan apa saja.Ivan Gunawan, komentator tetap di acara itu, misalnya, sering disapa Ruben Onsu dengan panggilan "Banteng", "Sapi", "Banci", sampai "Setengah Lelaki". Dan Ivan, meskipun berpura-pura marah, harus bisa menerima panggilan itu dengan riang, dan membalasnya kemudian. Baku hina antara kedua orang inilah yang selalu tertayang panjang di "Supermama Seleb Show", dan memancing riuh tawa penonton.
Acara itu sepertinya dibebaskan Indosiar berjalan apa adanya, termasuk soal waktu. Dimulai lepas maghrib, "Supermama Seleb Show" mungkin selesai pukul 22.30, namun acap lebih dari 23.30. Ivan bebas mengangkat kaki, bicara sambil nyanyi, berada di lingkaran penonton, bahkan menari dan berlarian di atas panggung. Tak ada yang melarang. Peserta juga tak dikenai aturan. Bedu misalnya, tiba-tiba menghilang ketika aksinya tengah dikomentari Hetty Koes Endang, dan ketika ditangkap kamera, tengah makan nasi bungkus berlauk sate. "Acara kelamaan, gue kelaperan," ucapnya ketika ditegur Eko Patrio. Apakah Eko menariknya ke atas panggung? Tidak. Dia ikut menemani Bedu dan makan bersama. Dan Dorce lalu melompat dari kursinya, menyusul Eko, mengambil sate dan mengunyahnya sambil tidur telungkup di panggung. Ulfa tak mau ketinggalan, dia pun telentang berebutan sate. Ketiganya seperti abai pada acara, ngerumpi rasa sate, dan tersadar ketika diteriaki Ruben untuk meneruskan acara. Penonton tertawa.
Tidak ada yang boleh jaim, jaga image, di acara ini. Maka komentator seperti Tri Utami, atau juga Maia, acap mati gaya, dan tak bisa bicara lama. Ruben terkadang harus bertanya dan bertanya agar Maia bisa bicara panjang dan "membual" sesukanya. Dan tetap gagal. Tri Utami lebih sering tertawa dan kehilangan konsentrasi karena penilaiannya selalu terpotong celotehan Ivan dan Ruben atau tingkah Eko di panggung. Inilah acara yang aksi peserta mungkin hanya 5 menit tapi dikomentari nyaris satu jam! Inilah acara yang setiap peserta harus rela ibunya dipermainkan dijadikan bahan lawakan, ditertawakan. Bedu misalnya, di penampilan awal pernah berkernyit dahi ketika ibunya, Mama Sri, dijadikan bahan lelucon oleh Eko. Namun, ketika nilai ibunya lebih tinggi dan membantunya untuk tetap bertahan, Bedu sepertinya mengikhlaskan keluguan Mama Sri dijadikan bahan tertawaaan.
Cinta tanpa Kalkulasi
Acara yang berisik sepertinya telah jadi magnet baru di televisi. Rating acara super berisik ini ajaibnya justru tinggi sekali. Cikal-bakalnya, barangkali, dimulai oleh "Ceriwis" di TransTV. Duet MC Indi Barens-Indra Bekti jadi warna baru dengan celotehan yang "kacau", penuh hahahihi. Namun, keberisikan itu masih normal dibandingkan "Silat Lidah" Anteve, dan kini "Supermama Seleb Show" Indosiar.
Nah, di tengah magnet berisik itu, TransTV justru menayangkan acara yang tenang, tak memicu konflik, dan naratif. Tayangan non-argumentatif itu diwakili oleh "Atas Nama Cinta" dan "Andai Aku Menjadi...". "Atas Nama Cinta" berisi paparan kisah nyata narasumber tentang cinta yang tak tergadai ketika bencana dan malapetaka datang. Cinta yang tetap tinggal di hati seorang istri ketika suaminya justru tengah menghadapi hukuman mati. Atau cinta istri yang tetap membara meski tubuh suami telah tak sempurna, dirusakkan nyala api. Acara itu dengan lembut menunjukkan manusia yang mencinta tanpa memakai kalkulator, ketika penilaian mata tunduk oleh suara hati. Manusia yang mencinta untuk, mengutip filsuf Gabriel Marcel, "dia yang hadir bagi saya dan kepadanyalah saya setia, kendati kematian telah memisahkan kami".
"Andai Aku Menjadi..." bercerita lebih nyata lagi, tentang kehidupan orang-orang kecil yang selama ini mungkin dipanglingi televisi. Kisah tukang sampah, nelayan, pengangon kambing, pemecah batu, diceritakan dengan wajar, tanpa hiperbola yang berlebihan. Kisah mereka diberi impresi kepada penonton dengan menghadirkan seorang peserta yang bersedia menjalani profesi dan memahami kehidupan mereka. Maka terbentanglah di layar kaca kamar yang sempit tanpa jendela, kasur bertumpuk, dan si nelayan yang berjaga sepanjang malam mengusiri nyamuk dari tubuh mungil anaknya. Atau peserta yang muntah tak tahan bau sampah, menangis karena menyaksikan anak yang merengek minta susu, atau melihat seorang ibu yang tak punya jawaban ketika anaknya meminta uang sekolah. Di layar itu, penonton melihat orang-orang kecil yang menjalani hidup tanpa keluh, yang menjawab kekurangan dengan doa. Manusia-manusia yang berusaha menampik kesulitan namun tak lari ketiga menemukan jalan buntu. Sosok-sosok yang menjalani hidup dengan sikap, seperti kata filsuf Nietzshe, amorfati, menerima apa pun yang diberi nasib dengan sepenuh rasa cinta. Mereka, tidak seperti di "Supermama Seleb Show", sehari-harinya pasti jarang tertawa. Karena tertawa, barangkali, menghapus sebagian tenaga mereka untuk mengais rejeki.
Menasehati Diri
"Supermama Seleb Show" dan "Andai Aku Menjadi" memang dua acara yang berbeda sekali. Namun, persamaan yang cukup kental dalam dua acara itu yakni penilaian komentator pada peserta. Bedanya, di "Supermama" penilaian kepada peserta terjadi hanya berdasarkan pandangan mata terhadap suara, busana, dan cara berkomunikasi. Ivan, Hetty Koes Endang, dan Pongky misalnya, menilai Bedu dengan liar dan bebas. "Kamu cukup jadi pelawak saja," kata Pongky, seakan Bedu memang sungguhan ingin menjadi penyanyi. Atau kritik Ivan yang acap menilai busana para mama dengan sinis, tak modis, kampungan, memberi efek gemuk, atau tabrak warna. Hetty apalagi, selalu memberi contoh dengan nada-nada tinggi, karena itulah cara bernyanyi yang dia sukai. Ketiga komentator itu menjadi pengamat, dan karena itu mereka berjarak dari para peserta. Jarak memang menisbatkan objektivitas. Tapi jarak juga membuat setiap objek pengamatan berada dalam rentang yang tak selalu dikuasai. Jarak juga membuat pengamat menjadi bersandar pada mungkin.
Dalam "Andai Aku Menjadi...", jarak itu yang coba ditampik. Pengamat masuk ke dalam kehidupan objek, merasakan apa pun yang dialami dan dilakukan objek. Anita, penyiar radio, misalnya, ikut masuk lumpur untuk membersihkan empang, memikul air, sampai tidur bersarung di karpet apak, dengan kamar yang tak sepenuhnya terhindar dari angin malam. Ruri, mahasiswi, ikut menjala, berjualan tahu campur, dan merasakan kesakitan seorang suami yang terpaksa membiarkan istrinya terbaring sakit, karena tak mampu mengirim ke rumah sakit. Ruri menjadi "anak" selama dua hari, akhirnya menangis dan menyatakan tak kuat melihat penderitaan tersebut.
Ketakberjarakan inilah yang membuat mereka kemudian sesenggukan ketika bercerita. Anita dan Ruri mengalami kejutan-kejutan batin ketika seluruh indranya merasakan hidup yang selama ini cuma dia lihat dan bayangkan. Anita berkaca-kaca karena tak pernah menyangka ada manusia yang tetap menjadi manusia di tengah segala himpitan yang nyaris tak masuk di akal. Manusia yang berusaha hidup dengan segala kehormatannya. Penilaian "komentator" di "Andai Aku Menjadi..." adalah objektivitas yang "aku alami", sedangkan di "Supermama" adalah penilaian yang "aku amati". Yang hilang di "Supermama" adalah keterlibatan diri, rasa empati dari kesakitan yang sama.
Jika, cara manusia memandang dunia adalah cara dia melihat dirinya sendiri," kata Cristoph Wulf dalam artikelnya "The Temporality of Word-Views and Self-Images", dan cara ia memahami dirinya sendiri adalah cara dia menilai dunia, maka kita jadi tahu "nilai" komentator di atas. Komentator di "Supermama..." sebenarnya mengomentari dan menilai diri mereka sendiri. Yang mereka lihat dari para peserta adalah kenaifan diri mereka sendiri. Dan semua komentar dan nasihat itu sesungguhnya untuk diri mereka sendiri juga. Jadi, wajahlah jika acara itu lucu dan lama sekali. Karena sudah watak manusia, tak pernah puas dan cukup waktu, untuk mematut diri, menjadi narsistik sejati.
[Artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 27 Januari 2008]