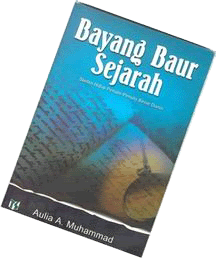...tera di sesela gegas-gesa
Thursday, November 15, 2007
Mereka yang Tumbuh dengan Tergesa
Industri metode perkembangan anak membuat orangtua tak memiliki kesabaran membiarkan anaknya tumbuh secara alamiah.
 "Fahmi, jujur ya, sebenarnya Fahmi mau pilih piala atau harimau?" tanya Marissa Haque.
"Fahmi, jujur ya, sebenarnya Fahmi mau pilih piala atau harimau?" tanya Marissa Haque.
"Sebenarnya sih, Fahmi maunya pilih piala, Bunda. Tapi kata kakak pembina harus pilih harimau. Kalau tidak pilih harimau, katanya Oom kameramen akan kreek!" jelas Fahmi sambil menebaskan tangannya ke leher. Barangkali maksudnya disembelih.
Marissa Haque tertawa. Penonton juga, bergelak. "Inilah anak-anak ya Ibu-Ibu, jujur dan lugu sekali...." Marissa menggelengkan kepalanya.
Saya tidak tertawa melihat kejujuran Fahmi dalam acara "Keluarga Dacil" yang tayang di Lativi, Jumat malam (9/11) itu. Kejujuran Fahmi di atas justru menunjukkan satu ironi bahwa apa yang dia tampilkan dalam tausyiah sebelumnya bukanlah suara hatinya, melainkan "pesanan" dari Kakak Pembina. Sikap moral yang dia sampaikan adalah pilihan yang sebenarnya tidak dia mengerti tapi harus dia katakan. Di pentas Pildacil itu, Fahmi belum memanggungkan dirinya.
Peserta lain, Aufa, menunjukkan ironi yang sama malam itu. Ketika Neno Warisman bertanya, "Buku apa yang harus dipelajari paling utama di muka bumi ini?", dengan enteng dia menjawab, "Buku-buku tentang agama Islam, Bunda."
Neno Warisman terlengak, wajahnya tampak tidak puas dengan jawaban Aufa. "Iya, tapi kalau antara al-Quran dan buku-buku agama Islam, mana yang lebih penting, Aufa?"
Aufa berpikir sebentar. "Mungkin harus kedua-duanya ya, Bunda."
Plass! Senyum di bibir Neno hilang sesaat. Setelah membuang napas, dia pun berkata, "Iya, tapi banyak orang yang salah belajar tentang Islam karena tidak mendahulukan al-Quran, Aufa. Mereka jadi sesat. Jadi al-Quran itu harus yang utama. Aufa mengerti kan?"
Aufa mengangguk. Neno kembali bersandar ke kursi.
Fahmi, Aufa, Ela, dan Kenia yang tampil malam itu, seperti kata Marissa, adalah anak-anak yang masih lugu dan jujur. Tapi lihatlah, bagaimana orang dewasa, para Kakak Pembina mereka, juga para Bunda yang menjadi juri, menganggap "aneh" kejujuran dan keluguan mereka, dan mencoba menarik mereka ke alam pikir orang dewasa.
Sekadar Hapalan
Dari jawaban Fahmi dan Aufa, kita dapat menduga bahwa tausyiah yang mereka sampaikan adalah hasil hapalan semata. Karena hasil hapalan, apa yang mereka sampaikan bukan lahir dari hasil penalaran, proses mengerti dan memahami. Sehingga kenapa harus memilih harimau dan mengapa harus mengutamakan membaca al-Quran, Fahmi dan Aufa tidak mengerti. Bagi mereka itulah yang harus disampaikan untuk dapat merebut simpati penonton. Proses yang tanpa penalaran itu membuat mereka menjawab berbeda dari tausyiah ketika ditanyai oleh para Bunda. Pilihan pribadi berdasarkan "nalar kanak" pun muncul, yang menimbulkan gelak tawa, sekaligus kerisauan, para Bunda.
Dari penampilan Fahmi, Aufa, Ela, dan Kenia, tampak sekali betapa berat mereka mengingat seluruh ajaran "Kakak Pembina". Kesetiaan pada hapalan ini membuat Ela tergeragap, dan Fahmi berberapa kali menjedai tausyiahnya, karena lupa. Pemanggungan itu, dalam arti yang sebenarnya, menjadi siksaan bagi mereka. Anak-anak itu cuma mengerti bahwa kesempurnaan penampilan mereka adalah kesetiaan pada hapalan. Tak ada improvisasi, negosiasi, apalagi imajinasi dari keseluruhan tausyiah yang harus disampaikan. Panggung "Keluarga Dacil" itu, senyatanya bukanlah arena kegembiraan, "ladang" permainan, melainkan sebuah tugas, kancah pertarungan siapa yang paling kuat ingatannya. Padahal, metode hapalan semacam itulah yang justru kelak akan merampas kekuatan kognisi anak-anak ini.
Psikolog perkembangan anak, Kathi Hirsh-Pasek dalam buku Einstein Never Used Flash Cards: How Our Children Really Learn - And Why They Need to Play More and Memorize Less menunjukkan "bahaya" jika anak-anak dipaksa menghapal. "Yang diperlukan bagi perkembangan kognisi anak-anak adalah kesempatan yang luas untuk bermain, bergembira, dan bukan menghapal," katanya. "Bermain akan membangun keahlian intelektual yang kaya, luwes, dan fleksibel, tempat di mana akan tumbuh kemampuan menyelesaikan masalah," tambahnya. "Bermain merupakan unsur penting dalam kemampuan berpikir ilmiah yang produktif," kata si jenius Einstein. Dan, Einstein pun ternyata, tak pernah menghapal.
Lalu apa unsur bermain? Pertama, bermain harus menyenangkan dan bisa dinikmati. Kedua, bermain tidak punya tujuan ekstrinsik. Bermain juga harus spontan, tidak memiliki aturan dan alur, melibatkan imajinasi dan ketakterduggan dalam proses bermain. Dari beberapa unsur itu, pementasan "Keluarga Dacil" dapatlah dilihat tak memenuhi syarat sebagai arena bermain.
Anak sebagai Proyek
Apa yang tampil dalam "Keluarga Dacil" atau "AFI Junior" sebenarnya adalah wujud dari progresivitas orang tua yang ingin "memamerkan anaknya". Progresivitas ini membuat anak-anak mengalami masa kanak denan tergesa-gesa. Tidak ada lagi kesabaran dari orangtua untuk melihat anaknya tumbuh dengan alamiah, belajar sendiri, sebagaimana pertumbuhan bayi sejak ribuan tahun lalu. Industri metode mendidik anak telah mendorong orangtua untuk mendapatkan anak dengan kecerdasan sempurna dan lebih dari anak yang lain. Setiap blue print bagaimana mendidik anak pun dipelajari, dipraktekkan, dengan kegembiraan dan kecemasan yang sama. Efek Mozart, Baby Shakespeare, sampai emotional intelligence untuk bayi, dan puluhan metode lain diikuti, tanpa menyadari semua itu adalah "ilusi" yang dibangun dunia industri. Masa kanak-kanak pun hilang karena program perlombaan kecerdasan dan kesuksesan ini. Anak-anak akhirnya tidak punya dunia sendiri, proyeksi dari harapan dan keinginan orangtua.
Lihatlah keluarga Aufa yang meminta dukungan masyarakat Solok, dan sibuk mendatangi media. Apa sesungguhnya arti popularitas dan kemenangan itu bagi dirinya pribadi? Atau Fahmi, yang mengucapkan "r" pun belum bisa, tentu dia tak mengerti rasa bangga tampil di teve lebih dari yang dialami orangtuanya. Anak-anak ini pun pasti belum tahu bagaimana menggunakan hadiah jika menang, yakni berupa ponsel, simcard, dan voucer Rp 500 ribu. Hadiah yang sungguh tidak ada kaitannya dengan kekanakan mereka. Anak-anak itu pun pasti tak mengerti apa yang dikatakan para Bunda --Marissa, Neno, dan Khofiffah-- yang selalu mengaitkan isi tausyiah mereka dengan pembalakan liar, kekalahan pilkada, korupsi, dan kecurangan para politisi.
Dari situ, kita dapat melihat, sesungguhnya pentas "Keluarga Dacil" dan aneka lomba sejenis itu, adalah panggung para orangtua untuk pamer diri atas pencapaian mereka. Anak-anak itu adalah buktinya. Dalam kasus ini, Kafka pun jadi benar ketika mengatakan, "Memiliki dan mendidik anak dalam dunia sekarang adalah pekerjaan paling mustahil." Mustahil karena anak-anak tidak dididik sebagai anak-anak. Mustahil karena anak-anak adalah pihak yang selalu dipaksa mendengar, diajari menghapal. Mereka adalah kaset yang memutar suara orangtua....
[Artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 18 November 2007]
 "Fahmi, jujur ya, sebenarnya Fahmi mau pilih piala atau harimau?" tanya Marissa Haque.
"Fahmi, jujur ya, sebenarnya Fahmi mau pilih piala atau harimau?" tanya Marissa Haque."Sebenarnya sih, Fahmi maunya pilih piala, Bunda. Tapi kata kakak pembina harus pilih harimau. Kalau tidak pilih harimau, katanya Oom kameramen akan kreek!" jelas Fahmi sambil menebaskan tangannya ke leher. Barangkali maksudnya disembelih.
Marissa Haque tertawa. Penonton juga, bergelak. "Inilah anak-anak ya Ibu-Ibu, jujur dan lugu sekali...." Marissa menggelengkan kepalanya.
Saya tidak tertawa melihat kejujuran Fahmi dalam acara "Keluarga Dacil" yang tayang di Lativi, Jumat malam (9/11) itu. Kejujuran Fahmi di atas justru menunjukkan satu ironi bahwa apa yang dia tampilkan dalam tausyiah sebelumnya bukanlah suara hatinya, melainkan "pesanan" dari Kakak Pembina. Sikap moral yang dia sampaikan adalah pilihan yang sebenarnya tidak dia mengerti tapi harus dia katakan. Di pentas Pildacil itu, Fahmi belum memanggungkan dirinya.
Peserta lain, Aufa, menunjukkan ironi yang sama malam itu. Ketika Neno Warisman bertanya, "Buku apa yang harus dipelajari paling utama di muka bumi ini?", dengan enteng dia menjawab, "Buku-buku tentang agama Islam, Bunda."
Neno Warisman terlengak, wajahnya tampak tidak puas dengan jawaban Aufa. "Iya, tapi kalau antara al-Quran dan buku-buku agama Islam, mana yang lebih penting, Aufa?"
Aufa berpikir sebentar. "Mungkin harus kedua-duanya ya, Bunda."
Plass! Senyum di bibir Neno hilang sesaat. Setelah membuang napas, dia pun berkata, "Iya, tapi banyak orang yang salah belajar tentang Islam karena tidak mendahulukan al-Quran, Aufa. Mereka jadi sesat. Jadi al-Quran itu harus yang utama. Aufa mengerti kan?"
Aufa mengangguk. Neno kembali bersandar ke kursi.
Fahmi, Aufa, Ela, dan Kenia yang tampil malam itu, seperti kata Marissa, adalah anak-anak yang masih lugu dan jujur. Tapi lihatlah, bagaimana orang dewasa, para Kakak Pembina mereka, juga para Bunda yang menjadi juri, menganggap "aneh" kejujuran dan keluguan mereka, dan mencoba menarik mereka ke alam pikir orang dewasa.
Sekadar Hapalan
Dari jawaban Fahmi dan Aufa, kita dapat menduga bahwa tausyiah yang mereka sampaikan adalah hasil hapalan semata. Karena hasil hapalan, apa yang mereka sampaikan bukan lahir dari hasil penalaran, proses mengerti dan memahami. Sehingga kenapa harus memilih harimau dan mengapa harus mengutamakan membaca al-Quran, Fahmi dan Aufa tidak mengerti. Bagi mereka itulah yang harus disampaikan untuk dapat merebut simpati penonton. Proses yang tanpa penalaran itu membuat mereka menjawab berbeda dari tausyiah ketika ditanyai oleh para Bunda. Pilihan pribadi berdasarkan "nalar kanak" pun muncul, yang menimbulkan gelak tawa, sekaligus kerisauan, para Bunda.
Dari penampilan Fahmi, Aufa, Ela, dan Kenia, tampak sekali betapa berat mereka mengingat seluruh ajaran "Kakak Pembina". Kesetiaan pada hapalan ini membuat Ela tergeragap, dan Fahmi berberapa kali menjedai tausyiahnya, karena lupa. Pemanggungan itu, dalam arti yang sebenarnya, menjadi siksaan bagi mereka. Anak-anak itu cuma mengerti bahwa kesempurnaan penampilan mereka adalah kesetiaan pada hapalan. Tak ada improvisasi, negosiasi, apalagi imajinasi dari keseluruhan tausyiah yang harus disampaikan. Panggung "Keluarga Dacil" itu, senyatanya bukanlah arena kegembiraan, "ladang" permainan, melainkan sebuah tugas, kancah pertarungan siapa yang paling kuat ingatannya. Padahal, metode hapalan semacam itulah yang justru kelak akan merampas kekuatan kognisi anak-anak ini.
Psikolog perkembangan anak, Kathi Hirsh-Pasek dalam buku Einstein Never Used Flash Cards: How Our Children Really Learn - And Why They Need to Play More and Memorize Less menunjukkan "bahaya" jika anak-anak dipaksa menghapal. "Yang diperlukan bagi perkembangan kognisi anak-anak adalah kesempatan yang luas untuk bermain, bergembira, dan bukan menghapal," katanya. "Bermain akan membangun keahlian intelektual yang kaya, luwes, dan fleksibel, tempat di mana akan tumbuh kemampuan menyelesaikan masalah," tambahnya. "Bermain merupakan unsur penting dalam kemampuan berpikir ilmiah yang produktif," kata si jenius Einstein. Dan, Einstein pun ternyata, tak pernah menghapal.
Lalu apa unsur bermain? Pertama, bermain harus menyenangkan dan bisa dinikmati. Kedua, bermain tidak punya tujuan ekstrinsik. Bermain juga harus spontan, tidak memiliki aturan dan alur, melibatkan imajinasi dan ketakterduggan dalam proses bermain. Dari beberapa unsur itu, pementasan "Keluarga Dacil" dapatlah dilihat tak memenuhi syarat sebagai arena bermain.
Anak sebagai Proyek
Apa yang tampil dalam "Keluarga Dacil" atau "AFI Junior" sebenarnya adalah wujud dari progresivitas orang tua yang ingin "memamerkan anaknya". Progresivitas ini membuat anak-anak mengalami masa kanak denan tergesa-gesa. Tidak ada lagi kesabaran dari orangtua untuk melihat anaknya tumbuh dengan alamiah, belajar sendiri, sebagaimana pertumbuhan bayi sejak ribuan tahun lalu. Industri metode mendidik anak telah mendorong orangtua untuk mendapatkan anak dengan kecerdasan sempurna dan lebih dari anak yang lain. Setiap blue print bagaimana mendidik anak pun dipelajari, dipraktekkan, dengan kegembiraan dan kecemasan yang sama. Efek Mozart, Baby Shakespeare, sampai emotional intelligence untuk bayi, dan puluhan metode lain diikuti, tanpa menyadari semua itu adalah "ilusi" yang dibangun dunia industri. Masa kanak-kanak pun hilang karena program perlombaan kecerdasan dan kesuksesan ini. Anak-anak akhirnya tidak punya dunia sendiri, proyeksi dari harapan dan keinginan orangtua.
Lihatlah keluarga Aufa yang meminta dukungan masyarakat Solok, dan sibuk mendatangi media. Apa sesungguhnya arti popularitas dan kemenangan itu bagi dirinya pribadi? Atau Fahmi, yang mengucapkan "r" pun belum bisa, tentu dia tak mengerti rasa bangga tampil di teve lebih dari yang dialami orangtuanya. Anak-anak ini pun pasti belum tahu bagaimana menggunakan hadiah jika menang, yakni berupa ponsel, simcard, dan voucer Rp 500 ribu. Hadiah yang sungguh tidak ada kaitannya dengan kekanakan mereka. Anak-anak itu pun pasti tak mengerti apa yang dikatakan para Bunda --Marissa, Neno, dan Khofiffah-- yang selalu mengaitkan isi tausyiah mereka dengan pembalakan liar, kekalahan pilkada, korupsi, dan kecurangan para politisi.
Dari situ, kita dapat melihat, sesungguhnya pentas "Keluarga Dacil" dan aneka lomba sejenis itu, adalah panggung para orangtua untuk pamer diri atas pencapaian mereka. Anak-anak itu adalah buktinya. Dalam kasus ini, Kafka pun jadi benar ketika mengatakan, "Memiliki dan mendidik anak dalam dunia sekarang adalah pekerjaan paling mustahil." Mustahil karena anak-anak tidak dididik sebagai anak-anak. Mustahil karena anak-anak adalah pihak yang selalu dipaksa mendengar, diajari menghapal. Mereka adalah kaset yang memutar suara orangtua....
[Artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 18 November 2007]