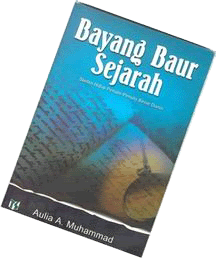...tera di sesela gegas-gesa
Friday, March 17, 2006
Mitos-mitos yang Dilumpuhkan
"KITA percaya, sebagai seorang ibu, Ayu Azhari akan memikirkan yang terbaik untuk anaknya. Ayu pasti telah melihat sosok Mike sebagai ayah yang baik bagi anak-anaknya."

Kalimat di atas dikatakan Fiantika Ambadar, presenter "Silet Spesial" (12/3) sebagai kesimpulan atas kisah asmara Ayu dan Mike "White Lion" Tramp. Dalam tayangan 30 menit itu, dikupas bagaimana masa depan anak-anak Ayu dengan dua suami terdahulu, ketika dia memutuskan akan mengikuti Mike ke Australia. "Ayu pasti telah memikirkan semuanya. Jika akan membawa anak-anak ke sana, dia pasti akan membicarakannya dengan saya," kata Teemu, mantan suami kedua Ayu.
Fiantika, juga Teemu, mengatakan sesuatu yang baik tentang Ayu. Lebih tepatnya, kedua orang ini menguatkan nilai baik pada sosok seorang ibu. Ketika Fiantika berkata, "Kita percaya, sebagai seorang ibu..." kita tahu, yang dia maksudkan adalah Ayu sebagai ibu, bukan Ayu sebagai yang lain. Karena, dalam tayangan "Silet" beberapa bulan lalu, moralitas Ayu dipertanyakan menyangkut kelahiran Isabel yang, sepertinya, tanpa didahulu pernikahan. Satu sosok yang sama, di mata "Silet", ternyata punya moralitas yang berbeda.
Kasus Zarima bisa lebih menerangkan dualitas ini. Dua bulan lalu, dia bagai singa terluka saat berikrar akan merebut hak asuh anaknya. "Saya ibunya. Tidak ada pun seorang ibu yang rela dipisahkan dari anaknya," ucapnya. Tapi, awal Maret ini, sosok yang sama justru diadukan ke polisi karena melakukan aborsi, yang juga melibatkan ibu Zarima, sebagai penjamin aborsi itu. Tak ada lagi kalimat, "Sebagai seorang ibu..." dari bibir tipis wanita seksi itu. Dia hanya menebar senyum, usaha paling maksimal untuk menutupi kegundahan hatinya.
Genggam Mitos
Menggenggam mitos. Itulah yang dilakukan oleh Ayu dan Zarima dalam kasus di atas. Tentu, mitos yang mereka genggam adalah mitos kebaikan, mitos seorang ibu. Dan cara ini bukan sesuatu yang baru. Nyaris semua artis pernah melakukan hal ini, menyandarkan diri pada sosok yang telah menjadi mitos (cerita) kebaikan. Sosok ibu hanya satu contoh, dan anehnya, citraan ibu ini pula yang paling sering digenggam. Fatma Farida, ibu Kiki Fatmala, pernah "memainkan" mitos itu dengan demikian baiknya. Dia tunjukkan bagaimana sebagai seorang ibu dia dilukai anaknya. "Sampai hati dia melakukan ini, pada ibunya sendiri... Anak durhaka..." Dia mengambil mitos ibu untuk menunjukkan bagaimana kesakitan dirinya pribadi agar dapat juga dipahami oleh orang lain, dan menjadi kesakitan bersama. Ini karena nilai mitos ibu, diyakini dan dijaga, serta terus dihidupkan oleh orang banyak. Karena itulah, mitos ini "wajib" digengam karena dia memiliki kekuatan untuk diyakini banyak pihak. "Kita percaya..." kata Fiantika Ambadar.
Penggenggaman mitos ini tidak hanya dilakukan artis, tapi juga tayangan teve lain. Sinetron Ramadan jelas tayangan yang paling suka berjalan di atas mitos-mitos itu. Sinetron religius-mistik yang sampai kini masih membanjiri tayangan malam, juga mengukuhi mitos ini, dan menguatkannya dengan "ancaman" bagi pelanggar mitos. Wawancara dan profil artis, juga banyak bersandar dari mitos, mulai dari kerja keras, keyakinan, doa, dan kekuatan mengalami penderitaan.
Kenapa menggenggam mitos itu penting? Banyak alasan yang dapat diungkapkan, meski dua faktor berikut sudah sangat mewakili. Pertama, mitos merupakan statement of fact. Mitos bukan hanya cerita, pernyataan, pesan, tapi sudah menjadi bukti bahwa konsep itu faktual. Nyata dan benar. Sebagai fakta, mitos tidak hanya benar dan menyakinkan, melainkan juga abadi. Mitos kasih seorang ibu barangkali contoh yang paling tepat tentang keabadian kebenaran itu. Dengan menjadi fakta, sebuah mitos tak lagi bisa diganggu-gugat. Terima, habis perkara!
Kedua, mitos itu motivasional. Selain tak dapat diganggu-gugat, mitos juga memotiasi orang untuk melakukan hal sama. Dalam hal ini, mitos berubah menjadi perintah, memerintah untuk diikuti, untuk di-alami. Ketika Fatma Farida mengatakan, "Sakit hati saya, ibu mana yang tidak sakit kalau..." otomatis telah terjadi loncatan perintah pada khalayak untuk ikut merasakan sakitnya.

Dengan dua ciri itu saja, sudah dapat dibayangkan betapa pentingnya mitos digenggam dan dikeluarkan di saat yang tepat, sebagai senjata untuk dapat dipahami dan dibenarkan tindakannya. Masalahnya kemudian adalah, berapa lama mitos itu dapat bertahan?
Siapa Kita?
Sebagai statement of fact, mitos memang tidak lagi dapat diganggu-gugat. Dia kuat, tak terbantahkan. Sayangnya, penggenggam-penggenggam mitos ini tidak mampu memainkan mitos itu selalu dalam situasi yang selalu tepat. Meski kuat, mitos memiliki kontradiksi dalam dirinya sendiri. Kasus Zarima dan Fatma Farida menunjukkan hal ini. Dengan mengenggam mitos seorang ibu, Fatma memang berhasil meraih simpati sebagai sang korban. Tapi, ketika "eksplorasi" kesakitan itu menjadi demikian mengerikannya, mitos tadi kehilangan daya motivasinya. Ada batas sebuah mitos, ketika dia digerakkan sebagai kebencian. Ketika Fatma mulai menyumpahi Kiki sebagai anak durhaka, dan "Jika mati, aku haramkan dia melihatku..." mitos ibu yang dia genggam, runtuh. Fatma telah melumpuhkan mitos ibu dengan kontradiksi dalam dirinya sendiri. Dia telah melepaskan genggamannya, karena ibu yang "menyakiti anaknya", "ibu yang suka menyumpah" dan "ibu yang berbicara dalam marah dan dengki" bukan merupakan statement of fact. Zarima, juga artis-artis lain, pun acap menggenggam mitos ibu dalam perebutan hal asuh anaknya. Tapi ketika Zarima tersangkut aborsi, ketika Reza meninggalkan anaknya untuk "pesiar" di Bali bersama Ary Suta, mitos itu lumpuh. Karena aborsi dan sosok ibu yang mementingkan diri sendiri, sosok ibu yang "selingkuh" bukan merupakan statement of fact dari mitos itu.
Pelumpuhan mitos semacam di atas telah lama berlangsung. Akibatnya, sesuatu yang semula bukan bagian dari statement of fact justru mengubah dirinya menjadi bagian dari yang tak dapat diganggu-gugat tadi. Mitos menciptakan anti-mitos. Dan kini, antimitos ini, telah menjadi mitos tersendiri.
Ketika Fiantika Ambadar berkata, "Kita percaya, sebagai seorang ibu...", pertanyaannya adalah, "Siapakah kita? Siapakah yang kita percaya?" Apakah kita percayai Ayu, Zarima, Fatma Farida yang memang seorang ibu, yang tahu bagaimana menggemggam mitos itu --sekaligus melumpuhkannya? Rasanya tidak. Karena dalam satu hari saja, kita dapat melihat di "TKP", Buser", "Patroli", "Lacak", "Jejak Kasus" dan "Sergap" bagaimana mitos-mitos ini dilumpuhkan dengan ringannya. Kita melihat ibu yang melacurkan anaknya, ibu yang menjual bayinya, ibu yang selingkuh! Bapak yang memperkosa anaknya, bapak yang menjual anaknya, Bapak yang memiliki cucu dari anak kandungnya! Kita "seperti" telah kehilangan mitos itu.
Maka, ketika Fiantika Ambadar berkata, "Kita percaya, sebagai seorang ibu..." Marilah kita percaya, bahwa mitos itu benar dalam dirinya sendiri, ketika sosok ibu hanya bernama IBU, dan belum berlabel Ayu, Zarima, atau Fatma Farida, atau nama-nama lainnya.
[Artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 19 Maret 2006]
( t.i.l.i.k ! )

Kalimat di atas dikatakan Fiantika Ambadar, presenter "Silet Spesial" (12/3) sebagai kesimpulan atas kisah asmara Ayu dan Mike "White Lion" Tramp. Dalam tayangan 30 menit itu, dikupas bagaimana masa depan anak-anak Ayu dengan dua suami terdahulu, ketika dia memutuskan akan mengikuti Mike ke Australia. "Ayu pasti telah memikirkan semuanya. Jika akan membawa anak-anak ke sana, dia pasti akan membicarakannya dengan saya," kata Teemu, mantan suami kedua Ayu.
Fiantika, juga Teemu, mengatakan sesuatu yang baik tentang Ayu. Lebih tepatnya, kedua orang ini menguatkan nilai baik pada sosok seorang ibu. Ketika Fiantika berkata, "Kita percaya, sebagai seorang ibu..." kita tahu, yang dia maksudkan adalah Ayu sebagai ibu, bukan Ayu sebagai yang lain. Karena, dalam tayangan "Silet" beberapa bulan lalu, moralitas Ayu dipertanyakan menyangkut kelahiran Isabel yang, sepertinya, tanpa didahulu pernikahan. Satu sosok yang sama, di mata "Silet", ternyata punya moralitas yang berbeda.
Kasus Zarima bisa lebih menerangkan dualitas ini. Dua bulan lalu, dia bagai singa terluka saat berikrar akan merebut hak asuh anaknya. "Saya ibunya. Tidak ada pun seorang ibu yang rela dipisahkan dari anaknya," ucapnya. Tapi, awal Maret ini, sosok yang sama justru diadukan ke polisi karena melakukan aborsi, yang juga melibatkan ibu Zarima, sebagai penjamin aborsi itu. Tak ada lagi kalimat, "Sebagai seorang ibu..." dari bibir tipis wanita seksi itu. Dia hanya menebar senyum, usaha paling maksimal untuk menutupi kegundahan hatinya.
Genggam Mitos
Menggenggam mitos. Itulah yang dilakukan oleh Ayu dan Zarima dalam kasus di atas. Tentu, mitos yang mereka genggam adalah mitos kebaikan, mitos seorang ibu. Dan cara ini bukan sesuatu yang baru. Nyaris semua artis pernah melakukan hal ini, menyandarkan diri pada sosok yang telah menjadi mitos (cerita) kebaikan. Sosok ibu hanya satu contoh, dan anehnya, citraan ibu ini pula yang paling sering digenggam. Fatma Farida, ibu Kiki Fatmala, pernah "memainkan" mitos itu dengan demikian baiknya. Dia tunjukkan bagaimana sebagai seorang ibu dia dilukai anaknya. "Sampai hati dia melakukan ini, pada ibunya sendiri... Anak durhaka..." Dia mengambil mitos ibu untuk menunjukkan bagaimana kesakitan dirinya pribadi agar dapat juga dipahami oleh orang lain, dan menjadi kesakitan bersama. Ini karena nilai mitos ibu, diyakini dan dijaga, serta terus dihidupkan oleh orang banyak. Karena itulah, mitos ini "wajib" digengam karena dia memiliki kekuatan untuk diyakini banyak pihak. "Kita percaya..." kata Fiantika Ambadar.
Penggenggaman mitos ini tidak hanya dilakukan artis, tapi juga tayangan teve lain. Sinetron Ramadan jelas tayangan yang paling suka berjalan di atas mitos-mitos itu. Sinetron religius-mistik yang sampai kini masih membanjiri tayangan malam, juga mengukuhi mitos ini, dan menguatkannya dengan "ancaman" bagi pelanggar mitos. Wawancara dan profil artis, juga banyak bersandar dari mitos, mulai dari kerja keras, keyakinan, doa, dan kekuatan mengalami penderitaan.
Kenapa menggenggam mitos itu penting? Banyak alasan yang dapat diungkapkan, meski dua faktor berikut sudah sangat mewakili. Pertama, mitos merupakan statement of fact. Mitos bukan hanya cerita, pernyataan, pesan, tapi sudah menjadi bukti bahwa konsep itu faktual. Nyata dan benar. Sebagai fakta, mitos tidak hanya benar dan menyakinkan, melainkan juga abadi. Mitos kasih seorang ibu barangkali contoh yang paling tepat tentang keabadian kebenaran itu. Dengan menjadi fakta, sebuah mitos tak lagi bisa diganggu-gugat. Terima, habis perkara!
Kedua, mitos itu motivasional. Selain tak dapat diganggu-gugat, mitos juga memotiasi orang untuk melakukan hal sama. Dalam hal ini, mitos berubah menjadi perintah, memerintah untuk diikuti, untuk di-alami. Ketika Fatma Farida mengatakan, "Sakit hati saya, ibu mana yang tidak sakit kalau..." otomatis telah terjadi loncatan perintah pada khalayak untuk ikut merasakan sakitnya.

Dengan dua ciri itu saja, sudah dapat dibayangkan betapa pentingnya mitos digenggam dan dikeluarkan di saat yang tepat, sebagai senjata untuk dapat dipahami dan dibenarkan tindakannya. Masalahnya kemudian adalah, berapa lama mitos itu dapat bertahan?
Siapa Kita?
Sebagai statement of fact, mitos memang tidak lagi dapat diganggu-gugat. Dia kuat, tak terbantahkan. Sayangnya, penggenggam-penggenggam mitos ini tidak mampu memainkan mitos itu selalu dalam situasi yang selalu tepat. Meski kuat, mitos memiliki kontradiksi dalam dirinya sendiri. Kasus Zarima dan Fatma Farida menunjukkan hal ini. Dengan mengenggam mitos seorang ibu, Fatma memang berhasil meraih simpati sebagai sang korban. Tapi, ketika "eksplorasi" kesakitan itu menjadi demikian mengerikannya, mitos tadi kehilangan daya motivasinya. Ada batas sebuah mitos, ketika dia digerakkan sebagai kebencian. Ketika Fatma mulai menyumpahi Kiki sebagai anak durhaka, dan "Jika mati, aku haramkan dia melihatku..." mitos ibu yang dia genggam, runtuh. Fatma telah melumpuhkan mitos ibu dengan kontradiksi dalam dirinya sendiri. Dia telah melepaskan genggamannya, karena ibu yang "menyakiti anaknya", "ibu yang suka menyumpah" dan "ibu yang berbicara dalam marah dan dengki" bukan merupakan statement of fact. Zarima, juga artis-artis lain, pun acap menggenggam mitos ibu dalam perebutan hal asuh anaknya. Tapi ketika Zarima tersangkut aborsi, ketika Reza meninggalkan anaknya untuk "pesiar" di Bali bersama Ary Suta, mitos itu lumpuh. Karena aborsi dan sosok ibu yang mementingkan diri sendiri, sosok ibu yang "selingkuh" bukan merupakan statement of fact dari mitos itu.
Pelumpuhan mitos semacam di atas telah lama berlangsung. Akibatnya, sesuatu yang semula bukan bagian dari statement of fact justru mengubah dirinya menjadi bagian dari yang tak dapat diganggu-gugat tadi. Mitos menciptakan anti-mitos. Dan kini, antimitos ini, telah menjadi mitos tersendiri.
Ketika Fiantika Ambadar berkata, "Kita percaya, sebagai seorang ibu...", pertanyaannya adalah, "Siapakah kita? Siapakah yang kita percaya?" Apakah kita percayai Ayu, Zarima, Fatma Farida yang memang seorang ibu, yang tahu bagaimana menggemggam mitos itu --sekaligus melumpuhkannya? Rasanya tidak. Karena dalam satu hari saja, kita dapat melihat di "TKP", Buser", "Patroli", "Lacak", "Jejak Kasus" dan "Sergap" bagaimana mitos-mitos ini dilumpuhkan dengan ringannya. Kita melihat ibu yang melacurkan anaknya, ibu yang menjual bayinya, ibu yang selingkuh! Bapak yang memperkosa anaknya, bapak yang menjual anaknya, Bapak yang memiliki cucu dari anak kandungnya! Kita "seperti" telah kehilangan mitos itu.
Maka, ketika Fiantika Ambadar berkata, "Kita percaya, sebagai seorang ibu..." Marilah kita percaya, bahwa mitos itu benar dalam dirinya sendiri, ketika sosok ibu hanya bernama IBU, dan belum berlabel Ayu, Zarima, atau Fatma Farida, atau nama-nama lainnya.
[Artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 19 Maret 2006]
( t.i.l.i.k ! )
Thursday, March 02, 2006
Iman di dalam Keluarga Tak Sempurna
"YA ALLAH, di manakah Ibu Kipli. Kipli Kangen. Kipli ingin Ibu. Jika Ibu Kipli masih hidup, kembalikanlah kepada Kipli ya Allah... Kipli kangen Ibu."
 Doa Kipli itu barangkali salah satu adegan yang paling mengharukan dalam sinetron "Kiamat Sudah Dekat". Doa ajaran Haji Romli, yang dilapalkan Kipli dengan bibir dower bergetar dan air mata, secara khusus menegaskan faktor ketiadaan orang tua di dalam sinetron itu. Bahkan, keseluruhan cerita di dalam sinetron itu justru dibangun oleh ketegangan di dalam keluarga yang tak sempurna: Saprol tak berayah, Kipli dan Sarah yang tanpa ibu. Di sisi lain, secara alamiah disandingkan Fandi, yang memiliki keluarga sempurna, berayah-ibu, ditambah seorang adik yang cukup jelita, dan ingat, kekayaan yang luar biasa. Dan dari perbandingan inilah kemudian lahir cerita.
Doa Kipli itu barangkali salah satu adegan yang paling mengharukan dalam sinetron "Kiamat Sudah Dekat". Doa ajaran Haji Romli, yang dilapalkan Kipli dengan bibir dower bergetar dan air mata, secara khusus menegaskan faktor ketiadaan orang tua di dalam sinetron itu. Bahkan, keseluruhan cerita di dalam sinetron itu justru dibangun oleh ketegangan di dalam keluarga yang tak sempurna: Saprol tak berayah, Kipli dan Sarah yang tanpa ibu. Di sisi lain, secara alamiah disandingkan Fandi, yang memiliki keluarga sempurna, berayah-ibu, ditambah seorang adik yang cukup jelita, dan ingat, kekayaan yang luar biasa. Dan dari perbandingan inilah kemudian lahir cerita.
Secara samar, sinetron ini sebenarnya menunjukkan kontras keimanan di dalam dua tipe keluarga, yang sempurna dan tidak. Fandi yang tak kekurangan apa pun di dalam hidupnya, awalnya tak memiliki keyakinan akan Tuhan. Salat pun dia tidak mengerti. Sementara Saprol, Kipli, dan Sarah, yang tumbuh di dalam keluarga tak sempurna, justru berada dalam balutan iman. Hidup mereka jalani dengan sabar dan istigfar. Dan kepada merekalah, Fandi berlabuh, mencari dan menumbuhkan iman di dalam dirinya, yang kemudian dia tularkan kepada keluarga dan temannya.
Keimanan di dalam keluarga yang tak sempurna? Ya. Cara tutur semacam ini memang bukan hal baru di dalam sinetron Indonesia. Keyatiman, atau kepiatuan, di dalam televisi, memang selalu didekatkan dengan keimanan. Meski dengan penceritaan yang tidak semanis "Kiamat Sudah Dekat", sinetron-sinetron Ramadan telah lama mengadopsi gaya seperti itu. Sinetron "Hikmah" misalnya, menggambarkan Ana (Tamara Bleszynksi)yang hanya beribu tiri, tapi hidup penuh syukur dan tafakkur. Sosok gadis yatim-piatu dan miskin yang selalu diperankan Krisdayanti, "Adam dan Hawa" yang dimainkan Syahrul dan Marshanda, juga menegaskan style ini.
Ada apa dengan keluarga yang sempurna? Mengapa kesempurnaan keluarga telah kehilangan pesona?
Tuturan Baru
 Film Ada Apa dengan Cinta? barangkali dapat dilihat sebagai pijakan awal pemihakan pada keluarga yang tak sempurna. Di film ini, sosok Alya (Ladya Cheryl) hidup dalam tekanan kekerasan rumah tangga. Ayahnya, tiap bertengkar, selalu memukul ibu, dan terkadang, dirinya. Tekanan ini pada puncaknya membuat Alya ingin bunuh diri. Alya terselamatkan. Dan untuk mengakhiri tekanan itu, ibu Alya memilih bercerai.
Film Ada Apa dengan Cinta? barangkali dapat dilihat sebagai pijakan awal pemihakan pada keluarga yang tak sempurna. Di film ini, sosok Alya (Ladya Cheryl) hidup dalam tekanan kekerasan rumah tangga. Ayahnya, tiap bertengkar, selalu memukul ibu, dan terkadang, dirinya. Tekanan ini pada puncaknya membuat Alya ingin bunuh diri. Alya terselamatkan. Dan untuk mengakhiri tekanan itu, ibu Alya memilih bercerai.
Perceraian sebagai jalan keluar. Itu cara tutur yang langka dalam film dan sinetron kita. Acap kali, untuk keutuhan keluarga, konflik pasti dapat dikelarkan. Ayah atau ibu bertobat. Harmoni terjaga. AADC? menihilkan kemungkinan itu.
Kritikus film Eric Sasono mencatat pengedepanan keluarga yang tak sempurna (single parent) menjadi tren baru dalam sinema. Setelah AADC?, Pasir Berbisik dan Eliana-Eliana pun menuturkan hal yang sama, tentang single parent. Bahkan Banyu Biru dan Brownis masih juga memakai pola ini. Ketiadaan salah satu orang tua menjadi sumber konflik di satu sisi, dan di sisi lain mendekatkan. Daya dalam Pasir berbisik dan Eliana dalam Eliana-Eliana memang mempertanyakan sosok ayah dan berontak dari kukungan ibu. Tapi, apa pun bentuknya, cerita kemudian menjadikan ketaksempurnaan itu diterima dengan kesadaran.
Nah, dalam sinetron, konflik tentang single parent ini justru tidak lahir dengan pertanyaan atas ketaksempurnaan itu. Dalam sinetron Ramadan misalnya, konflik lahir dari hubungan antara keluarga yang tak sempurna dengan keluarga sempurna, dan pasti berkait dengan cinta dan harta. Nyaris tak ada ruang untuk mempertanyakan ketaksempurnaan itu. Ana yang yatim tak meminta diceritakan, bahkan tak merasakan "apa pun" atas keyatiman itu. Annisa (Krisdayanti) pun tak pernah goyah "identitas" atas keyatiman atau kepiatuannya. Adam dan Hawa malah melenggang, "kekurangan" sebagai anak yang tak berayah atau ibu tak tampil atau tak mendapat porsi dalam cerita. Konflik batin bukan lahir dari pertanyaan atas identitas diri, melainkan konflik yang selalu mengerucut pada cinta. Dalam Kiamat Sudah Dekat pun ketaksempurnaan itu semula tidak mendapat porsi besar. Setelah "cerita utama" tentang cinta Fandi-Sarah selesai, barulah pertanyaan tentang ibu oleh Kipli mengemuka. Pertanyaan Saprol tentang ayahnya pun lahir kemudian, ketika ibunya akan dinikahi Haji Romli. Dan, ini yang menarik, pertanyaan itu hanya berupa keingintahuan belaka --ibu di mana, bapak di mana-- tidak sampai merasuk pada krisis konflik diri. Atau mungkin karena Kipli dan Saprol masih anak-anak? Jelas tidak, karena Sarah yang sudah dewasa pun tidak mengalami hal itu. Artinya, ketaksempurnaan keluarga di dalam sinetron sudah jadi begitu saja, diterima, dijalani, habis perkara. Seakan, sekali lagi, seakan, keluarga single parent adalah hal yang biasa, lumrah, wajar, dan tak perlu lagi dipersoalkan.
Gerusan Idealisasi
 Apakah keluarga yang sempurna memang telah kehilangan pesona? Jelas tidak. Sinetron dan film di atas hanya mencoba menggambarkan "arus besar" penerimaan pada hal itu. Artinya, sebagai cerminan realitas sosial, sinetron semacam itu menunjukkan pergeseran pandang tentang keluarga. Ideologisasi Orde baru tentang keluarga sempurna yang bahagia --ayah, ibu, dua anak lelaki dan perempuan, (diwakili keluarga Fandi) telah runtuh. Ideologisasi itu memang masih terjaga dalam bentuk fisik, tapi mengalami pengerdilan makna, seperti keluarga Fandi yang kehilangan pegangan hidup: raibnya cahaya iman. Pengikisan ideologi ini diperparah dengan penggambaran keluarga utuh yang tidak bahagia. Kasus perceraian, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, yang acap tayang di infotainmen, lalu juga sinetron, makin menggerus. Apalagi, citra single parent seperti yang tampil dalam diri Tety Liz, ibu dari Marcella Zalianty, sangat mengena. Atau seperti kiprah Kanaya Tabitha.
Apakah keluarga yang sempurna memang telah kehilangan pesona? Jelas tidak. Sinetron dan film di atas hanya mencoba menggambarkan "arus besar" penerimaan pada hal itu. Artinya, sebagai cerminan realitas sosial, sinetron semacam itu menunjukkan pergeseran pandang tentang keluarga. Ideologisasi Orde baru tentang keluarga sempurna yang bahagia --ayah, ibu, dua anak lelaki dan perempuan, (diwakili keluarga Fandi) telah runtuh. Ideologisasi itu memang masih terjaga dalam bentuk fisik, tapi mengalami pengerdilan makna, seperti keluarga Fandi yang kehilangan pegangan hidup: raibnya cahaya iman. Pengikisan ideologi ini diperparah dengan penggambaran keluarga utuh yang tidak bahagia. Kasus perceraian, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, yang acap tayang di infotainmen, lalu juga sinetron, makin menggerus. Apalagi, citra single parent seperti yang tampil dalam diri Tety Liz, ibu dari Marcella Zalianty, sangat mengena. Atau seperti kiprah Kanaya Tabitha.
Namun, penggerusan terkuat idealisasi keluarga sempurna itu datang seperti dalam doa Kipli di atas: pengakuan kepada kekuasaan Tuhan. Pergi dan hilangnya seorang ibu atau ayah, adalah bagian dari rencana-Nya. Kesempurnaan atau ketaksempurnaan keluarga bukan rencana manusia, tapi pemberian dan karunia-Nya. Karena sesempurnanya keluarga bukan terletak pada sosok ayah dan ibu, anak lelaki atau perempuan, juga harta kekayaan, melainkan hadirnya cahaya keimanan. Keimananlah yang menjadikan sebuah keluarga sempurna, bagaimanapun kondisinya. Dan sinetron "Kiamat Sudah Dekat" menunjukkan dengan manis hal itu.
[Artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 6 Maret 2006]
( t.i.l.i.k ! )
 Doa Kipli itu barangkali salah satu adegan yang paling mengharukan dalam sinetron "Kiamat Sudah Dekat". Doa ajaran Haji Romli, yang dilapalkan Kipli dengan bibir dower bergetar dan air mata, secara khusus menegaskan faktor ketiadaan orang tua di dalam sinetron itu. Bahkan, keseluruhan cerita di dalam sinetron itu justru dibangun oleh ketegangan di dalam keluarga yang tak sempurna: Saprol tak berayah, Kipli dan Sarah yang tanpa ibu. Di sisi lain, secara alamiah disandingkan Fandi, yang memiliki keluarga sempurna, berayah-ibu, ditambah seorang adik yang cukup jelita, dan ingat, kekayaan yang luar biasa. Dan dari perbandingan inilah kemudian lahir cerita.
Doa Kipli itu barangkali salah satu adegan yang paling mengharukan dalam sinetron "Kiamat Sudah Dekat". Doa ajaran Haji Romli, yang dilapalkan Kipli dengan bibir dower bergetar dan air mata, secara khusus menegaskan faktor ketiadaan orang tua di dalam sinetron itu. Bahkan, keseluruhan cerita di dalam sinetron itu justru dibangun oleh ketegangan di dalam keluarga yang tak sempurna: Saprol tak berayah, Kipli dan Sarah yang tanpa ibu. Di sisi lain, secara alamiah disandingkan Fandi, yang memiliki keluarga sempurna, berayah-ibu, ditambah seorang adik yang cukup jelita, dan ingat, kekayaan yang luar biasa. Dan dari perbandingan inilah kemudian lahir cerita.Secara samar, sinetron ini sebenarnya menunjukkan kontras keimanan di dalam dua tipe keluarga, yang sempurna dan tidak. Fandi yang tak kekurangan apa pun di dalam hidupnya, awalnya tak memiliki keyakinan akan Tuhan. Salat pun dia tidak mengerti. Sementara Saprol, Kipli, dan Sarah, yang tumbuh di dalam keluarga tak sempurna, justru berada dalam balutan iman. Hidup mereka jalani dengan sabar dan istigfar. Dan kepada merekalah, Fandi berlabuh, mencari dan menumbuhkan iman di dalam dirinya, yang kemudian dia tularkan kepada keluarga dan temannya.
Keimanan di dalam keluarga yang tak sempurna? Ya. Cara tutur semacam ini memang bukan hal baru di dalam sinetron Indonesia. Keyatiman, atau kepiatuan, di dalam televisi, memang selalu didekatkan dengan keimanan. Meski dengan penceritaan yang tidak semanis "Kiamat Sudah Dekat", sinetron-sinetron Ramadan telah lama mengadopsi gaya seperti itu. Sinetron "Hikmah" misalnya, menggambarkan Ana (Tamara Bleszynksi)yang hanya beribu tiri, tapi hidup penuh syukur dan tafakkur. Sosok gadis yatim-piatu dan miskin yang selalu diperankan Krisdayanti, "Adam dan Hawa" yang dimainkan Syahrul dan Marshanda, juga menegaskan style ini.
Ada apa dengan keluarga yang sempurna? Mengapa kesempurnaan keluarga telah kehilangan pesona?
Tuturan Baru
 Film Ada Apa dengan Cinta? barangkali dapat dilihat sebagai pijakan awal pemihakan pada keluarga yang tak sempurna. Di film ini, sosok Alya (Ladya Cheryl) hidup dalam tekanan kekerasan rumah tangga. Ayahnya, tiap bertengkar, selalu memukul ibu, dan terkadang, dirinya. Tekanan ini pada puncaknya membuat Alya ingin bunuh diri. Alya terselamatkan. Dan untuk mengakhiri tekanan itu, ibu Alya memilih bercerai.
Film Ada Apa dengan Cinta? barangkali dapat dilihat sebagai pijakan awal pemihakan pada keluarga yang tak sempurna. Di film ini, sosok Alya (Ladya Cheryl) hidup dalam tekanan kekerasan rumah tangga. Ayahnya, tiap bertengkar, selalu memukul ibu, dan terkadang, dirinya. Tekanan ini pada puncaknya membuat Alya ingin bunuh diri. Alya terselamatkan. Dan untuk mengakhiri tekanan itu, ibu Alya memilih bercerai.Perceraian sebagai jalan keluar. Itu cara tutur yang langka dalam film dan sinetron kita. Acap kali, untuk keutuhan keluarga, konflik pasti dapat dikelarkan. Ayah atau ibu bertobat. Harmoni terjaga. AADC? menihilkan kemungkinan itu.
Kritikus film Eric Sasono mencatat pengedepanan keluarga yang tak sempurna (single parent) menjadi tren baru dalam sinema. Setelah AADC?, Pasir Berbisik dan Eliana-Eliana pun menuturkan hal yang sama, tentang single parent. Bahkan Banyu Biru dan Brownis masih juga memakai pola ini. Ketiadaan salah satu orang tua menjadi sumber konflik di satu sisi, dan di sisi lain mendekatkan. Daya dalam Pasir berbisik dan Eliana dalam Eliana-Eliana memang mempertanyakan sosok ayah dan berontak dari kukungan ibu. Tapi, apa pun bentuknya, cerita kemudian menjadikan ketaksempurnaan itu diterima dengan kesadaran.
Nah, dalam sinetron, konflik tentang single parent ini justru tidak lahir dengan pertanyaan atas ketaksempurnaan itu. Dalam sinetron Ramadan misalnya, konflik lahir dari hubungan antara keluarga yang tak sempurna dengan keluarga sempurna, dan pasti berkait dengan cinta dan harta. Nyaris tak ada ruang untuk mempertanyakan ketaksempurnaan itu. Ana yang yatim tak meminta diceritakan, bahkan tak merasakan "apa pun" atas keyatiman itu. Annisa (Krisdayanti) pun tak pernah goyah "identitas" atas keyatiman atau kepiatuannya. Adam dan Hawa malah melenggang, "kekurangan" sebagai anak yang tak berayah atau ibu tak tampil atau tak mendapat porsi dalam cerita. Konflik batin bukan lahir dari pertanyaan atas identitas diri, melainkan konflik yang selalu mengerucut pada cinta. Dalam Kiamat Sudah Dekat pun ketaksempurnaan itu semula tidak mendapat porsi besar. Setelah "cerita utama" tentang cinta Fandi-Sarah selesai, barulah pertanyaan tentang ibu oleh Kipli mengemuka. Pertanyaan Saprol tentang ayahnya pun lahir kemudian, ketika ibunya akan dinikahi Haji Romli. Dan, ini yang menarik, pertanyaan itu hanya berupa keingintahuan belaka --ibu di mana, bapak di mana-- tidak sampai merasuk pada krisis konflik diri. Atau mungkin karena Kipli dan Saprol masih anak-anak? Jelas tidak, karena Sarah yang sudah dewasa pun tidak mengalami hal itu. Artinya, ketaksempurnaan keluarga di dalam sinetron sudah jadi begitu saja, diterima, dijalani, habis perkara. Seakan, sekali lagi, seakan, keluarga single parent adalah hal yang biasa, lumrah, wajar, dan tak perlu lagi dipersoalkan.
Gerusan Idealisasi
 Apakah keluarga yang sempurna memang telah kehilangan pesona? Jelas tidak. Sinetron dan film di atas hanya mencoba menggambarkan "arus besar" penerimaan pada hal itu. Artinya, sebagai cerminan realitas sosial, sinetron semacam itu menunjukkan pergeseran pandang tentang keluarga. Ideologisasi Orde baru tentang keluarga sempurna yang bahagia --ayah, ibu, dua anak lelaki dan perempuan, (diwakili keluarga Fandi) telah runtuh. Ideologisasi itu memang masih terjaga dalam bentuk fisik, tapi mengalami pengerdilan makna, seperti keluarga Fandi yang kehilangan pegangan hidup: raibnya cahaya iman. Pengikisan ideologi ini diperparah dengan penggambaran keluarga utuh yang tidak bahagia. Kasus perceraian, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, yang acap tayang di infotainmen, lalu juga sinetron, makin menggerus. Apalagi, citra single parent seperti yang tampil dalam diri Tety Liz, ibu dari Marcella Zalianty, sangat mengena. Atau seperti kiprah Kanaya Tabitha.
Apakah keluarga yang sempurna memang telah kehilangan pesona? Jelas tidak. Sinetron dan film di atas hanya mencoba menggambarkan "arus besar" penerimaan pada hal itu. Artinya, sebagai cerminan realitas sosial, sinetron semacam itu menunjukkan pergeseran pandang tentang keluarga. Ideologisasi Orde baru tentang keluarga sempurna yang bahagia --ayah, ibu, dua anak lelaki dan perempuan, (diwakili keluarga Fandi) telah runtuh. Ideologisasi itu memang masih terjaga dalam bentuk fisik, tapi mengalami pengerdilan makna, seperti keluarga Fandi yang kehilangan pegangan hidup: raibnya cahaya iman. Pengikisan ideologi ini diperparah dengan penggambaran keluarga utuh yang tidak bahagia. Kasus perceraian, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, yang acap tayang di infotainmen, lalu juga sinetron, makin menggerus. Apalagi, citra single parent seperti yang tampil dalam diri Tety Liz, ibu dari Marcella Zalianty, sangat mengena. Atau seperti kiprah Kanaya Tabitha.Namun, penggerusan terkuat idealisasi keluarga sempurna itu datang seperti dalam doa Kipli di atas: pengakuan kepada kekuasaan Tuhan. Pergi dan hilangnya seorang ibu atau ayah, adalah bagian dari rencana-Nya. Kesempurnaan atau ketaksempurnaan keluarga bukan rencana manusia, tapi pemberian dan karunia-Nya. Karena sesempurnanya keluarga bukan terletak pada sosok ayah dan ibu, anak lelaki atau perempuan, juga harta kekayaan, melainkan hadirnya cahaya keimanan. Keimananlah yang menjadikan sebuah keluarga sempurna, bagaimanapun kondisinya. Dan sinetron "Kiamat Sudah Dekat" menunjukkan dengan manis hal itu.
[Artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 6 Maret 2006]
( t.i.l.i.k ! )