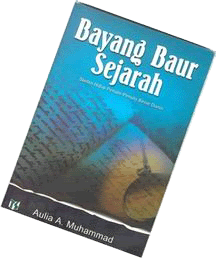...tera di sesela gegas-gesa
Friday, June 06, 2008
Poligami, Musik, dan Imagologi
Agama industri hiburan, dan juga politik, adalah uang!
 "Saya jengkel dengan sinetron Munajah Cinta, meniru habis film Ayat-ayat Cinta. Sudah pemainnya sama, sejak awal, cerita sinetron itu pun sudah mengampanyekan poligami. Saya takut, nanti poligami itu akan jadi kewajaran dan diterima oleh masyarakat kita. Mas Aulia mbok sesekali membahas soal itu."
"Saya jengkel dengan sinetron Munajah Cinta, meniru habis film Ayat-ayat Cinta. Sudah pemainnya sama, sejak awal, cerita sinetron itu pun sudah mengampanyekan poligami. Saya takut, nanti poligami itu akan jadi kewajaran dan diterima oleh masyarakat kita. Mas Aulia mbok sesekali membahas soal itu."
Kutipan di atas adalah petikan e-mail dari Ibu (?) Indah. Sudah agak lama e-mail itu terdiam di inbox, terbiarkan karena saya belum memikirkan bagaimana menjawabnya. Jujur saja, Munajah Cinta belum mampu membuat saya berdiam lama di teve untuk menontonnya, apalagi membahasnya. Karena tak ada hal baru dari sinetron ini, baik dari segi cerita, penyutradaraan, akting, bahkan pemotongan antar-adegan sebelum bersambung. Namun, kekawatiran dari Indah membuat saya berpikir, apakah benar, jika sebuah tayangan menawarkan "sikap" tentang poligami, sinetron itu patut dikhawatirkan? Apakah sebuah nilai yang dipajang bisa langsung "menginfeksii" penonton, menulari dengan cepat seperti virus?
Penonton tentu saja bukan kertas kosong, dan teve menjadi pensil yang akan segera menggarisi kekosongan itu. Pemirsa selalu membawa "bekal" ketika melihat sebuah tayangan. Bekal itulah yang nanti akan "memilihkan" posisi penonton di hadapan "nilai" yang ditawarkan teve. Penonton mungkin saja mengadopsi nilai itu, karena merasa sejalur dan sepaham. Tapi mungkin juga menegasi, menolak, karena "bekal" yang penonton "bawa" merasakan nilai itu sebagai ancaman. Dan tersedia "posisi" ketiga, menegosiasi nilai itu, mengadaftasi, menyaring, mana yang mungkin dan mana yang tidak. Dan menyangkut "tawaran" poligami dalam Munajah Cinta, sikap penonton pasti berada dalam salah satu dari tiga posisi itu.
Jadi Indah, tampaknya tak perlu khawatir. Apalagi, kian hari, saya menyadari industri sebenarnya tidak "berurusan" dengan pemasaran nilai-nilai. Nilai yang dikenal industri adalah nominal dalam bentuk uang. Dan penonton pun, pelan tapi pasti, memandang industri hiburan dalam kerangka semacam itu. Dunia musik adalah contoh terbaik.
Cuma Citra
Dyta kecewa. Malam itu, bersama tiga temannya, dia gagal menemui The Changcuters yang manggung di Surabaya. Padahal, tart sudah mereka bawa, untuk Alda yang berulang tahun. Mereka pun sudah berpakaian ala "Changcuters Angel", dan antre di depan tenda tempat istrahat band itu. Mengiba, memohon, izin tak juga dapat. Ketika mobil yang membawa Tria dan lainnya melaju, Dyta cuma terpaku. Ada yang meleleh di matanya.
Semua ekspresi Dyta tertayang jelas di acara "Fans" TransTV, Minggu (1/6) sore. Juga kerumun fans lain, yang berloncatan di sisi panggung, ketika Tria, dengan gaya dan dandanan khasnya, bernyanyi. Lihatlah, ketika lagu "Racun Dunia" membahana, penonton histeris. Di barisan paling depan, di sisi panggung, sembari meneriakkan nama Tria, puluhan penonton wanita yang tertangkap kamera, ikut mendendangkan lagu itu. Racun...racun...racun/ Hilang akal sehatku 3x/ Memang kau racun // Wanita racun dunia/ Karna dia butakan semua/ Wanita racun dunia/ Apa daya itu adanya.
Ajaib! Dyta dan puluhan penggemar lain, yang juga wanita, justru menikmati lagu itu. Mereka berjejingkrak, bersesorak, seakan menjadi bagian dari "racun" yang diteriakkan Tria.
Apakah The Changcuters menawarkan "nilai" dengan lagu itu? Apakah Dyta dan puluhan fans lainnya, terutama yang wanita, mengakui dan mengadopsi "tawaran" Tria itu?
Tentu tidak.
Kegembiraan mereka adalah ungkapan keterlibatan emosi atas citra yang dibawa The Changcuters. Sekali lagi, keterlibatan emosi!, yang akhirnya menjadi ketersambungan imaji. Jadi, imaji personal Changcuters-lah yang membuat fans itu bergerak. Lagu Changcuters pun adalah bagian dari imaji mereka, termasuk "Racun Dunia". Sebagai bagian dari imaji, syair lagu "Racun Dunia" tidak lagi "bicara", tidak membawa pesan khusus, tergerus dalam keseluruhan citraan kejadulan band itu. "Racun Dunia" bahkan adalah kejadulan itu sendiri, yang dirayakan, dinyanyikan, dalam ketakbermaknaan (meaningless). Sebagai kejadulan, kelampauan, "Racun Dunia" adalah kenangan, juga kerinduan; selebihnya perayaan, selebrasi. Seperti lagu "Begadang" Rhoma Irama, yang berisi larangan begadang, tapi justru lebih sering dinyanyikan mereka yang tengah begadang. Jadi, masihkah kita bisa mendapatkan nilai, mempersoalkan pesan?
Ya, begitulah industri. Sangat mungkin, industri hiburan mengaku memajang nilai, mewartakan kebaikan, menawarkan sebuah ideologi. Tapi saya percaya, pengakuan itu tak lebih hanya kiat pemasaran. Ideologi, dalam industri hiburan, --dan kini masuk ke ranah politik-- telah lama menjadi imagologi, penguatan atas imaji. Hanya dengan kemampuan mempermainkan imaji, industri hiburan, dan juga politik, dengan segenap pelakunya dapat terus bertahan. Imajilah yang mereka jual, dan terus mereka ubah. Seperti Mulan, dari Kwok ke Jameela, dari China ke Arabia. Semua cuma soal citra, dan tentu, nilai uang juga.
Jadi Indah, soal Munajah Cinta itu, tak perlu cemas ya? Poligami itu saat ini hanya citraan yang tengah laku. Imaji, dan bukan ideologi, yang ditunggangi industri. Nikmati saja selagi bisa, hitung-hitung sebagai pelipur lara, di tengah harga kebutuhan yang melambung tak terkira, yang bisa membuat kita gila.
[Artikel ini telah terbit di Harian Suara Merdeka, Minggu 8 Juni 2008]
 "Saya jengkel dengan sinetron Munajah Cinta, meniru habis film Ayat-ayat Cinta. Sudah pemainnya sama, sejak awal, cerita sinetron itu pun sudah mengampanyekan poligami. Saya takut, nanti poligami itu akan jadi kewajaran dan diterima oleh masyarakat kita. Mas Aulia mbok sesekali membahas soal itu."
"Saya jengkel dengan sinetron Munajah Cinta, meniru habis film Ayat-ayat Cinta. Sudah pemainnya sama, sejak awal, cerita sinetron itu pun sudah mengampanyekan poligami. Saya takut, nanti poligami itu akan jadi kewajaran dan diterima oleh masyarakat kita. Mas Aulia mbok sesekali membahas soal itu."Kutipan di atas adalah petikan e-mail dari Ibu (?) Indah. Sudah agak lama e-mail itu terdiam di inbox, terbiarkan karena saya belum memikirkan bagaimana menjawabnya. Jujur saja, Munajah Cinta belum mampu membuat saya berdiam lama di teve untuk menontonnya, apalagi membahasnya. Karena tak ada hal baru dari sinetron ini, baik dari segi cerita, penyutradaraan, akting, bahkan pemotongan antar-adegan sebelum bersambung. Namun, kekawatiran dari Indah membuat saya berpikir, apakah benar, jika sebuah tayangan menawarkan "sikap" tentang poligami, sinetron itu patut dikhawatirkan? Apakah sebuah nilai yang dipajang bisa langsung "menginfeksii" penonton, menulari dengan cepat seperti virus?
Penonton tentu saja bukan kertas kosong, dan teve menjadi pensil yang akan segera menggarisi kekosongan itu. Pemirsa selalu membawa "bekal" ketika melihat sebuah tayangan. Bekal itulah yang nanti akan "memilihkan" posisi penonton di hadapan "nilai" yang ditawarkan teve. Penonton mungkin saja mengadopsi nilai itu, karena merasa sejalur dan sepaham. Tapi mungkin juga menegasi, menolak, karena "bekal" yang penonton "bawa" merasakan nilai itu sebagai ancaman. Dan tersedia "posisi" ketiga, menegosiasi nilai itu, mengadaftasi, menyaring, mana yang mungkin dan mana yang tidak. Dan menyangkut "tawaran" poligami dalam Munajah Cinta, sikap penonton pasti berada dalam salah satu dari tiga posisi itu.
Jadi Indah, tampaknya tak perlu khawatir. Apalagi, kian hari, saya menyadari industri sebenarnya tidak "berurusan" dengan pemasaran nilai-nilai. Nilai yang dikenal industri adalah nominal dalam bentuk uang. Dan penonton pun, pelan tapi pasti, memandang industri hiburan dalam kerangka semacam itu. Dunia musik adalah contoh terbaik.
Cuma Citra
Dyta kecewa. Malam itu, bersama tiga temannya, dia gagal menemui The Changcuters yang manggung di Surabaya. Padahal, tart sudah mereka bawa, untuk Alda yang berulang tahun. Mereka pun sudah berpakaian ala "Changcuters Angel", dan antre di depan tenda tempat istrahat band itu. Mengiba, memohon, izin tak juga dapat. Ketika mobil yang membawa Tria dan lainnya melaju, Dyta cuma terpaku. Ada yang meleleh di matanya.
Semua ekspresi Dyta tertayang jelas di acara "Fans" TransTV, Minggu (1/6) sore. Juga kerumun fans lain, yang berloncatan di sisi panggung, ketika Tria, dengan gaya dan dandanan khasnya, bernyanyi. Lihatlah, ketika lagu "Racun Dunia" membahana, penonton histeris. Di barisan paling depan, di sisi panggung, sembari meneriakkan nama Tria, puluhan penonton wanita yang tertangkap kamera, ikut mendendangkan lagu itu. Racun...racun...racun/ Hilang akal sehatku 3x/ Memang kau racun // Wanita racun dunia/ Karna dia butakan semua/ Wanita racun dunia/ Apa daya itu adanya.
Ajaib! Dyta dan puluhan penggemar lain, yang juga wanita, justru menikmati lagu itu. Mereka berjejingkrak, bersesorak, seakan menjadi bagian dari "racun" yang diteriakkan Tria.
Apakah The Changcuters menawarkan "nilai" dengan lagu itu? Apakah Dyta dan puluhan fans lainnya, terutama yang wanita, mengakui dan mengadopsi "tawaran" Tria itu?
Tentu tidak.
Kegembiraan mereka adalah ungkapan keterlibatan emosi atas citra yang dibawa The Changcuters. Sekali lagi, keterlibatan emosi!, yang akhirnya menjadi ketersambungan imaji. Jadi, imaji personal Changcuters-lah yang membuat fans itu bergerak. Lagu Changcuters pun adalah bagian dari imaji mereka, termasuk "Racun Dunia". Sebagai bagian dari imaji, syair lagu "Racun Dunia" tidak lagi "bicara", tidak membawa pesan khusus, tergerus dalam keseluruhan citraan kejadulan band itu. "Racun Dunia" bahkan adalah kejadulan itu sendiri, yang dirayakan, dinyanyikan, dalam ketakbermaknaan (meaningless). Sebagai kejadulan, kelampauan, "Racun Dunia" adalah kenangan, juga kerinduan; selebihnya perayaan, selebrasi. Seperti lagu "Begadang" Rhoma Irama, yang berisi larangan begadang, tapi justru lebih sering dinyanyikan mereka yang tengah begadang. Jadi, masihkah kita bisa mendapatkan nilai, mempersoalkan pesan?
Ya, begitulah industri. Sangat mungkin, industri hiburan mengaku memajang nilai, mewartakan kebaikan, menawarkan sebuah ideologi. Tapi saya percaya, pengakuan itu tak lebih hanya kiat pemasaran. Ideologi, dalam industri hiburan, --dan kini masuk ke ranah politik-- telah lama menjadi imagologi, penguatan atas imaji. Hanya dengan kemampuan mempermainkan imaji, industri hiburan, dan juga politik, dengan segenap pelakunya dapat terus bertahan. Imajilah yang mereka jual, dan terus mereka ubah. Seperti Mulan, dari Kwok ke Jameela, dari China ke Arabia. Semua cuma soal citra, dan tentu, nilai uang juga.
Jadi Indah, soal Munajah Cinta itu, tak perlu cemas ya? Poligami itu saat ini hanya citraan yang tengah laku. Imaji, dan bukan ideologi, yang ditunggangi industri. Nikmati saja selagi bisa, hitung-hitung sebagai pelipur lara, di tengah harga kebutuhan yang melambung tak terkira, yang bisa membuat kita gila.
[Artikel ini telah terbit di Harian Suara Merdeka, Minggu 8 Juni 2008]