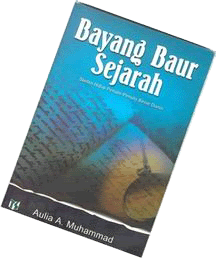...tera di sesela gegas-gesa
Monday, July 23, 2007
Singkong di Paha Lasmini
Dongeng padi berasal dari Dewi Sri, seharusnya tidak muncul sebagai versi "sejarah" di televisi.

LASMINI tersenyum. Dia terus berjalan, seolah tak menyadari puluhan pasang mata yang mengawasinya dari semak dan rerimbun tegalan. Di ujung jalan, langkahnya berhenti, dan sambil membusungkan dada, dia berteriak, "Kisanak, keluarlah! Berapa lama lagi kalian akan terus bersembunyi?!"
Dan dari rerimbun singkong, dua lelaki berkumis bapang keluar, mengadang jalannya. Di sisi kanannya, dari balik jajaran pohon pepaya, dua lelaki gemuk, ngakak gagak, mengurungnya. Tapi Lasmini tetap tenang. Dia tahu, percakapan panjang tak akan ada gunanya. Sambil tetap tersenyum, dia geser kaki kanannya membentuk kuda-kuda. Lasmini telah bersiap diri untuk menghadapi kemungkinan apa pun.
Ya, pasti, pertarungan akan terjadi. Pertempuran yang "indah", bukan karena kelihaian jurus dan kehebatan tenaga dalam, melainkan kelebat tubuh Lasmini yang membuat paha kuningnya acap terpamerkan, perut dan belahan dadanya yang jadi gampang tertangkap kamera. "Lasmini adalah sinetron yang paling saya suka," kata Ayu Anjani, sang pemeran utama di sinetron laga itu, yang nyaris tiap tengah malam tayang di Anteve.
Namun, selain paha dan dada Lasmini, ada beberapa hal lain yang membuat saya selalu menunggu sinetron ini. Pertama, sinetron ini mendekatkan saya dengan masa kecil, senja yang selalu digemai dengan sandiwara radio "Saur Sepuh" dan "Babat Tanah Leluhur". Lasmini adalah tokoh sentral di sini, yang digambarkan sensual, centil, dan tentu saja, sakti. Suara Ivone Rose yang sungguh seksi, apalagi saat dia mendesah menggoda Raden Bentar, melambungkan imajinasi kecil saya ke sudut keliaran yang terdalam. Meski sinetron Lasmini memangkas imajinasi tersebut, yang lari dari pakem cerita di radionya, namun perhubungan kenangan itu tetap saja otomatis terjadi.
Kedua, sinetron ini, juga sinetron laga pada umumnya, berada dalam sebuah lingkup "sejarah" atau epos besar. Lasmini misalnya, diletakkan dalam situasi Kerajaan Pasundan. Akibatnya, mau tidak mau, terkadang cerita fiktif itu harus memasukkan data-data sejarah tentang kerajaan Pasundan dan atau Prabu Siliwangi, juga tentu, struktur kemasyarakatan pada saat itu. Jadi, di balik kelebat tubuh para jagoan dan betinaan, penonton juga mendapatkan renik-renik sejarah, yang bisa dibaca sebagai variasi atau versi lain dari sejarah babon kita. Hal yang sama misalnya, juga dilakukan drama Korea Jewel in The Palace yang tayang setiap sore di Indosiar. Drama itu sangat detil menampilkan Korea tempo dulu. Bukan saja pilihan latar, cara ujar, dan arsitektur bangunan didekatkan dengan situasi asli pada era kerajaan itu, bahkan beda jenis pakaian dan sandal antara kelas masyarakat pun tak lalai ditunjukkan. Drama itu secara piawai menghadirkan masa lalu dengan potret senyatanya. Dan, hal semacam itulah yang sangat sulit ditemukan dalam sinetron laga kita, yang menjadikan latar sejarah hanya sebagai sejarah-sejarahan saja.
1000 tahun Singkong
Dalam adegan Lasmini di atas misalnya, sepintas tak ada yang bermasalah. Penonton akan menganggap wajar pengadangan itu terjadi di tegalan yang ditumbuhi rerimbun pepaya dan singkong. Penonton pasti juga merasa tak terganggu dengan jenis sandal bertali Lasmini, jenis bahan dan gaya busananya. Atau motif kain, ragam senjata, dan jalinan ikat kepala para penjahat. Semua dapat diterima dalam sebuah kewajaran cerita, tak mengganggu, bahkan menambah seru. Namun, jika cerita itu diletakkan dalam latar peristiwa, masa kerajaan Pasundan, akan terciptalah puluhan pertanyaan menyangkut hal di atas. Misalnya konsep tegalan, apakah sudah dikenal pada saat itu? Atau motif batik, sandal menali ke betis, dan gaya berpakaian, apakah memang demikian adanya? Baiklah, penonton bisa menafikan hal itu. Tapi, jajaran pohon pepaya dan rerimbun singkong, dapatkah diterima sebagai kenyataan dari sebuah latar yang dipilih berada di masa keemasan Pasundan?
Kehadiran singkong, entah dalam bentuk pepohonan atau makanan, memang lazim dalam sinetron dan sinema laga kita, untuk menggambarkan kehidupan strata bawah masyarakat. Berbagai sinetron berlatar sejarah kerajaan Majapahit sampai Mataram Islam, acap meletakkan kehadiran kebun singkong dan atau panganan singkong. Padahal, dalam kesejarahannya, singkong dan atau pepaya, tidak mungkin telah "lahir" di masa itu. Ubi kayu atau singkong misalnya, pertama kali hadir justru bukan di tanah Jawa, melainkan di kepulauan Maluku. Itu pun di masa yang jauh kemudian, ketika petualang Portugis membawa tanaman itu dari Amerika Selatan dan mencoba membiakkannya di Maluku. Ingat, kedatangan Portugis tentu di era yang sangat berbeda jauh dengan Majapahit, Pasundan, dan atau Mataram.
Di tanah Jawa, menurut Haryono Rinardi dalam Politik Singkong Zaman Kolonial, sampai tahun 1850-an, singkong belum menjadi tanaman palawija. Hal itu karena jenis singkong dari Amerika Latin tidak cocok ditanam di tanah Jawa. Baru pada tahun 1854, setelah didatangkan varietas singkong dari Kepulauan Antilen Kecil di Karibia, residen di Jawa dan Palembang diperintahkan Belanda untuk mulai menanamnya. Dan setelah tahun 1870-an, singkong ditanam secara besar-besaran di Pulau Jawa akibat meningkatnya permintaan dari Prancis, yang menjadikan ubi kayu sebagai bahan mentah minuman keras pengganti anggur.
Bayangkan, baru 1870-an singkong dijadikan perkebunan di tanah Jawa, tapi mengapa ubi kayu sudah "hadir" dalam sinetron Lasmini, dan cerita berlatar kerajaan lainnya? Itu berarti, oleh perajin sinetron, kelahiran singkong dimajukan nyaris 1000 tahun!
Teh dan Apel
Selain singkong, teh dan apel pun acap tampil dalam sinetron laga kita. Memang, teh hadir bukan sebagai minuman, melainkan menjadi latar pertarungan dan percintaan. Bertarung, lari dan sembunyi di rerimbun teh menjadi hal lazim, sebiasa berkejaran dan bercinta di kebun teh. Padahal, seperti singkong, teh juga bukan tanaman asli Indonesia. Setelah dipopulerkan oleh pedagang Cina dan Arab ke penjuru dunia, teh sampai di Nusantara berkat tangan Andreas Cleyer, yang mencoba membiakkannya di perkebunan Batavia, tahun 1686. Tak ada catatan lengkap mengenai keberhasilan usaha ini. Situs wikipedia pun tak memberikan penjelasan berarti soal Andreas Cleyer. Namun, lewat wikipedia juga, ditemukan sebuah fakta menarik bahwa perkebunan pertama teh di Nusantara baru berhasil di tahun 1828 berkat tangan dingin sinyo JLLL Jacobson. Sebelum itu, meski ada, teh hanya berupa tanaman sporadis, bukan berbentuk perkebunan untuk kepentingan komersial. Jadi, bayangkanlah kehadirannya dalam kebun-kebun penduduk di era kerajaan dulu. Aneh bin ajaib.
Jangan tertawa dulu, karena "penghadiran" singkong dan teh belum seberapa menggelikan. Apel-lah yang memegang rekor kenaifan sejarah ini. Seperti singkong, apel diposisikan sebagai makanan juga, tapi untuk strata atas. Dan kehadirannya acap tertampil sebagai latar dalam sebuah persidangan agung di istana. Dalam sinetron berlatar kerajaan, nyaris kita saksikan selain para pengawal, piala atau nampan makanan pasti menemani duduknya sang raja di singgasana. Dan di atas piala atau nampan buahan itu, dengan "sombong" tampak apel merah. Istana dan raja yang dikelilingi bebuahan mewah, anggur, apel, dan lainnya. Tidakkah pengerajin sinetron itu berpikir, bagaimana caranya apel bisa sampai ke masa itu? Barangkali, hanya raja Brama Kumbara yang bisa menikmati apel itu, karena dia memiliki rajawali sakti yang dapat terbang dan mencapai Amerika, lalu meletakkan apel di dalam paruh besarnya. Itu pun dengan syarat, rajawali tersebut dapat terbang secepat Boeing 747, atau ada lemari pendingin di dalam paruhnya!
Kalau sedikit cerdas, tentu yang hadir sebagai bebuahan raja adalah apel hijau yang dapat penonton identikkan dengan apel Batu, dari Malang. Namun malangnya, apel ini pun baru ditanam di "Indonesia" sekitar tahun 1934. Jadi, sebenarnya, tidak ada satu pun alasan sejarah yang dapat membenarkan kehadiran apel sebagai bebuahan para raja. Demikian juga singkong, teh, kopi, bahkan padi. Karena, menurut sejarawan Prof Dr Soegijanto Padmo, sampai abad ke-19, menanam padi belum menjadi tradisi orang kebanyakan di tanah Jawa.
Jadi, jika Anda menonton sinetron laga berlatar kerajaan di masa Nusantara, janganlah ikutkan pengetahuan sejarah. Tayang di tengah malam, seperti juga Mak Lampir di Indosiar, sejarah singkong, teh dan apel pasti sirna dalam visual sensual, pesona desah-senyum, belahan dada, dan gading paha Lasmini. Ciiaaattt.....
[Artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 29 Juli 2007]
( t.i.l.i.k ! )

LASMINI tersenyum. Dia terus berjalan, seolah tak menyadari puluhan pasang mata yang mengawasinya dari semak dan rerimbun tegalan. Di ujung jalan, langkahnya berhenti, dan sambil membusungkan dada, dia berteriak, "Kisanak, keluarlah! Berapa lama lagi kalian akan terus bersembunyi?!"
Dan dari rerimbun singkong, dua lelaki berkumis bapang keluar, mengadang jalannya. Di sisi kanannya, dari balik jajaran pohon pepaya, dua lelaki gemuk, ngakak gagak, mengurungnya. Tapi Lasmini tetap tenang. Dia tahu, percakapan panjang tak akan ada gunanya. Sambil tetap tersenyum, dia geser kaki kanannya membentuk kuda-kuda. Lasmini telah bersiap diri untuk menghadapi kemungkinan apa pun.
Ya, pasti, pertarungan akan terjadi. Pertempuran yang "indah", bukan karena kelihaian jurus dan kehebatan tenaga dalam, melainkan kelebat tubuh Lasmini yang membuat paha kuningnya acap terpamerkan, perut dan belahan dadanya yang jadi gampang tertangkap kamera. "Lasmini adalah sinetron yang paling saya suka," kata Ayu Anjani, sang pemeran utama di sinetron laga itu, yang nyaris tiap tengah malam tayang di Anteve.
Namun, selain paha dan dada Lasmini, ada beberapa hal lain yang membuat saya selalu menunggu sinetron ini. Pertama, sinetron ini mendekatkan saya dengan masa kecil, senja yang selalu digemai dengan sandiwara radio "Saur Sepuh" dan "Babat Tanah Leluhur". Lasmini adalah tokoh sentral di sini, yang digambarkan sensual, centil, dan tentu saja, sakti. Suara Ivone Rose yang sungguh seksi, apalagi saat dia mendesah menggoda Raden Bentar, melambungkan imajinasi kecil saya ke sudut keliaran yang terdalam. Meski sinetron Lasmini memangkas imajinasi tersebut, yang lari dari pakem cerita di radionya, namun perhubungan kenangan itu tetap saja otomatis terjadi.
Kedua, sinetron ini, juga sinetron laga pada umumnya, berada dalam sebuah lingkup "sejarah" atau epos besar. Lasmini misalnya, diletakkan dalam situasi Kerajaan Pasundan. Akibatnya, mau tidak mau, terkadang cerita fiktif itu harus memasukkan data-data sejarah tentang kerajaan Pasundan dan atau Prabu Siliwangi, juga tentu, struktur kemasyarakatan pada saat itu. Jadi, di balik kelebat tubuh para jagoan dan betinaan, penonton juga mendapatkan renik-renik sejarah, yang bisa dibaca sebagai variasi atau versi lain dari sejarah babon kita. Hal yang sama misalnya, juga dilakukan drama Korea Jewel in The Palace yang tayang setiap sore di Indosiar. Drama itu sangat detil menampilkan Korea tempo dulu. Bukan saja pilihan latar, cara ujar, dan arsitektur bangunan didekatkan dengan situasi asli pada era kerajaan itu, bahkan beda jenis pakaian dan sandal antara kelas masyarakat pun tak lalai ditunjukkan. Drama itu secara piawai menghadirkan masa lalu dengan potret senyatanya. Dan, hal semacam itulah yang sangat sulit ditemukan dalam sinetron laga kita, yang menjadikan latar sejarah hanya sebagai sejarah-sejarahan saja.
1000 tahun Singkong
Dalam adegan Lasmini di atas misalnya, sepintas tak ada yang bermasalah. Penonton akan menganggap wajar pengadangan itu terjadi di tegalan yang ditumbuhi rerimbun pepaya dan singkong. Penonton pasti juga merasa tak terganggu dengan jenis sandal bertali Lasmini, jenis bahan dan gaya busananya. Atau motif kain, ragam senjata, dan jalinan ikat kepala para penjahat. Semua dapat diterima dalam sebuah kewajaran cerita, tak mengganggu, bahkan menambah seru. Namun, jika cerita itu diletakkan dalam latar peristiwa, masa kerajaan Pasundan, akan terciptalah puluhan pertanyaan menyangkut hal di atas. Misalnya konsep tegalan, apakah sudah dikenal pada saat itu? Atau motif batik, sandal menali ke betis, dan gaya berpakaian, apakah memang demikian adanya? Baiklah, penonton bisa menafikan hal itu. Tapi, jajaran pohon pepaya dan rerimbun singkong, dapatkah diterima sebagai kenyataan dari sebuah latar yang dipilih berada di masa keemasan Pasundan?
Kehadiran singkong, entah dalam bentuk pepohonan atau makanan, memang lazim dalam sinetron dan sinema laga kita, untuk menggambarkan kehidupan strata bawah masyarakat. Berbagai sinetron berlatar sejarah kerajaan Majapahit sampai Mataram Islam, acap meletakkan kehadiran kebun singkong dan atau panganan singkong. Padahal, dalam kesejarahannya, singkong dan atau pepaya, tidak mungkin telah "lahir" di masa itu. Ubi kayu atau singkong misalnya, pertama kali hadir justru bukan di tanah Jawa, melainkan di kepulauan Maluku. Itu pun di masa yang jauh kemudian, ketika petualang Portugis membawa tanaman itu dari Amerika Selatan dan mencoba membiakkannya di Maluku. Ingat, kedatangan Portugis tentu di era yang sangat berbeda jauh dengan Majapahit, Pasundan, dan atau Mataram.
Di tanah Jawa, menurut Haryono Rinardi dalam Politik Singkong Zaman Kolonial, sampai tahun 1850-an, singkong belum menjadi tanaman palawija. Hal itu karena jenis singkong dari Amerika Latin tidak cocok ditanam di tanah Jawa. Baru pada tahun 1854, setelah didatangkan varietas singkong dari Kepulauan Antilen Kecil di Karibia, residen di Jawa dan Palembang diperintahkan Belanda untuk mulai menanamnya. Dan setelah tahun 1870-an, singkong ditanam secara besar-besaran di Pulau Jawa akibat meningkatnya permintaan dari Prancis, yang menjadikan ubi kayu sebagai bahan mentah minuman keras pengganti anggur.
Bayangkan, baru 1870-an singkong dijadikan perkebunan di tanah Jawa, tapi mengapa ubi kayu sudah "hadir" dalam sinetron Lasmini, dan cerita berlatar kerajaan lainnya? Itu berarti, oleh perajin sinetron, kelahiran singkong dimajukan nyaris 1000 tahun!
Teh dan Apel
Selain singkong, teh dan apel pun acap tampil dalam sinetron laga kita. Memang, teh hadir bukan sebagai minuman, melainkan menjadi latar pertarungan dan percintaan. Bertarung, lari dan sembunyi di rerimbun teh menjadi hal lazim, sebiasa berkejaran dan bercinta di kebun teh. Padahal, seperti singkong, teh juga bukan tanaman asli Indonesia. Setelah dipopulerkan oleh pedagang Cina dan Arab ke penjuru dunia, teh sampai di Nusantara berkat tangan Andreas Cleyer, yang mencoba membiakkannya di perkebunan Batavia, tahun 1686. Tak ada catatan lengkap mengenai keberhasilan usaha ini. Situs wikipedia pun tak memberikan penjelasan berarti soal Andreas Cleyer. Namun, lewat wikipedia juga, ditemukan sebuah fakta menarik bahwa perkebunan pertama teh di Nusantara baru berhasil di tahun 1828 berkat tangan dingin sinyo JLLL Jacobson. Sebelum itu, meski ada, teh hanya berupa tanaman sporadis, bukan berbentuk perkebunan untuk kepentingan komersial. Jadi, bayangkanlah kehadirannya dalam kebun-kebun penduduk di era kerajaan dulu. Aneh bin ajaib.
Jangan tertawa dulu, karena "penghadiran" singkong dan teh belum seberapa menggelikan. Apel-lah yang memegang rekor kenaifan sejarah ini. Seperti singkong, apel diposisikan sebagai makanan juga, tapi untuk strata atas. Dan kehadirannya acap tertampil sebagai latar dalam sebuah persidangan agung di istana. Dalam sinetron berlatar kerajaan, nyaris kita saksikan selain para pengawal, piala atau nampan makanan pasti menemani duduknya sang raja di singgasana. Dan di atas piala atau nampan buahan itu, dengan "sombong" tampak apel merah. Istana dan raja yang dikelilingi bebuahan mewah, anggur, apel, dan lainnya. Tidakkah pengerajin sinetron itu berpikir, bagaimana caranya apel bisa sampai ke masa itu? Barangkali, hanya raja Brama Kumbara yang bisa menikmati apel itu, karena dia memiliki rajawali sakti yang dapat terbang dan mencapai Amerika, lalu meletakkan apel di dalam paruh besarnya. Itu pun dengan syarat, rajawali tersebut dapat terbang secepat Boeing 747, atau ada lemari pendingin di dalam paruhnya!
Kalau sedikit cerdas, tentu yang hadir sebagai bebuahan raja adalah apel hijau yang dapat penonton identikkan dengan apel Batu, dari Malang. Namun malangnya, apel ini pun baru ditanam di "Indonesia" sekitar tahun 1934. Jadi, sebenarnya, tidak ada satu pun alasan sejarah yang dapat membenarkan kehadiran apel sebagai bebuahan para raja. Demikian juga singkong, teh, kopi, bahkan padi. Karena, menurut sejarawan Prof Dr Soegijanto Padmo, sampai abad ke-19, menanam padi belum menjadi tradisi orang kebanyakan di tanah Jawa.
Jadi, jika Anda menonton sinetron laga berlatar kerajaan di masa Nusantara, janganlah ikutkan pengetahuan sejarah. Tayang di tengah malam, seperti juga Mak Lampir di Indosiar, sejarah singkong, teh dan apel pasti sirna dalam visual sensual, pesona desah-senyum, belahan dada, dan gading paha Lasmini. Ciiaaattt.....
[Artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 29 Juli 2007]
( t.i.l.i.k ! )
Friday, July 13, 2007
Kami Lepas Kau dengan Senyuman
"Dia pernah ngomong, 'Gue pengen jadi presiden anak yatim saja'," cerita Heri, adik Taufik.

"Tidak usah takut. Jika gagal, engkau tak akan sempat merasakan apa-apa," kata Sersan Cappy. Di depannya, Cahill tampak gugup dan takut, berkali-kali tak berani meletakkan pipet untuk menambal picu bom gas syaraf agar tak meledak. Tapi, setelah mendengar kalimat Cappy, dia mengerdikkan bahu, terdiam, dan kembali mencoba menaklukkan bom itu. Ketakutannya telah padam.
"Engkau tak akan sempat merasakan apa-apa." Cappy mengatakan itu sekitar pukul 10 malam, lewat adegan dalam film Executive Decision yang tayang di TransTV, Rabu (11/7) lalu. Dan di sekitar waktu itu juga, dalam dimensi ruang yang berbeda, di KM 13 jalan Purworejo-Yogyakarta, Taufik Savalas kecelakaan. Truk bermuatan semen menghantam Kijang yang dia tumpangi. Hantaman yang teramat dahsyat. Melalui kamera teve, tertayang badan Kijang yang hancur di sisi kanan, ringsek. Dan di dalam ringsekan itu, berdiam tubuh Taufik, terjepit lesakan rangka kabin. Tubuh, raga, jasad, yang sudah dilupakan nyawa. Tubuh yang "tak akan sempat merasakan apa-apa", karena nyawa lepas dengan lekas.
"Taufik meninggal seketika," terang Indro Warkop, saat menggelar jumpa pers, Kamis dini hari, dengan suara terbata-bata. Di sebelahnya, duduk Eko Patrio dan Derry "Empat Sekawan", tanpa wajah ceria sebagaimana biasanya mereka jika berhadapan dengan kamera. "Keluarga sampai saat ini masih shock, masih sulit menerima. Saya memahami hal itu," tambah Indro.
"Meninggal seketika," seperti kata Indro, adalah terma untuk mewartakan kematian yang baik, kematian tanpa siksa, tubuh yang "tak akan sempat merasakan apa-apa", ketika fase sakratul maut seakan luput. "Gue cuma ingin jadi orang baik, itu saja. Di mana ketika ninggalin dunia ini, gue mendapat khusnul khatimah," kata Taufik, suatu saat. "Setiap beribadah, salat, umroh, haji, doa saya cuma satu, ridlo-Mu ya Allah. Jika Allah sudah ridlo, sudahlah... Itu saja."
Meninggal seketika juga menunjukkan bahwa maut bukanlah sesuatu yang datang dari jauh. Dia dekat, memeluk kita sejak ruh berada dalam jasad. "Dan kematian jadi akrab," tulis Subagio Sastrowardoyo, "seakan kawan berkelakar yang mengajak tertawa." Mati atau maut bersenyawa dan bertaut dalam hidup. Maut dengan demikian, seharusnya, bukanlah sesuatu yang dapat membuat takut.
Tapi, memang ada maut yang membuat ciut. "Ketika dia datang dengan wajah hitam-jelaga dan merah-marah," kata Bawa Muhaiyaddeen, mursyid dari India itu. Maut yang hitam, maut yang merah, menjemput hidup dengan marah, dengan paksa, memberi siksa. Terentang jeda panjang ketika nyawa, meski tahu pasti kalah, tetap ingin bertahan di dunia. Hanya wajah putih-kertas yang membuat nyawa pergi dengan gegas, bayi yang kehausan dan mendapat susu. Di situ, maut datang dengan membujuk, agar tubuh tak sempat merasakan apa-apa. "Aku tak dapat membayangkan jika sampai mati di atas tempat tidur. Hidupku dalam perang, aku ingin mati dalam kelebat pedang," kata Khalid bin Ibnu Walid, panglima perang Islam. Mati di kelebat pedang, bagi Khalid adalah mati dalam kerja, dalam tugas, ketika maut menjemput nyawa dengan lekas. Tubuh yang tak akan sempat merasakan apa-apa.
Taufik pun mati dalam semangat yang sama dengan keinginan Khalid, dalam kerja, dalam tugas. Kecelakaan itu, akhir hidup itu, tak perlu dipandang sebagai sesuatu yang tragis.
Tapi memang ada yang tetap terasa tragis. Karena kematian selalu meletakkan seseorang pada kelampauan, keterikatan dalam kenangan, rasa kehilangan. Kematian Taufik pun jadi penuh tangis. "Taufik itu tidak ada celanya, baik sama semua orang. Saat istri saya meninggal, dia yang membawa sampai ke liang lahat," kenang Doyok.
"Kita sayang sama Taufik, tapi Allah lebih sayang. Taufik orang yang tidak pernah bersedih," ucap Derry "Empat Sekawan".
"Dia selalu bahagia. Orangnya baik banget. Dia selalu ingin orang juga bahagia. Kalau dia ada, kita selalu bisa tertawa," cerita Nia Zulkarnain.
Taufik ingin orang lain selalu bahagia, terus tertawa. Itulah kesamaan kenangan di banyak sahabatnya. Tapi, menyaksikan layar teve di hari kematiannya, kesamaan kenangan itu justru lenyap. Yang tampil adalah wajah-wajah sahabat yang sedih, cemas, rimbun airmata dan ratapan. Semangat Taufik seakan tak bersisa lagi, meski dalam isak, Derry masih berkata, "Semoga keceriaan Taufik masih selalu hidup bersama kita." Keceriaan yang mana?
Jika semua sahabat bersaksi bahwa Taufik adalah orang baik, penuh perhatian, kuat memegang bahul agama, apa yang harus diisakkan dari kematiannya. "Dia kerja tidak untuk dirinya sendiri, selalu berbagi. Dia pernah ngomong, 'Gue pengen jadi presiden anak yatim saja'," cerita Heri, adik Taufik. Lalu, untuk apa semua ratapan? Tidakkah tangisan itu hanya untuk menjadi semacam "tanda" keterhubungan dan kedekatan dengan sang mayit? Apalagi, "Setiap tangis kematian," kata Khoping Hoo, "adalah ratapan untuk diri sendiri, yang merasa rugi telah ditinggalkan."
"Dia ingin semua orang bahagia, tertawa," kata Nia, dan tak satu pun layar televisi yang menggambarkannya. Kesedihan disebarluaskan, airmata hanya menjadi milik kematian Taufik. Padahal, yang meninggal bukan Taufik saja, ada dua orang lain yang ikut pergi bersamanya. Padahal, ada kesedihan lain yang juga "dimiliki" keluarga sang supir, Hairuddin, juga Suharsono. Tapi kamera, dan mungkin sahabat Taufik, lupa menunjukkannya. Jika Taufik hidup, saya kira dia akan meminta "penghormatan" kematian yang sama untuk dua orang rekan seperjalanannya, tanpa airmata.
"Sehabis mengerjakan haji wada', Nabi Muhammad SAW menggamit Fatimah," cerita H Mahyaruddin Salim dalam kaset Di Seberang Kematian. "Anakku, ini haji terakhir Ayah. Waktu Ayah tak lama lagi..." Mendengar itu, Fatimah menangis. Rasulullah pun memeluknya, dan bertanya, "Mengapa engkau menangis, Nak? Engkau tidak boleh sedih. Lihat, Ayah akan berada di sana," tunjuk Nabi ke arah langit. Dan saat itu, Fatimah melihat langit terbuka, dan tampaknyalah surga.
"Ayah akan di sana, Yah?"
Rasulullah mengangguk. "Ya, dan engkau yang pertama akan ke sana juga, Anakku. Tidak berapa lama lagi."
Sejak saat itu, Fatimah selalu tersenyum. Ketika Nabi wafat pun, Fatimah tetap tersenyum. Dan benarlah, tak berapa lama, 8 bulan setelah nabi wafat, Fatimah pun menyusulnya.
Meski tak sesempurna Rasulullah, Taufik adalah orang baik, manusia yang selalu ingin berdekatan dengan sang Khalik. Para sahabat menjadi saksi hal itu. Maka, seharusnya, seperti Fatimah RA, sahabat Taufik pun dapat "melihat" surga, dan mengantarnya dengan senyuman. Apalagi, almarhum adalah orang yang selalu ingin menyemaikan kebahagiaan, menetaskan tawa di mana-mana.
Mungkin akan lebih baik, daripada meratap-tangis, para sahabat berkata, "Selamat jalan Fik, kami lepas kau dengan senyuman. Karena kami percaya, maut yang merenggutmu dengan cepat, adalah kerinduan surga. Kami akan tersenyum, karena yang kau tinggalkan adalah kenangan baik, yang kau tuju adalah keabadian yang terbaik. Ya, kami menangis, Fik. Tapi kami percaya, engkau tahu di balik tangis ini tersimpan senyuman, bahkan tawa, bibit yang selalu engkau semai di dunia, yang menafkahi keluargamu, dan jadi ladangmu meraih surga. Selamat jalan Fik, kami lepas kau dengan senyuman..."
[Artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 15 Juli 2007]
( t.i.l.i.k ! )

"Tidak usah takut. Jika gagal, engkau tak akan sempat merasakan apa-apa," kata Sersan Cappy. Di depannya, Cahill tampak gugup dan takut, berkali-kali tak berani meletakkan pipet untuk menambal picu bom gas syaraf agar tak meledak. Tapi, setelah mendengar kalimat Cappy, dia mengerdikkan bahu, terdiam, dan kembali mencoba menaklukkan bom itu. Ketakutannya telah padam.
"Engkau tak akan sempat merasakan apa-apa." Cappy mengatakan itu sekitar pukul 10 malam, lewat adegan dalam film Executive Decision yang tayang di TransTV, Rabu (11/7) lalu. Dan di sekitar waktu itu juga, dalam dimensi ruang yang berbeda, di KM 13 jalan Purworejo-Yogyakarta, Taufik Savalas kecelakaan. Truk bermuatan semen menghantam Kijang yang dia tumpangi. Hantaman yang teramat dahsyat. Melalui kamera teve, tertayang badan Kijang yang hancur di sisi kanan, ringsek. Dan di dalam ringsekan itu, berdiam tubuh Taufik, terjepit lesakan rangka kabin. Tubuh, raga, jasad, yang sudah dilupakan nyawa. Tubuh yang "tak akan sempat merasakan apa-apa", karena nyawa lepas dengan lekas.
"Taufik meninggal seketika," terang Indro Warkop, saat menggelar jumpa pers, Kamis dini hari, dengan suara terbata-bata. Di sebelahnya, duduk Eko Patrio dan Derry "Empat Sekawan", tanpa wajah ceria sebagaimana biasanya mereka jika berhadapan dengan kamera. "Keluarga sampai saat ini masih shock, masih sulit menerima. Saya memahami hal itu," tambah Indro.
"Meninggal seketika," seperti kata Indro, adalah terma untuk mewartakan kematian yang baik, kematian tanpa siksa, tubuh yang "tak akan sempat merasakan apa-apa", ketika fase sakratul maut seakan luput. "Gue cuma ingin jadi orang baik, itu saja. Di mana ketika ninggalin dunia ini, gue mendapat khusnul khatimah," kata Taufik, suatu saat. "Setiap beribadah, salat, umroh, haji, doa saya cuma satu, ridlo-Mu ya Allah. Jika Allah sudah ridlo, sudahlah... Itu saja."
Meninggal seketika juga menunjukkan bahwa maut bukanlah sesuatu yang datang dari jauh. Dia dekat, memeluk kita sejak ruh berada dalam jasad. "Dan kematian jadi akrab," tulis Subagio Sastrowardoyo, "seakan kawan berkelakar yang mengajak tertawa." Mati atau maut bersenyawa dan bertaut dalam hidup. Maut dengan demikian, seharusnya, bukanlah sesuatu yang dapat membuat takut.
Tapi, memang ada maut yang membuat ciut. "Ketika dia datang dengan wajah hitam-jelaga dan merah-marah," kata Bawa Muhaiyaddeen, mursyid dari India itu. Maut yang hitam, maut yang merah, menjemput hidup dengan marah, dengan paksa, memberi siksa. Terentang jeda panjang ketika nyawa, meski tahu pasti kalah, tetap ingin bertahan di dunia. Hanya wajah putih-kertas yang membuat nyawa pergi dengan gegas, bayi yang kehausan dan mendapat susu. Di situ, maut datang dengan membujuk, agar tubuh tak sempat merasakan apa-apa. "Aku tak dapat membayangkan jika sampai mati di atas tempat tidur. Hidupku dalam perang, aku ingin mati dalam kelebat pedang," kata Khalid bin Ibnu Walid, panglima perang Islam. Mati di kelebat pedang, bagi Khalid adalah mati dalam kerja, dalam tugas, ketika maut menjemput nyawa dengan lekas. Tubuh yang tak akan sempat merasakan apa-apa.
Taufik pun mati dalam semangat yang sama dengan keinginan Khalid, dalam kerja, dalam tugas. Kecelakaan itu, akhir hidup itu, tak perlu dipandang sebagai sesuatu yang tragis.
Tapi memang ada yang tetap terasa tragis. Karena kematian selalu meletakkan seseorang pada kelampauan, keterikatan dalam kenangan, rasa kehilangan. Kematian Taufik pun jadi penuh tangis. "Taufik itu tidak ada celanya, baik sama semua orang. Saat istri saya meninggal, dia yang membawa sampai ke liang lahat," kenang Doyok.
"Kita sayang sama Taufik, tapi Allah lebih sayang. Taufik orang yang tidak pernah bersedih," ucap Derry "Empat Sekawan".
"Dia selalu bahagia. Orangnya baik banget. Dia selalu ingin orang juga bahagia. Kalau dia ada, kita selalu bisa tertawa," cerita Nia Zulkarnain.
Taufik ingin orang lain selalu bahagia, terus tertawa. Itulah kesamaan kenangan di banyak sahabatnya. Tapi, menyaksikan layar teve di hari kematiannya, kesamaan kenangan itu justru lenyap. Yang tampil adalah wajah-wajah sahabat yang sedih, cemas, rimbun airmata dan ratapan. Semangat Taufik seakan tak bersisa lagi, meski dalam isak, Derry masih berkata, "Semoga keceriaan Taufik masih selalu hidup bersama kita." Keceriaan yang mana?
Jika semua sahabat bersaksi bahwa Taufik adalah orang baik, penuh perhatian, kuat memegang bahul agama, apa yang harus diisakkan dari kematiannya. "Dia kerja tidak untuk dirinya sendiri, selalu berbagi. Dia pernah ngomong, 'Gue pengen jadi presiden anak yatim saja'," cerita Heri, adik Taufik. Lalu, untuk apa semua ratapan? Tidakkah tangisan itu hanya untuk menjadi semacam "tanda" keterhubungan dan kedekatan dengan sang mayit? Apalagi, "Setiap tangis kematian," kata Khoping Hoo, "adalah ratapan untuk diri sendiri, yang merasa rugi telah ditinggalkan."
"Dia ingin semua orang bahagia, tertawa," kata Nia, dan tak satu pun layar televisi yang menggambarkannya. Kesedihan disebarluaskan, airmata hanya menjadi milik kematian Taufik. Padahal, yang meninggal bukan Taufik saja, ada dua orang lain yang ikut pergi bersamanya. Padahal, ada kesedihan lain yang juga "dimiliki" keluarga sang supir, Hairuddin, juga Suharsono. Tapi kamera, dan mungkin sahabat Taufik, lupa menunjukkannya. Jika Taufik hidup, saya kira dia akan meminta "penghormatan" kematian yang sama untuk dua orang rekan seperjalanannya, tanpa airmata.
"Sehabis mengerjakan haji wada', Nabi Muhammad SAW menggamit Fatimah," cerita H Mahyaruddin Salim dalam kaset Di Seberang Kematian. "Anakku, ini haji terakhir Ayah. Waktu Ayah tak lama lagi..." Mendengar itu, Fatimah menangis. Rasulullah pun memeluknya, dan bertanya, "Mengapa engkau menangis, Nak? Engkau tidak boleh sedih. Lihat, Ayah akan berada di sana," tunjuk Nabi ke arah langit. Dan saat itu, Fatimah melihat langit terbuka, dan tampaknyalah surga.
"Ayah akan di sana, Yah?"
Rasulullah mengangguk. "Ya, dan engkau yang pertama akan ke sana juga, Anakku. Tidak berapa lama lagi."
Sejak saat itu, Fatimah selalu tersenyum. Ketika Nabi wafat pun, Fatimah tetap tersenyum. Dan benarlah, tak berapa lama, 8 bulan setelah nabi wafat, Fatimah pun menyusulnya.
Meski tak sesempurna Rasulullah, Taufik adalah orang baik, manusia yang selalu ingin berdekatan dengan sang Khalik. Para sahabat menjadi saksi hal itu. Maka, seharusnya, seperti Fatimah RA, sahabat Taufik pun dapat "melihat" surga, dan mengantarnya dengan senyuman. Apalagi, almarhum adalah orang yang selalu ingin menyemaikan kebahagiaan, menetaskan tawa di mana-mana.
Mungkin akan lebih baik, daripada meratap-tangis, para sahabat berkata, "Selamat jalan Fik, kami lepas kau dengan senyuman. Karena kami percaya, maut yang merenggutmu dengan cepat, adalah kerinduan surga. Kami akan tersenyum, karena yang kau tinggalkan adalah kenangan baik, yang kau tuju adalah keabadian yang terbaik. Ya, kami menangis, Fik. Tapi kami percaya, engkau tahu di balik tangis ini tersimpan senyuman, bahkan tawa, bibit yang selalu engkau semai di dunia, yang menafkahi keluargamu, dan jadi ladangmu meraih surga. Selamat jalan Fik, kami lepas kau dengan senyuman..."
[Artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 15 Juli 2007]
( t.i.l.i.k ! )
Monday, July 09, 2007
Dasi tanpa Latar Budaya
Dasi di leher para direktur berwajah siswa SMU adalah jerat yang melilit akal sehat para penjiplak cerita
 Akhirnya Farrel mendapatkan kembali posisinya di dalam perusahaan keluarga. Dia pun meminta Fitri menjadi sekretarisnya. "Karena hanya engkau Fit, yang tetap tabah, sabar, kalau aku marah. Cuma kamu yang bisa mengerti aku," pintanya. Fitri menolak. Dia tak ingin, kehadirannya akan memicu lagi "konflik" antara Farrel dan ayahnya. Farrel kecewa.
Akhirnya Farrel mendapatkan kembali posisinya di dalam perusahaan keluarga. Dia pun meminta Fitri menjadi sekretarisnya. "Karena hanya engkau Fit, yang tetap tabah, sabar, kalau aku marah. Cuma kamu yang bisa mengerti aku," pintanya. Fitri menolak. Dia tak ingin, kehadirannya akan memicu lagi "konflik" antara Farrel dan ayahnya. Farrel kecewa.
Itulah cuplikan sinetron Cinta Fitri yang tayang Minggu malam (1/7) di SCTV. Tak ada yang berubah dari tampilan Farrel, kecuali dasi panjang yang memberati lehernya. Dasi itulah yang menjadi tanda hadirnya kekuasaan, sehingga dia mampu melakukan apa pun untuk menaikkan "status" Fitri.
Dalam Cinta Fitri, selain Farrel, tokoh lain pun acap memakai dasi. Dan dasi itu menjadi "aneh" karena menggayuti leher dari wajah-wajah yang sepantasnya masih duduk di bangku SMU. Lho, kan tidak mengapa anak SMU memakai dasi? Itulah masalahnya. "Wajah" SMU itu sudah menjadi direktur, atau paling rendah, manajer di sebuah perusahaan. Kan perusahaan keluarga? Perusahaan dari keluarga yang paling gila sekalipun tidak akan mungkin meletakkan tanggungjawab usaha di pundak wajah SMU, dan menafikan karier pekerja lain.
Dasi tampaknya menjadi hal yang penting di sinetron "kita". Selain Cinta Fitri, dalam Intan pun "pameran" wajah SMU berdasi ikut mendominasi. Hal sejenis juga hadir dalam Wulan, Sumpah Gue Sayang Loe, Liontin, dan I love U, Boss. Tapi, hadirnya dasi di sinetron itu hanya menjadi tanda status, untuk menjalankan "logika" cerita. Dasi sebagai "tanda" kekuasaan, pengambil keputusan dalam sebuah perusahaan tidak pernah terlihat. Itulah sebabnya, dasi itu hanya hadir di belakang meja penuh berkas dan komputer bagus, bukan dalam situasi rapat yang sarat perdebatan. Ada kontras situasi yang coba dihindari. Sama seperti hilangnya proses karier sehingga sang tokoh belia pantas memakai dasi tersebut.
Cinta Sehari-hari
Ya, proses. Itulah yang alfa dalam jalinan isi sinetron "kita". Barangkali, Si Doel-lah sinetron terakhir yang masih menganggap proses itu penting. Dalam cerita terlihat perjuangan Si Doel meraih karier, sehingga kehadiran dasi di lehernya menjadi sebuah kepantasan. Proses "meraih" dasi itu bukan saja melahirkan konflik, melainkan mengubah seluruh karakter orang-orang yang terlibat dengannya. Doel yang semula rendah diri, perlahan jadi bisa menerima statusnya sebagai anak kampung, dan bangga dengan kebetawiannya. Seiring proses dalam diri si Doel, terjadi juga pergesekan dan pergeseran karakter dalam diri Sarah, Zainab, dan tokoh lainnya. Hebatnya, proses meraih "dasi" itu tersimulasi dalam tarik-menarik antarbudaya. Betawi dan Jawa, Arab dan Belanda, semua memberi andil dalam cerita.
Persoalan cinta dalam Si Doel diletakkan secara wajar, sebagai salah satu warna kehidupan. Bagi Doel, cinta bukan sesuatu yang harus dituhankan, bahkan kadang dianggap tidak penting ketika kehidupan menyeretnya dalam masalah yang lain. Si Doel menunjukkan bahwa hubungan lelaki dan perempuan, bahwa kehidupan, tidak hanya harus bergubal dalam persoalan cinta. Ada percabangan cinta, tapi tak memicu kedengkian dan kejahatan, melainkan kesadaran diri. Dan memang begitulah seharusnya.
Kita kemudian mencatat, Si Doel adalah sinetron yang fenomenal, bukan hanya dalam raihan iklan, melainkan juga respon penonton. Ribuan penonton merasa berhak untuk menentukan kisah cinta Doel dan Sarah. Proses antarmereka --perjuangan Sarah mengubah watak dan kehidupan Si Doel-- di mata penonton, harus diganjar dengan keterpilihannya sebagai istri. Penonton bahkan mendesak Rano Karno, produser sinetron itu, untuk segera menikahkan Si Doel dengan Sarah atau mencarikan lelaki lain untuk menikahi Zainab. Penonton terlibat karena cinta dalam cerita Si Doel adalah cinta yang juga penonton libati dalam kehidupan sehari-hari. Cinta yang lahir sebagai proses kesadaran diri.
Cerita dalam Budaya
Mengapa Si Doel menjadi berbeda? Mengapa Bajaj Bajuri, OB, dan Kiamat Sudah Dekat terasa dekat dengan kehidupan kita? Mungkin, karena sedari awal penonton tahu di wilayah budaya mana lingkup cerita itu terjadi. Ada beda idiom bahasa dan kode busana yang memberi warna dalam keseluruhan cerita, yang dapat kita sepakati sebagai "Indonesia". Sinetron itu berada dalam wilayah yang terjelaskan.
Cinta Fitri, Wulan, Sumpah Gue Sayang Loe, Liontin, dan I love U, Boss berada dalam wilayah imajinasi. Benar, situasi kota, dan plat nomor kendaraan yang mereka gunakan, menjelaskan setting cerita. Tapi, kebeliaan sang tokoh, kode busana, dan struktur cerita justru mengingkarinya. Dan jika cerita itu dipindahkan ke sudut kota mana pun, ke wilayah negara mana pun, pasti tidak akan menimbulkan dampak yang berarti. Karena sedari awal, cerita memang tidak memunculkan dan atau menganggap penting setting budaya.
Ketidakhadiran latar budaya ini dikarenakan banyak cerita sinetron "kita" berasal dari wilayah budaya yang berbeda, Korea. Yang hadir kemudian hanyalah logika cerita, tanpa didukung struktur budaya. Cerita dari drama Korea dicabut begitu saja, dan dimampatkan ke dalam situasi "kita". Itu sebabnya, banyak hal yang kemudian terasa janggal. Karena cerita disesakkan, dijejalkan dalam sebuah situasi yang sebenarnya tidak mendukung. Yang penting kisah bisa berjalan, sinetron dapat diproduksi.
Buku Harian Nayla, misalnya, yang merupakan jiplakan Ichi Rittoru No Namida (1 Litre of Tears), tidak menumbulkan simpati yang berlebih di sini. Di Jepang, karena berasal dari kisah nyata, drama ini terasa begitu membumi dan menimbulkan simpati yang luar biasa. Penonton Jepang merasa memiliki dan mengalami perjuangan Kitou Aya yang hadir dalam struktur budaya sana. Atau Endless Love, yang berdampak luar biasa di Korea. Tabloid Bintang Indonesia pernah mencatat, ada "kesepakatan" di Korea bahwa perempuan yang tidak menangis ketika melihat drama itu dianggap bukan perempuan. Ribuan telepon dan surat penggemar mendatangi stasiun teve KBS meminta agar sang tokoh Eun Suh (Song Hye Kyo) disembuhkan dari leukemianya, dan dijodohkan dengan Joon Suh. Direktur KBS pun meminta sutradara mengubah, tapi tak dikabulkan. Dan seri terakhir drama itu, ketika Eun Suh mati, dan Joon Suh yang kehilangan harapan, justru tertabrak truk saat menyeberangi jalan sambil menggendong jenazah kekasihnya, menjadi adegan yang terpatri dalam ingatan banyak penonton di sana. Dan ketika tayang di sini, di Indosiar, meski sangat memesona penonton, respon yang terjadi tidaklah sedahsyat di Korea. Meski terhanyut, latar budaya Korea cukup "mengasingkan" keterlibatan penonton.
Kita punya Si Doel, Korea punya Endless Love --dua cerita yang lahir dalam wilayah budaya penontonnya-- yang menggerakkan penonton, mengundang simpati, untuk merasa wajib menentukan jalan cerita. Dan seharusnya, pembuat sinetron, pengelola televisi, mau belajar dari sini. Sehingga, kelak tak perlu lagi tertayang karya jiplakan, cerita curian, yang tak mempertimbangkan budaya penonton. Sehingga kelak akan hadir cerita yang membiarkan wajah-wajah SMU berbicara tentang cinta, tanpa harus meleletkan dasi direktur di lehernya. Karena dasi di leher mereka adalah tanda jerat yang melilit akal sehat para penjiplak cerita.
[Artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 8 Juli 2007]
( t.i.l.i.k ! )
 Akhirnya Farrel mendapatkan kembali posisinya di dalam perusahaan keluarga. Dia pun meminta Fitri menjadi sekretarisnya. "Karena hanya engkau Fit, yang tetap tabah, sabar, kalau aku marah. Cuma kamu yang bisa mengerti aku," pintanya. Fitri menolak. Dia tak ingin, kehadirannya akan memicu lagi "konflik" antara Farrel dan ayahnya. Farrel kecewa.
Akhirnya Farrel mendapatkan kembali posisinya di dalam perusahaan keluarga. Dia pun meminta Fitri menjadi sekretarisnya. "Karena hanya engkau Fit, yang tetap tabah, sabar, kalau aku marah. Cuma kamu yang bisa mengerti aku," pintanya. Fitri menolak. Dia tak ingin, kehadirannya akan memicu lagi "konflik" antara Farrel dan ayahnya. Farrel kecewa.Itulah cuplikan sinetron Cinta Fitri yang tayang Minggu malam (1/7) di SCTV. Tak ada yang berubah dari tampilan Farrel, kecuali dasi panjang yang memberati lehernya. Dasi itulah yang menjadi tanda hadirnya kekuasaan, sehingga dia mampu melakukan apa pun untuk menaikkan "status" Fitri.
Dalam Cinta Fitri, selain Farrel, tokoh lain pun acap memakai dasi. Dan dasi itu menjadi "aneh" karena menggayuti leher dari wajah-wajah yang sepantasnya masih duduk di bangku SMU. Lho, kan tidak mengapa anak SMU memakai dasi? Itulah masalahnya. "Wajah" SMU itu sudah menjadi direktur, atau paling rendah, manajer di sebuah perusahaan. Kan perusahaan keluarga? Perusahaan dari keluarga yang paling gila sekalipun tidak akan mungkin meletakkan tanggungjawab usaha di pundak wajah SMU, dan menafikan karier pekerja lain.
Dasi tampaknya menjadi hal yang penting di sinetron "kita". Selain Cinta Fitri, dalam Intan pun "pameran" wajah SMU berdasi ikut mendominasi. Hal sejenis juga hadir dalam Wulan, Sumpah Gue Sayang Loe, Liontin, dan I love U, Boss. Tapi, hadirnya dasi di sinetron itu hanya menjadi tanda status, untuk menjalankan "logika" cerita. Dasi sebagai "tanda" kekuasaan, pengambil keputusan dalam sebuah perusahaan tidak pernah terlihat. Itulah sebabnya, dasi itu hanya hadir di belakang meja penuh berkas dan komputer bagus, bukan dalam situasi rapat yang sarat perdebatan. Ada kontras situasi yang coba dihindari. Sama seperti hilangnya proses karier sehingga sang tokoh belia pantas memakai dasi tersebut.
Cinta Sehari-hari
Ya, proses. Itulah yang alfa dalam jalinan isi sinetron "kita". Barangkali, Si Doel-lah sinetron terakhir yang masih menganggap proses itu penting. Dalam cerita terlihat perjuangan Si Doel meraih karier, sehingga kehadiran dasi di lehernya menjadi sebuah kepantasan. Proses "meraih" dasi itu bukan saja melahirkan konflik, melainkan mengubah seluruh karakter orang-orang yang terlibat dengannya. Doel yang semula rendah diri, perlahan jadi bisa menerima statusnya sebagai anak kampung, dan bangga dengan kebetawiannya. Seiring proses dalam diri si Doel, terjadi juga pergesekan dan pergeseran karakter dalam diri Sarah, Zainab, dan tokoh lainnya. Hebatnya, proses meraih "dasi" itu tersimulasi dalam tarik-menarik antarbudaya. Betawi dan Jawa, Arab dan Belanda, semua memberi andil dalam cerita.
Persoalan cinta dalam Si Doel diletakkan secara wajar, sebagai salah satu warna kehidupan. Bagi Doel, cinta bukan sesuatu yang harus dituhankan, bahkan kadang dianggap tidak penting ketika kehidupan menyeretnya dalam masalah yang lain. Si Doel menunjukkan bahwa hubungan lelaki dan perempuan, bahwa kehidupan, tidak hanya harus bergubal dalam persoalan cinta. Ada percabangan cinta, tapi tak memicu kedengkian dan kejahatan, melainkan kesadaran diri. Dan memang begitulah seharusnya.
Kita kemudian mencatat, Si Doel adalah sinetron yang fenomenal, bukan hanya dalam raihan iklan, melainkan juga respon penonton. Ribuan penonton merasa berhak untuk menentukan kisah cinta Doel dan Sarah. Proses antarmereka --perjuangan Sarah mengubah watak dan kehidupan Si Doel-- di mata penonton, harus diganjar dengan keterpilihannya sebagai istri. Penonton bahkan mendesak Rano Karno, produser sinetron itu, untuk segera menikahkan Si Doel dengan Sarah atau mencarikan lelaki lain untuk menikahi Zainab. Penonton terlibat karena cinta dalam cerita Si Doel adalah cinta yang juga penonton libati dalam kehidupan sehari-hari. Cinta yang lahir sebagai proses kesadaran diri.
Cerita dalam Budaya
Mengapa Si Doel menjadi berbeda? Mengapa Bajaj Bajuri, OB, dan Kiamat Sudah Dekat terasa dekat dengan kehidupan kita? Mungkin, karena sedari awal penonton tahu di wilayah budaya mana lingkup cerita itu terjadi. Ada beda idiom bahasa dan kode busana yang memberi warna dalam keseluruhan cerita, yang dapat kita sepakati sebagai "Indonesia". Sinetron itu berada dalam wilayah yang terjelaskan.
Cinta Fitri, Wulan, Sumpah Gue Sayang Loe, Liontin, dan I love U, Boss berada dalam wilayah imajinasi. Benar, situasi kota, dan plat nomor kendaraan yang mereka gunakan, menjelaskan setting cerita. Tapi, kebeliaan sang tokoh, kode busana, dan struktur cerita justru mengingkarinya. Dan jika cerita itu dipindahkan ke sudut kota mana pun, ke wilayah negara mana pun, pasti tidak akan menimbulkan dampak yang berarti. Karena sedari awal, cerita memang tidak memunculkan dan atau menganggap penting setting budaya.
Ketidakhadiran latar budaya ini dikarenakan banyak cerita sinetron "kita" berasal dari wilayah budaya yang berbeda, Korea. Yang hadir kemudian hanyalah logika cerita, tanpa didukung struktur budaya. Cerita dari drama Korea dicabut begitu saja, dan dimampatkan ke dalam situasi "kita". Itu sebabnya, banyak hal yang kemudian terasa janggal. Karena cerita disesakkan, dijejalkan dalam sebuah situasi yang sebenarnya tidak mendukung. Yang penting kisah bisa berjalan, sinetron dapat diproduksi.
Buku Harian Nayla, misalnya, yang merupakan jiplakan Ichi Rittoru No Namida (1 Litre of Tears), tidak menumbulkan simpati yang berlebih di sini. Di Jepang, karena berasal dari kisah nyata, drama ini terasa begitu membumi dan menimbulkan simpati yang luar biasa. Penonton Jepang merasa memiliki dan mengalami perjuangan Kitou Aya yang hadir dalam struktur budaya sana. Atau Endless Love, yang berdampak luar biasa di Korea. Tabloid Bintang Indonesia pernah mencatat, ada "kesepakatan" di Korea bahwa perempuan yang tidak menangis ketika melihat drama itu dianggap bukan perempuan. Ribuan telepon dan surat penggemar mendatangi stasiun teve KBS meminta agar sang tokoh Eun Suh (Song Hye Kyo) disembuhkan dari leukemianya, dan dijodohkan dengan Joon Suh. Direktur KBS pun meminta sutradara mengubah, tapi tak dikabulkan. Dan seri terakhir drama itu, ketika Eun Suh mati, dan Joon Suh yang kehilangan harapan, justru tertabrak truk saat menyeberangi jalan sambil menggendong jenazah kekasihnya, menjadi adegan yang terpatri dalam ingatan banyak penonton di sana. Dan ketika tayang di sini, di Indosiar, meski sangat memesona penonton, respon yang terjadi tidaklah sedahsyat di Korea. Meski terhanyut, latar budaya Korea cukup "mengasingkan" keterlibatan penonton.
Kita punya Si Doel, Korea punya Endless Love --dua cerita yang lahir dalam wilayah budaya penontonnya-- yang menggerakkan penonton, mengundang simpati, untuk merasa wajib menentukan jalan cerita. Dan seharusnya, pembuat sinetron, pengelola televisi, mau belajar dari sini. Sehingga, kelak tak perlu lagi tertayang karya jiplakan, cerita curian, yang tak mempertimbangkan budaya penonton. Sehingga kelak akan hadir cerita yang membiarkan wajah-wajah SMU berbicara tentang cinta, tanpa harus meleletkan dasi direktur di lehernya. Karena dasi di leher mereka adalah tanda jerat yang melilit akal sehat para penjiplak cerita.
[Artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 8 Juli 2007]
( t.i.l.i.k ! )