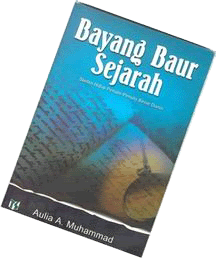...tera di sesela gegas-gesa
Monday, July 23, 2007
Singkong di Paha Lasmini
Dongeng padi berasal dari Dewi Sri, seharusnya tidak muncul sebagai versi "sejarah" di televisi.

LASMINI tersenyum. Dia terus berjalan, seolah tak menyadari puluhan pasang mata yang mengawasinya dari semak dan rerimbun tegalan. Di ujung jalan, langkahnya berhenti, dan sambil membusungkan dada, dia berteriak, "Kisanak, keluarlah! Berapa lama lagi kalian akan terus bersembunyi?!"
Dan dari rerimbun singkong, dua lelaki berkumis bapang keluar, mengadang jalannya. Di sisi kanannya, dari balik jajaran pohon pepaya, dua lelaki gemuk, ngakak gagak, mengurungnya. Tapi Lasmini tetap tenang. Dia tahu, percakapan panjang tak akan ada gunanya. Sambil tetap tersenyum, dia geser kaki kanannya membentuk kuda-kuda. Lasmini telah bersiap diri untuk menghadapi kemungkinan apa pun.
Ya, pasti, pertarungan akan terjadi. Pertempuran yang "indah", bukan karena kelihaian jurus dan kehebatan tenaga dalam, melainkan kelebat tubuh Lasmini yang membuat paha kuningnya acap terpamerkan, perut dan belahan dadanya yang jadi gampang tertangkap kamera. "Lasmini adalah sinetron yang paling saya suka," kata Ayu Anjani, sang pemeran utama di sinetron laga itu, yang nyaris tiap tengah malam tayang di Anteve.
Namun, selain paha dan dada Lasmini, ada beberapa hal lain yang membuat saya selalu menunggu sinetron ini. Pertama, sinetron ini mendekatkan saya dengan masa kecil, senja yang selalu digemai dengan sandiwara radio "Saur Sepuh" dan "Babat Tanah Leluhur". Lasmini adalah tokoh sentral di sini, yang digambarkan sensual, centil, dan tentu saja, sakti. Suara Ivone Rose yang sungguh seksi, apalagi saat dia mendesah menggoda Raden Bentar, melambungkan imajinasi kecil saya ke sudut keliaran yang terdalam. Meski sinetron Lasmini memangkas imajinasi tersebut, yang lari dari pakem cerita di radionya, namun perhubungan kenangan itu tetap saja otomatis terjadi.
Kedua, sinetron ini, juga sinetron laga pada umumnya, berada dalam sebuah lingkup "sejarah" atau epos besar. Lasmini misalnya, diletakkan dalam situasi Kerajaan Pasundan. Akibatnya, mau tidak mau, terkadang cerita fiktif itu harus memasukkan data-data sejarah tentang kerajaan Pasundan dan atau Prabu Siliwangi, juga tentu, struktur kemasyarakatan pada saat itu. Jadi, di balik kelebat tubuh para jagoan dan betinaan, penonton juga mendapatkan renik-renik sejarah, yang bisa dibaca sebagai variasi atau versi lain dari sejarah babon kita. Hal yang sama misalnya, juga dilakukan drama Korea Jewel in The Palace yang tayang setiap sore di Indosiar. Drama itu sangat detil menampilkan Korea tempo dulu. Bukan saja pilihan latar, cara ujar, dan arsitektur bangunan didekatkan dengan situasi asli pada era kerajaan itu, bahkan beda jenis pakaian dan sandal antara kelas masyarakat pun tak lalai ditunjukkan. Drama itu secara piawai menghadirkan masa lalu dengan potret senyatanya. Dan, hal semacam itulah yang sangat sulit ditemukan dalam sinetron laga kita, yang menjadikan latar sejarah hanya sebagai sejarah-sejarahan saja.
1000 tahun Singkong
Dalam adegan Lasmini di atas misalnya, sepintas tak ada yang bermasalah. Penonton akan menganggap wajar pengadangan itu terjadi di tegalan yang ditumbuhi rerimbun pepaya dan singkong. Penonton pasti juga merasa tak terganggu dengan jenis sandal bertali Lasmini, jenis bahan dan gaya busananya. Atau motif kain, ragam senjata, dan jalinan ikat kepala para penjahat. Semua dapat diterima dalam sebuah kewajaran cerita, tak mengganggu, bahkan menambah seru. Namun, jika cerita itu diletakkan dalam latar peristiwa, masa kerajaan Pasundan, akan terciptalah puluhan pertanyaan menyangkut hal di atas. Misalnya konsep tegalan, apakah sudah dikenal pada saat itu? Atau motif batik, sandal menali ke betis, dan gaya berpakaian, apakah memang demikian adanya? Baiklah, penonton bisa menafikan hal itu. Tapi, jajaran pohon pepaya dan rerimbun singkong, dapatkah diterima sebagai kenyataan dari sebuah latar yang dipilih berada di masa keemasan Pasundan?
Kehadiran singkong, entah dalam bentuk pepohonan atau makanan, memang lazim dalam sinetron dan sinema laga kita, untuk menggambarkan kehidupan strata bawah masyarakat. Berbagai sinetron berlatar sejarah kerajaan Majapahit sampai Mataram Islam, acap meletakkan kehadiran kebun singkong dan atau panganan singkong. Padahal, dalam kesejarahannya, singkong dan atau pepaya, tidak mungkin telah "lahir" di masa itu. Ubi kayu atau singkong misalnya, pertama kali hadir justru bukan di tanah Jawa, melainkan di kepulauan Maluku. Itu pun di masa yang jauh kemudian, ketika petualang Portugis membawa tanaman itu dari Amerika Selatan dan mencoba membiakkannya di Maluku. Ingat, kedatangan Portugis tentu di era yang sangat berbeda jauh dengan Majapahit, Pasundan, dan atau Mataram.
Di tanah Jawa, menurut Haryono Rinardi dalam Politik Singkong Zaman Kolonial, sampai tahun 1850-an, singkong belum menjadi tanaman palawija. Hal itu karena jenis singkong dari Amerika Latin tidak cocok ditanam di tanah Jawa. Baru pada tahun 1854, setelah didatangkan varietas singkong dari Kepulauan Antilen Kecil di Karibia, residen di Jawa dan Palembang diperintahkan Belanda untuk mulai menanamnya. Dan setelah tahun 1870-an, singkong ditanam secara besar-besaran di Pulau Jawa akibat meningkatnya permintaan dari Prancis, yang menjadikan ubi kayu sebagai bahan mentah minuman keras pengganti anggur.
Bayangkan, baru 1870-an singkong dijadikan perkebunan di tanah Jawa, tapi mengapa ubi kayu sudah "hadir" dalam sinetron Lasmini, dan cerita berlatar kerajaan lainnya? Itu berarti, oleh perajin sinetron, kelahiran singkong dimajukan nyaris 1000 tahun!
Teh dan Apel
Selain singkong, teh dan apel pun acap tampil dalam sinetron laga kita. Memang, teh hadir bukan sebagai minuman, melainkan menjadi latar pertarungan dan percintaan. Bertarung, lari dan sembunyi di rerimbun teh menjadi hal lazim, sebiasa berkejaran dan bercinta di kebun teh. Padahal, seperti singkong, teh juga bukan tanaman asli Indonesia. Setelah dipopulerkan oleh pedagang Cina dan Arab ke penjuru dunia, teh sampai di Nusantara berkat tangan Andreas Cleyer, yang mencoba membiakkannya di perkebunan Batavia, tahun 1686. Tak ada catatan lengkap mengenai keberhasilan usaha ini. Situs wikipedia pun tak memberikan penjelasan berarti soal Andreas Cleyer. Namun, lewat wikipedia juga, ditemukan sebuah fakta menarik bahwa perkebunan pertama teh di Nusantara baru berhasil di tahun 1828 berkat tangan dingin sinyo JLLL Jacobson. Sebelum itu, meski ada, teh hanya berupa tanaman sporadis, bukan berbentuk perkebunan untuk kepentingan komersial. Jadi, bayangkanlah kehadirannya dalam kebun-kebun penduduk di era kerajaan dulu. Aneh bin ajaib.
Jangan tertawa dulu, karena "penghadiran" singkong dan teh belum seberapa menggelikan. Apel-lah yang memegang rekor kenaifan sejarah ini. Seperti singkong, apel diposisikan sebagai makanan juga, tapi untuk strata atas. Dan kehadirannya acap tertampil sebagai latar dalam sebuah persidangan agung di istana. Dalam sinetron berlatar kerajaan, nyaris kita saksikan selain para pengawal, piala atau nampan makanan pasti menemani duduknya sang raja di singgasana. Dan di atas piala atau nampan buahan itu, dengan "sombong" tampak apel merah. Istana dan raja yang dikelilingi bebuahan mewah, anggur, apel, dan lainnya. Tidakkah pengerajin sinetron itu berpikir, bagaimana caranya apel bisa sampai ke masa itu? Barangkali, hanya raja Brama Kumbara yang bisa menikmati apel itu, karena dia memiliki rajawali sakti yang dapat terbang dan mencapai Amerika, lalu meletakkan apel di dalam paruh besarnya. Itu pun dengan syarat, rajawali tersebut dapat terbang secepat Boeing 747, atau ada lemari pendingin di dalam paruhnya!
Kalau sedikit cerdas, tentu yang hadir sebagai bebuahan raja adalah apel hijau yang dapat penonton identikkan dengan apel Batu, dari Malang. Namun malangnya, apel ini pun baru ditanam di "Indonesia" sekitar tahun 1934. Jadi, sebenarnya, tidak ada satu pun alasan sejarah yang dapat membenarkan kehadiran apel sebagai bebuahan para raja. Demikian juga singkong, teh, kopi, bahkan padi. Karena, menurut sejarawan Prof Dr Soegijanto Padmo, sampai abad ke-19, menanam padi belum menjadi tradisi orang kebanyakan di tanah Jawa.
Jadi, jika Anda menonton sinetron laga berlatar kerajaan di masa Nusantara, janganlah ikutkan pengetahuan sejarah. Tayang di tengah malam, seperti juga Mak Lampir di Indosiar, sejarah singkong, teh dan apel pasti sirna dalam visual sensual, pesona desah-senyum, belahan dada, dan gading paha Lasmini. Ciiaaattt.....
[Artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 29 Juli 2007]

LASMINI tersenyum. Dia terus berjalan, seolah tak menyadari puluhan pasang mata yang mengawasinya dari semak dan rerimbun tegalan. Di ujung jalan, langkahnya berhenti, dan sambil membusungkan dada, dia berteriak, "Kisanak, keluarlah! Berapa lama lagi kalian akan terus bersembunyi?!"
Dan dari rerimbun singkong, dua lelaki berkumis bapang keluar, mengadang jalannya. Di sisi kanannya, dari balik jajaran pohon pepaya, dua lelaki gemuk, ngakak gagak, mengurungnya. Tapi Lasmini tetap tenang. Dia tahu, percakapan panjang tak akan ada gunanya. Sambil tetap tersenyum, dia geser kaki kanannya membentuk kuda-kuda. Lasmini telah bersiap diri untuk menghadapi kemungkinan apa pun.
Ya, pasti, pertarungan akan terjadi. Pertempuran yang "indah", bukan karena kelihaian jurus dan kehebatan tenaga dalam, melainkan kelebat tubuh Lasmini yang membuat paha kuningnya acap terpamerkan, perut dan belahan dadanya yang jadi gampang tertangkap kamera. "Lasmini adalah sinetron yang paling saya suka," kata Ayu Anjani, sang pemeran utama di sinetron laga itu, yang nyaris tiap tengah malam tayang di Anteve.
Namun, selain paha dan dada Lasmini, ada beberapa hal lain yang membuat saya selalu menunggu sinetron ini. Pertama, sinetron ini mendekatkan saya dengan masa kecil, senja yang selalu digemai dengan sandiwara radio "Saur Sepuh" dan "Babat Tanah Leluhur". Lasmini adalah tokoh sentral di sini, yang digambarkan sensual, centil, dan tentu saja, sakti. Suara Ivone Rose yang sungguh seksi, apalagi saat dia mendesah menggoda Raden Bentar, melambungkan imajinasi kecil saya ke sudut keliaran yang terdalam. Meski sinetron Lasmini memangkas imajinasi tersebut, yang lari dari pakem cerita di radionya, namun perhubungan kenangan itu tetap saja otomatis terjadi.
Kedua, sinetron ini, juga sinetron laga pada umumnya, berada dalam sebuah lingkup "sejarah" atau epos besar. Lasmini misalnya, diletakkan dalam situasi Kerajaan Pasundan. Akibatnya, mau tidak mau, terkadang cerita fiktif itu harus memasukkan data-data sejarah tentang kerajaan Pasundan dan atau Prabu Siliwangi, juga tentu, struktur kemasyarakatan pada saat itu. Jadi, di balik kelebat tubuh para jagoan dan betinaan, penonton juga mendapatkan renik-renik sejarah, yang bisa dibaca sebagai variasi atau versi lain dari sejarah babon kita. Hal yang sama misalnya, juga dilakukan drama Korea Jewel in The Palace yang tayang setiap sore di Indosiar. Drama itu sangat detil menampilkan Korea tempo dulu. Bukan saja pilihan latar, cara ujar, dan arsitektur bangunan didekatkan dengan situasi asli pada era kerajaan itu, bahkan beda jenis pakaian dan sandal antara kelas masyarakat pun tak lalai ditunjukkan. Drama itu secara piawai menghadirkan masa lalu dengan potret senyatanya. Dan, hal semacam itulah yang sangat sulit ditemukan dalam sinetron laga kita, yang menjadikan latar sejarah hanya sebagai sejarah-sejarahan saja.
1000 tahun Singkong
Dalam adegan Lasmini di atas misalnya, sepintas tak ada yang bermasalah. Penonton akan menganggap wajar pengadangan itu terjadi di tegalan yang ditumbuhi rerimbun pepaya dan singkong. Penonton pasti juga merasa tak terganggu dengan jenis sandal bertali Lasmini, jenis bahan dan gaya busananya. Atau motif kain, ragam senjata, dan jalinan ikat kepala para penjahat. Semua dapat diterima dalam sebuah kewajaran cerita, tak mengganggu, bahkan menambah seru. Namun, jika cerita itu diletakkan dalam latar peristiwa, masa kerajaan Pasundan, akan terciptalah puluhan pertanyaan menyangkut hal di atas. Misalnya konsep tegalan, apakah sudah dikenal pada saat itu? Atau motif batik, sandal menali ke betis, dan gaya berpakaian, apakah memang demikian adanya? Baiklah, penonton bisa menafikan hal itu. Tapi, jajaran pohon pepaya dan rerimbun singkong, dapatkah diterima sebagai kenyataan dari sebuah latar yang dipilih berada di masa keemasan Pasundan?
Kehadiran singkong, entah dalam bentuk pepohonan atau makanan, memang lazim dalam sinetron dan sinema laga kita, untuk menggambarkan kehidupan strata bawah masyarakat. Berbagai sinetron berlatar sejarah kerajaan Majapahit sampai Mataram Islam, acap meletakkan kehadiran kebun singkong dan atau panganan singkong. Padahal, dalam kesejarahannya, singkong dan atau pepaya, tidak mungkin telah "lahir" di masa itu. Ubi kayu atau singkong misalnya, pertama kali hadir justru bukan di tanah Jawa, melainkan di kepulauan Maluku. Itu pun di masa yang jauh kemudian, ketika petualang Portugis membawa tanaman itu dari Amerika Selatan dan mencoba membiakkannya di Maluku. Ingat, kedatangan Portugis tentu di era yang sangat berbeda jauh dengan Majapahit, Pasundan, dan atau Mataram.
Di tanah Jawa, menurut Haryono Rinardi dalam Politik Singkong Zaman Kolonial, sampai tahun 1850-an, singkong belum menjadi tanaman palawija. Hal itu karena jenis singkong dari Amerika Latin tidak cocok ditanam di tanah Jawa. Baru pada tahun 1854, setelah didatangkan varietas singkong dari Kepulauan Antilen Kecil di Karibia, residen di Jawa dan Palembang diperintahkan Belanda untuk mulai menanamnya. Dan setelah tahun 1870-an, singkong ditanam secara besar-besaran di Pulau Jawa akibat meningkatnya permintaan dari Prancis, yang menjadikan ubi kayu sebagai bahan mentah minuman keras pengganti anggur.
Bayangkan, baru 1870-an singkong dijadikan perkebunan di tanah Jawa, tapi mengapa ubi kayu sudah "hadir" dalam sinetron Lasmini, dan cerita berlatar kerajaan lainnya? Itu berarti, oleh perajin sinetron, kelahiran singkong dimajukan nyaris 1000 tahun!
Teh dan Apel
Selain singkong, teh dan apel pun acap tampil dalam sinetron laga kita. Memang, teh hadir bukan sebagai minuman, melainkan menjadi latar pertarungan dan percintaan. Bertarung, lari dan sembunyi di rerimbun teh menjadi hal lazim, sebiasa berkejaran dan bercinta di kebun teh. Padahal, seperti singkong, teh juga bukan tanaman asli Indonesia. Setelah dipopulerkan oleh pedagang Cina dan Arab ke penjuru dunia, teh sampai di Nusantara berkat tangan Andreas Cleyer, yang mencoba membiakkannya di perkebunan Batavia, tahun 1686. Tak ada catatan lengkap mengenai keberhasilan usaha ini. Situs wikipedia pun tak memberikan penjelasan berarti soal Andreas Cleyer. Namun, lewat wikipedia juga, ditemukan sebuah fakta menarik bahwa perkebunan pertama teh di Nusantara baru berhasil di tahun 1828 berkat tangan dingin sinyo JLLL Jacobson. Sebelum itu, meski ada, teh hanya berupa tanaman sporadis, bukan berbentuk perkebunan untuk kepentingan komersial. Jadi, bayangkanlah kehadirannya dalam kebun-kebun penduduk di era kerajaan dulu. Aneh bin ajaib.
Jangan tertawa dulu, karena "penghadiran" singkong dan teh belum seberapa menggelikan. Apel-lah yang memegang rekor kenaifan sejarah ini. Seperti singkong, apel diposisikan sebagai makanan juga, tapi untuk strata atas. Dan kehadirannya acap tertampil sebagai latar dalam sebuah persidangan agung di istana. Dalam sinetron berlatar kerajaan, nyaris kita saksikan selain para pengawal, piala atau nampan makanan pasti menemani duduknya sang raja di singgasana. Dan di atas piala atau nampan buahan itu, dengan "sombong" tampak apel merah. Istana dan raja yang dikelilingi bebuahan mewah, anggur, apel, dan lainnya. Tidakkah pengerajin sinetron itu berpikir, bagaimana caranya apel bisa sampai ke masa itu? Barangkali, hanya raja Brama Kumbara yang bisa menikmati apel itu, karena dia memiliki rajawali sakti yang dapat terbang dan mencapai Amerika, lalu meletakkan apel di dalam paruh besarnya. Itu pun dengan syarat, rajawali tersebut dapat terbang secepat Boeing 747, atau ada lemari pendingin di dalam paruhnya!
Kalau sedikit cerdas, tentu yang hadir sebagai bebuahan raja adalah apel hijau yang dapat penonton identikkan dengan apel Batu, dari Malang. Namun malangnya, apel ini pun baru ditanam di "Indonesia" sekitar tahun 1934. Jadi, sebenarnya, tidak ada satu pun alasan sejarah yang dapat membenarkan kehadiran apel sebagai bebuahan para raja. Demikian juga singkong, teh, kopi, bahkan padi. Karena, menurut sejarawan Prof Dr Soegijanto Padmo, sampai abad ke-19, menanam padi belum menjadi tradisi orang kebanyakan di tanah Jawa.
Jadi, jika Anda menonton sinetron laga berlatar kerajaan di masa Nusantara, janganlah ikutkan pengetahuan sejarah. Tayang di tengah malam, seperti juga Mak Lampir di Indosiar, sejarah singkong, teh dan apel pasti sirna dalam visual sensual, pesona desah-senyum, belahan dada, dan gading paha Lasmini. Ciiaaattt.....
[Artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 29 Juli 2007]