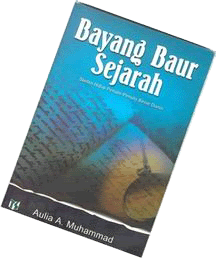...tera di sesela gegas-gesa
Friday, July 13, 2007
Kami Lepas Kau dengan Senyuman
"Dia pernah ngomong, 'Gue pengen jadi presiden anak yatim saja'," cerita Heri, adik Taufik.

"Tidak usah takut. Jika gagal, engkau tak akan sempat merasakan apa-apa," kata Sersan Cappy. Di depannya, Cahill tampak gugup dan takut, berkali-kali tak berani meletakkan pipet untuk menambal picu bom gas syaraf agar tak meledak. Tapi, setelah mendengar kalimat Cappy, dia mengerdikkan bahu, terdiam, dan kembali mencoba menaklukkan bom itu. Ketakutannya telah padam.
"Engkau tak akan sempat merasakan apa-apa." Cappy mengatakan itu sekitar pukul 10 malam, lewat adegan dalam film Executive Decision yang tayang di TransTV, Rabu (11/7) lalu. Dan di sekitar waktu itu juga, dalam dimensi ruang yang berbeda, di KM 13 jalan Purworejo-Yogyakarta, Taufik Savalas kecelakaan. Truk bermuatan semen menghantam Kijang yang dia tumpangi. Hantaman yang teramat dahsyat. Melalui kamera teve, tertayang badan Kijang yang hancur di sisi kanan, ringsek. Dan di dalam ringsekan itu, berdiam tubuh Taufik, terjepit lesakan rangka kabin. Tubuh, raga, jasad, yang sudah dilupakan nyawa. Tubuh yang "tak akan sempat merasakan apa-apa", karena nyawa lepas dengan lekas.
"Taufik meninggal seketika," terang Indro Warkop, saat menggelar jumpa pers, Kamis dini hari, dengan suara terbata-bata. Di sebelahnya, duduk Eko Patrio dan Derry "Empat Sekawan", tanpa wajah ceria sebagaimana biasanya mereka jika berhadapan dengan kamera. "Keluarga sampai saat ini masih shock, masih sulit menerima. Saya memahami hal itu," tambah Indro.
"Meninggal seketika," seperti kata Indro, adalah terma untuk mewartakan kematian yang baik, kematian tanpa siksa, tubuh yang "tak akan sempat merasakan apa-apa", ketika fase sakratul maut seakan luput. "Gue cuma ingin jadi orang baik, itu saja. Di mana ketika ninggalin dunia ini, gue mendapat khusnul khatimah," kata Taufik, suatu saat. "Setiap beribadah, salat, umroh, haji, doa saya cuma satu, ridlo-Mu ya Allah. Jika Allah sudah ridlo, sudahlah... Itu saja."
Meninggal seketika juga menunjukkan bahwa maut bukanlah sesuatu yang datang dari jauh. Dia dekat, memeluk kita sejak ruh berada dalam jasad. "Dan kematian jadi akrab," tulis Subagio Sastrowardoyo, "seakan kawan berkelakar yang mengajak tertawa." Mati atau maut bersenyawa dan bertaut dalam hidup. Maut dengan demikian, seharusnya, bukanlah sesuatu yang dapat membuat takut.
Tapi, memang ada maut yang membuat ciut. "Ketika dia datang dengan wajah hitam-jelaga dan merah-marah," kata Bawa Muhaiyaddeen, mursyid dari India itu. Maut yang hitam, maut yang merah, menjemput hidup dengan marah, dengan paksa, memberi siksa. Terentang jeda panjang ketika nyawa, meski tahu pasti kalah, tetap ingin bertahan di dunia. Hanya wajah putih-kertas yang membuat nyawa pergi dengan gegas, bayi yang kehausan dan mendapat susu. Di situ, maut datang dengan membujuk, agar tubuh tak sempat merasakan apa-apa. "Aku tak dapat membayangkan jika sampai mati di atas tempat tidur. Hidupku dalam perang, aku ingin mati dalam kelebat pedang," kata Khalid bin Ibnu Walid, panglima perang Islam. Mati di kelebat pedang, bagi Khalid adalah mati dalam kerja, dalam tugas, ketika maut menjemput nyawa dengan lekas. Tubuh yang tak akan sempat merasakan apa-apa.
Taufik pun mati dalam semangat yang sama dengan keinginan Khalid, dalam kerja, dalam tugas. Kecelakaan itu, akhir hidup itu, tak perlu dipandang sebagai sesuatu yang tragis.
Tapi memang ada yang tetap terasa tragis. Karena kematian selalu meletakkan seseorang pada kelampauan, keterikatan dalam kenangan, rasa kehilangan. Kematian Taufik pun jadi penuh tangis. "Taufik itu tidak ada celanya, baik sama semua orang. Saat istri saya meninggal, dia yang membawa sampai ke liang lahat," kenang Doyok.
"Kita sayang sama Taufik, tapi Allah lebih sayang. Taufik orang yang tidak pernah bersedih," ucap Derry "Empat Sekawan".
"Dia selalu bahagia. Orangnya baik banget. Dia selalu ingin orang juga bahagia. Kalau dia ada, kita selalu bisa tertawa," cerita Nia Zulkarnain.
Taufik ingin orang lain selalu bahagia, terus tertawa. Itulah kesamaan kenangan di banyak sahabatnya. Tapi, menyaksikan layar teve di hari kematiannya, kesamaan kenangan itu justru lenyap. Yang tampil adalah wajah-wajah sahabat yang sedih, cemas, rimbun airmata dan ratapan. Semangat Taufik seakan tak bersisa lagi, meski dalam isak, Derry masih berkata, "Semoga keceriaan Taufik masih selalu hidup bersama kita." Keceriaan yang mana?
Jika semua sahabat bersaksi bahwa Taufik adalah orang baik, penuh perhatian, kuat memegang bahul agama, apa yang harus diisakkan dari kematiannya. "Dia kerja tidak untuk dirinya sendiri, selalu berbagi. Dia pernah ngomong, 'Gue pengen jadi presiden anak yatim saja'," cerita Heri, adik Taufik. Lalu, untuk apa semua ratapan? Tidakkah tangisan itu hanya untuk menjadi semacam "tanda" keterhubungan dan kedekatan dengan sang mayit? Apalagi, "Setiap tangis kematian," kata Khoping Hoo, "adalah ratapan untuk diri sendiri, yang merasa rugi telah ditinggalkan."
"Dia ingin semua orang bahagia, tertawa," kata Nia, dan tak satu pun layar televisi yang menggambarkannya. Kesedihan disebarluaskan, airmata hanya menjadi milik kematian Taufik. Padahal, yang meninggal bukan Taufik saja, ada dua orang lain yang ikut pergi bersamanya. Padahal, ada kesedihan lain yang juga "dimiliki" keluarga sang supir, Hairuddin, juga Suharsono. Tapi kamera, dan mungkin sahabat Taufik, lupa menunjukkannya. Jika Taufik hidup, saya kira dia akan meminta "penghormatan" kematian yang sama untuk dua orang rekan seperjalanannya, tanpa airmata.
"Sehabis mengerjakan haji wada', Nabi Muhammad SAW menggamit Fatimah," cerita H Mahyaruddin Salim dalam kaset Di Seberang Kematian. "Anakku, ini haji terakhir Ayah. Waktu Ayah tak lama lagi..." Mendengar itu, Fatimah menangis. Rasulullah pun memeluknya, dan bertanya, "Mengapa engkau menangis, Nak? Engkau tidak boleh sedih. Lihat, Ayah akan berada di sana," tunjuk Nabi ke arah langit. Dan saat itu, Fatimah melihat langit terbuka, dan tampaknyalah surga.
"Ayah akan di sana, Yah?"
Rasulullah mengangguk. "Ya, dan engkau yang pertama akan ke sana juga, Anakku. Tidak berapa lama lagi."
Sejak saat itu, Fatimah selalu tersenyum. Ketika Nabi wafat pun, Fatimah tetap tersenyum. Dan benarlah, tak berapa lama, 8 bulan setelah nabi wafat, Fatimah pun menyusulnya.
Meski tak sesempurna Rasulullah, Taufik adalah orang baik, manusia yang selalu ingin berdekatan dengan sang Khalik. Para sahabat menjadi saksi hal itu. Maka, seharusnya, seperti Fatimah RA, sahabat Taufik pun dapat "melihat" surga, dan mengantarnya dengan senyuman. Apalagi, almarhum adalah orang yang selalu ingin menyemaikan kebahagiaan, menetaskan tawa di mana-mana.
Mungkin akan lebih baik, daripada meratap-tangis, para sahabat berkata, "Selamat jalan Fik, kami lepas kau dengan senyuman. Karena kami percaya, maut yang merenggutmu dengan cepat, adalah kerinduan surga. Kami akan tersenyum, karena yang kau tinggalkan adalah kenangan baik, yang kau tuju adalah keabadian yang terbaik. Ya, kami menangis, Fik. Tapi kami percaya, engkau tahu di balik tangis ini tersimpan senyuman, bahkan tawa, bibit yang selalu engkau semai di dunia, yang menafkahi keluargamu, dan jadi ladangmu meraih surga. Selamat jalan Fik, kami lepas kau dengan senyuman..."
[Artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 15 Juli 2007]

"Tidak usah takut. Jika gagal, engkau tak akan sempat merasakan apa-apa," kata Sersan Cappy. Di depannya, Cahill tampak gugup dan takut, berkali-kali tak berani meletakkan pipet untuk menambal picu bom gas syaraf agar tak meledak. Tapi, setelah mendengar kalimat Cappy, dia mengerdikkan bahu, terdiam, dan kembali mencoba menaklukkan bom itu. Ketakutannya telah padam.
"Engkau tak akan sempat merasakan apa-apa." Cappy mengatakan itu sekitar pukul 10 malam, lewat adegan dalam film Executive Decision yang tayang di TransTV, Rabu (11/7) lalu. Dan di sekitar waktu itu juga, dalam dimensi ruang yang berbeda, di KM 13 jalan Purworejo-Yogyakarta, Taufik Savalas kecelakaan. Truk bermuatan semen menghantam Kijang yang dia tumpangi. Hantaman yang teramat dahsyat. Melalui kamera teve, tertayang badan Kijang yang hancur di sisi kanan, ringsek. Dan di dalam ringsekan itu, berdiam tubuh Taufik, terjepit lesakan rangka kabin. Tubuh, raga, jasad, yang sudah dilupakan nyawa. Tubuh yang "tak akan sempat merasakan apa-apa", karena nyawa lepas dengan lekas.
"Taufik meninggal seketika," terang Indro Warkop, saat menggelar jumpa pers, Kamis dini hari, dengan suara terbata-bata. Di sebelahnya, duduk Eko Patrio dan Derry "Empat Sekawan", tanpa wajah ceria sebagaimana biasanya mereka jika berhadapan dengan kamera. "Keluarga sampai saat ini masih shock, masih sulit menerima. Saya memahami hal itu," tambah Indro.
"Meninggal seketika," seperti kata Indro, adalah terma untuk mewartakan kematian yang baik, kematian tanpa siksa, tubuh yang "tak akan sempat merasakan apa-apa", ketika fase sakratul maut seakan luput. "Gue cuma ingin jadi orang baik, itu saja. Di mana ketika ninggalin dunia ini, gue mendapat khusnul khatimah," kata Taufik, suatu saat. "Setiap beribadah, salat, umroh, haji, doa saya cuma satu, ridlo-Mu ya Allah. Jika Allah sudah ridlo, sudahlah... Itu saja."
Meninggal seketika juga menunjukkan bahwa maut bukanlah sesuatu yang datang dari jauh. Dia dekat, memeluk kita sejak ruh berada dalam jasad. "Dan kematian jadi akrab," tulis Subagio Sastrowardoyo, "seakan kawan berkelakar yang mengajak tertawa." Mati atau maut bersenyawa dan bertaut dalam hidup. Maut dengan demikian, seharusnya, bukanlah sesuatu yang dapat membuat takut.
Tapi, memang ada maut yang membuat ciut. "Ketika dia datang dengan wajah hitam-jelaga dan merah-marah," kata Bawa Muhaiyaddeen, mursyid dari India itu. Maut yang hitam, maut yang merah, menjemput hidup dengan marah, dengan paksa, memberi siksa. Terentang jeda panjang ketika nyawa, meski tahu pasti kalah, tetap ingin bertahan di dunia. Hanya wajah putih-kertas yang membuat nyawa pergi dengan gegas, bayi yang kehausan dan mendapat susu. Di situ, maut datang dengan membujuk, agar tubuh tak sempat merasakan apa-apa. "Aku tak dapat membayangkan jika sampai mati di atas tempat tidur. Hidupku dalam perang, aku ingin mati dalam kelebat pedang," kata Khalid bin Ibnu Walid, panglima perang Islam. Mati di kelebat pedang, bagi Khalid adalah mati dalam kerja, dalam tugas, ketika maut menjemput nyawa dengan lekas. Tubuh yang tak akan sempat merasakan apa-apa.
Taufik pun mati dalam semangat yang sama dengan keinginan Khalid, dalam kerja, dalam tugas. Kecelakaan itu, akhir hidup itu, tak perlu dipandang sebagai sesuatu yang tragis.
Tapi memang ada yang tetap terasa tragis. Karena kematian selalu meletakkan seseorang pada kelampauan, keterikatan dalam kenangan, rasa kehilangan. Kematian Taufik pun jadi penuh tangis. "Taufik itu tidak ada celanya, baik sama semua orang. Saat istri saya meninggal, dia yang membawa sampai ke liang lahat," kenang Doyok.
"Kita sayang sama Taufik, tapi Allah lebih sayang. Taufik orang yang tidak pernah bersedih," ucap Derry "Empat Sekawan".
"Dia selalu bahagia. Orangnya baik banget. Dia selalu ingin orang juga bahagia. Kalau dia ada, kita selalu bisa tertawa," cerita Nia Zulkarnain.
Taufik ingin orang lain selalu bahagia, terus tertawa. Itulah kesamaan kenangan di banyak sahabatnya. Tapi, menyaksikan layar teve di hari kematiannya, kesamaan kenangan itu justru lenyap. Yang tampil adalah wajah-wajah sahabat yang sedih, cemas, rimbun airmata dan ratapan. Semangat Taufik seakan tak bersisa lagi, meski dalam isak, Derry masih berkata, "Semoga keceriaan Taufik masih selalu hidup bersama kita." Keceriaan yang mana?
Jika semua sahabat bersaksi bahwa Taufik adalah orang baik, penuh perhatian, kuat memegang bahul agama, apa yang harus diisakkan dari kematiannya. "Dia kerja tidak untuk dirinya sendiri, selalu berbagi. Dia pernah ngomong, 'Gue pengen jadi presiden anak yatim saja'," cerita Heri, adik Taufik. Lalu, untuk apa semua ratapan? Tidakkah tangisan itu hanya untuk menjadi semacam "tanda" keterhubungan dan kedekatan dengan sang mayit? Apalagi, "Setiap tangis kematian," kata Khoping Hoo, "adalah ratapan untuk diri sendiri, yang merasa rugi telah ditinggalkan."
"Dia ingin semua orang bahagia, tertawa," kata Nia, dan tak satu pun layar televisi yang menggambarkannya. Kesedihan disebarluaskan, airmata hanya menjadi milik kematian Taufik. Padahal, yang meninggal bukan Taufik saja, ada dua orang lain yang ikut pergi bersamanya. Padahal, ada kesedihan lain yang juga "dimiliki" keluarga sang supir, Hairuddin, juga Suharsono. Tapi kamera, dan mungkin sahabat Taufik, lupa menunjukkannya. Jika Taufik hidup, saya kira dia akan meminta "penghormatan" kematian yang sama untuk dua orang rekan seperjalanannya, tanpa airmata.
"Sehabis mengerjakan haji wada', Nabi Muhammad SAW menggamit Fatimah," cerita H Mahyaruddin Salim dalam kaset Di Seberang Kematian. "Anakku, ini haji terakhir Ayah. Waktu Ayah tak lama lagi..." Mendengar itu, Fatimah menangis. Rasulullah pun memeluknya, dan bertanya, "Mengapa engkau menangis, Nak? Engkau tidak boleh sedih. Lihat, Ayah akan berada di sana," tunjuk Nabi ke arah langit. Dan saat itu, Fatimah melihat langit terbuka, dan tampaknyalah surga.
"Ayah akan di sana, Yah?"
Rasulullah mengangguk. "Ya, dan engkau yang pertama akan ke sana juga, Anakku. Tidak berapa lama lagi."
Sejak saat itu, Fatimah selalu tersenyum. Ketika Nabi wafat pun, Fatimah tetap tersenyum. Dan benarlah, tak berapa lama, 8 bulan setelah nabi wafat, Fatimah pun menyusulnya.
Meski tak sesempurna Rasulullah, Taufik adalah orang baik, manusia yang selalu ingin berdekatan dengan sang Khalik. Para sahabat menjadi saksi hal itu. Maka, seharusnya, seperti Fatimah RA, sahabat Taufik pun dapat "melihat" surga, dan mengantarnya dengan senyuman. Apalagi, almarhum adalah orang yang selalu ingin menyemaikan kebahagiaan, menetaskan tawa di mana-mana.
Mungkin akan lebih baik, daripada meratap-tangis, para sahabat berkata, "Selamat jalan Fik, kami lepas kau dengan senyuman. Karena kami percaya, maut yang merenggutmu dengan cepat, adalah kerinduan surga. Kami akan tersenyum, karena yang kau tinggalkan adalah kenangan baik, yang kau tuju adalah keabadian yang terbaik. Ya, kami menangis, Fik. Tapi kami percaya, engkau tahu di balik tangis ini tersimpan senyuman, bahkan tawa, bibit yang selalu engkau semai di dunia, yang menafkahi keluargamu, dan jadi ladangmu meraih surga. Selamat jalan Fik, kami lepas kau dengan senyuman..."
[Artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 15 Juli 2007]