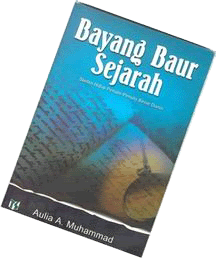...tera di sesela gegas-gesa
Monday, July 09, 2007
Dasi tanpa Latar Budaya
Dasi di leher para direktur berwajah siswa SMU adalah jerat yang melilit akal sehat para penjiplak cerita
 Akhirnya Farrel mendapatkan kembali posisinya di dalam perusahaan keluarga. Dia pun meminta Fitri menjadi sekretarisnya. "Karena hanya engkau Fit, yang tetap tabah, sabar, kalau aku marah. Cuma kamu yang bisa mengerti aku," pintanya. Fitri menolak. Dia tak ingin, kehadirannya akan memicu lagi "konflik" antara Farrel dan ayahnya. Farrel kecewa.
Akhirnya Farrel mendapatkan kembali posisinya di dalam perusahaan keluarga. Dia pun meminta Fitri menjadi sekretarisnya. "Karena hanya engkau Fit, yang tetap tabah, sabar, kalau aku marah. Cuma kamu yang bisa mengerti aku," pintanya. Fitri menolak. Dia tak ingin, kehadirannya akan memicu lagi "konflik" antara Farrel dan ayahnya. Farrel kecewa.
Itulah cuplikan sinetron Cinta Fitri yang tayang Minggu malam (1/7) di SCTV. Tak ada yang berubah dari tampilan Farrel, kecuali dasi panjang yang memberati lehernya. Dasi itulah yang menjadi tanda hadirnya kekuasaan, sehingga dia mampu melakukan apa pun untuk menaikkan "status" Fitri.
Dalam Cinta Fitri, selain Farrel, tokoh lain pun acap memakai dasi. Dan dasi itu menjadi "aneh" karena menggayuti leher dari wajah-wajah yang sepantasnya masih duduk di bangku SMU. Lho, kan tidak mengapa anak SMU memakai dasi? Itulah masalahnya. "Wajah" SMU itu sudah menjadi direktur, atau paling rendah, manajer di sebuah perusahaan. Kan perusahaan keluarga? Perusahaan dari keluarga yang paling gila sekalipun tidak akan mungkin meletakkan tanggungjawab usaha di pundak wajah SMU, dan menafikan karier pekerja lain.
Dasi tampaknya menjadi hal yang penting di sinetron "kita". Selain Cinta Fitri, dalam Intan pun "pameran" wajah SMU berdasi ikut mendominasi. Hal sejenis juga hadir dalam Wulan, Sumpah Gue Sayang Loe, Liontin, dan I love U, Boss. Tapi, hadirnya dasi di sinetron itu hanya menjadi tanda status, untuk menjalankan "logika" cerita. Dasi sebagai "tanda" kekuasaan, pengambil keputusan dalam sebuah perusahaan tidak pernah terlihat. Itulah sebabnya, dasi itu hanya hadir di belakang meja penuh berkas dan komputer bagus, bukan dalam situasi rapat yang sarat perdebatan. Ada kontras situasi yang coba dihindari. Sama seperti hilangnya proses karier sehingga sang tokoh belia pantas memakai dasi tersebut.
Cinta Sehari-hari
Ya, proses. Itulah yang alfa dalam jalinan isi sinetron "kita". Barangkali, Si Doel-lah sinetron terakhir yang masih menganggap proses itu penting. Dalam cerita terlihat perjuangan Si Doel meraih karier, sehingga kehadiran dasi di lehernya menjadi sebuah kepantasan. Proses "meraih" dasi itu bukan saja melahirkan konflik, melainkan mengubah seluruh karakter orang-orang yang terlibat dengannya. Doel yang semula rendah diri, perlahan jadi bisa menerima statusnya sebagai anak kampung, dan bangga dengan kebetawiannya. Seiring proses dalam diri si Doel, terjadi juga pergesekan dan pergeseran karakter dalam diri Sarah, Zainab, dan tokoh lainnya. Hebatnya, proses meraih "dasi" itu tersimulasi dalam tarik-menarik antarbudaya. Betawi dan Jawa, Arab dan Belanda, semua memberi andil dalam cerita.
Persoalan cinta dalam Si Doel diletakkan secara wajar, sebagai salah satu warna kehidupan. Bagi Doel, cinta bukan sesuatu yang harus dituhankan, bahkan kadang dianggap tidak penting ketika kehidupan menyeretnya dalam masalah yang lain. Si Doel menunjukkan bahwa hubungan lelaki dan perempuan, bahwa kehidupan, tidak hanya harus bergubal dalam persoalan cinta. Ada percabangan cinta, tapi tak memicu kedengkian dan kejahatan, melainkan kesadaran diri. Dan memang begitulah seharusnya.
Kita kemudian mencatat, Si Doel adalah sinetron yang fenomenal, bukan hanya dalam raihan iklan, melainkan juga respon penonton. Ribuan penonton merasa berhak untuk menentukan kisah cinta Doel dan Sarah. Proses antarmereka --perjuangan Sarah mengubah watak dan kehidupan Si Doel-- di mata penonton, harus diganjar dengan keterpilihannya sebagai istri. Penonton bahkan mendesak Rano Karno, produser sinetron itu, untuk segera menikahkan Si Doel dengan Sarah atau mencarikan lelaki lain untuk menikahi Zainab. Penonton terlibat karena cinta dalam cerita Si Doel adalah cinta yang juga penonton libati dalam kehidupan sehari-hari. Cinta yang lahir sebagai proses kesadaran diri.
Cerita dalam Budaya
Mengapa Si Doel menjadi berbeda? Mengapa Bajaj Bajuri, OB, dan Kiamat Sudah Dekat terasa dekat dengan kehidupan kita? Mungkin, karena sedari awal penonton tahu di wilayah budaya mana lingkup cerita itu terjadi. Ada beda idiom bahasa dan kode busana yang memberi warna dalam keseluruhan cerita, yang dapat kita sepakati sebagai "Indonesia". Sinetron itu berada dalam wilayah yang terjelaskan.
Cinta Fitri, Wulan, Sumpah Gue Sayang Loe, Liontin, dan I love U, Boss berada dalam wilayah imajinasi. Benar, situasi kota, dan plat nomor kendaraan yang mereka gunakan, menjelaskan setting cerita. Tapi, kebeliaan sang tokoh, kode busana, dan struktur cerita justru mengingkarinya. Dan jika cerita itu dipindahkan ke sudut kota mana pun, ke wilayah negara mana pun, pasti tidak akan menimbulkan dampak yang berarti. Karena sedari awal, cerita memang tidak memunculkan dan atau menganggap penting setting budaya.
Ketidakhadiran latar budaya ini dikarenakan banyak cerita sinetron "kita" berasal dari wilayah budaya yang berbeda, Korea. Yang hadir kemudian hanyalah logika cerita, tanpa didukung struktur budaya. Cerita dari drama Korea dicabut begitu saja, dan dimampatkan ke dalam situasi "kita". Itu sebabnya, banyak hal yang kemudian terasa janggal. Karena cerita disesakkan, dijejalkan dalam sebuah situasi yang sebenarnya tidak mendukung. Yang penting kisah bisa berjalan, sinetron dapat diproduksi.
Buku Harian Nayla, misalnya, yang merupakan jiplakan Ichi Rittoru No Namida (1 Litre of Tears), tidak menumbulkan simpati yang berlebih di sini. Di Jepang, karena berasal dari kisah nyata, drama ini terasa begitu membumi dan menimbulkan simpati yang luar biasa. Penonton Jepang merasa memiliki dan mengalami perjuangan Kitou Aya yang hadir dalam struktur budaya sana. Atau Endless Love, yang berdampak luar biasa di Korea. Tabloid Bintang Indonesia pernah mencatat, ada "kesepakatan" di Korea bahwa perempuan yang tidak menangis ketika melihat drama itu dianggap bukan perempuan. Ribuan telepon dan surat penggemar mendatangi stasiun teve KBS meminta agar sang tokoh Eun Suh (Song Hye Kyo) disembuhkan dari leukemianya, dan dijodohkan dengan Joon Suh. Direktur KBS pun meminta sutradara mengubah, tapi tak dikabulkan. Dan seri terakhir drama itu, ketika Eun Suh mati, dan Joon Suh yang kehilangan harapan, justru tertabrak truk saat menyeberangi jalan sambil menggendong jenazah kekasihnya, menjadi adegan yang terpatri dalam ingatan banyak penonton di sana. Dan ketika tayang di sini, di Indosiar, meski sangat memesona penonton, respon yang terjadi tidaklah sedahsyat di Korea. Meski terhanyut, latar budaya Korea cukup "mengasingkan" keterlibatan penonton.
Kita punya Si Doel, Korea punya Endless Love --dua cerita yang lahir dalam wilayah budaya penontonnya-- yang menggerakkan penonton, mengundang simpati, untuk merasa wajib menentukan jalan cerita. Dan seharusnya, pembuat sinetron, pengelola televisi, mau belajar dari sini. Sehingga, kelak tak perlu lagi tertayang karya jiplakan, cerita curian, yang tak mempertimbangkan budaya penonton. Sehingga kelak akan hadir cerita yang membiarkan wajah-wajah SMU berbicara tentang cinta, tanpa harus meleletkan dasi direktur di lehernya. Karena dasi di leher mereka adalah tanda jerat yang melilit akal sehat para penjiplak cerita.
[Artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 8 Juli 2007]
 Akhirnya Farrel mendapatkan kembali posisinya di dalam perusahaan keluarga. Dia pun meminta Fitri menjadi sekretarisnya. "Karena hanya engkau Fit, yang tetap tabah, sabar, kalau aku marah. Cuma kamu yang bisa mengerti aku," pintanya. Fitri menolak. Dia tak ingin, kehadirannya akan memicu lagi "konflik" antara Farrel dan ayahnya. Farrel kecewa.
Akhirnya Farrel mendapatkan kembali posisinya di dalam perusahaan keluarga. Dia pun meminta Fitri menjadi sekretarisnya. "Karena hanya engkau Fit, yang tetap tabah, sabar, kalau aku marah. Cuma kamu yang bisa mengerti aku," pintanya. Fitri menolak. Dia tak ingin, kehadirannya akan memicu lagi "konflik" antara Farrel dan ayahnya. Farrel kecewa.Itulah cuplikan sinetron Cinta Fitri yang tayang Minggu malam (1/7) di SCTV. Tak ada yang berubah dari tampilan Farrel, kecuali dasi panjang yang memberati lehernya. Dasi itulah yang menjadi tanda hadirnya kekuasaan, sehingga dia mampu melakukan apa pun untuk menaikkan "status" Fitri.
Dalam Cinta Fitri, selain Farrel, tokoh lain pun acap memakai dasi. Dan dasi itu menjadi "aneh" karena menggayuti leher dari wajah-wajah yang sepantasnya masih duduk di bangku SMU. Lho, kan tidak mengapa anak SMU memakai dasi? Itulah masalahnya. "Wajah" SMU itu sudah menjadi direktur, atau paling rendah, manajer di sebuah perusahaan. Kan perusahaan keluarga? Perusahaan dari keluarga yang paling gila sekalipun tidak akan mungkin meletakkan tanggungjawab usaha di pundak wajah SMU, dan menafikan karier pekerja lain.
Dasi tampaknya menjadi hal yang penting di sinetron "kita". Selain Cinta Fitri, dalam Intan pun "pameran" wajah SMU berdasi ikut mendominasi. Hal sejenis juga hadir dalam Wulan, Sumpah Gue Sayang Loe, Liontin, dan I love U, Boss. Tapi, hadirnya dasi di sinetron itu hanya menjadi tanda status, untuk menjalankan "logika" cerita. Dasi sebagai "tanda" kekuasaan, pengambil keputusan dalam sebuah perusahaan tidak pernah terlihat. Itulah sebabnya, dasi itu hanya hadir di belakang meja penuh berkas dan komputer bagus, bukan dalam situasi rapat yang sarat perdebatan. Ada kontras situasi yang coba dihindari. Sama seperti hilangnya proses karier sehingga sang tokoh belia pantas memakai dasi tersebut.
Cinta Sehari-hari
Ya, proses. Itulah yang alfa dalam jalinan isi sinetron "kita". Barangkali, Si Doel-lah sinetron terakhir yang masih menganggap proses itu penting. Dalam cerita terlihat perjuangan Si Doel meraih karier, sehingga kehadiran dasi di lehernya menjadi sebuah kepantasan. Proses "meraih" dasi itu bukan saja melahirkan konflik, melainkan mengubah seluruh karakter orang-orang yang terlibat dengannya. Doel yang semula rendah diri, perlahan jadi bisa menerima statusnya sebagai anak kampung, dan bangga dengan kebetawiannya. Seiring proses dalam diri si Doel, terjadi juga pergesekan dan pergeseran karakter dalam diri Sarah, Zainab, dan tokoh lainnya. Hebatnya, proses meraih "dasi" itu tersimulasi dalam tarik-menarik antarbudaya. Betawi dan Jawa, Arab dan Belanda, semua memberi andil dalam cerita.
Persoalan cinta dalam Si Doel diletakkan secara wajar, sebagai salah satu warna kehidupan. Bagi Doel, cinta bukan sesuatu yang harus dituhankan, bahkan kadang dianggap tidak penting ketika kehidupan menyeretnya dalam masalah yang lain. Si Doel menunjukkan bahwa hubungan lelaki dan perempuan, bahwa kehidupan, tidak hanya harus bergubal dalam persoalan cinta. Ada percabangan cinta, tapi tak memicu kedengkian dan kejahatan, melainkan kesadaran diri. Dan memang begitulah seharusnya.
Kita kemudian mencatat, Si Doel adalah sinetron yang fenomenal, bukan hanya dalam raihan iklan, melainkan juga respon penonton. Ribuan penonton merasa berhak untuk menentukan kisah cinta Doel dan Sarah. Proses antarmereka --perjuangan Sarah mengubah watak dan kehidupan Si Doel-- di mata penonton, harus diganjar dengan keterpilihannya sebagai istri. Penonton bahkan mendesak Rano Karno, produser sinetron itu, untuk segera menikahkan Si Doel dengan Sarah atau mencarikan lelaki lain untuk menikahi Zainab. Penonton terlibat karena cinta dalam cerita Si Doel adalah cinta yang juga penonton libati dalam kehidupan sehari-hari. Cinta yang lahir sebagai proses kesadaran diri.
Cerita dalam Budaya
Mengapa Si Doel menjadi berbeda? Mengapa Bajaj Bajuri, OB, dan Kiamat Sudah Dekat terasa dekat dengan kehidupan kita? Mungkin, karena sedari awal penonton tahu di wilayah budaya mana lingkup cerita itu terjadi. Ada beda idiom bahasa dan kode busana yang memberi warna dalam keseluruhan cerita, yang dapat kita sepakati sebagai "Indonesia". Sinetron itu berada dalam wilayah yang terjelaskan.
Cinta Fitri, Wulan, Sumpah Gue Sayang Loe, Liontin, dan I love U, Boss berada dalam wilayah imajinasi. Benar, situasi kota, dan plat nomor kendaraan yang mereka gunakan, menjelaskan setting cerita. Tapi, kebeliaan sang tokoh, kode busana, dan struktur cerita justru mengingkarinya. Dan jika cerita itu dipindahkan ke sudut kota mana pun, ke wilayah negara mana pun, pasti tidak akan menimbulkan dampak yang berarti. Karena sedari awal, cerita memang tidak memunculkan dan atau menganggap penting setting budaya.
Ketidakhadiran latar budaya ini dikarenakan banyak cerita sinetron "kita" berasal dari wilayah budaya yang berbeda, Korea. Yang hadir kemudian hanyalah logika cerita, tanpa didukung struktur budaya. Cerita dari drama Korea dicabut begitu saja, dan dimampatkan ke dalam situasi "kita". Itu sebabnya, banyak hal yang kemudian terasa janggal. Karena cerita disesakkan, dijejalkan dalam sebuah situasi yang sebenarnya tidak mendukung. Yang penting kisah bisa berjalan, sinetron dapat diproduksi.
Buku Harian Nayla, misalnya, yang merupakan jiplakan Ichi Rittoru No Namida (1 Litre of Tears), tidak menumbulkan simpati yang berlebih di sini. Di Jepang, karena berasal dari kisah nyata, drama ini terasa begitu membumi dan menimbulkan simpati yang luar biasa. Penonton Jepang merasa memiliki dan mengalami perjuangan Kitou Aya yang hadir dalam struktur budaya sana. Atau Endless Love, yang berdampak luar biasa di Korea. Tabloid Bintang Indonesia pernah mencatat, ada "kesepakatan" di Korea bahwa perempuan yang tidak menangis ketika melihat drama itu dianggap bukan perempuan. Ribuan telepon dan surat penggemar mendatangi stasiun teve KBS meminta agar sang tokoh Eun Suh (Song Hye Kyo) disembuhkan dari leukemianya, dan dijodohkan dengan Joon Suh. Direktur KBS pun meminta sutradara mengubah, tapi tak dikabulkan. Dan seri terakhir drama itu, ketika Eun Suh mati, dan Joon Suh yang kehilangan harapan, justru tertabrak truk saat menyeberangi jalan sambil menggendong jenazah kekasihnya, menjadi adegan yang terpatri dalam ingatan banyak penonton di sana. Dan ketika tayang di sini, di Indosiar, meski sangat memesona penonton, respon yang terjadi tidaklah sedahsyat di Korea. Meski terhanyut, latar budaya Korea cukup "mengasingkan" keterlibatan penonton.
Kita punya Si Doel, Korea punya Endless Love --dua cerita yang lahir dalam wilayah budaya penontonnya-- yang menggerakkan penonton, mengundang simpati, untuk merasa wajib menentukan jalan cerita. Dan seharusnya, pembuat sinetron, pengelola televisi, mau belajar dari sini. Sehingga, kelak tak perlu lagi tertayang karya jiplakan, cerita curian, yang tak mempertimbangkan budaya penonton. Sehingga kelak akan hadir cerita yang membiarkan wajah-wajah SMU berbicara tentang cinta, tanpa harus meleletkan dasi direktur di lehernya. Karena dasi di leher mereka adalah tanda jerat yang melilit akal sehat para penjiplak cerita.
[Artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 8 Juli 2007]