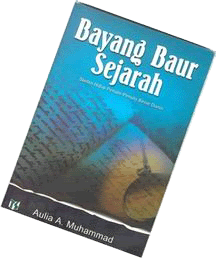...tera di sesela gegas-gesa
Tuesday, May 15, 2007
Keluar dari Batas Kenyataan
Memasuki panggung berarti memisahkan diri dari kenyataan.

"Wanita itu harus memakai jilbab, Kikan. Dengan menutup aurat, dia akan terlindungi," kata Nila, sembari mengelus rambut Kikan, anaknya. Nila baru saja usai salat, dan berjanji pada Allah, mulai hari itu dia akan menutup auratnya.
Itulah sepotong adegan dalam sinema "Hikayah: Penyanyi Dangdut Banting Setir Jadi Pembantu" yang tayang Selasa (1/5) lalu. Sinetron itu bercerita tentang pertobatan penyanyi dangdut, Nila, yang biasa bergoyang erotis. Dia yakin, dengan menutup aurat, berjilbab pun, panggung dangdut masih terbuka untuknya. Tapi Nila salah. Tak ada lagi panggung yang menerima. Dia dihina, dicampakkan, disudutkan. Godaan pun datang bertubi-tubi, tapi Nila tetap kuat. "Maaf, aku tidak bisa membuka jilbab. Ini sudah prinsip," elaknya.
Nila diperankan dengan cukup baik oleh Inul Daratista. Inul? Inul, pedangdut ngebor itu? Iya, Inul yang juga berseteru dengan Rhoma Irama itu. Di "Hikayah", yang juga seperti "Hidayah" --terinspirasi dari kisah nyata-- Inul menjadi Nila yang menyadari bahwa bergoyang ngebor dekat dengan kemaksiatan, mendorong orang untuk berbuat dosa. Ketika penonton tidak menerima prinsipnya, dia rela berganti profesi meski harus hanya menjadi pembantu rumah tangga.
Seminggu sebelumnya, Silvana Herman tampil sebagai pemain utama dalam "Hidayah: Perawan Tua". Dia menjadi sosok yang jahat karena tak mampu menanggungkan status ganda: tua dan perawan. Cerita pun berjalan dalam konflik batin yang berkembang jadi kedengki-irian. Sampai saat ini, Silvana Herman memang masih lajang. Usianya nyaris 40 tahun. Dalam tayangan infotainmen, setiap ditanya statusnya, Silvana tak pernah merasa risau. "Jodoh itu di tangan Tuhan. Nanti juga datang," ucapnya rileks.
Panggung Nilai
Kemampuan memerankan "sebuah" karakter adalah tuntutan utama untuk menjadi aktris. Seorang aktris, dapat menjadi apa saja ketika berlakon, termasuk menjadi sosok yang dia benci di dalam kehidupan nyata. "Akan menjadi tantangan yang hebat," demikian biasanya sang pelakon menggambarkan kegembiraan ketika mendapat peran yang berbeda dari karakter aslinya. Itulah sebabnya, setiap aktris riang gembira saja memerankan tokoh apa pun, dalam cerita apa pun, dan dengan kemuskilan apa pun. Yang penting berakting. "Karena berakting aku ada".
Karena akting hanya peranan, karakter apa pun yang dimainkan dipahami oleh mereka bukan sebagai cerminan dari watak pribadi sang pelakon. Itulah sebabnya, Silvana mau menjadi sosok perawan tua dan jahat. Silvana tahu, itu hanya akting. Meski menyandang status yang sama di kehidupan nyata, dia tahu penonton tak akan mempersepsikannya dengan kejahatan yang sama. Itu juga sebabnya, Inul riang gembira menjadi Nila, yang bertobat dari jalan ngebor. Inul tahu, karakter itu hanya rekaan, bagian dari akting. Hanya sandiwara. Tak ada korelasi antara Inul dan Nila.
Sebagai dua karakter, memang tak ada korelasi antara watak di dalam sinetron dan watak asali di dalam kenyataan. Tapi sebagai "pembawa" nilai, seharusnya Inul menyadari "makna" yang lebih daripada sekadar pemeranan. Inul adalah ikon yang mencoba meletakkan sebuah perspektif baru di dalam memandang panggung dangdut. Bersama beberapa aktivis perempuan, Inul mencoba melawan dominasi nilai bahwa dangdut adalah medium dakwah, yang sebagai hiburan seharusnya mengajak orang dekat pada sang pencipta. Karena itu, goyangan yang dianggap menabuh syahwat bukan bagian dari dangdut. Goyangan sejenis itu membawa dangdut ke gerbang comberan. Inul mencoba "memetakan" posisi persepsi dan fakta, harapan dan kenyataan. Bagi Inul, goyangan adalah wilayah terbuka yang bisa dimaknai apa pun, dalam konteks apa pun. Tidak bermakna tunggal, dan harus dilihat dari persepektif hiburan, permintaan dan penawaran, bukan agama. Inul mencoba membebaskan seni dari beban moral, membebaskan dangdut dari kepemilikan satu orang.
Nah, nilai "kenyataan" Inul ini yang justru ditampik Nila. Padahal, sebagai nilai, korelasi keduanya amat jelas. Ada hubungan kausatif antara sinetron dan kenyataan dalam tautan nilai. Sinetron, film, pementasan drama, bahkan opera pun, bukan produk yang lepas nilai. Itulah sebabnya, tak boleh ada sinetron yang menghina agama. Tak ada satu karakter cerita yang boleh menghina agama orang lain, suku, atau personalitas seseorang. Seluruh cerita sebuah film atau sinetron, mungkin tidak berangkat dari dunia nyata. Tapi "ketidaknyataan" itu tetap saja digayuti nilai-nilai yang justru datang dari dunia nyata. Dalam tataran nilai itu juga, seorang pelakon terhubung dengan kenyataan kesehariannya. Seorang pelakon, seharusnya tidak "memperlawankan" karakter yang dia mainkan dengan sikap moral pribadi. Leonardo DiCaprio misalnya, selalu menolak memerankan sosok yang merusak lingkungan. Dia bahkan berusaha memerankan karakter yang mengampanyekan lingkungan, misalnya dalam film Blood Diamond. Sebagai aktivis lingkungan, Leo bahkan berusaha mengampanyekan "moral pribadi" tersebut di dalam film-filmnya. Saat ini, dia sedang membuat film The 11th Hour, yang bercerita tentang kehancuran bumi akibat pemanasan global. Leo melihat film adalah medium untuk menyampaikan sikap "politiknya". Jika boleh, cerita yang dia mainkan sedapat mungkin mengekspresikan "sikap moral yang dia pilih".
Kesadaran semacam inilah yang tidak dipunyai Inul, dan juga aktris Indonesia lainnya. Panggung bagi mereka adalah sesuatu yang bebas nilai dan pasti terpisah dari kehidupan nyata. Begitu memasuki panggung, mereka merasa telah keluar dari batas kenyataan, terlepas dari sikap moral pribadi. Yang mereka mainkan adalah "cerita" khayalan. Nilai di dalamnya pun khayalan. "Saya tidak seperti itu lho...." begitulah ucapan mereka. Panggung adalah pemanggungan, tempat "identitas" di pertukarkan, saling menegasi, dan absurd. Panggung adalah sebuah teritorial yang memutus sejarah hidup sang aktris dari kenyataan.
Sinetron dan atau film bagi aktris kita bukanlah wadah ekspresi sikap moral pribadi melainkan "cara berada". Sebagai "cara berada", yang utama adalah imbal balik dari pemeranan karakter itu: materi. Panggung dengan demikian adalah wadah untuk semata-mata mendapatkan materi, dan persetan dengan nilai! Dengan cara yang sama, dapat juga dibaca bahwa "perjuangan" Inul dulu untuk "memetakan" posisi dangdut bukanlah bicara tentang nilai, tapi peluang materi yang dia dapatkan. Perlawanan Inul adalah perlawanan materi, pemosisian ladang nafkah. Jika pun bicara nilai, pastilah itu "nilai" yang dapat dimasukkan ke dalam kantong!
Sayang, sikap anutan semacam itu ternyata tidak hanya dihinggapi para aktris kita. Wakil rakyat di DPR sana, pun menghayati panggung politik tak berbeda dari panggung sinetron, sebuah dunia yang terpisah dari kenyataan, sebuah panggung yang tak harus mengekspresikan sikap moral yang mereka pilih. Karena itu, ketika memasuki panggung politik, mereka rileks berkolusi, korupsi, berzina, dan jutaan kali cidera janji. Mereka tahu, panggung selalu berbeda dari kenyataan. Di panggung politik, mereka boleh jadi jahat, boleh korup, karena itu hanya peranan, hanya lakon yang harus mereka mainkan. Dan rakyat, hmmm.. tentu mereka anggap hanya penonton....
[Dalam versi yang lebih ringkas, artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 13 Mei 2007]

"Wanita itu harus memakai jilbab, Kikan. Dengan menutup aurat, dia akan terlindungi," kata Nila, sembari mengelus rambut Kikan, anaknya. Nila baru saja usai salat, dan berjanji pada Allah, mulai hari itu dia akan menutup auratnya.
Itulah sepotong adegan dalam sinema "Hikayah: Penyanyi Dangdut Banting Setir Jadi Pembantu" yang tayang Selasa (1/5) lalu. Sinetron itu bercerita tentang pertobatan penyanyi dangdut, Nila, yang biasa bergoyang erotis. Dia yakin, dengan menutup aurat, berjilbab pun, panggung dangdut masih terbuka untuknya. Tapi Nila salah. Tak ada lagi panggung yang menerima. Dia dihina, dicampakkan, disudutkan. Godaan pun datang bertubi-tubi, tapi Nila tetap kuat. "Maaf, aku tidak bisa membuka jilbab. Ini sudah prinsip," elaknya.
Nila diperankan dengan cukup baik oleh Inul Daratista. Inul? Inul, pedangdut ngebor itu? Iya, Inul yang juga berseteru dengan Rhoma Irama itu. Di "Hikayah", yang juga seperti "Hidayah" --terinspirasi dari kisah nyata-- Inul menjadi Nila yang menyadari bahwa bergoyang ngebor dekat dengan kemaksiatan, mendorong orang untuk berbuat dosa. Ketika penonton tidak menerima prinsipnya, dia rela berganti profesi meski harus hanya menjadi pembantu rumah tangga.
Seminggu sebelumnya, Silvana Herman tampil sebagai pemain utama dalam "Hidayah: Perawan Tua". Dia menjadi sosok yang jahat karena tak mampu menanggungkan status ganda: tua dan perawan. Cerita pun berjalan dalam konflik batin yang berkembang jadi kedengki-irian. Sampai saat ini, Silvana Herman memang masih lajang. Usianya nyaris 40 tahun. Dalam tayangan infotainmen, setiap ditanya statusnya, Silvana tak pernah merasa risau. "Jodoh itu di tangan Tuhan. Nanti juga datang," ucapnya rileks.
Panggung Nilai
Kemampuan memerankan "sebuah" karakter adalah tuntutan utama untuk menjadi aktris. Seorang aktris, dapat menjadi apa saja ketika berlakon, termasuk menjadi sosok yang dia benci di dalam kehidupan nyata. "Akan menjadi tantangan yang hebat," demikian biasanya sang pelakon menggambarkan kegembiraan ketika mendapat peran yang berbeda dari karakter aslinya. Itulah sebabnya, setiap aktris riang gembira saja memerankan tokoh apa pun, dalam cerita apa pun, dan dengan kemuskilan apa pun. Yang penting berakting. "Karena berakting aku ada".
Karena akting hanya peranan, karakter apa pun yang dimainkan dipahami oleh mereka bukan sebagai cerminan dari watak pribadi sang pelakon. Itulah sebabnya, Silvana mau menjadi sosok perawan tua dan jahat. Silvana tahu, itu hanya akting. Meski menyandang status yang sama di kehidupan nyata, dia tahu penonton tak akan mempersepsikannya dengan kejahatan yang sama. Itu juga sebabnya, Inul riang gembira menjadi Nila, yang bertobat dari jalan ngebor. Inul tahu, karakter itu hanya rekaan, bagian dari akting. Hanya sandiwara. Tak ada korelasi antara Inul dan Nila.
Sebagai dua karakter, memang tak ada korelasi antara watak di dalam sinetron dan watak asali di dalam kenyataan. Tapi sebagai "pembawa" nilai, seharusnya Inul menyadari "makna" yang lebih daripada sekadar pemeranan. Inul adalah ikon yang mencoba meletakkan sebuah perspektif baru di dalam memandang panggung dangdut. Bersama beberapa aktivis perempuan, Inul mencoba melawan dominasi nilai bahwa dangdut adalah medium dakwah, yang sebagai hiburan seharusnya mengajak orang dekat pada sang pencipta. Karena itu, goyangan yang dianggap menabuh syahwat bukan bagian dari dangdut. Goyangan sejenis itu membawa dangdut ke gerbang comberan. Inul mencoba "memetakan" posisi persepsi dan fakta, harapan dan kenyataan. Bagi Inul, goyangan adalah wilayah terbuka yang bisa dimaknai apa pun, dalam konteks apa pun. Tidak bermakna tunggal, dan harus dilihat dari persepektif hiburan, permintaan dan penawaran, bukan agama. Inul mencoba membebaskan seni dari beban moral, membebaskan dangdut dari kepemilikan satu orang.
Nah, nilai "kenyataan" Inul ini yang justru ditampik Nila. Padahal, sebagai nilai, korelasi keduanya amat jelas. Ada hubungan kausatif antara sinetron dan kenyataan dalam tautan nilai. Sinetron, film, pementasan drama, bahkan opera pun, bukan produk yang lepas nilai. Itulah sebabnya, tak boleh ada sinetron yang menghina agama. Tak ada satu karakter cerita yang boleh menghina agama orang lain, suku, atau personalitas seseorang. Seluruh cerita sebuah film atau sinetron, mungkin tidak berangkat dari dunia nyata. Tapi "ketidaknyataan" itu tetap saja digayuti nilai-nilai yang justru datang dari dunia nyata. Dalam tataran nilai itu juga, seorang pelakon terhubung dengan kenyataan kesehariannya. Seorang pelakon, seharusnya tidak "memperlawankan" karakter yang dia mainkan dengan sikap moral pribadi. Leonardo DiCaprio misalnya, selalu menolak memerankan sosok yang merusak lingkungan. Dia bahkan berusaha memerankan karakter yang mengampanyekan lingkungan, misalnya dalam film Blood Diamond. Sebagai aktivis lingkungan, Leo bahkan berusaha mengampanyekan "moral pribadi" tersebut di dalam film-filmnya. Saat ini, dia sedang membuat film The 11th Hour, yang bercerita tentang kehancuran bumi akibat pemanasan global. Leo melihat film adalah medium untuk menyampaikan sikap "politiknya". Jika boleh, cerita yang dia mainkan sedapat mungkin mengekspresikan "sikap moral yang dia pilih".
Kesadaran semacam inilah yang tidak dipunyai Inul, dan juga aktris Indonesia lainnya. Panggung bagi mereka adalah sesuatu yang bebas nilai dan pasti terpisah dari kehidupan nyata. Begitu memasuki panggung, mereka merasa telah keluar dari batas kenyataan, terlepas dari sikap moral pribadi. Yang mereka mainkan adalah "cerita" khayalan. Nilai di dalamnya pun khayalan. "Saya tidak seperti itu lho...." begitulah ucapan mereka. Panggung adalah pemanggungan, tempat "identitas" di pertukarkan, saling menegasi, dan absurd. Panggung adalah sebuah teritorial yang memutus sejarah hidup sang aktris dari kenyataan.
Sinetron dan atau film bagi aktris kita bukanlah wadah ekspresi sikap moral pribadi melainkan "cara berada". Sebagai "cara berada", yang utama adalah imbal balik dari pemeranan karakter itu: materi. Panggung dengan demikian adalah wadah untuk semata-mata mendapatkan materi, dan persetan dengan nilai! Dengan cara yang sama, dapat juga dibaca bahwa "perjuangan" Inul dulu untuk "memetakan" posisi dangdut bukanlah bicara tentang nilai, tapi peluang materi yang dia dapatkan. Perlawanan Inul adalah perlawanan materi, pemosisian ladang nafkah. Jika pun bicara nilai, pastilah itu "nilai" yang dapat dimasukkan ke dalam kantong!
Sayang, sikap anutan semacam itu ternyata tidak hanya dihinggapi para aktris kita. Wakil rakyat di DPR sana, pun menghayati panggung politik tak berbeda dari panggung sinetron, sebuah dunia yang terpisah dari kenyataan, sebuah panggung yang tak harus mengekspresikan sikap moral yang mereka pilih. Karena itu, ketika memasuki panggung politik, mereka rileks berkolusi, korupsi, berzina, dan jutaan kali cidera janji. Mereka tahu, panggung selalu berbeda dari kenyataan. Di panggung politik, mereka boleh jadi jahat, boleh korup, karena itu hanya peranan, hanya lakon yang harus mereka mainkan. Dan rakyat, hmmm.. tentu mereka anggap hanya penonton....
[Dalam versi yang lebih ringkas, artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 13 Mei 2007]