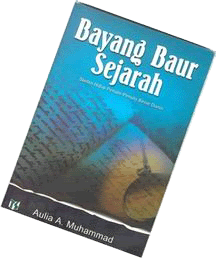...tera di sesela gegas-gesa
Friday, April 27, 2007
Wajah Ceria Kekerasan
Kekerasan, keonaran, kebrutalan, acap datang dengan wajah ceria. Kita mencintainya.

TAK ada yang lebih mencintai "kebandelan" selain Yamaha. Bahkan, "persepsi" kebandelan itu terus diperbarui menjadi keonaran dan kebrutalan. Lihatlah iklan-iklannya. Awalnya, Komeng hanya zig-zag di jalan raya, menyalip siapa saja, cepat, dan sampai tujuan dengan baju compang-camping. Atau memboncengkan Tessa Kaunang, dengan hasil rambut yang jadi awut-awutan. Selanjutnya, efek "kebandelan" Yamaha dipertegas. Mulai mengacaukan roda delman, merubuhkan pot-pot bunga, sampai merusak kacamata. Korbannya selalu Didi Petet, dan pencetus kagum Dedy Mizwar. Terakhir, efek itu dipertegas dengan "super-duper" hiperbolis, meruntuhkan jembatan Kalibeber, dan terakhir merontokkan motor lain, sampai hanya layak jadi rongsokan.
Yamaha dengan iklannya mereprentasikan kebandelan sebagai kekerasan. Efeknya adalah kehancuran bagi pihak lain. Kekerasan atau pun keonaran divisualisasikan dengan jelas, berulang-ulang, dan menjadi bagian dari kesenangan.
Kini, keonaran dan kehancuran itu juga punya pengikut. Iklan minuman Tebs contohnya. Versi terbaru iklan teh bersoda ini menampilkan keonaran akibat "kejutan rasa" Tebs. Rekaman video di kantor polisi menunjukkan bagaimana dahsyatnya dampak tegukan Tebs; mobil bertubrukan, pedagang dengan jualan yang berhamburan, orang-orang yang panik. Selanjutnya adalah rasa bangga penenggaknya. Itulah iklan yang secara bagus mampu membahasakan kenikmatan sebagai kehancuran bagi orang lain.
"Moral" cerita iklan di atas jelas tidak baik. Yamaha misalnya, tak hanya menghancurkan produk sejenis, tapi juga lingkungan sekitar. Namun, bagi konsumen, "citra" semacam itulah yang justru diharapkan. Imaji kekerasan, pembuat onar, justru mampu mendongkrak penjualan Yamaha. Hasilnya, untuk kali pertama, penjualan Yamaha mengalahkan Honda, di bulan Maret. Yamaha menjual lebih banyak 7.961 unit motor daripada Honda.
Manajer pemasaran PT Yamaha Motor Kencana Indonesia Herry Setyanto, mengutip data dari Asosiasi Industri Sepeda Motor, mengatakan, Yamaha menjual 159.035 unit untuk bulan Maret. "Honda hanya 151.074 unit," katanya. Keberhasilan itu, kata Herry, tak lepas dari strategi iklan mereka. Ke depan, mereka akan kian menggencarkan iklan dengan tetap mempetahankan model Dedy Mizwar, Didi Petet, dan Komeng. "Mereka bagian dari strategi pemasaran," ucapnya.
Anda ingat wajah ceria Komeng sehabis "mengamuk" dengan Jupiter MX-nya? Itulah "strategi pemasaran" yang dimaksudkan Herry. Anda juga pasti ingat senyum maklum dan bangga Deddy Mizwar?
Kenikmatan Onar
Kekerasan, keonaran, agresivitas, bukanlah suatu sifat yang berdiri sendiri, melainkan sebuah sindrom. Kekerasan terstimulasi dari sebuah sistem, dapat berupa hierarki yang kaku, dominasi suatu kelompok masyarakat, stratifikasi kelas sosial, ras dan agama. Itulah yang dikatakan Erich Fromm dalam bukunya The Anatomy of Human Destructiveness. Fromm yakin, agresi adalah nilai yang ditanamkan melalui budaya dan menjadi bagian dari karakter sosial. Sebagai nilai sosial, agresi adalah "modal diam" yang suatu saat meledak ketika ada picu pelontarnya.
Iklan Yamaha dapat dibaca dalam kacamata yang sama. Pilihan kekerasan adalah "modal diam" yang lahir akibat dominasi yang terlalu kuat dari Honda selama ini. Namun, "kekerasan" jahat justru terletak pada senyum bangga Komeng dan Deddy Mizwar setelah aksi brutalnya.
Senyum itu adalah visualisasi dari kenikmatan. Dan tak ada kekerasan yang lebih mengerikan daripada ketika hal itu dimaknai sebagai kenikmatan, kepuasan. "Kejahatan yang paling sempurna," kata George Bataille, "adalah ketika si pelaku merasa dia justru melakukan sebuah perbuatan heroik." Wajah ceria Komeng menunjukkan hal itu. Keonaran sebagai kesenangan, mainan, guyonan, sesuatu yang riang-gembira. "Kamu boleh ambil apa pun dari juniormu, tapi sisakan nyawanya," itulah "hukum" di IPDN. Atau, "Kalau kau tidak dapat mengambil hati juniormu, 'ambillah' ulu hatinya."
Senyum itu, keriang-gembiraan itu adalah tanda hilangnya sense of humanity, rasa insani. Korban adalah sesuatu yang harus dan wajib. "Masih berani pilih yang lain," kata Deddy Mizwar. "Apalah artinya 33 nyawa dibandingkan pengabdian para lulusan IPDN," begitulah testimoni alumnus institut itu, sebagaimana pernah tercantum di http://ipdnmania.wordpress.com.
Korban hanya dimaknai sebagai bencana, situasi yang tak terelakkan. Tak ada meaning of humanity, hikmah, dosa, rasa malu, apalagi pengungkapan kebenaran. Bebasnya sepuluh praja pembunuh Wahyu Hidayat adalah bukti hal itu. Diangkatnya mereka menjadi PNS kian menunjukkan tak ada rasa bersalah pemerintah atas pembunuhan itu. Wahyu hanya bencana, hanya akibat dari kedisiplinan. Hukuman penjara tidak relevan untuk sebuah pembunuhan yang dimaknai sebagai bencana.
Bangsa Penerima
Iklan Yamaha dan Tebs, juga IPDN, adalah "bencana" bagi rasa kemanusiaan. Tapi, siapa yang dapat menampiknya. Keonaran dan kekerasan yang diiklankan Yamaha, justru menaikkan penjualannya. Kekerasan dan pembunuhan di IPDN tak menyurutkan "pamornya". Tak ada keinginan pemerintah untuk menutup sekolah semi-militer itu. Hanya sedikit daerah yang berencana tak lagi mengirimkan putra daerah ke sana. Dan yakinlah, sangat banyak orangtua yang memimpikan anaknya untuk tetap diterima dan bersekolah di sana. Kekerasan itu adalah bagian dari resiko yang dapat diterima sepanjang ada janji di sebaliknya. Yamaha menjanjikan kecepatan dan kebandelan, IPDN menjanjikan karier yang gemilang dan pasti. Karena sepuluh praja pembunuh itu pun akan tetap sebagai PNS lepas dari hukumannya nanti.
"Kekerasan dapat diterima sebagai kenikmatan ketika seseorang sadar posisinya sebagai si lemah, si tanpa harapan," tulis Fyodor Dostoevsky dalam Notes from Underground. Dan kita, adalah masyarakat yang putus asa, tanpa harapan, hanya berani bermimpi untuk kehidupan yang lebih baik. Karena kita juga sebuah bangsa, yang dengan enteng, menganggap kejahatan sebagai bencana. Itulah sebabnya, kita menerima kekerasan, tak pernah sungguh mengutuknya, seperti kita menerima IPDN dan iklan Yamaha. Kita berharap, ada wajah bangga, ada paras ceria, saat kekerasan itu usai bekerja.
[Artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 29 April 2007]
( t.i.l.i.k ! )

TAK ada yang lebih mencintai "kebandelan" selain Yamaha. Bahkan, "persepsi" kebandelan itu terus diperbarui menjadi keonaran dan kebrutalan. Lihatlah iklan-iklannya. Awalnya, Komeng hanya zig-zag di jalan raya, menyalip siapa saja, cepat, dan sampai tujuan dengan baju compang-camping. Atau memboncengkan Tessa Kaunang, dengan hasil rambut yang jadi awut-awutan. Selanjutnya, efek "kebandelan" Yamaha dipertegas. Mulai mengacaukan roda delman, merubuhkan pot-pot bunga, sampai merusak kacamata. Korbannya selalu Didi Petet, dan pencetus kagum Dedy Mizwar. Terakhir, efek itu dipertegas dengan "super-duper" hiperbolis, meruntuhkan jembatan Kalibeber, dan terakhir merontokkan motor lain, sampai hanya layak jadi rongsokan.
Yamaha dengan iklannya mereprentasikan kebandelan sebagai kekerasan. Efeknya adalah kehancuran bagi pihak lain. Kekerasan atau pun keonaran divisualisasikan dengan jelas, berulang-ulang, dan menjadi bagian dari kesenangan.
Kini, keonaran dan kehancuran itu juga punya pengikut. Iklan minuman Tebs contohnya. Versi terbaru iklan teh bersoda ini menampilkan keonaran akibat "kejutan rasa" Tebs. Rekaman video di kantor polisi menunjukkan bagaimana dahsyatnya dampak tegukan Tebs; mobil bertubrukan, pedagang dengan jualan yang berhamburan, orang-orang yang panik. Selanjutnya adalah rasa bangga penenggaknya. Itulah iklan yang secara bagus mampu membahasakan kenikmatan sebagai kehancuran bagi orang lain.
"Moral" cerita iklan di atas jelas tidak baik. Yamaha misalnya, tak hanya menghancurkan produk sejenis, tapi juga lingkungan sekitar. Namun, bagi konsumen, "citra" semacam itulah yang justru diharapkan. Imaji kekerasan, pembuat onar, justru mampu mendongkrak penjualan Yamaha. Hasilnya, untuk kali pertama, penjualan Yamaha mengalahkan Honda, di bulan Maret. Yamaha menjual lebih banyak 7.961 unit motor daripada Honda.
Manajer pemasaran PT Yamaha Motor Kencana Indonesia Herry Setyanto, mengutip data dari Asosiasi Industri Sepeda Motor, mengatakan, Yamaha menjual 159.035 unit untuk bulan Maret. "Honda hanya 151.074 unit," katanya. Keberhasilan itu, kata Herry, tak lepas dari strategi iklan mereka. Ke depan, mereka akan kian menggencarkan iklan dengan tetap mempetahankan model Dedy Mizwar, Didi Petet, dan Komeng. "Mereka bagian dari strategi pemasaran," ucapnya.
Anda ingat wajah ceria Komeng sehabis "mengamuk" dengan Jupiter MX-nya? Itulah "strategi pemasaran" yang dimaksudkan Herry. Anda juga pasti ingat senyum maklum dan bangga Deddy Mizwar?
Kenikmatan Onar
Kekerasan, keonaran, agresivitas, bukanlah suatu sifat yang berdiri sendiri, melainkan sebuah sindrom. Kekerasan terstimulasi dari sebuah sistem, dapat berupa hierarki yang kaku, dominasi suatu kelompok masyarakat, stratifikasi kelas sosial, ras dan agama. Itulah yang dikatakan Erich Fromm dalam bukunya The Anatomy of Human Destructiveness. Fromm yakin, agresi adalah nilai yang ditanamkan melalui budaya dan menjadi bagian dari karakter sosial. Sebagai nilai sosial, agresi adalah "modal diam" yang suatu saat meledak ketika ada picu pelontarnya.
Iklan Yamaha dapat dibaca dalam kacamata yang sama. Pilihan kekerasan adalah "modal diam" yang lahir akibat dominasi yang terlalu kuat dari Honda selama ini. Namun, "kekerasan" jahat justru terletak pada senyum bangga Komeng dan Deddy Mizwar setelah aksi brutalnya.
Senyum itu adalah visualisasi dari kenikmatan. Dan tak ada kekerasan yang lebih mengerikan daripada ketika hal itu dimaknai sebagai kenikmatan, kepuasan. "Kejahatan yang paling sempurna," kata George Bataille, "adalah ketika si pelaku merasa dia justru melakukan sebuah perbuatan heroik." Wajah ceria Komeng menunjukkan hal itu. Keonaran sebagai kesenangan, mainan, guyonan, sesuatu yang riang-gembira. "Kamu boleh ambil apa pun dari juniormu, tapi sisakan nyawanya," itulah "hukum" di IPDN. Atau, "Kalau kau tidak dapat mengambil hati juniormu, 'ambillah' ulu hatinya."
Senyum itu, keriang-gembiraan itu adalah tanda hilangnya sense of humanity, rasa insani. Korban adalah sesuatu yang harus dan wajib. "Masih berani pilih yang lain," kata Deddy Mizwar. "Apalah artinya 33 nyawa dibandingkan pengabdian para lulusan IPDN," begitulah testimoni alumnus institut itu, sebagaimana pernah tercantum di http://ipdnmania.wordpress.com.
Korban hanya dimaknai sebagai bencana, situasi yang tak terelakkan. Tak ada meaning of humanity, hikmah, dosa, rasa malu, apalagi pengungkapan kebenaran. Bebasnya sepuluh praja pembunuh Wahyu Hidayat adalah bukti hal itu. Diangkatnya mereka menjadi PNS kian menunjukkan tak ada rasa bersalah pemerintah atas pembunuhan itu. Wahyu hanya bencana, hanya akibat dari kedisiplinan. Hukuman penjara tidak relevan untuk sebuah pembunuhan yang dimaknai sebagai bencana.
Bangsa Penerima
Iklan Yamaha dan Tebs, juga IPDN, adalah "bencana" bagi rasa kemanusiaan. Tapi, siapa yang dapat menampiknya. Keonaran dan kekerasan yang diiklankan Yamaha, justru menaikkan penjualannya. Kekerasan dan pembunuhan di IPDN tak menyurutkan "pamornya". Tak ada keinginan pemerintah untuk menutup sekolah semi-militer itu. Hanya sedikit daerah yang berencana tak lagi mengirimkan putra daerah ke sana. Dan yakinlah, sangat banyak orangtua yang memimpikan anaknya untuk tetap diterima dan bersekolah di sana. Kekerasan itu adalah bagian dari resiko yang dapat diterima sepanjang ada janji di sebaliknya. Yamaha menjanjikan kecepatan dan kebandelan, IPDN menjanjikan karier yang gemilang dan pasti. Karena sepuluh praja pembunuh itu pun akan tetap sebagai PNS lepas dari hukumannya nanti.
"Kekerasan dapat diterima sebagai kenikmatan ketika seseorang sadar posisinya sebagai si lemah, si tanpa harapan," tulis Fyodor Dostoevsky dalam Notes from Underground. Dan kita, adalah masyarakat yang putus asa, tanpa harapan, hanya berani bermimpi untuk kehidupan yang lebih baik. Karena kita juga sebuah bangsa, yang dengan enteng, menganggap kejahatan sebagai bencana. Itulah sebabnya, kita menerima kekerasan, tak pernah sungguh mengutuknya, seperti kita menerima IPDN dan iklan Yamaha. Kita berharap, ada wajah bangga, ada paras ceria, saat kekerasan itu usai bekerja.
[Artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 29 April 2007]
( t.i.l.i.k ! )
Thursday, April 19, 2007
Panggung dan Arsip Ingatan
Hidup kadang diisi oleh hal-hal yang dramatik. Dan menjadi indah jika itu bukan bagian dari sandiwara.

GENTA bernilai ketika dibunyikan, cinta bermakna hanya saat diungkapkan. Tamara menyadari sungguh hal itu. Di depan rumah Rafli, berpegangan teralis-pagar hijau pupus itu, dia berteriak, "Rasya... i love youuu...." Berulang-ulang. Suaranya menggema di ramai jalan Tirtayasa.
Sore itu, dia ingin bertemu Rasya. Dia ingin bertanya, benarkah anak semata-wayangnya itu tak mau bersua dengannya, sebagaimana yang kerap dinyatakan Rafli. Benarkah Rasya menyimpan trauma atas perlakuannya? Itulah sebabnya dia berteriak. Bukan karena dia tak percaya bahwa Rasya tak ada, melainkan lebih sebagai jeritan ibu yang terluka, yang dianggap tak tahu cara mencinta.
Seharusnya akan jadi adegan yang mengharukan. Tapi, entah mengapa, teriakan Tamara, guncangan tangannya pada teralis pagar, wajah kecewa dan gegasnya memasuki mobil untuk menyurukkan tangis, jadi terasa begitu biasa. Tiada mencipratkan iba. Saya merasa akrab sekali dengan adegan itu. Dan menjadi tertawa, ketika Cut Tari, dengan ringannya berkata, "Pemirsa, mulai sekarang jangan nonton sinetron lagi ya? Nonton "Insert" aja, toh isinya sama saja, hehehe..." Indra Herlambang yang berada di sampingnya pun ngakak, lalu menggelengkan kepala.
Cut Tari benar, adegan Tamara itu terasa akrab karena tipikalitasnya acap muncul dalam sinetron kita. Itulah sebabnya, gesture Tamara tak terasa alamiah, apalagi mengejutkan. Seluruh sikapnya terasa tertib, seakan mengikuti hukum dramaturgi; ritme yang diatur untuk menunggu ending. Dan akhir itu tercukupi dengan peluk-haru dia dan Rasya, sentuhan pipi dia dan Rafli, dan wicara yang saling memuji. Selesai.
Kalau kau hanya merasa mampu berakting, dunia akan selalu kau lihat sebagai panggung. Tamara agaknya berada di titik ini. Juga Dhini Aminarti. Di dalam sinetron Wulan, dia menghadiahkan dompet untuk suaminya, dan berkata, "Dompet itu akan membuat aku selalu bersama kamu. Dan kau akan selalu ingat aku, merasa ditemani." Di kehidupan nyata, ketika ulangtahun kekasihnya, Fardan, dia pun menghadiahi dompet. Dan ketika ditanya infotainmen, mengapa sebuah dompet, dengan tersenyum Dhini berkata, "Biar aku selalu bersama dia. Biar dia selalu ingat aku, merasa ditemani, di mana pun dia berada."
Pemanggungan sinetron. Agaknya itu yang terjadi kini, ketika karakter yang biasa diperani seseorang begitu menyatu dan tak bisa dengan gampang dienyahkan. Film Being John Malkovich dengan getir mencontohkan hal ini. Karakter peranan yang kemudian terbawa ke dunia nyata, menginfiltrasi hidupnya jadi sebuah nestapa. Craig Schwartz (John Cussack) tidak bahagia dengan hal itu. Dia merasa ada beda yang tegas antara dunia dan panggung, dan hidup tak bisa dicukupi hanya dengan sebuah karakter.
Tamara dan Dhini barangkali tidak seperti Craig. Mereka masih hidup dalam karakter peranan ketika "panggung" yang dihadapi justru sudah berbeda. Mereka mungkin merasa dihidupi oleh kemampuan berakting, dan karena itu melihat semua orang sebagai juru kamera. Mungkin juga karena mereka lupa bahwa hidup mereka selalu diarsip, dan penonton acap punya ingatan yang sama.
Hidup dalam ingatan banyak orang itulah yang coba ditampik Anna. Ketika tertangkap basah kamera menginap di rumah pemilik toko buku William Tracker, dia menjadi begitu panik.
"Tenanglah," kata William, "Kisahmu hanya akan dimuat hari ini, besok semua orang sudah melupakannya."
Anna justru meradang. "Kau tidak tahu, begitu peristiwa ini dicatat, dia akan menjadi arsip dalam kehidupanku. Dan ketika orang bicara tentang diriku, arsip ini pasti dibuka lagi, akan selalu diulang...."
Anna adalah tokoh fiktif yang diperankan dengan bagus oleh Julia Robert dalam Notting Hill, selebritis yang ingin hidup wajar dan menampik kamera. Dia ingin kehidupan pribadinya menjadi milik dirinya sendiri. Dia tahu, popularitas berumur pendek tapi meminta terlalu banyak, merenggut yang paling intim di dalam hatinya, menjadi diri sendiri. Anna mengerti, saat yang paling pedih adalah ketika dirinya hidup dalam ingatan banyak orang. Itulah sebab, mengapa dia selalu bersembunyi. Selalu kembali kepada William (Hugh Grant), lelaki yang riuh aroma pasar dan jalan, kealamiahan.
Anna memang bukan Tamara. Bagi sebagian aktris kita, hidup dalam ingatan banyak orang adalah kebahagiaan. Mereka lupa, ingatan bersama itu juga yang kelak menjadi hakim atas sikap mereka. Seperti kisah Tamara dan Rafli yang memperebutkan Rasya.
Tamara merasa dijauhkan dari buah hatinya. Dia menilai Rafli tidak berlaku adil. Haknya sebagai ibu tidak dipenuhi. Dia mengecam, dan melaporkan psikolog Yussy ke polisi. "Saya tidak ingin ada pihak ketiga yang selalu mencampuri urusan kami," katanya. Tamara lupa, puluhan kamera yang mengikuti seluruh geraknya di rumah Rafli, yang merekam teriakan dan airmatanya, juga adalah pihak ketiga. Polisi, Ersa Syarif pengacaranya, adalah juga pihak ketiga-kesekian. Penonton juga pihak ketiga, yang dilibatkan Tamara untuk melihatnya dengan iba, mendukungnya dengan bela. Tapi penonton tak pernah lupa, karena "Insert", "Kabar-kabari", "Silet", "Kasak-Kusuk" dan puluhan infotainmen lain telah mengarsip hidup Tamara, dan membukanya di setiap pagi, siang dan senja; bahwa pernah dulu Tamara melakukan hal yang sama, menghaki Rassya hanya untuk dirinya. "Kini posisi itu berubah sudah," kata narator "Insert".
Mungkin, ingatan itu juga yang membuat kisah Tamara berbeda dari Notting Hill. Ada yang terasa menyentuh ketika dengan putus asa Anna mengiba, "...lihatlah aku. Bagaimanapun aku seorang perempuan, yang menyatakan cintanya pada seorang lelaki, yang hanya minta dicintai..." Anna hanya ingin dilihat sebagai seorang perempuan, sosok yang tak mengemban karakter apa pun. Diri yang bersih dari kamera. Adegan itu pun terjadi di toko buku wisata, tempat orang datang dengan kesadaran untuk pergi, bergegas, berpindah. Anna ingin berhenti. Dia capek menanggungkan kebohongan. "Apakah kau berharap aku jujur berkata tentang perasaanku di depan kamera?" Begitulah dia berkata sebelumnya, ketika William mengungkit kebohongannya di depan kamera.
Saya bayangkan Tamara mendatangi Rafli, Rasya, dan mertuanya di Tirtayasa, seorang diri, tanpa kamera. Saya angankan dengan lelah dia berkata, "Rafli, bagaimanapun aku adalah seorang ibu, yang haus memeluk anaknya. Bagaimanapun aku adalah perempuan yang pernah engkau cintai, yang engkau percayai merahimi Rasya. Pandanglah aku dengan semua kebaikan itu. Lihatlah, pernah ada hal yang begitu indah dalam kehidupan kita. Apakah engkau percaya bahwa aku akan merusak keindahan itu?"
Saya bayangkan Rafli akan menuntun Rasya, dan mendekapkannya ke Tamara, sambil berbisik, "Begitulah Tamara, begitulah seharusnya..." Dan di sudut sana, Cut Haslinda, mertua Tamara, tersenyum, mengucap hamdallah, dengan menyusut airmata.
Hidup kadang diisi oleh hal-hal yang dramatik. Dan semua bisa jadi indah jika itu bukan bagian dari sandiwara....
[Artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 22 April 2007]
( t.i.l.i.k ! )

GENTA bernilai ketika dibunyikan, cinta bermakna hanya saat diungkapkan. Tamara menyadari sungguh hal itu. Di depan rumah Rafli, berpegangan teralis-pagar hijau pupus itu, dia berteriak, "Rasya... i love youuu...." Berulang-ulang. Suaranya menggema di ramai jalan Tirtayasa.
Sore itu, dia ingin bertemu Rasya. Dia ingin bertanya, benarkah anak semata-wayangnya itu tak mau bersua dengannya, sebagaimana yang kerap dinyatakan Rafli. Benarkah Rasya menyimpan trauma atas perlakuannya? Itulah sebabnya dia berteriak. Bukan karena dia tak percaya bahwa Rasya tak ada, melainkan lebih sebagai jeritan ibu yang terluka, yang dianggap tak tahu cara mencinta.
Seharusnya akan jadi adegan yang mengharukan. Tapi, entah mengapa, teriakan Tamara, guncangan tangannya pada teralis pagar, wajah kecewa dan gegasnya memasuki mobil untuk menyurukkan tangis, jadi terasa begitu biasa. Tiada mencipratkan iba. Saya merasa akrab sekali dengan adegan itu. Dan menjadi tertawa, ketika Cut Tari, dengan ringannya berkata, "Pemirsa, mulai sekarang jangan nonton sinetron lagi ya? Nonton "Insert" aja, toh isinya sama saja, hehehe..." Indra Herlambang yang berada di sampingnya pun ngakak, lalu menggelengkan kepala.
Cut Tari benar, adegan Tamara itu terasa akrab karena tipikalitasnya acap muncul dalam sinetron kita. Itulah sebabnya, gesture Tamara tak terasa alamiah, apalagi mengejutkan. Seluruh sikapnya terasa tertib, seakan mengikuti hukum dramaturgi; ritme yang diatur untuk menunggu ending. Dan akhir itu tercukupi dengan peluk-haru dia dan Rasya, sentuhan pipi dia dan Rafli, dan wicara yang saling memuji. Selesai.
Kalau kau hanya merasa mampu berakting, dunia akan selalu kau lihat sebagai panggung. Tamara agaknya berada di titik ini. Juga Dhini Aminarti. Di dalam sinetron Wulan, dia menghadiahkan dompet untuk suaminya, dan berkata, "Dompet itu akan membuat aku selalu bersama kamu. Dan kau akan selalu ingat aku, merasa ditemani." Di kehidupan nyata, ketika ulangtahun kekasihnya, Fardan, dia pun menghadiahi dompet. Dan ketika ditanya infotainmen, mengapa sebuah dompet, dengan tersenyum Dhini berkata, "Biar aku selalu bersama dia. Biar dia selalu ingat aku, merasa ditemani, di mana pun dia berada."
Pemanggungan sinetron. Agaknya itu yang terjadi kini, ketika karakter yang biasa diperani seseorang begitu menyatu dan tak bisa dengan gampang dienyahkan. Film Being John Malkovich dengan getir mencontohkan hal ini. Karakter peranan yang kemudian terbawa ke dunia nyata, menginfiltrasi hidupnya jadi sebuah nestapa. Craig Schwartz (John Cussack) tidak bahagia dengan hal itu. Dia merasa ada beda yang tegas antara dunia dan panggung, dan hidup tak bisa dicukupi hanya dengan sebuah karakter.
Tamara dan Dhini barangkali tidak seperti Craig. Mereka masih hidup dalam karakter peranan ketika "panggung" yang dihadapi justru sudah berbeda. Mereka mungkin merasa dihidupi oleh kemampuan berakting, dan karena itu melihat semua orang sebagai juru kamera. Mungkin juga karena mereka lupa bahwa hidup mereka selalu diarsip, dan penonton acap punya ingatan yang sama.
Hidup dalam ingatan banyak orang itulah yang coba ditampik Anna. Ketika tertangkap basah kamera menginap di rumah pemilik toko buku William Tracker, dia menjadi begitu panik.
"Tenanglah," kata William, "Kisahmu hanya akan dimuat hari ini, besok semua orang sudah melupakannya."
Anna justru meradang. "Kau tidak tahu, begitu peristiwa ini dicatat, dia akan menjadi arsip dalam kehidupanku. Dan ketika orang bicara tentang diriku, arsip ini pasti dibuka lagi, akan selalu diulang...."
Anna adalah tokoh fiktif yang diperankan dengan bagus oleh Julia Robert dalam Notting Hill, selebritis yang ingin hidup wajar dan menampik kamera. Dia ingin kehidupan pribadinya menjadi milik dirinya sendiri. Dia tahu, popularitas berumur pendek tapi meminta terlalu banyak, merenggut yang paling intim di dalam hatinya, menjadi diri sendiri. Anna mengerti, saat yang paling pedih adalah ketika dirinya hidup dalam ingatan banyak orang. Itulah sebab, mengapa dia selalu bersembunyi. Selalu kembali kepada William (Hugh Grant), lelaki yang riuh aroma pasar dan jalan, kealamiahan.
Anna memang bukan Tamara. Bagi sebagian aktris kita, hidup dalam ingatan banyak orang adalah kebahagiaan. Mereka lupa, ingatan bersama itu juga yang kelak menjadi hakim atas sikap mereka. Seperti kisah Tamara dan Rafli yang memperebutkan Rasya.
Tamara merasa dijauhkan dari buah hatinya. Dia menilai Rafli tidak berlaku adil. Haknya sebagai ibu tidak dipenuhi. Dia mengecam, dan melaporkan psikolog Yussy ke polisi. "Saya tidak ingin ada pihak ketiga yang selalu mencampuri urusan kami," katanya. Tamara lupa, puluhan kamera yang mengikuti seluruh geraknya di rumah Rafli, yang merekam teriakan dan airmatanya, juga adalah pihak ketiga. Polisi, Ersa Syarif pengacaranya, adalah juga pihak ketiga-kesekian. Penonton juga pihak ketiga, yang dilibatkan Tamara untuk melihatnya dengan iba, mendukungnya dengan bela. Tapi penonton tak pernah lupa, karena "Insert", "Kabar-kabari", "Silet", "Kasak-Kusuk" dan puluhan infotainmen lain telah mengarsip hidup Tamara, dan membukanya di setiap pagi, siang dan senja; bahwa pernah dulu Tamara melakukan hal yang sama, menghaki Rassya hanya untuk dirinya. "Kini posisi itu berubah sudah," kata narator "Insert".
Mungkin, ingatan itu juga yang membuat kisah Tamara berbeda dari Notting Hill. Ada yang terasa menyentuh ketika dengan putus asa Anna mengiba, "...lihatlah aku. Bagaimanapun aku seorang perempuan, yang menyatakan cintanya pada seorang lelaki, yang hanya minta dicintai..." Anna hanya ingin dilihat sebagai seorang perempuan, sosok yang tak mengemban karakter apa pun. Diri yang bersih dari kamera. Adegan itu pun terjadi di toko buku wisata, tempat orang datang dengan kesadaran untuk pergi, bergegas, berpindah. Anna ingin berhenti. Dia capek menanggungkan kebohongan. "Apakah kau berharap aku jujur berkata tentang perasaanku di depan kamera?" Begitulah dia berkata sebelumnya, ketika William mengungkit kebohongannya di depan kamera.
Saya bayangkan Tamara mendatangi Rafli, Rasya, dan mertuanya di Tirtayasa, seorang diri, tanpa kamera. Saya angankan dengan lelah dia berkata, "Rafli, bagaimanapun aku adalah seorang ibu, yang haus memeluk anaknya. Bagaimanapun aku adalah perempuan yang pernah engkau cintai, yang engkau percayai merahimi Rasya. Pandanglah aku dengan semua kebaikan itu. Lihatlah, pernah ada hal yang begitu indah dalam kehidupan kita. Apakah engkau percaya bahwa aku akan merusak keindahan itu?"
Saya bayangkan Rafli akan menuntun Rasya, dan mendekapkannya ke Tamara, sambil berbisik, "Begitulah Tamara, begitulah seharusnya..." Dan di sudut sana, Cut Haslinda, mertua Tamara, tersenyum, mengucap hamdallah, dengan menyusut airmata.
Hidup kadang diisi oleh hal-hal yang dramatik. Dan semua bisa jadi indah jika itu bukan bagian dari sandiwara....
[Artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 22 April 2007]
( t.i.l.i.k ! )
Thursday, April 12, 2007
Uang Sebagai Mata Ketiga
Uang adalah solusi sekaligus masalah tanpa henti.
 Di depan 500 juta kita barangkali sulit untuk tertawa. Tapi Jack melakukan itu. Dia tertawa, bahunya berguncang, ketika rivalnya, Richard, menahan mual memakan senampan kecil keju, sesuap-suap. Di sampingnya, Mandy, juga rivalnya, memegangi perut dengan wajah pucat, menahan muntah. Hanya Joe Rogan, pembawa acara, yang juga mengumbar senyum, meski alisnya sesekali terangkat, mengusir rasa jijik.
Di depan 500 juta kita barangkali sulit untuk tertawa. Tapi Jack melakukan itu. Dia tertawa, bahunya berguncang, ketika rivalnya, Richard, menahan mual memakan senampan kecil keju, sesuap-suap. Di sampingnya, Mandy, juga rivalnya, memegangi perut dengan wajah pucat, menahan muntah. Hanya Joe Rogan, pembawa acara, yang juga mengumbar senyum, meski alisnya sesekali terangkat, mengusir rasa jijik.
Richard memang menderita. Keju itu, yang dideskripsikan Joe dengan, "dicampur bola mata dan limpa sapi, dan disimpan selama dua tahun, sehingga belatung muncul dan bersarang di dalamnya," terasa begitu menyiksa. Airmata Richard menetes, berkali-kali dia terbatuk dan nyaris muntah, tubuhnya limbung. Tapi, keju menjijikkan itu tetap dia masukkan, sejumput, terus, dimotivasi Joe yang selalu mengingatkan jumlah uang yang akan dia raih jika berhasil menyelesaikan sesi kedua itu. Joe juga memarahi Jack yang seperti mengejek. "Nanti baru kau rasakan ketika giliranmu tiba." Jack tetap tertawa.
Richard memang berhasil. Senampan keju itu pun tandas. Dia lalu berjalan ke luar arena, mengorek mulutnya dengan jari, dan memuntahkan seluruh keju busuk itu. Jack tetap tertawa. "Sekarang, 50 ribu dollar makin dekat ke Richard," puji Joe. "Giliranmu Jack. Semoga kau masih bisa tertawa."
Jack tersenyum, dengan ringan berjalan ke meja, mengambil nampan keju jatahnya. Dilihatnya Richard, Mandy, Joe yang menunggu suapan pertamanya. Tapi, tiba-tiba, Jack membanting nampan itu ke lantai. "Ini sinting! Aku tidak akan pernah mau makan ini. Dan kau Richard, kau orang paling bodoh yang pernah kulihat mau merendahkan harga diri hanya karena uang. Aku jijik berada di sini, aku jijik bersama kalian yang karena uang mau melakukan apa pun!" Berbalik badan, Jack pergi.
Joe terdiam. Itu reaksi yang tidak pernah dia bayangkan. Richard, Mandy, mematung beberapa saat. Ucapan Jack barangkali lebih terasa menyakitkan daripada keju busuk itu. Tapi Joe tak boleh membiarkan kesadaran itu menyusup terlalu dalam. Dia segera mencairkan suasana, bertepuk tangan, dengan lugas berkata, "Yeah, kita tidak tahu apa yang ada di kepala Jack. Dia terlalu serius dengan hidupnya. Apa pun itu, dia telah gagal, dan 50 ribu dolar kini tinggal kalian berdua yang akan mendapatkannya. Mandy, giliranmu...."
Joe mungkin benar, Jack terlalu serius memaknai "permainan" itu. Bagi Joe yang telah mengampu ratusan episode "Fear Factor", sikap Jack adalah sebuah anomali. Telah dia saksikan puluhan orang yang meski terbatuk, muntah, mual berat sampai meneteskan liur dan airmata, tetap "menikmati" permainan itu. Telah ratusan orang berhasil dia motivasi untuk dapat memakan keju busuk, jus limpa babi busuk berbelatung, dan bola mata sapi, sampai bubur dari campuran empedu ular, isi perut ikan dan zakar sapi. Semuanya berhasil. 50 ribu dolar terlalu sayang untuk hilang hanya karena makanan busuk itu. Joe berbicara atas dasar pengalaman, Jack bukan bagian dari itu. Tawa Jack jadi sebuah keseriusan di matanya.
Cermin Uang
"Fear Factor" memang cermin tentang sikap manusia yang tak bisa tertawa di depan uang. Sikap yang juga pernah kita temukan dalam "Tantangan" di Indosiar, dan "Fear Factor Indonesia" Di RCTI. Ketika makan kepingan pisau silet, jus cacing tanah-otak sapi mentah, atau jus cabai-cacing, menjadi hal ringan. Tiga juta rupiah di "Tantangan" dan 50 juta rupiah di "Fear Faktor Indonesia" membuat mulut dan perut jadi mungkin mengunyah segalanya. Uang, dengan kekuatan sihirnya, membuat sesuatu yang semula tak terbayangkan dapat dimakan, dengan enteng dikunyah, dimamah. Selebihnya terselip juga rasa bangga, mungkin prestasi.
Memaknai hal di atas sebagai prestasi dilakukan dengan cerdas oleh "Gong Show" yang tayang setiap Sabtu-Minggu di TransTV. Di acara itu, melukis dengan lidah, menelan berpuluh telur mentah, memotong rambut dengan api, atau menguyah cabai rawit satu gelas, disambut dengan tepukan dan rasa puas. Ada Arie K Untung yang memandu, detik yang mencatat, dan gong yang menghentikan aksi. Waktu yang tercatat adalah ukuran uang yang didapat. Satu menit mengunyah cabai rawit bernilai Rp 1,2 juta ketika Komeng memukulkan palu ke gong. 42 detik adalah ratusan ribu rupiah, ketika Anya Dwinov atau Ulfa memukul gong. Uang adalah hasil akhir, tujuan. Pepatah waktu adalah uang, termanifestasikan dengan tepat di acara ini.
Waktu adalah uang, prestasi maknanya pun harus uang. Itulah roh zaman. Penyair Jerman Goethe pun mengakuinya dengan mengatakan, "Kini, uang adalah dewa dunia." Goethe memakai kata "kini" karena dia tahu, pernah dulu, uang bukanlah apa-apa, hanya sekadar alat tukar, sebuah instrumen yang diciptakan untuk membantu dan memudahkan aktivitas manusia. Sebagai alat, uang adalah solusi, penyelesai masalah.
Kini, peran uang berubah secara drastis, menjadi aktor utama di dalam kehidupan manusia. Uang menjadi roda ekonomi. Perputaran ekonomi diukur dari perputaran uang. Bahkan, kini dunia pun berputar dan berporos dari uang. Tak heran kalau sosiolog Jerman Georg Simmel melihat uang sebagai manifestasi totalitas kehidupan manusia. Melalui buku The Philosophy of Money, Simmel melihat uang berimplikasi pada kehidupan manusia secara luas, membentuk dan mempengaruhi budaya. Jika ketika hanya berfungsi sebagai alat tukar uang adalah solusi, kini sebaliknya. Uang yang telah menjadi tujuan hidup, lebih disarati masalah. Uang sebagai tujuan mengubah pola pandang masyarakat, mengubah struktur pergaulan, pola komunikasi, dan nilai-nilai. Nilai pertemanan bahkan dapat diukur dari uang yang seseorang rela utangkan. Uang adalah mata ketiga, yang membuat kita dapat melihat realitas yang semula tak terbayangkan. Hidup yang mungkin tempak jadi lebih indah, atau mengerikan. Uang membuat waktu terasa lebih cepat, dan hidup menjadi begitu padat, ringkas, sekaligus serius. Itulah sebabnya, sulit mencari orang yang seperti Jack, yang dapat tertawa di depan uang, dapat menampiknya dengan ringan.
Jack adalah contoh watak yang tak mau diringkus oleh pesona uang. Uang memang penting, tapi bukan segalanya. Uang mungkin dapat membeli apa pun, tapi tidak harga dirinya. Jack adalah contoh sedikit orang yang masih percaya, bahwa manusia lebih berkuasa di depan uang. Itulah sebabnya dia tertawa. Karena dia tahu, di depan uang, manusia bisa memilih untuk tetap menjadi manusia atau berubah jadi seonggok campuran keju busuk berbelatung. Jack memilih mengedepankan akal budinya, tak runduk, tak tunduk. Uang adalah godaan yang dia usir dengan tawa. Sungguh, sebuah sikap yang "aneh" di zaman ini. Watak yang sulit dicari, yang diam-diam juga kita rindui....
[Artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 15 April 2007]
( t.i.l.i.k ! )
 Di depan 500 juta kita barangkali sulit untuk tertawa. Tapi Jack melakukan itu. Dia tertawa, bahunya berguncang, ketika rivalnya, Richard, menahan mual memakan senampan kecil keju, sesuap-suap. Di sampingnya, Mandy, juga rivalnya, memegangi perut dengan wajah pucat, menahan muntah. Hanya Joe Rogan, pembawa acara, yang juga mengumbar senyum, meski alisnya sesekali terangkat, mengusir rasa jijik.
Di depan 500 juta kita barangkali sulit untuk tertawa. Tapi Jack melakukan itu. Dia tertawa, bahunya berguncang, ketika rivalnya, Richard, menahan mual memakan senampan kecil keju, sesuap-suap. Di sampingnya, Mandy, juga rivalnya, memegangi perut dengan wajah pucat, menahan muntah. Hanya Joe Rogan, pembawa acara, yang juga mengumbar senyum, meski alisnya sesekali terangkat, mengusir rasa jijik.Richard memang menderita. Keju itu, yang dideskripsikan Joe dengan, "dicampur bola mata dan limpa sapi, dan disimpan selama dua tahun, sehingga belatung muncul dan bersarang di dalamnya," terasa begitu menyiksa. Airmata Richard menetes, berkali-kali dia terbatuk dan nyaris muntah, tubuhnya limbung. Tapi, keju menjijikkan itu tetap dia masukkan, sejumput, terus, dimotivasi Joe yang selalu mengingatkan jumlah uang yang akan dia raih jika berhasil menyelesaikan sesi kedua itu. Joe juga memarahi Jack yang seperti mengejek. "Nanti baru kau rasakan ketika giliranmu tiba." Jack tetap tertawa.
Richard memang berhasil. Senampan keju itu pun tandas. Dia lalu berjalan ke luar arena, mengorek mulutnya dengan jari, dan memuntahkan seluruh keju busuk itu. Jack tetap tertawa. "Sekarang, 50 ribu dollar makin dekat ke Richard," puji Joe. "Giliranmu Jack. Semoga kau masih bisa tertawa."
Jack tersenyum, dengan ringan berjalan ke meja, mengambil nampan keju jatahnya. Dilihatnya Richard, Mandy, Joe yang menunggu suapan pertamanya. Tapi, tiba-tiba, Jack membanting nampan itu ke lantai. "Ini sinting! Aku tidak akan pernah mau makan ini. Dan kau Richard, kau orang paling bodoh yang pernah kulihat mau merendahkan harga diri hanya karena uang. Aku jijik berada di sini, aku jijik bersama kalian yang karena uang mau melakukan apa pun!" Berbalik badan, Jack pergi.
Joe terdiam. Itu reaksi yang tidak pernah dia bayangkan. Richard, Mandy, mematung beberapa saat. Ucapan Jack barangkali lebih terasa menyakitkan daripada keju busuk itu. Tapi Joe tak boleh membiarkan kesadaran itu menyusup terlalu dalam. Dia segera mencairkan suasana, bertepuk tangan, dengan lugas berkata, "Yeah, kita tidak tahu apa yang ada di kepala Jack. Dia terlalu serius dengan hidupnya. Apa pun itu, dia telah gagal, dan 50 ribu dolar kini tinggal kalian berdua yang akan mendapatkannya. Mandy, giliranmu...."
Joe mungkin benar, Jack terlalu serius memaknai "permainan" itu. Bagi Joe yang telah mengampu ratusan episode "Fear Factor", sikap Jack adalah sebuah anomali. Telah dia saksikan puluhan orang yang meski terbatuk, muntah, mual berat sampai meneteskan liur dan airmata, tetap "menikmati" permainan itu. Telah ratusan orang berhasil dia motivasi untuk dapat memakan keju busuk, jus limpa babi busuk berbelatung, dan bola mata sapi, sampai bubur dari campuran empedu ular, isi perut ikan dan zakar sapi. Semuanya berhasil. 50 ribu dolar terlalu sayang untuk hilang hanya karena makanan busuk itu. Joe berbicara atas dasar pengalaman, Jack bukan bagian dari itu. Tawa Jack jadi sebuah keseriusan di matanya.
Cermin Uang
"Fear Factor" memang cermin tentang sikap manusia yang tak bisa tertawa di depan uang. Sikap yang juga pernah kita temukan dalam "Tantangan" di Indosiar, dan "Fear Factor Indonesia" Di RCTI. Ketika makan kepingan pisau silet, jus cacing tanah-otak sapi mentah, atau jus cabai-cacing, menjadi hal ringan. Tiga juta rupiah di "Tantangan" dan 50 juta rupiah di "Fear Faktor Indonesia" membuat mulut dan perut jadi mungkin mengunyah segalanya. Uang, dengan kekuatan sihirnya, membuat sesuatu yang semula tak terbayangkan dapat dimakan, dengan enteng dikunyah, dimamah. Selebihnya terselip juga rasa bangga, mungkin prestasi.
Memaknai hal di atas sebagai prestasi dilakukan dengan cerdas oleh "Gong Show" yang tayang setiap Sabtu-Minggu di TransTV. Di acara itu, melukis dengan lidah, menelan berpuluh telur mentah, memotong rambut dengan api, atau menguyah cabai rawit satu gelas, disambut dengan tepukan dan rasa puas. Ada Arie K Untung yang memandu, detik yang mencatat, dan gong yang menghentikan aksi. Waktu yang tercatat adalah ukuran uang yang didapat. Satu menit mengunyah cabai rawit bernilai Rp 1,2 juta ketika Komeng memukulkan palu ke gong. 42 detik adalah ratusan ribu rupiah, ketika Anya Dwinov atau Ulfa memukul gong. Uang adalah hasil akhir, tujuan. Pepatah waktu adalah uang, termanifestasikan dengan tepat di acara ini.
Waktu adalah uang, prestasi maknanya pun harus uang. Itulah roh zaman. Penyair Jerman Goethe pun mengakuinya dengan mengatakan, "Kini, uang adalah dewa dunia." Goethe memakai kata "kini" karena dia tahu, pernah dulu, uang bukanlah apa-apa, hanya sekadar alat tukar, sebuah instrumen yang diciptakan untuk membantu dan memudahkan aktivitas manusia. Sebagai alat, uang adalah solusi, penyelesai masalah.
Kini, peran uang berubah secara drastis, menjadi aktor utama di dalam kehidupan manusia. Uang menjadi roda ekonomi. Perputaran ekonomi diukur dari perputaran uang. Bahkan, kini dunia pun berputar dan berporos dari uang. Tak heran kalau sosiolog Jerman Georg Simmel melihat uang sebagai manifestasi totalitas kehidupan manusia. Melalui buku The Philosophy of Money, Simmel melihat uang berimplikasi pada kehidupan manusia secara luas, membentuk dan mempengaruhi budaya. Jika ketika hanya berfungsi sebagai alat tukar uang adalah solusi, kini sebaliknya. Uang yang telah menjadi tujuan hidup, lebih disarati masalah. Uang sebagai tujuan mengubah pola pandang masyarakat, mengubah struktur pergaulan, pola komunikasi, dan nilai-nilai. Nilai pertemanan bahkan dapat diukur dari uang yang seseorang rela utangkan. Uang adalah mata ketiga, yang membuat kita dapat melihat realitas yang semula tak terbayangkan. Hidup yang mungkin tempak jadi lebih indah, atau mengerikan. Uang membuat waktu terasa lebih cepat, dan hidup menjadi begitu padat, ringkas, sekaligus serius. Itulah sebabnya, sulit mencari orang yang seperti Jack, yang dapat tertawa di depan uang, dapat menampiknya dengan ringan.
Jack adalah contoh watak yang tak mau diringkus oleh pesona uang. Uang memang penting, tapi bukan segalanya. Uang mungkin dapat membeli apa pun, tapi tidak harga dirinya. Jack adalah contoh sedikit orang yang masih percaya, bahwa manusia lebih berkuasa di depan uang. Itulah sebabnya dia tertawa. Karena dia tahu, di depan uang, manusia bisa memilih untuk tetap menjadi manusia atau berubah jadi seonggok campuran keju busuk berbelatung. Jack memilih mengedepankan akal budinya, tak runduk, tak tunduk. Uang adalah godaan yang dia usir dengan tawa. Sungguh, sebuah sikap yang "aneh" di zaman ini. Watak yang sulit dicari, yang diam-diam juga kita rindui....
[Artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 15 April 2007]
( t.i.l.i.k ! )