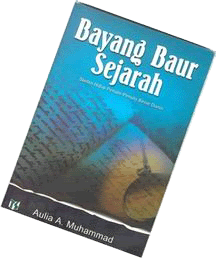...tera di sesela gegas-gesa
Thursday, August 25, 2005
Pangeran Pewarta Kecemasan
 JIKA ada satu sosok yang mampu mengubah ketakutan, nyeri dan sadis, juga pedih, menjadi candu ketagihan, memesona dan menghipnotis, jelas Stephen King orangnya. Puluhan novel "yang mencekam sampai ke mimpi Anda" lahir dari tangannya, dan antrean pembaca tetap saja ada, rela mengeluarkan uang membeli ketakutan tersebut. Kenyataan inilah yang membuat banyak pengamat cerita menjuluki Stephen sebagai raja kegelapan, pengeran kengerian di dekade ini.
JIKA ada satu sosok yang mampu mengubah ketakutan, nyeri dan sadis, juga pedih, menjadi candu ketagihan, memesona dan menghipnotis, jelas Stephen King orangnya. Puluhan novel "yang mencekam sampai ke mimpi Anda" lahir dari tangannya, dan antrean pembaca tetap saja ada, rela mengeluarkan uang membeli ketakutan tersebut. Kenyataan inilah yang membuat banyak pengamat cerita menjuluki Stephen sebagai raja kegelapan, pengeran kengerian di dekade ini.Mei tiga tahun lalu, ketika ia meluncurkan Dreamcatcher, banyak yang tak yakin pesona misterinya masih menakjubkan. Tapi, begitu toko-toko buku meminta terus cetak ulang, tak ada lagi kesangsian bagi ahli bahasa ini, novel itu bahkan mencatatkan diri terlaris di New York Times.
Sebelum Dreamcatcher dibincangkan, Stephen sudah menggebrak, meluncurkan novel maya, electronic book, The Plant, di internet, sebagai cerita bersambung, di situs pribadinya. Ia meminta para pembaca yang men-download cerita itu hanya membayar US$ 1 saja. Hasilnya, sampai 6 bulan pertama, ia meraih US$ 463.832, sebuah hasil yang amat fantastis!
Namun, karena menilai karya itu lebih banyak dicuri daripada dibayar, King hanya menampilkannya selama 6 bulan itu, dan menarik dari situsnya. "Masih selalu ada orang yang keberatan membayar satu dolar untuk sebuah petualangan kecil yang amat memesona. Ini mengecewakan," katanya.
Sebelum The Plant, sebenarnya ia telah mencoba menjelajahi internet dengan karya magisnya, Riding the Bullets, dan sukses. Ini sekaligus juga menandai kiprah seorang penulis yang memakai media maya itu sebagai ajang distribusi dan "cetak". Sejak awal ia memang telah yakin, internet adalah masa depan yang dapat memecahkan masalah perbukuan, distribusi dan harga. Melalui dunia maya itu King bertekad memperluas bentangan pengaruh kemisteriusan dan ngeri, yang menjadi spesialisasinya.
Satu Rumah Satu Novel
King lahir di Portland, Maine, Amerika Serikat, 1947. Sejak kecil, ia telah tak lagi mengenal bapaknya, dan bersama kakaknya, David, ia diasuh oleh ibunya, sebagai orang tua tunggal. Sampai usia 1 tahun, ia mengikuti ibunya yang bertugas sebagai perawat di Fort Wayne, Indiana, serta di Stratford, Connecticut, AS. Selanjutnya, sampai dewasa, ia menetap di Maine, karena ibunya kembali ke rumah nenek dan kakeknya yang telah renta dan butuh perawatan.
Setelah kakek-neneknya meninggal, ibunya tetap memilih Maine sebagai tempat tinggal. King malah berangkat ke Durham, dan kemudian ke Lisbon Falls High School sampai tahun 1966, mempelajari tata bahasa.
"Di masa itu kepalaku mulai dipenuhi ledakan-ledakan kecil, sebuah arus cerita," kenangnya.
Memasuki tahun kedua di Universitas Maine, Orono, namanya mulai terkenal, karena aktif menulis di koran kampus, The Maine Campus.
Di kampus ia juga aktif berpolitik dan menjadi anggota senat. Dia juga bersuara keras saat Amerika berperang di Vietnam, menentangnya. "Itu perang yang tidak konstitusional," kecamnya.
Setelah lulus sebagai sarjana muda Bahasa Inggris tahun 1970, ia langsung mengajar di sekolah menengah atas, sebagai honorer. Setahun kemudian ia menikah, padahal pekerjaan sebagai guru tetap tak juga ia dapatkan. Untuk membiayai kehidupan keluarganya, tak ada jalan lain, ia menjadi binatu.
Masa itu dikenang King dengan penuh senyum karena ketika menjadi binatu itulah, saat kesulitan menghadang, ide-ide bepercikan, memijar di kepalanya. Ia pun menulis cerita pendek, semata-mata hanya untuk menambah penghasilan. Dengan malu, juga harap cemas, ia tawarkan cerita-cerita pendek itu ke belbagai majalah, dan kemudian diterbitkan dalam antologi Night Shift. Ini tangga awal perjalanan kariernya, yang King juga tak pernah duga.
 Setahun kemudian, ia menjadi guru tetap di sekolah menengah di Hampden Academy, Maine. Sepulang mengajar, King selalu kembali ke kamar kerjanya, menulis sepanjang malam, membuat cerita pendek dan novel. Namun, baru pada tahun 1973, penerbit Doubleday & Co bersepakat menerbitkan novel perdananya, Carrie.
Setahun kemudian, ia menjadi guru tetap di sekolah menengah di Hampden Academy, Maine. Sepulang mengajar, King selalu kembali ke kamar kerjanya, menulis sepanjang malam, membuat cerita pendek dan novel. Namun, baru pada tahun 1973, penerbit Doubleday & Co bersepakat menerbitkan novel perdananya, Carrie.Membaca gaya bercerita yang dia kembangkan, penyunting buku King menganjurkan agar ia secepatnya keluar dari profesinya sebagai pengajar, berkonsentrasi penuh sebagai novelis. Dan King, tanpa ragu, patuh.
Sejak itulah, ia fokus. Tahun berikutnya lahir Second Coming dan Jerussalem's Lot, yang kemudian ia ubah menjadi Salem's Lot. Kedua novel ini ia kerjakan di garasi rumahnya!
Carrie dipublikasikan pada musim gugur 1974, dan ia segera berpindah dari Maine menuju Boulder, Colorado. Mereka tinggal di sini setidaknya satu tahun, dan begitu karyanya The Shinning terbit, ia pun pindah lagi, kembali ke Maine, membeli tanah dan rumah di Lakes Region, bagian barat Maine. Di sini kembali ia melahirkan The Stand dengan latar cerita di Boulder, dan novel mencekam lainnya, Dead Zone. Ia pun pindah rumah lagi.
Tahun berikutnya, 1980, ia melahirkan Firestarter, dan seterusnya untuk setiap tahun, Cujo, The Dark Tower, Cristine, Pet Sematari, The Talisman, IT, The Eyes of the Dragon and Misery (1987). Dan, untuk satu cerita, setidaknya ia akan pindah rumah satu kali. Karena itu, banyak yang mengatakan setiap tempat yang ia singgahi atau ia beli, akan selalu menjadi bagian dari ceritanya. Kegemarannya berpindah bahkan menjadi cerita tersendiri di mata penggemarnya, untuk menebak apa cerita yang akan ia buat dengan latar belakang daerah yang baru ia tinggali.
Kepiawaiannya itu bukan hanya menambah tebal pundi-pundinya, tapi juga melambungkan namanya. Naskahnya pun diminta produser Hollywood untuk difilmkan, dan hebatnya, juga meraih sukses!
Sejumlah novelnya yang diangkat ke layar perak adalah Carrie, The Dead Zone, dan The Shinning. Ia juga menulis skenario dua film, Knightriders dan Creepshow. Novelnya The Body diadaptasikan ke film sebagai Stand By Me. Ia malah menjadi seorang menteri untuk filmnya Pet Sematary, dan berkeliling universitas memberi kuliah proses kreatif dan jalan lahirnya ide.
Sampai kini, terhitung ada 60 novel dan cerita pendek yang telah lahir dari tangannya, dan semua mendapatkan tanggapan yang tak pernah mengecewakan, bahkan kian melambungkan namanya. Tak heran, setidaknya 10 buku pun telah dibuat orang lain untuk memaparkan pribadi, perjalanan karier dan proses kreatif, serta ide-ide dari pangeran kegelapan ini.
( t.i.l.i.k ! )
Thursday, August 18, 2005
Indonesia tak Pernah Memilih
 "INDONESIA memilih...." teriak Atta dan Irgi, lalu mereka diam, menyebarkan suasana tegang ke seluruh arena. Kamera mensyut wajah Mike, Judika, lalu menjauh, menyorot empat sosok itu. Sesaat kemudian, kamera menangkap ibu Mike, Yudhayani, yang menangkupkan tangan ke wajahnya, dengan bibir yang tersamar berdoa. Kamera kembali ke panggung, sesaat sebelum Atta dan Irgi meneriakkan nama Mike sebagai pemenang.
"INDONESIA memilih...." teriak Atta dan Irgi, lalu mereka diam, menyebarkan suasana tegang ke seluruh arena. Kamera mensyut wajah Mike, Judika, lalu menjauh, menyorot empat sosok itu. Sesaat kemudian, kamera menangkap ibu Mike, Yudhayani, yang menangkupkan tangan ke wajahnya, dengan bibir yang tersamar berdoa. Kamera kembali ke panggung, sesaat sebelum Atta dan Irgi meneriakkan nama Mike sebagai pemenang.Ucapan "Indonesia memilih...." dari lengking Atta barangkali menjadi penanda yang paling berbeda dari acara sejenis di teve lain. "Indonesia Idol" memang punya pesaing semacam "AFI", "KDI", atau "KondangIn", yang juga memanfaatkan poling melalui SMS untuk menentukan pemenang. Tapi, meski memakai metode yang sama, hanya "Indonesia Idol" yang secara berani mengatakan "Dan Indonesia memilih...." Ucapan yang biasanya selalu menjadi akhir dari ajakan, "Anda yang memilih, Anda yang menentukan". Dan saya kira, ucapan ini sudah layak untuk ditelusuri validitasnya, apakah benar acara-acara di atas sungguh-sungguh memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk bebas memilih.
Mike # Delon
Kita mulai dari kasus Mike. Sedari awal memang penampilannya sudah mengagumkan. Suaranya merdu, dan dengan tubuh gemuknya, dia masih mampu menjangkau nada-nada tinggi. Penampilannya di panggung santun, terkesan rendah hati, dan ini yang paling penting, sangat sayang pada ibunya. Saat 12 calon idola itu bertarung, Mike secara cerdas justru mempersembahkan lagu yang dia bawakan untuk ibunya. Cara yang tidak ditempuh oleh peserta lain. Dan, mulai dari sinilah kamera "melakukan" intervensinya atas citra Mike. Sejak malam perdana itu, sosok ibu Mike selalu mendapat porsi. Wajah Yudhayani yang tegang, tertawa, bangga, cemas, gugup, menangis, meletakkan tangan di dada, menangkupkan tangan di wajah, getar bibir berdoa, tangan yang cemas mencari pegangan dengan ibu di sebelahnya, mata yang selalu basah, selalu tersaji selama perhelatan itu. Puncak paling dramatis adalah di saat tiga besar, kala Mike menyanyikan lagu "Bunda" milik Melly. Kamera secara cerdas --dan juga memihak-- menunjukkan sesenggukan Yudhayani, dan hening arena yang terhisap dalam aura kasih-sayang Mike. Kamera juga memperlihatkan Titi DJ yang menangis, Indra yang tanpa sadar berdiri dengan mata berkaca, dan wajah-wajah para pendukung Judika yang seperti tersihir, terdiam. Ketika Mike terlihat menangis, kamera secara cepat menuju ke ibunya, yang juga menangis. Saya pun, ribuan kilo dari panggung itu, terhisap, airmata saya berloncatan.
Cara kerja kamera ini bukan hal yang biasa. Judika tidak mendapatkan "pembentukan" imaji yang sama sejak semula. Benar bahwa orangtua Judika tidak berada di atas panggung. Tapi "mempertontonkan" cinta Mike dan ibunya dalam sebuah tayangan yang memang berharap simpati dari penonton, tentu bukan sesuatu yang dapat diterima sebagai sebuah kewajaran.
Tidak hanya kamera, juri pun melakukan pembedaan. Di sinilah kita dapat melihat beda Mike dan Delon. Secara visual, "kelemahan" Mike adalah pada bentuk tubuhnya. Tapi sejak awal, "kelemahan" itu dianulir oleh para juri. Titi DJ mengatakan, "Mike, kamu jangan minder dengan bentuk tubuhmu. Kebesaran kamu menyimpan cinta dan kelembutan..." Indra Lesmana menghilangkan kegemukan itu dengan, "Mike, kamu bernyanyi dengan hati. Kerasa banget..." Dimas Jay membuat absen faktor gemuk itu, "Ternyata kamu juga lincah, bisa berjoged..."
Menyangkut visual, terutama di televisi, ketampanan dan kelangsingan, adalah nilai tambah, bahkan utama. Popularitas dan ketampanan selalu bersanding. Tapi Delon tidak mendapatkannya dari juri. Ketampanannya adalah kelemahannya, dan selalu menjadi bahan ejekan juri. "Indonesia Idol tak hanya butuh tampang!" kata Indra suatu kali. Titi DJ pun berkata, "Kamu hanya punya tampang!"
Dalam dua kali penyelenggarakan Indonesia Idol kita dapat melihat bagaimana tubuh seseorang menjadi sorotan untuk sebuah ajang penilaian suara. Nilai tubuh yang justru didudukkan tidak dalam porsi yang adil, terutama jika dinilai dari kacamata ajang popularitas.
Masihkan kita berpikir Indonesia memang memilih?
Penonton = Objek
 Contoh sama dari acara yang berbeda, AFI. Tayangan pertama dimulai dengan keterkejutan kita pada Very. Penyanyi yang hanya bisa berdangdut itu melejit. Selain permainan kamera, Veri juga memenuhi benak banyak orang karena rumor yang "diskenariokan" untuknya. "Percintaannya" dengan Mawar memenuhi "Diari AFI". Dan yang paling heboh adalah perjuangannya untuk bisa mengikuti ajang tersebut, dengan harus menjual cincin perkawinan ibunya. Media --terutama Indosiar dan tabloid Gaul-- mencitrakannya sebagai sosok yang paling pantas untuk didukung. Peserta lain, Kia, Mawar, Rini, dan Romi mendapat porsi di kamera justru berkaitan dengan kehadiran Very.
Contoh sama dari acara yang berbeda, AFI. Tayangan pertama dimulai dengan keterkejutan kita pada Very. Penyanyi yang hanya bisa berdangdut itu melejit. Selain permainan kamera, Veri juga memenuhi benak banyak orang karena rumor yang "diskenariokan" untuknya. "Percintaannya" dengan Mawar memenuhi "Diari AFI". Dan yang paling heboh adalah perjuangannya untuk bisa mengikuti ajang tersebut, dengan harus menjual cincin perkawinan ibunya. Media --terutama Indosiar dan tabloid Gaul-- mencitrakannya sebagai sosok yang paling pantas untuk didukung. Peserta lain, Kia, Mawar, Rini, dan Romi mendapat porsi di kamera justru berkaitan dengan kehadiran Very.dan contoh yang paling parah ada pada AFI 2005. Sejak awal, porsi kamera dapat dilihat sebagai dukungan pada Bojes. Strategi seperti pada Very pun ditempuh. Bojes "dijodohkan" dengan Tiwi. Diary AFI dipenuhi gosip itu. Tapi berbeda dari Mawar, langkah Tiwi cuma sampai 6 besar. Ia tersingkir. Strategi itu tidak berjalan seperti yang diinginkan. Bukan hanya Tiwi, Bojes yang dijuluki sebagai "smart boy" pun juga terancam.
Pada eliminasi 5 besar Minggu (7/7), sedari awal acara, dukungan SMS untuk Bojes paling rendah. Dan 2 menit sebelum pengiriman SMS ditutup, di layar teve masih terlihat Bojes berada di bawah, dengan prosentasi yang cukup jauh dari peserta yang lain. Dan ketika di akhir acara, satu persatu kontestan diminta membuka amplop untuk melihat foto siapa yang tak ada. Hasilnya, dengan enteng Adi Nugroho mengatakan bahwa malam itu tidak ada eliminasi, semua hanya latihan saja. Sungguh mengagetkan. Bagaimana perasaan ribuan orang yang mengirimkan SMS dan berharap cemas, hanya dipatahkan dengan sebuah keputusan tak adanya eliminasi. Tidakkah Indosiar melakukan "kecurangan?" Tidakkah hal itu dilakukan hanya untuk menyelamatkan Bojes, yang sudah sejak awal terlihat memenuhi "standart" untuk dijadikan bintang? Jawaban Indosiar, tidak. Melalui Adi Nugroho, mereka menyatakan tak ada kecurangan, karena dukungan SMS digabungkan pada Minggu (14/7) lalu. Hasilnya, Luri yang dikorbankan. Padahal, di Minggu (7/7), dia berada dalam posisi aman.
Masihkan Indonesia sungguh-sungguh memilih?
Mike jelas, seperti kata Indra, sosok yang lahir memang sudah untuk menjadi bintang. Dan Mike memang layak memenangi "Indonesia Idol", sama layaknya dengan Judika, yang di empat minggu terakhir, menunjukkan pencapaian kualitas suara dan aksi panggung luar biasa. Masalahnya adalah penilaian layak ini --yang secara awal sudah dinilai dan dilihat oleh RCTI, Fremantle, dan para juri-- dijajahkan ke dalam benak penonton melalui mekanisme yang tidak adil bagi kontestan lain. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan acara itu menghendaki sosok yang "bernilai jual" di panggung hiburan --dan kelak bisa menghasilkan kapital yang besar-- juga disukai dan dipilih oleh penonton, yang kelak dapat mereka mintai tanggungjawabnya. Dan satu cara untuk membuat semua itu menjadi nyata adalah dengan memilihkan untuk penonton sosok mana yang paling pantas dijadikan bintang. Kia lebih bagus dari Veri, tapi harus Very yang menang. Adek dan Indri lebih bagus dari Bojes, tapi Bojes harus dilindungi. Mike dan Judika sama bagusnya. Tapi ingat Mike punya nilai lebih, sentuhan sayangnya pada ibu. Dan semua ini harus dikawal, harus "paksakan" dipilih penonton. Dengan cara halus, seperti Mike, dengan cara cukup kasar seperti Very dan Bojes, semua menjadi legal. Dan penonton tak pernah menjadi subjek, karena kesadaran mereka selalu sulit untuk menghadapi canggihnya rekayasa rasa yang dimamahkan media. Dan beginilah, Indonesia sungguh tidak pernah memilih.
[Esai ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 21 Agustus 2005]
( t.i.l.i.k ! )
Wednesday, August 10, 2005
Kepalan yang Bekerja Sendiri
 SEBELUM bel berbunyi, Ray sempat melontarkan jabnya. Dia lalu tersenyum, mengepalkan tangan. Pelipisnya biru membengkak, matanya menyipit lebam, tapi ia seperti tak merasakan. Ia bahkan tak kembali ke sudut ring, mendatangi dan memeluk lawannya. "Maaf, Hagler, aku kini membuat sejarah."
SEBELUM bel berbunyi, Ray sempat melontarkan jabnya. Dia lalu tersenyum, mengepalkan tangan. Pelipisnya biru membengkak, matanya menyipit lebam, tapi ia seperti tak merasakan. Ia bahkan tak kembali ke sudut ring, mendatangi dan memeluk lawannya. "Maaf, Hagler, aku kini membuat sejarah."Lawannya, "si kulit badak" Marvin Hagler, hanya menunduk. Dia tak sempat memberikan jawaban karena lelaki yang menyalaminya tadi, Sugar Ray Leonard, yang telah sibuk menghadapi teriakan banyak orang, official-nya yang mengerubuti, menyambut kemenangannya.
Itu memang hari yang bersejarah. 6 April 1987, di dalam ring di Caesars Palace Hotel, Las Vegas, Ray menunjukkan dirinya masih yang terbesar. Padahal, ia telah meninggalkan ring 5 tahun lamanya. Tak banyak petunju yang mampu melakukan hal semacam itu. Hanya tercatat dua nama, Sugar Ray Robinson di tahun 1950-an, dan si mulut besar Muhammad Ali, yang meng-KO-kan Joe Frazier.
Lama absen dari ring, bukan hanya soal waktu dan latihan, juga mental. Dan masalah ini, banyak petinju yang gagal. Kegamangan menginjakkan kaki di tengah puluhan pasang mata adalah satu hal. Menjawab pertanyaan pers yang meragukan, bahkan menyulut emosi, adalah hal lain. Kini Tyson membuktikan betapa beratnya hal itu. Tapi tidak bagi Ray. Ia melenggang, seolah begitu mudah, mirip keajaiban.
Padahal, siapa yang tak tahu Hagler; tubuhnya pejal berotot, tangan kanan-kirinya memukul keras. Mentalnya singa, ia telah 66 kali naik ring, 62 menang, 52 dengan KO, dan hanya 2 kali kalah, itu pundi awal karier.
Ray adalah kebalikannya; ceking, dan ia harus menaikkan berat badan untuk menantang Hagler, dan tua. Tapi ia punya otak, dan kelincahan kaki. Ia pun telah melatih diri selama setahun untuk partai itu. "Pertandingan di ring bukan cuma mengadu fisik. Ini perang psikologis," ia berkata, "Saya pun belum digerogoti karat."
Mengikutkan takdir
Seumpama tak dihisap ring, Ray hanya akan jadi pendeta. Di masa kecil, ia adalah penyanyi di "rumah Tuhan". Nama lengkapnya pun, Ray Charles Leonard, meniru penyanyi pop terkenal, Ray Charles di tahun 1950-an, yang populer dengan "I Can't Stop Loving You".
Ibunya, Getha, memang menginginkannya menjadi penyanyi, saat melahirkannya di kota kecil Wilmington, 17 Mei 1956. Ayahnya, Cicero, hanya tersenyum melihat keinginan istrinya.
Cicero yang buruh dan Getha yang pembantu di rumah sakit, tak memberi kemewahan pada Ray. Ia melewatkan masa kanak-kanak yang biasa di Washington DC. remaja, ia ikut hijrah ke Palmer Park di Maryland. Ia anak yang saleh.
"Saya tak pernah punya masalah dengan dia. Dia baik dan agak pemalu," ibunya mengenang. Ray tak suka berkelahi.
Namun, ketika teman-temannya mengatakan dia banci, perasaanya terusik. Oleh Roger, kakaknya, ia diajari bertinju, kala usianya 14. Dan takdir menuntunnya, postur tubuhnya berkembang dengan bakat itu, diasuh oleh Janks Morton, mantan petinju amatir secara sukarela, di taman rekreasi kota.
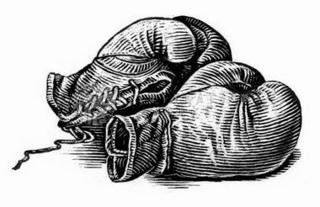 Ia lalu terinspirasi pada Sugar Robinson, juara dunia 5 kali. Untuk mendapatkan tuah, Ray menambahkan kata Sugar di depan namanya.
Ia lalu terinspirasi pada Sugar Robinson, juara dunia 5 kali. Untuk mendapatkan tuah, Ray menambahkan kata Sugar di depan namanya.Di dunia amatir, ia tak punya lawan. Puncaknya, ia dikirim ke Olimpiade Montreal '76. Ia mendapat emas di kelas welter ringan. Tapi, gayanya yang menyengat bak lebah, langsung menjadi pujaan Amerika.
Tapi, ia malah berniat menggantung sarung tinju. "Keputusan ini mutlak. Impian saya telah tercapai, perjalanan tinju telah usai," katanya. Ia bersiap sekolah di University of Maryland.
Tapi, takdir tak boleh ditolak. Ibunya masuk rumah sakit, ayahnya diserang spinal pneumonia. Ia tak punya pilihan selain bertinju untuk membiayai mereka. 1977, tangannya ia kepalkan. Luis Vega menjadi lawan pertama, 5 Februari 1977, dan ia pecundangi dalam 6 ronde. Tahun itu, ia bertarung 6 kali, menang semua.
Bayarannya melesat, gaya bertinjunya memang memikat. Di tahun itu ia telah dibayar 40 ribu dolar. Bayangkan, Hagler saja hanya mendapat 1500 dolar di tahun yang sama. Hebatnya, saat kalah dari Roberto duran Juni 1980, ia bahkan memecahkan rekor bayaran, 9,7 juta dolar. 5 bulan kemudian, Duran ia jungkalkan di ronde ke-7!
Bayarannya hebat, kariernya pun melesat. Dua tahun saja, ia sudah juara dunia kelas welter WBC. Ia menang KO atas jagoan saat itu, Wilfred Benitez. Pertarungan 15 ronde mereka bahkan menjadi partai klasik dalam dunia tinju.
Ray kian merajalela. Ia naik kelas ke menengah ringan, tetap juara. Dan semua itu takkan terjadi tanpa campur tangan Ali.
April 1976, Ali mengenalkannya pada Angelo Dundee, pelatih Ali juga, yang ingin melatih gaya bertinjunya. Dan memang, gayanya kian tak dapat dikalahkan.
September 1981, ia jungkalkan si tukang jagal Thomas Hearns, ia mendapat 10 juta dolar. Tapi, ia harus menangis, kemenangan itu meminta retina mata kirinya yang sobek. Ia terancam buta.
9 Mei 1982, operasi retinanya sukses. Dan sebagai tanda syukur, ia mengundurkan diri dari ring. Tapi, kegilaan dunia tinju, gemerlap celebration dan kibar dolar, acap menggodanya. Hanya 5 tahun Ray kuat beristirahat, 1987, ia kembali. Istrinya, Juanita, menangis darah melarang. Tapi Ray meyakinkan, tinju adalah dunianya.
Kevin Howard ia tantang, dan dia jungkalkan, KO. Kegilaannya bertambah, dan ia sesumbar akan mengalahkan Hagler.
Juanita menangis memohon Ray membatalkan partai itu. Hagler saat itu tak terkalahkan, tukang bantai nomor wahid di kelas menengah. Ray pun, harus menambah bobot badannya 6 kg untuk masuk ke kelas itu. Tapi Ray yakin, ia akan dapat mengalahkan si badak itu. Di mana pun, kapan pun, ia selalu meyakinkan Juanita.
"Aku tak akan bisa bertinju tanpa restunya. Aku akan terus membujuknya. Tapi jika dia tetap bilang tidak, aku akan patuh."
Juanita tahu dunia Ray, cita-cita terbesar suaminya. Ia pun mengizinkan. Tapi, WBA dan IBF justru menolak partai itu. Kedua badan tinju ini takut retina Ray akan jadi korban. Ray bergeming. Ia yakin menang.
WBA dan IBF gantian menekan Hagler. Hagler bahkan diwajibkan bertarung wajib dengan juara Inggris, Herol Graham. Hagler menolak, dan membiarkan dua gelarnya dicabut. Ia lebih memilih Ray karena ingin menjatuhkan si Mr Middle Class itu --sindiran Hagler karena bayaran Ray yang selalu lebih mahal.
Dalam jumpa pers sebelum bertanding, Ray bahkan tak gusar ketika diejek Hagler. Ia bahkan tersenyum saat wartawan Washington Pos mencemoohnya: "Berbagai taktik dan strategi bisa saja Anda kuasai. Tapi bagaimana mengatasi karat di tubuh Anda?" Pasar taruhan menyepelekannya, memasang 4:1 untuk kemenangan Hagler. Tapi, dengan senyum Juanita, Ray membalikkan semuanya.
"Ketika berada di ring, semuanya beres. Kepalan ini tiba-tiba saja bekerja sendiri tanpa disuruh," katanya usai pertandingan, saat istrinya mengelap darah di sudut bibirnya. Ya, Ray adalah amsal tentang keberhasilan sebuah niat, semangat, dan doa sang istri.
( t.i.l.i.k ! )