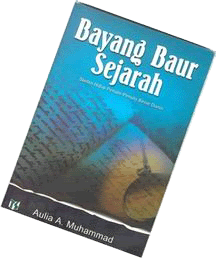...tera di sesela gegas-gesa
Wednesday, March 14, 2007
Memaknai Maknyus Si Bondan
Gesture Bondan, kaget-nikmat, senyum dan gelengan kepala bukanlah ekspresi dari citarasa makanan melainkan bujukan agar pemirsa tertarik untuk mencari atau menikmati makanan yang ditampilkan
 "Maknyus," kata Bondan. "Nyamleng," puji Arletta. "Wuenakee..." teriak Dorce. Semua kata-kata itu untuk mengungkapkan citarasa makanan yang tengah mereka santap. Idiom atau magic word ini tentu sudah sangat dihapal pemisra televisi. Bahkan, saking hapalnya, begitu Bondan menyesap kuah makanan, pemirsa pasti duluan mengatakan, "Maknyuss", dan tertawa bersama.
"Maknyus," kata Bondan. "Nyamleng," puji Arletta. "Wuenakee..." teriak Dorce. Semua kata-kata itu untuk mengungkapkan citarasa makanan yang tengah mereka santap. Idiom atau magic word ini tentu sudah sangat dihapal pemisra televisi. Bahkan, saking hapalnya, begitu Bondan menyesap kuah makanan, pemirsa pasti duluan mengatakan, "Maknyuss", dan tertawa bersama.
Bondan dan "Maknyus-nya" memang menjadi ikon baru di tayangan kuliner televisi. "Maknyus" itu juga yang menjadi pembeda utama acara Bondan dengan tayangan kuliner lainnya, yang bahkan lebih dulu ada sebelum "Wisata Kuliner" TransTV. Tak heran jika Dorce pun sampai "mencemburui" Bondan. Berkali-kali dalam "Dorce Show: Jalan-Jalan" dia mengungkapkan kecemburuan itu. "Pemirsa, sekarang ya, banyak sekali acara makan-makan, pada meniru saya. Tapi, mana ada yang makannya seperti saya. Semua pake gaya, nggak berani gila seperti saya, ya pemirsa. Kalau saya tidak dibuat-buat, pemirsa. Kalau makan ya makan, kalau enak ya enak aja..." ucapnya sambil mengadukkan kuah rendang ke nasinya, dengan mulut berkecipak berminyak.
Dorce benar, setidaknya dalam dua . Pertama, acara kuliner memang luar biasa banyaknya. Jika tidak mandiri, acara ini menjadi imbuhan di acara lain. TransTV misalnya, punya tayangan "Wisata Kuliner" Bondan, "Gula-Gula" Bara Patiradjawane, dan "Jalan-jalan" Dorce. TVRI mengeluarkan "Dunia Wanita", TPI dengan "Santapan Nusantara", dan Indosiar memasang "Aroma", "Iron Chef" serta "Bango Selera Nusantara". Stasiun televisi lain pun tak ketinggalan, meski tidak menjadikan kuliner sebagai acara khusus. Namun, dari semua stasiun, hanya Trans TV yang sangat "menggilai" acara makan-makan ini. Tak cukup dengan tiga tayangan di atas, makan-makan pun selalu mengambil jatah di "Good Morning", "Koper dan Ransel", "Sisi Lain", "Jelang Siang", "Jelajah", bahkan nyusup di "Reportase Sore". Di Trans TV, acara kuliner-lah yang dapat menandingi infotainmen, dalam keragaman dan perulangannya.
Kedua, memang hanya Dorce yang berani "gila" ketika makan. Dia jarang memakai sendok, makan sambil bicara, bibirnya berkecipak, dan kadang, duduk dengan satu kaki yang diangkat ke kursi. Dorce juga tak rikuh menunjukkan selera primordialnya, menyantap petai, jengkol, dan sambal sampai berkeringat. Hal yang sampai saat ini belum pernah ditunjukkan pembawa acara kuliner yang lain.
Pemanggungan
Banyaknya acara kuliner di televisi menunjukkan telah terjadi "pemanggungan" makanan. Karena itu, makanan yang tampil pun --pengecualian di acara "Dorce Jalan-Jalan"-- dimake-up maksimal agar sesuai dengan pakem panggung. Makanan ditata sedemikian rupa di meja dengan ukuran-ukuran estetika sajian, mulai posisi penempatan, kontras warna piring dan taplak meja, sampai latar fisik tempat meja itu berada. Pencahayaan juga diefektifkan, dan tak lupa, point of view, yang akan menjadi sudut pandang penonton juga. Presentasi dan atau narator juga diperhitungkan secara saksama untuk menciptakan sapuan suasana yang sungguh menggugah selera. Pemilihan menu pun mempertimbangkan hukum pementasan, mulai perkenalan, konflik (menu yang unik, ragam, kaya rasa), dan peleraian (minuman yang menghanyutkan semua sensasi rasa makanan tadi).
Aspek pemanggungan itu, entah apa sebabnya, justru tidak maksimal di dalam tayangan "Dorce Jalan-jalan" dan "Bango Selera Nusantara" yang dulu juga digawangi Bondan Winarno. Makanan hadir apa adanya, kadang bersama "rombongannya" di etalase warung atau restoran. Dorce juga tidak melakukan "penilain" profesional, hanya celetukan-celetukan kecil sebagai ungkapan pribadi. Selebihnya, rasa nikmat itu dapat dikira pemirsa melalui kerakusan, kecipak mulut dan kealfaan Dorce pada kamera. Dorce makan, dan tidak sedang membujuk pemirsa untuk dapat menikmati makanan yang sama. "Kealfaannya" pada kamera ketika makan itulah salah satu yang membuat acara ini menjadi sangat berbeda. Keberbedaan itu justru menunjukkan "hakikat" yang sebenarnya, makan sebagai makan dan makanan sebagai makanan. Dorce makan sebagai aktivitas alamiah, laku umum ketika orang menghadapi makanan. Antusiasmenya pada masakan padang, caranya mencampur lauk, sayur dan nasi, bahkan memasukkan ke mulut dan mengunyah, tipikalitas orang kebanyakan. Gaya Dorce adalah "pertunjukan" yang setiap hari dapat kita temukan pada orang yang makan di warung Padang pinggir jalan, staf rendahan, para abang becak dan kuli bangunan. Makanan yang disantap Dorce pun nyaris tak berbeda. Ia selalu kembali ke selera yang sama. Dorce merepresentasikan makan dan makanan sebagai sesuatu yang hanya berurusan dengan mulut dan perut. Makan sebagai kewajiban agar raga dapat terus hidup.
Makan Gaya
 "Wisata Kuliner" dan pembawa acara yang setipikalitas dengan Bondan, sudah melangkah lebih jauh dari apa yang dilakukan Dorce. Bondan, sebagaimana pengakuannya di Nova, bukan berposisi sebagai pemandu selera, tapi promotor makanan. Jadi, semua tindakan Bondan adalah representasi dari usaha untuk mempromosikan. Gesture Bondan, kaget-nikmat, senyum dan gelengan kepala bukan ekspresi dari citarasa makanan melainkan bujukan agar pemirsa tertarik untuk mencari atau menikmati makanan yang ditampilkan. Citarasa makanan kemudian hadir hanya dalam bentuk ucapan verbal "maknyus", "nendang banget" dan atau "pecah di lidah". Bondan sebanding dengan Titi Kamal yang mempromosikan produk mie instan, "Pokoknya.... megang banged!" Semua enak, indah, dan sempurna.
"Wisata Kuliner" dan pembawa acara yang setipikalitas dengan Bondan, sudah melangkah lebih jauh dari apa yang dilakukan Dorce. Bondan, sebagaimana pengakuannya di Nova, bukan berposisi sebagai pemandu selera, tapi promotor makanan. Jadi, semua tindakan Bondan adalah representasi dari usaha untuk mempromosikan. Gesture Bondan, kaget-nikmat, senyum dan gelengan kepala bukan ekspresi dari citarasa makanan melainkan bujukan agar pemirsa tertarik untuk mencari atau menikmati makanan yang ditampilkan. Citarasa makanan kemudian hadir hanya dalam bentuk ucapan verbal "maknyus", "nendang banget" dan atau "pecah di lidah". Bondan sebanding dengan Titi Kamal yang mempromosikan produk mie instan, "Pokoknya.... megang banged!" Semua enak, indah, dan sempurna.
Model representasi di atas juga otomatis membagi posisi makan sebagai kebutuhan primer, dan makan yang sudah menjadi kebutuhan tertier, lux. Aktivitas makan sebagai kebutuhan tertier tidak berurusan dengan kenyang perut. Itulah sebabnya, nyaris tak pernah ada tayangan yang menunjukkan Bondan menghabiskan makanannya semaknyus apa pun itu. Beda dengan Dorce yang menandaskan nasinya, bahkan sampai mulutnya berbunyi "Eeegg...". Sebagai kebutuhan lux, makan adalah wisata, penjelajahan citarasa dan bukan kepatuhan pada selera. Sebagai wisata, makan adalah kebutuhan non-lahiriah, rasa kenyang didapatkan di dalam "nilai gaib" yang terkandung di makanan itu. "Ini lho, sarapan Hamengkubuwono VIII," kata Arletta, ketika wisata kuliner ke Yogya.
Membayangkan telah mengonsumsi "nilai gaib" itulah yang kemudian membuat makanan berubah menjadi arena pementasan diri. Orang makan untuk menunjukkan personalitas diri, gaya hidup, bahkan perbedaan kelas. Makanan menjadi cermin untuk berkaca dan memaknai diri. Ketika ke warung Mbah Jingkrak di Semarang, misalnya, tanpa disadari "Wisata Kuliner" telah meletakkan "nilai lain" ke Warung itu. "Promosi" yang dilakukan Bondan sekaligus meninggalkan nilai tanda di Warung itu. Dan kemudian, mereka yang makan ke warung itu bukan sekadar mencari rasa pedas melainkan terutama membeli "nilai tanda" tersebut. Nilai tanda itu bahkan bisa melebar ke spektrum yang tak terbayangkan. Makan di sana menjadi identitas baru sebagai warga yang melek kuliner, tahu selera, dan ngerti gaya hidup. Bahkan mungkin, muncul perasaan tak lengkap sebagai orang Semarang jika belum merasakan ikon-ikon kuliner di kota ini.
Pada akhirnya, menonton acara kuliner di teve, kita diberikan pilihan untuk menjadi manusia yang menghargai makanan atau manusia yang dihargai karena makanannya. Semua terserah kita.
[Artikel ini sudah dimuat di Harian Suara Merdeka, 11 Maret 2007. Foto-foto diambil dari www.jalansutra.org]
 "Maknyus," kata Bondan. "Nyamleng," puji Arletta. "Wuenakee..." teriak Dorce. Semua kata-kata itu untuk mengungkapkan citarasa makanan yang tengah mereka santap. Idiom atau magic word ini tentu sudah sangat dihapal pemisra televisi. Bahkan, saking hapalnya, begitu Bondan menyesap kuah makanan, pemirsa pasti duluan mengatakan, "Maknyuss", dan tertawa bersama.
"Maknyus," kata Bondan. "Nyamleng," puji Arletta. "Wuenakee..." teriak Dorce. Semua kata-kata itu untuk mengungkapkan citarasa makanan yang tengah mereka santap. Idiom atau magic word ini tentu sudah sangat dihapal pemisra televisi. Bahkan, saking hapalnya, begitu Bondan menyesap kuah makanan, pemirsa pasti duluan mengatakan, "Maknyuss", dan tertawa bersama.Bondan dan "Maknyus-nya" memang menjadi ikon baru di tayangan kuliner televisi. "Maknyus" itu juga yang menjadi pembeda utama acara Bondan dengan tayangan kuliner lainnya, yang bahkan lebih dulu ada sebelum "Wisata Kuliner" TransTV. Tak heran jika Dorce pun sampai "mencemburui" Bondan. Berkali-kali dalam "Dorce Show: Jalan-Jalan" dia mengungkapkan kecemburuan itu. "Pemirsa, sekarang ya, banyak sekali acara makan-makan, pada meniru saya. Tapi, mana ada yang makannya seperti saya. Semua pake gaya, nggak berani gila seperti saya, ya pemirsa. Kalau saya tidak dibuat-buat, pemirsa. Kalau makan ya makan, kalau enak ya enak aja..." ucapnya sambil mengadukkan kuah rendang ke nasinya, dengan mulut berkecipak berminyak.
Dorce benar, setidaknya dalam dua . Pertama, acara kuliner memang luar biasa banyaknya. Jika tidak mandiri, acara ini menjadi imbuhan di acara lain. TransTV misalnya, punya tayangan "Wisata Kuliner" Bondan, "Gula-Gula" Bara Patiradjawane, dan "Jalan-jalan" Dorce. TVRI mengeluarkan "Dunia Wanita", TPI dengan "Santapan Nusantara", dan Indosiar memasang "Aroma", "Iron Chef" serta "Bango Selera Nusantara". Stasiun televisi lain pun tak ketinggalan, meski tidak menjadikan kuliner sebagai acara khusus. Namun, dari semua stasiun, hanya Trans TV yang sangat "menggilai" acara makan-makan ini. Tak cukup dengan tiga tayangan di atas, makan-makan pun selalu mengambil jatah di "Good Morning", "Koper dan Ransel", "Sisi Lain", "Jelang Siang", "Jelajah", bahkan nyusup di "Reportase Sore". Di Trans TV, acara kuliner-lah yang dapat menandingi infotainmen, dalam keragaman dan perulangannya.
Kedua, memang hanya Dorce yang berani "gila" ketika makan. Dia jarang memakai sendok, makan sambil bicara, bibirnya berkecipak, dan kadang, duduk dengan satu kaki yang diangkat ke kursi. Dorce juga tak rikuh menunjukkan selera primordialnya, menyantap petai, jengkol, dan sambal sampai berkeringat. Hal yang sampai saat ini belum pernah ditunjukkan pembawa acara kuliner yang lain.
Pemanggungan
Banyaknya acara kuliner di televisi menunjukkan telah terjadi "pemanggungan" makanan. Karena itu, makanan yang tampil pun --pengecualian di acara "Dorce Jalan-Jalan"-- dimake-up maksimal agar sesuai dengan pakem panggung. Makanan ditata sedemikian rupa di meja dengan ukuran-ukuran estetika sajian, mulai posisi penempatan, kontras warna piring dan taplak meja, sampai latar fisik tempat meja itu berada. Pencahayaan juga diefektifkan, dan tak lupa, point of view, yang akan menjadi sudut pandang penonton juga. Presentasi dan atau narator juga diperhitungkan secara saksama untuk menciptakan sapuan suasana yang sungguh menggugah selera. Pemilihan menu pun mempertimbangkan hukum pementasan, mulai perkenalan, konflik (menu yang unik, ragam, kaya rasa), dan peleraian (minuman yang menghanyutkan semua sensasi rasa makanan tadi).
Aspek pemanggungan itu, entah apa sebabnya, justru tidak maksimal di dalam tayangan "Dorce Jalan-jalan" dan "Bango Selera Nusantara" yang dulu juga digawangi Bondan Winarno. Makanan hadir apa adanya, kadang bersama "rombongannya" di etalase warung atau restoran. Dorce juga tidak melakukan "penilain" profesional, hanya celetukan-celetukan kecil sebagai ungkapan pribadi. Selebihnya, rasa nikmat itu dapat dikira pemirsa melalui kerakusan, kecipak mulut dan kealfaan Dorce pada kamera. Dorce makan, dan tidak sedang membujuk pemirsa untuk dapat menikmati makanan yang sama. "Kealfaannya" pada kamera ketika makan itulah salah satu yang membuat acara ini menjadi sangat berbeda. Keberbedaan itu justru menunjukkan "hakikat" yang sebenarnya, makan sebagai makan dan makanan sebagai makanan. Dorce makan sebagai aktivitas alamiah, laku umum ketika orang menghadapi makanan. Antusiasmenya pada masakan padang, caranya mencampur lauk, sayur dan nasi, bahkan memasukkan ke mulut dan mengunyah, tipikalitas orang kebanyakan. Gaya Dorce adalah "pertunjukan" yang setiap hari dapat kita temukan pada orang yang makan di warung Padang pinggir jalan, staf rendahan, para abang becak dan kuli bangunan. Makanan yang disantap Dorce pun nyaris tak berbeda. Ia selalu kembali ke selera yang sama. Dorce merepresentasikan makan dan makanan sebagai sesuatu yang hanya berurusan dengan mulut dan perut. Makan sebagai kewajiban agar raga dapat terus hidup.
Makan Gaya
 "Wisata Kuliner" dan pembawa acara yang setipikalitas dengan Bondan, sudah melangkah lebih jauh dari apa yang dilakukan Dorce. Bondan, sebagaimana pengakuannya di Nova, bukan berposisi sebagai pemandu selera, tapi promotor makanan. Jadi, semua tindakan Bondan adalah representasi dari usaha untuk mempromosikan. Gesture Bondan, kaget-nikmat, senyum dan gelengan kepala bukan ekspresi dari citarasa makanan melainkan bujukan agar pemirsa tertarik untuk mencari atau menikmati makanan yang ditampilkan. Citarasa makanan kemudian hadir hanya dalam bentuk ucapan verbal "maknyus", "nendang banget" dan atau "pecah di lidah". Bondan sebanding dengan Titi Kamal yang mempromosikan produk mie instan, "Pokoknya.... megang banged!" Semua enak, indah, dan sempurna.
"Wisata Kuliner" dan pembawa acara yang setipikalitas dengan Bondan, sudah melangkah lebih jauh dari apa yang dilakukan Dorce. Bondan, sebagaimana pengakuannya di Nova, bukan berposisi sebagai pemandu selera, tapi promotor makanan. Jadi, semua tindakan Bondan adalah representasi dari usaha untuk mempromosikan. Gesture Bondan, kaget-nikmat, senyum dan gelengan kepala bukan ekspresi dari citarasa makanan melainkan bujukan agar pemirsa tertarik untuk mencari atau menikmati makanan yang ditampilkan. Citarasa makanan kemudian hadir hanya dalam bentuk ucapan verbal "maknyus", "nendang banget" dan atau "pecah di lidah". Bondan sebanding dengan Titi Kamal yang mempromosikan produk mie instan, "Pokoknya.... megang banged!" Semua enak, indah, dan sempurna.Model representasi di atas juga otomatis membagi posisi makan sebagai kebutuhan primer, dan makan yang sudah menjadi kebutuhan tertier, lux. Aktivitas makan sebagai kebutuhan tertier tidak berurusan dengan kenyang perut. Itulah sebabnya, nyaris tak pernah ada tayangan yang menunjukkan Bondan menghabiskan makanannya semaknyus apa pun itu. Beda dengan Dorce yang menandaskan nasinya, bahkan sampai mulutnya berbunyi "Eeegg...". Sebagai kebutuhan lux, makan adalah wisata, penjelajahan citarasa dan bukan kepatuhan pada selera. Sebagai wisata, makan adalah kebutuhan non-lahiriah, rasa kenyang didapatkan di dalam "nilai gaib" yang terkandung di makanan itu. "Ini lho, sarapan Hamengkubuwono VIII," kata Arletta, ketika wisata kuliner ke Yogya.
Membayangkan telah mengonsumsi "nilai gaib" itulah yang kemudian membuat makanan berubah menjadi arena pementasan diri. Orang makan untuk menunjukkan personalitas diri, gaya hidup, bahkan perbedaan kelas. Makanan menjadi cermin untuk berkaca dan memaknai diri. Ketika ke warung Mbah Jingkrak di Semarang, misalnya, tanpa disadari "Wisata Kuliner" telah meletakkan "nilai lain" ke Warung itu. "Promosi" yang dilakukan Bondan sekaligus meninggalkan nilai tanda di Warung itu. Dan kemudian, mereka yang makan ke warung itu bukan sekadar mencari rasa pedas melainkan terutama membeli "nilai tanda" tersebut. Nilai tanda itu bahkan bisa melebar ke spektrum yang tak terbayangkan. Makan di sana menjadi identitas baru sebagai warga yang melek kuliner, tahu selera, dan ngerti gaya hidup. Bahkan mungkin, muncul perasaan tak lengkap sebagai orang Semarang jika belum merasakan ikon-ikon kuliner di kota ini.
Pada akhirnya, menonton acara kuliner di teve, kita diberikan pilihan untuk menjadi manusia yang menghargai makanan atau manusia yang dihargai karena makanannya. Semua terserah kita.
[Artikel ini sudah dimuat di Harian Suara Merdeka, 11 Maret 2007. Foto-foto diambil dari www.jalansutra.org]