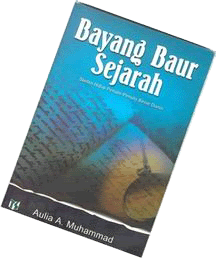...tera di sesela gegas-gesa
Monday, August 13, 2007
Dan di Manakah Indonesia?
Keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia harus diakui bukan hanya sebagai kekayaan melainkan yang lebih utama sebagai kesederajatan.

MAT SOLAR bukan sopir bajaj. Tapi perannya dalam Bajaj Bajuri mengidentikannya dengan profesi tersebut. Popularitas itulah yang dirangkul tim kampanye Adang Daradjatun-Dani Anwar untuk mendongkrak suara. Maka, dua minggu lalu, dengan bajajnya, Mat Solar mengantar Adang-Dani ke DPRD Jakarta.
Saya melihat adegan itu sekilas. Kampanye Adang-Dani memang diliput dengan "kadar" yang berbeda dari gemebyar Fauzy Bowo. Namun, meski selintas, ucapan Mat Solar memberi nilai yang sangat tegas tentang keindonesiaan. "Insya Allah menang, 23% ude di tangan. Asal jangan jual-jual Betawi deh, nggak bakal laku. Ini kan buat calon Gubernur Jakarta. Emangnya Jakarta itu Betawi doang?"
Jakarta tentu bukan hanya milik Betawi. Tapi, berapa banyak yang punya kesadaran semacam Mat Solar, yang justru orang Betawi asli, itu. Kampanye Fauzy Bowo misalnya, seperti yang disindir Mat Solar, justru menjual kebetawiannya. Mandra, Atun, dan "keluarga" Si Doel lainnya selalu menekankan kewajiban memilih Fauzi Bowo karena kebetawiannya. "Orang Betawi ya pilih yang Betawi." Sentimen kesukuan dikuatkan sebagai penarik suara. "Kualitas" kebetawian Fauzi Bowo-lah yang dijadikan nilai kepantasannya untuk memimpin Jakarta, bukan rekam jejak kinerjanya selama ini, bukan kecakapannya secara pribadi.
Tipikalitas "putra daerah" seperti di atas memang sudah menjadi penyakit akut di Indonesia. Bukan hanya untuk memimpin negara, gubernur, bupati, walikota, camat, lurah, bahkan pemilihan ketua RT/RW pun memperhitungkan warga asli dan pendatang. Keindonesiaan --kekitaan-- cepat sekali memisah menjadi dua titik pijak, kami dan mereka. Betawi dan bukan Betawi, putra daerah dan warga pendatang. Lucunya, pengimaman pada kedaerahan ini kadang sampai melupakan akal sehat. Sepanjang seseorang itu berasal dari suatu daerah maka dia menjadi pantas dipilih dan atau dicalonkan, meskipun namanya tidak dikenal dan atau tidak pernah berada di daerah tersebut. Geovany misalnya, pernah dicalonkan PAN menjadi Gubernur Sumatra Barat. Padahal dia tak berdomisili, bahkan nyaris tak pernah dikenali oleh masyarakat Padang. Dia kalah, dan lalu menjadi pasangan Sarwono untuk pemilihan Jakarta, yang juga gagal. Kelak, "penyakit" semacam itu masih akan kita saksikan lagi.
Indonesia yang Wangi
Bukan hanya iklan kampanye Fauzi Bowo, acara lain di televisi pun banyak yang sengaja melupakan "keindonesiaan", bahkan tayangan yang menggunakan nama Indonesia, seperti "Indonesian Idol". Tayangan ini pun memakai unsur kedaerahan sebagai cara menjaring suara melalui SMS. Rini yang asal Medan, "dijual" ke Medan. Wilson yang nyong Ambon, "dipasarkan" di Maluku, sebelum keduanya diadu. Sentimen kesukuan dikuatkan untuk saling mengalahkan. Dua daerah "dibenturkan" agar berlomba untuk menjadi yang paling pantas menyandang gelar "idola Indonesia". Acara itu memasarkan dan menyebarkan sikap bahwa idola Indonesia adalah orang Medan yang dipilih orang Medan atau nyong Ambon yang didukung warga asal Maluku. Dan karena penduduk di dan atau berasal dari Sumatra Utara lebih banyak dibandingkan Maluku, Wilson pun kalah. Tahun lalu, Dirly juga kalah melawan Ihsan yang asal Medan. Acara ini, tanpa sadar, mengerdilkan makna "Indonesia".
Tayangan sinetron apalagi, secara masif justru mengaburkan makna "Indonesia". Yang tampil adalah "Indonesia" yang bersih, menarik, tentram, dan cantik. Sekolah-sekolah dengan bangunan dan fasilitas lengkap, pelajar-pelajar wangi yang pergi-pulang naik mobil, dengan kepala hanya berisi intrik untuk mendapatkan idaman hati. Tak ada "Indonesia" yang kotor. Tak ada sekolah yang reyot berlantai tanah, tanpa fasilitas apa pun, dengan satu guru dan satu murid sebagaimana terdapat di Kepulauan Mapia, Papua. Tak pernah ada pelajar yang bangun jam 3 pagi, lalu dengan obor, berjalan kaki berangkat ke sekolah sejauh 10 KM, sebagaimana yang sudah belasan tahun terjadi di dusun Datarkupa, Desa Cimaskara, 120 KM dari Cianjur. Itulah sebabnya, dalam Festival Film Indonesia, yang menang adalah Ekskul, film dengan cerita remaja SMA yang sakit jiwa dan main senjata, dan bukan Denias, film tentang semangat untuk meraih cita-cita dari anak Papua.
Di sinetron yang tampil adalah derita para korban dukun, pelet, babi ngepet dan pesugihan lainnya, dan sampai kini belum ada cerita orang tua yang gila karena kehilangan anak-anaknya akibat bencana gempa dan tsunami, korban lumpur Lapindo, dan penggusuran. Di sinetron polisi selalu bersih, berwibawa, anti-korupsi, dan tak gampang main senjata. Tak pernah ada polisi yang suka main tembak sendiri, melawan atasan, pungli dan korupsi, dan mabuk-mabukan, sebagaimana yang terkadang menghiasi halaman koran dan media massa lainnya. Di sinetron, Indonesia adalah apa yang ingin kita imajinasikan, bukan Indonesia yang kita hidupi, bukan Indonesia yang tiap hari kita hadapi.
Indonesia, terkadang, juga berarti Jakarta. Teve nasional, yang artinya bukan teve daerah, justru tak pernah menayangkan azan magrib untuk wilayah nasional. Di mana pun kita menonton, azan magrib selalu milik Jakarta. Jakarta harus selalu lebih istimewa dari daerah mana pun. Itulah sebabnya, untuk Jakarta, pemilihan Putri Indonesia bisa diwakili 4-5 peserta, dan daerah lain cukup satu saja.
Memandang Indonesia
Lalu, di teve, di manakah Indonesia? Tentu ada dalam tayangan berita dan kuliner. Juga dalam "Jejak Petualang", "Si Bolang", "Surat Sahabat", dan "Arcipelago". Di ragam acara itu, tampil Indonesia yang "apa adanya", dengan keragaman budaya, wilayah, suku yang memiliki cara hidup dan pandangan dunia yang berbeda. Dalam "Surat Sahabat" kisah rekan dari Papua, Aceh, Kalimantan, bertemu dengan kisah anak-anak dari Jawa, dan saling mempertukarkan keragaman lingkungan, termasuk cara pandang terhadap diri dan dunia. Kisah anak-anak itu berdiri sederajat, dengan keunikan tersendiri, dan diterima sebagai sebuah kewajaran hidup dari sebuah komunitas tertentu, dan dalam esensinya, sama-sama memiliki keadiluhungan tersendiri. Anak Flores yang makan durilandak, Anak Batak yang memanggang babi, anak Blitar yang makan keong, dan anak Jakarta yang menguyah Burger, berdiri sama tinggi. Di acara itu, tak ada budaya yang dihakimi, direndahkan, semua dimartabatkan.
"Surat Sahabat" dalam kesederhanaannya justru mengajarkan bagaimana memandang Indonesia. Bahwa keragaman itu harus diakui bukan hanya sebagai kekayaan melainkan yang lebih utama sebagai kesederajatan. Kesederajatan itulah yang membuat satu suku, satu budaya, tidak merasa lebih baik, lebih beradab, lebih modern, dan lebih layak berada di atas suku dan atau budaya yang lain.
Melalui "Surat Sahabat", Indonesia kita temukan dalam wajahnya yang belum selesai didefenisikan. Indonesia yang masih dalam proses, bergerak liar dalam imajinasi banyak orang dengan ragam ras, etnik, agama, yang dengan demikian, menjadi sangat kaya warna. Itulah Indonesia yang tidak diringkus dalam pengertian esensial, yakni pendefenisian yang mementingkan kemurnian, keaslian, dan kepribumian. Melalui "Surat Sahabat" Indonesia tampil dalam semangat dan imajinasi yang bahkan memperkaya "keindonesiaan" di Taman Mini Indonesia, --yang tidak mengakui kesederajatan etnik India, Arab, Cina, dan Koja sebagai bagian integral dari keindonesiaan etnisitas.
Sebagai "identitas" yang belum selesai didefenisikan, Indonesia masih merdeka untuk merangkum banyak pengertian baru, yang dapat mewadahi semua mimpi dan imajinasi banyak orang. Sebuah pengertian yang dapat diterima tanpa keterpaksaan, perasaan terpinggirkan, dan dianaktirikan. Pengertian yang lahir dan diterima seperti dari surat sahabat.
[Artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 12 Agustus 2007]

MAT SOLAR bukan sopir bajaj. Tapi perannya dalam Bajaj Bajuri mengidentikannya dengan profesi tersebut. Popularitas itulah yang dirangkul tim kampanye Adang Daradjatun-Dani Anwar untuk mendongkrak suara. Maka, dua minggu lalu, dengan bajajnya, Mat Solar mengantar Adang-Dani ke DPRD Jakarta.
Saya melihat adegan itu sekilas. Kampanye Adang-Dani memang diliput dengan "kadar" yang berbeda dari gemebyar Fauzy Bowo. Namun, meski selintas, ucapan Mat Solar memberi nilai yang sangat tegas tentang keindonesiaan. "Insya Allah menang, 23% ude di tangan. Asal jangan jual-jual Betawi deh, nggak bakal laku. Ini kan buat calon Gubernur Jakarta. Emangnya Jakarta itu Betawi doang?"
Jakarta tentu bukan hanya milik Betawi. Tapi, berapa banyak yang punya kesadaran semacam Mat Solar, yang justru orang Betawi asli, itu. Kampanye Fauzy Bowo misalnya, seperti yang disindir Mat Solar, justru menjual kebetawiannya. Mandra, Atun, dan "keluarga" Si Doel lainnya selalu menekankan kewajiban memilih Fauzi Bowo karena kebetawiannya. "Orang Betawi ya pilih yang Betawi." Sentimen kesukuan dikuatkan sebagai penarik suara. "Kualitas" kebetawian Fauzi Bowo-lah yang dijadikan nilai kepantasannya untuk memimpin Jakarta, bukan rekam jejak kinerjanya selama ini, bukan kecakapannya secara pribadi.
Tipikalitas "putra daerah" seperti di atas memang sudah menjadi penyakit akut di Indonesia. Bukan hanya untuk memimpin negara, gubernur, bupati, walikota, camat, lurah, bahkan pemilihan ketua RT/RW pun memperhitungkan warga asli dan pendatang. Keindonesiaan --kekitaan-- cepat sekali memisah menjadi dua titik pijak, kami dan mereka. Betawi dan bukan Betawi, putra daerah dan warga pendatang. Lucunya, pengimaman pada kedaerahan ini kadang sampai melupakan akal sehat. Sepanjang seseorang itu berasal dari suatu daerah maka dia menjadi pantas dipilih dan atau dicalonkan, meskipun namanya tidak dikenal dan atau tidak pernah berada di daerah tersebut. Geovany misalnya, pernah dicalonkan PAN menjadi Gubernur Sumatra Barat. Padahal dia tak berdomisili, bahkan nyaris tak pernah dikenali oleh masyarakat Padang. Dia kalah, dan lalu menjadi pasangan Sarwono untuk pemilihan Jakarta, yang juga gagal. Kelak, "penyakit" semacam itu masih akan kita saksikan lagi.
Indonesia yang Wangi
Bukan hanya iklan kampanye Fauzi Bowo, acara lain di televisi pun banyak yang sengaja melupakan "keindonesiaan", bahkan tayangan yang menggunakan nama Indonesia, seperti "Indonesian Idol". Tayangan ini pun memakai unsur kedaerahan sebagai cara menjaring suara melalui SMS. Rini yang asal Medan, "dijual" ke Medan. Wilson yang nyong Ambon, "dipasarkan" di Maluku, sebelum keduanya diadu. Sentimen kesukuan dikuatkan untuk saling mengalahkan. Dua daerah "dibenturkan" agar berlomba untuk menjadi yang paling pantas menyandang gelar "idola Indonesia". Acara itu memasarkan dan menyebarkan sikap bahwa idola Indonesia adalah orang Medan yang dipilih orang Medan atau nyong Ambon yang didukung warga asal Maluku. Dan karena penduduk di dan atau berasal dari Sumatra Utara lebih banyak dibandingkan Maluku, Wilson pun kalah. Tahun lalu, Dirly juga kalah melawan Ihsan yang asal Medan. Acara ini, tanpa sadar, mengerdilkan makna "Indonesia".
Tayangan sinetron apalagi, secara masif justru mengaburkan makna "Indonesia". Yang tampil adalah "Indonesia" yang bersih, menarik, tentram, dan cantik. Sekolah-sekolah dengan bangunan dan fasilitas lengkap, pelajar-pelajar wangi yang pergi-pulang naik mobil, dengan kepala hanya berisi intrik untuk mendapatkan idaman hati. Tak ada "Indonesia" yang kotor. Tak ada sekolah yang reyot berlantai tanah, tanpa fasilitas apa pun, dengan satu guru dan satu murid sebagaimana terdapat di Kepulauan Mapia, Papua. Tak pernah ada pelajar yang bangun jam 3 pagi, lalu dengan obor, berjalan kaki berangkat ke sekolah sejauh 10 KM, sebagaimana yang sudah belasan tahun terjadi di dusun Datarkupa, Desa Cimaskara, 120 KM dari Cianjur. Itulah sebabnya, dalam Festival Film Indonesia, yang menang adalah Ekskul, film dengan cerita remaja SMA yang sakit jiwa dan main senjata, dan bukan Denias, film tentang semangat untuk meraih cita-cita dari anak Papua.
Di sinetron yang tampil adalah derita para korban dukun, pelet, babi ngepet dan pesugihan lainnya, dan sampai kini belum ada cerita orang tua yang gila karena kehilangan anak-anaknya akibat bencana gempa dan tsunami, korban lumpur Lapindo, dan penggusuran. Di sinetron polisi selalu bersih, berwibawa, anti-korupsi, dan tak gampang main senjata. Tak pernah ada polisi yang suka main tembak sendiri, melawan atasan, pungli dan korupsi, dan mabuk-mabukan, sebagaimana yang terkadang menghiasi halaman koran dan media massa lainnya. Di sinetron, Indonesia adalah apa yang ingin kita imajinasikan, bukan Indonesia yang kita hidupi, bukan Indonesia yang tiap hari kita hadapi.
Indonesia, terkadang, juga berarti Jakarta. Teve nasional, yang artinya bukan teve daerah, justru tak pernah menayangkan azan magrib untuk wilayah nasional. Di mana pun kita menonton, azan magrib selalu milik Jakarta. Jakarta harus selalu lebih istimewa dari daerah mana pun. Itulah sebabnya, untuk Jakarta, pemilihan Putri Indonesia bisa diwakili 4-5 peserta, dan daerah lain cukup satu saja.
Memandang Indonesia
Lalu, di teve, di manakah Indonesia? Tentu ada dalam tayangan berita dan kuliner. Juga dalam "Jejak Petualang", "Si Bolang", "Surat Sahabat", dan "Arcipelago". Di ragam acara itu, tampil Indonesia yang "apa adanya", dengan keragaman budaya, wilayah, suku yang memiliki cara hidup dan pandangan dunia yang berbeda. Dalam "Surat Sahabat" kisah rekan dari Papua, Aceh, Kalimantan, bertemu dengan kisah anak-anak dari Jawa, dan saling mempertukarkan keragaman lingkungan, termasuk cara pandang terhadap diri dan dunia. Kisah anak-anak itu berdiri sederajat, dengan keunikan tersendiri, dan diterima sebagai sebuah kewajaran hidup dari sebuah komunitas tertentu, dan dalam esensinya, sama-sama memiliki keadiluhungan tersendiri. Anak Flores yang makan durilandak, Anak Batak yang memanggang babi, anak Blitar yang makan keong, dan anak Jakarta yang menguyah Burger, berdiri sama tinggi. Di acara itu, tak ada budaya yang dihakimi, direndahkan, semua dimartabatkan.
"Surat Sahabat" dalam kesederhanaannya justru mengajarkan bagaimana memandang Indonesia. Bahwa keragaman itu harus diakui bukan hanya sebagai kekayaan melainkan yang lebih utama sebagai kesederajatan. Kesederajatan itulah yang membuat satu suku, satu budaya, tidak merasa lebih baik, lebih beradab, lebih modern, dan lebih layak berada di atas suku dan atau budaya yang lain.
Melalui "Surat Sahabat", Indonesia kita temukan dalam wajahnya yang belum selesai didefenisikan. Indonesia yang masih dalam proses, bergerak liar dalam imajinasi banyak orang dengan ragam ras, etnik, agama, yang dengan demikian, menjadi sangat kaya warna. Itulah Indonesia yang tidak diringkus dalam pengertian esensial, yakni pendefenisian yang mementingkan kemurnian, keaslian, dan kepribumian. Melalui "Surat Sahabat" Indonesia tampil dalam semangat dan imajinasi yang bahkan memperkaya "keindonesiaan" di Taman Mini Indonesia, --yang tidak mengakui kesederajatan etnik India, Arab, Cina, dan Koja sebagai bagian integral dari keindonesiaan etnisitas.
Sebagai "identitas" yang belum selesai didefenisikan, Indonesia masih merdeka untuk merangkum banyak pengertian baru, yang dapat mewadahi semua mimpi dan imajinasi banyak orang. Sebuah pengertian yang dapat diterima tanpa keterpaksaan, perasaan terpinggirkan, dan dianaktirikan. Pengertian yang lahir dan diterima seperti dari surat sahabat.
[Artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 12 Agustus 2007]