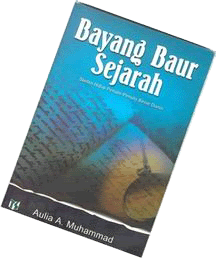...tera di sesela gegas-gesa
Monday, September 12, 2005
Pencerita yang Luar Biasa
 PELABUHAN Jeddah, 1923.
PELABUHAN Jeddah, 1923.Kapal haji milik Chasan Imazi "Bombay" melempar sauh. Dan penumpang kapal, para jamaah haji yang akan pulang ke Indonesia, bergegas naik. Satu jam kemudian, penumpang yang naik mulai menipis. Tapi di dermaga, satu keluarga asal Rembang, Jawa Tengah, masih tak bergegas naik.
Sirena kapal berbunyi, kapal akan bergerak. Tapi, keluarga yang berjumlah enam orang itu tak juga beranjak. Semua tampak sibuk merubung sang ayah, yang sekarat meregang nyawa.
Tapi, kapal tak bisa menunggu, tangga mulai akan dilepas. Mereka panik, dan menyerah. Dengan airmata bercucur, tangis yang pecah, mereka bergerak mengejar kapal, meninggalkan sang ayah yang sudah menjadi jenazah, di tangan seorang syekh.
Keperihan itu paling mencekam bagi Mashadi dan Hj Chadidjah. Tiga adik Mashadi masih terlalu kecil untuk mengerti duka itu. Mashadi, yang sesudah dewasa nanti menjadi KH Bisri Musthofa, baru berusia 8 tahun, adiknya, Salamah 5,5 tahun, Misbah 3,5 tahun dan Ma'sum baru 1 tahun. Mereka sedang menunaikan ibadah haji.
Mereka memang dari keluarga yang berada. Tapi, usai kematian ayahnya, H Zaenal Musthofa, babak kehidupan Mashadi dimulai. Ia diasuh N Zuhdi, kakak tirinya, anak ayahnya dari istri pertama, Dakilah.
Mashadi bukanlah anak pesantren. Dia paling ogah mengaji. Seusai tamat sekolah Ongko Loro misalnya, ia dikirim ke pesantren Kajen asuhan Kiai Chasbullah, tapi tak betah. Ketika pindah ke pesantren Kiai Cholil Kasingan, di Rembang, dia tak juga senang.
Dalam biografinya, Mashadi mengaku belajar di pesantren amat sulit, terutama nahwu dan sharaf. Lebih lagi, Kiai Cholil di mata Mashadi waktu itu, sangat angker dan menakutkan. Mendingan tak usah mengaji daripada dipukuli saat mengaji, begitu batinnya.
Tapi, akhirnya Mashadi kembali ke Kasingan, meski menghindari Kiai Cholil. Dia memilih mengaji pada santri senior, Sudja'i, ipar Cholil. Dan secara nekat, Mashadi mengaji kitab Alfiyah Ibnu Malik, kitab Nahwu 1000 nazham.
Mashadi berhasil. Dia bahkan tampil sebagai santri yang paling pintar pelajaran nahwu, dan mendapat posisi lurah pondok, pengulang pelajaran kiai.
1932, Mashadi meminta restu kepada Kiai Cholil akan pindah ke Pesantren Termas, asuhan Kiai Dimyati. Cholil tak mengabulkan, bahkan meminta Mashadi menjadi menantunya.
Juni 1935, masih berusia 20 tahun, Bisri menikahi Ma'rufah Binti Cholil, yang baru berusia 10 tahun.
Menjadi menantu Kiai Cholil lebih banyak tak enaknya bagi Birsi. Ini karena para santrinya menuntut ia mengajarkan kitab, yang bentuknya saja ia tak pernah lihat. Sebagai akal, Bisri lalu mengaji di Kranggeneng bersama Kiai Kamil, dan mengulang pelajarannya di depan santrinya. Tapi acap, kalau pengajian Kranggeneng libur, ia tak mengajar, karena tak punya bahan.
Untuk menghindari beban ini, berbekal uang berjualan kitab Bijuraimi Iqna', ia "melarikan" diri ke Mekah, 1936, menunaikan ibadah haji. Di sana, Bisri menjadi khadam di rumah Syekh Chamid Said.
Saat pulang, mengingat ilmunya yang pas-pasan, ia tak kembali, bahkan bersama Suyuti Cholil dan Zuhdi dari Tuban, berguru kepada Kiai Bakir, Syekh Umah Hamdan al-Maghribi, Syekh al-Maliki, Sayid Amin, Syekh Hasan Masysyath, Sayid Alawie dan Kiai Abdul Muhaimin. Tahun berikutnya, Bisri pulang.
Menjual Gigi Emas
 8 Desember 1941, Jepang mengumumkan perang melawan Sekutu, dan santri pesantren diminta siap menjadi milisi. Situasi kian mencekam, Bisri dan keluarganya mengungsi dari Rembang. 1943, Jepang mengadakan latihan alim ulama di Jakarta selama satu bulan. Angkatan pertama dari daerah Pati diwakili KH A Jalil Kudus, dan angkatan kedua diwakili Bisri Musthofa. Selain orang Jepang, KH Wahab Chasbullah, H Agus Salim dan KH Mas Mansur juga menjadi pengajar.
8 Desember 1941, Jepang mengumumkan perang melawan Sekutu, dan santri pesantren diminta siap menjadi milisi. Situasi kian mencekam, Bisri dan keluarganya mengungsi dari Rembang. 1943, Jepang mengadakan latihan alim ulama di Jakarta selama satu bulan. Angkatan pertama dari daerah Pati diwakili KH A Jalil Kudus, dan angkatan kedua diwakili Bisri Musthofa. Selain orang Jepang, KH Wahab Chasbullah, H Agus Salim dan KH Mas Mansur juga menjadi pengajar.Setelah itu Jepang membentuk Masyumi, dan menunjuk KH Hasyim Asy'ari dari Jombang sebagai Ketua dan Ki Bagus Hadikusumo sebagai wakil. Birsi menjadi ketua daerah kabupaten.
Tapi keadaan saat itu amat mengerikan. Harga melonjak, makanan tak terbeli. Keluarga Bisri pun terpaksa makan jagung. Selain itu, kornea Bisri ternyata rusak, dan perlu dicangkok. Tapi, mereka malah ke Jombang, menemui tabib. Enam bulan mereka menunggu kornea, dan tinggal menumpang di rumah Mak Puk. Mereka papa, dan untuk menyambung hidup, Bisri menjual semua pakaiannya, kecuali satu sarung, kaos dan baju dril. Terakhir, ia mencabut dan menjual gigi emasnya, dengan harga Rp 400,-
Bisri selanjutnya membuat kerajinan tas, dari modal Rp 1000 yang diberikan Mak Puk. Tapi, PKI memberontak, dan bersama laskar Hizbullah, Bisri kembali ke Rembang. Ia kemudian berjualan garam, dan gagal. Pindah ke Sulang, Cabean, ke Trembes Gunen, lalu ke Sedan, dan menetap di Sarang, dengan amat menderita, hanya makan jagung pemberian orang. Uang Rp 200, dari Mbah Imam pemimpin Pesantren Sarang, ia belikan nasi, dan Rp 40 siasanya, ia belikan jagung, merica, yang ia goreng gosong, lalu dicampur gula dan minyak, dan ia jual dengan nama Ma'jun, jamu obat kuat lelaki. 1949, Bisri terpilih sebagai Penghulu Darurat, dengan kekuasaan meliputi seluruh kabupaten. Kehidupannya mulai membaik.
KH Bisri Musthofa adalah orator, mubaligh yang mendekati sempurna, pengarang yang amat produktif. Ia bisa bicara apa saja, dengan kemampuan panggung yang tak terbantahkan.
Di podium, dia mampu menyedot emosi massa, menghanyutkan dalam arus cerita yang luar biasa. Suaranya seakan irama gaib, yang membuat wanita, terutama jika ia bercerita tentang Ratu Bilqis yang dipecundangi Sulaiman, menarik kainnya, meniru sang ratu yang takut basah, di istana kaca Sulaiman. Ia tak sekadar orator, imajinasi dan kekayaan referensinya, membuat pendengar diajak masuk menjadi tokoh cerita.
Riwayat kiai ini amat menarik, karena ia seakan menyimpang dari jalan hidup kiai pesantren lainnya. Dia misalnya, mengatakan ikhlas adalah kondisi ketika orang merasa lega atas hasil ikhtiarnya. Ia adalah kiai yang tak risi berbicara motif ekonomi.
"Menulis dengan niat mencari nafkah untuk kehidupan keluarga adalah hal yang wajar," kata almarhum, suatu saat kepada KH Ali Ma'shum Krapyak, yang menegurnya karena sibuk berceramah, tak sempat mengajar santrinya.
"Meskipun saya tak mengajar, sesungguhnya para santri tetap mengaji pada saya, termasuk santri sampeyan," katanya, yang memang buku-buku karyanya, dipakai di Krapyak. Kiai yang lahir di Pati 18 september 1886 ini juga aktif di Partai NU, lalu ke PPP tahun 1973. Dia adalah juru kampanye yang andal. Kariernya di di NU dan partai melesat, sejak ia menanggalkan posisinya sebagai Kepala Kantor Agama Rembang.
Tapi, seminggu setelah ia memberangkatkan putranya, Musthofa Bisri, ke Arab Saudi, di masa kampanye, 16 Pebruari 1977, sakit menerjangnya. Dan karena terlalu parah, dokter angkat tangan, Yang Kuasa memanggilnya. Partai PPP pun berduka, kampanye di Jateng seperti tanpa suasana. Ia pergi meninggalkan 8 anaknya, KH Cholil Birsi, KH Musthofa Bisri, KH Adieb Bisri, Audah, Najihah, Labib, Nihayah, dan Atikah.
"Yang patah memang bisa tumbuh, yang hilang dapat berganti. Tapi seorang Bisri Musthofa? Ah, tidak mudah mendapatkan penggantinya," kata KH Saifuddun Zuhri, menggambarkan rasa kehilangannya.