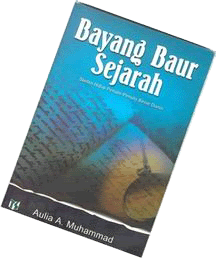...tera di sesela gegas-gesa
Tuesday, May 15, 2007
Keluar dari Batas Kenyataan
Memasuki panggung berarti memisahkan diri dari kenyataan.

"Wanita itu harus memakai jilbab, Kikan. Dengan menutup aurat, dia akan terlindungi," kata Nila, sembari mengelus rambut Kikan, anaknya. Nila baru saja usai salat, dan berjanji pada Allah, mulai hari itu dia akan menutup auratnya.
Itulah sepotong adegan dalam sinema "Hikayah: Penyanyi Dangdut Banting Setir Jadi Pembantu" yang tayang Selasa (1/5) lalu. Sinetron itu bercerita tentang pertobatan penyanyi dangdut, Nila, yang biasa bergoyang erotis. Dia yakin, dengan menutup aurat, berjilbab pun, panggung dangdut masih terbuka untuknya. Tapi Nila salah. Tak ada lagi panggung yang menerima. Dia dihina, dicampakkan, disudutkan. Godaan pun datang bertubi-tubi, tapi Nila tetap kuat. "Maaf, aku tidak bisa membuka jilbab. Ini sudah prinsip," elaknya.
Nila diperankan dengan cukup baik oleh Inul Daratista. Inul? Inul, pedangdut ngebor itu? Iya, Inul yang juga berseteru dengan Rhoma Irama itu. Di "Hikayah", yang juga seperti "Hidayah" --terinspirasi dari kisah nyata-- Inul menjadi Nila yang menyadari bahwa bergoyang ngebor dekat dengan kemaksiatan, mendorong orang untuk berbuat dosa. Ketika penonton tidak menerima prinsipnya, dia rela berganti profesi meski harus hanya menjadi pembantu rumah tangga.
Seminggu sebelumnya, Silvana Herman tampil sebagai pemain utama dalam "Hidayah: Perawan Tua". Dia menjadi sosok yang jahat karena tak mampu menanggungkan status ganda: tua dan perawan. Cerita pun berjalan dalam konflik batin yang berkembang jadi kedengki-irian. Sampai saat ini, Silvana Herman memang masih lajang. Usianya nyaris 40 tahun. Dalam tayangan infotainmen, setiap ditanya statusnya, Silvana tak pernah merasa risau. "Jodoh itu di tangan Tuhan. Nanti juga datang," ucapnya rileks.
Panggung Nilai
Kemampuan memerankan "sebuah" karakter adalah tuntutan utama untuk menjadi aktris. Seorang aktris, dapat menjadi apa saja ketika berlakon, termasuk menjadi sosok yang dia benci di dalam kehidupan nyata. "Akan menjadi tantangan yang hebat," demikian biasanya sang pelakon menggambarkan kegembiraan ketika mendapat peran yang berbeda dari karakter aslinya. Itulah sebabnya, setiap aktris riang gembira saja memerankan tokoh apa pun, dalam cerita apa pun, dan dengan kemuskilan apa pun. Yang penting berakting. "Karena berakting aku ada".
Karena akting hanya peranan, karakter apa pun yang dimainkan dipahami oleh mereka bukan sebagai cerminan dari watak pribadi sang pelakon. Itulah sebabnya, Silvana mau menjadi sosok perawan tua dan jahat. Silvana tahu, itu hanya akting. Meski menyandang status yang sama di kehidupan nyata, dia tahu penonton tak akan mempersepsikannya dengan kejahatan yang sama. Itu juga sebabnya, Inul riang gembira menjadi Nila, yang bertobat dari jalan ngebor. Inul tahu, karakter itu hanya rekaan, bagian dari akting. Hanya sandiwara. Tak ada korelasi antara Inul dan Nila.
Sebagai dua karakter, memang tak ada korelasi antara watak di dalam sinetron dan watak asali di dalam kenyataan. Tapi sebagai "pembawa" nilai, seharusnya Inul menyadari "makna" yang lebih daripada sekadar pemeranan. Inul adalah ikon yang mencoba meletakkan sebuah perspektif baru di dalam memandang panggung dangdut. Bersama beberapa aktivis perempuan, Inul mencoba melawan dominasi nilai bahwa dangdut adalah medium dakwah, yang sebagai hiburan seharusnya mengajak orang dekat pada sang pencipta. Karena itu, goyangan yang dianggap menabuh syahwat bukan bagian dari dangdut. Goyangan sejenis itu membawa dangdut ke gerbang comberan. Inul mencoba "memetakan" posisi persepsi dan fakta, harapan dan kenyataan. Bagi Inul, goyangan adalah wilayah terbuka yang bisa dimaknai apa pun, dalam konteks apa pun. Tidak bermakna tunggal, dan harus dilihat dari persepektif hiburan, permintaan dan penawaran, bukan agama. Inul mencoba membebaskan seni dari beban moral, membebaskan dangdut dari kepemilikan satu orang.
Nah, nilai "kenyataan" Inul ini yang justru ditampik Nila. Padahal, sebagai nilai, korelasi keduanya amat jelas. Ada hubungan kausatif antara sinetron dan kenyataan dalam tautan nilai. Sinetron, film, pementasan drama, bahkan opera pun, bukan produk yang lepas nilai. Itulah sebabnya, tak boleh ada sinetron yang menghina agama. Tak ada satu karakter cerita yang boleh menghina agama orang lain, suku, atau personalitas seseorang. Seluruh cerita sebuah film atau sinetron, mungkin tidak berangkat dari dunia nyata. Tapi "ketidaknyataan" itu tetap saja digayuti nilai-nilai yang justru datang dari dunia nyata. Dalam tataran nilai itu juga, seorang pelakon terhubung dengan kenyataan kesehariannya. Seorang pelakon, seharusnya tidak "memperlawankan" karakter yang dia mainkan dengan sikap moral pribadi. Leonardo DiCaprio misalnya, selalu menolak memerankan sosok yang merusak lingkungan. Dia bahkan berusaha memerankan karakter yang mengampanyekan lingkungan, misalnya dalam film Blood Diamond. Sebagai aktivis lingkungan, Leo bahkan berusaha mengampanyekan "moral pribadi" tersebut di dalam film-filmnya. Saat ini, dia sedang membuat film The 11th Hour, yang bercerita tentang kehancuran bumi akibat pemanasan global. Leo melihat film adalah medium untuk menyampaikan sikap "politiknya". Jika boleh, cerita yang dia mainkan sedapat mungkin mengekspresikan "sikap moral yang dia pilih".
Kesadaran semacam inilah yang tidak dipunyai Inul, dan juga aktris Indonesia lainnya. Panggung bagi mereka adalah sesuatu yang bebas nilai dan pasti terpisah dari kehidupan nyata. Begitu memasuki panggung, mereka merasa telah keluar dari batas kenyataan, terlepas dari sikap moral pribadi. Yang mereka mainkan adalah "cerita" khayalan. Nilai di dalamnya pun khayalan. "Saya tidak seperti itu lho...." begitulah ucapan mereka. Panggung adalah pemanggungan, tempat "identitas" di pertukarkan, saling menegasi, dan absurd. Panggung adalah sebuah teritorial yang memutus sejarah hidup sang aktris dari kenyataan.
Sinetron dan atau film bagi aktris kita bukanlah wadah ekspresi sikap moral pribadi melainkan "cara berada". Sebagai "cara berada", yang utama adalah imbal balik dari pemeranan karakter itu: materi. Panggung dengan demikian adalah wadah untuk semata-mata mendapatkan materi, dan persetan dengan nilai! Dengan cara yang sama, dapat juga dibaca bahwa "perjuangan" Inul dulu untuk "memetakan" posisi dangdut bukanlah bicara tentang nilai, tapi peluang materi yang dia dapatkan. Perlawanan Inul adalah perlawanan materi, pemosisian ladang nafkah. Jika pun bicara nilai, pastilah itu "nilai" yang dapat dimasukkan ke dalam kantong!
Sayang, sikap anutan semacam itu ternyata tidak hanya dihinggapi para aktris kita. Wakil rakyat di DPR sana, pun menghayati panggung politik tak berbeda dari panggung sinetron, sebuah dunia yang terpisah dari kenyataan, sebuah panggung yang tak harus mengekspresikan sikap moral yang mereka pilih. Karena itu, ketika memasuki panggung politik, mereka rileks berkolusi, korupsi, berzina, dan jutaan kali cidera janji. Mereka tahu, panggung selalu berbeda dari kenyataan. Di panggung politik, mereka boleh jadi jahat, boleh korup, karena itu hanya peranan, hanya lakon yang harus mereka mainkan. Dan rakyat, hmmm.. tentu mereka anggap hanya penonton....
[Dalam versi yang lebih ringkas, artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 13 Mei 2007]
( t.i.l.i.k ! )

"Wanita itu harus memakai jilbab, Kikan. Dengan menutup aurat, dia akan terlindungi," kata Nila, sembari mengelus rambut Kikan, anaknya. Nila baru saja usai salat, dan berjanji pada Allah, mulai hari itu dia akan menutup auratnya.
Itulah sepotong adegan dalam sinema "Hikayah: Penyanyi Dangdut Banting Setir Jadi Pembantu" yang tayang Selasa (1/5) lalu. Sinetron itu bercerita tentang pertobatan penyanyi dangdut, Nila, yang biasa bergoyang erotis. Dia yakin, dengan menutup aurat, berjilbab pun, panggung dangdut masih terbuka untuknya. Tapi Nila salah. Tak ada lagi panggung yang menerima. Dia dihina, dicampakkan, disudutkan. Godaan pun datang bertubi-tubi, tapi Nila tetap kuat. "Maaf, aku tidak bisa membuka jilbab. Ini sudah prinsip," elaknya.
Nila diperankan dengan cukup baik oleh Inul Daratista. Inul? Inul, pedangdut ngebor itu? Iya, Inul yang juga berseteru dengan Rhoma Irama itu. Di "Hikayah", yang juga seperti "Hidayah" --terinspirasi dari kisah nyata-- Inul menjadi Nila yang menyadari bahwa bergoyang ngebor dekat dengan kemaksiatan, mendorong orang untuk berbuat dosa. Ketika penonton tidak menerima prinsipnya, dia rela berganti profesi meski harus hanya menjadi pembantu rumah tangga.
Seminggu sebelumnya, Silvana Herman tampil sebagai pemain utama dalam "Hidayah: Perawan Tua". Dia menjadi sosok yang jahat karena tak mampu menanggungkan status ganda: tua dan perawan. Cerita pun berjalan dalam konflik batin yang berkembang jadi kedengki-irian. Sampai saat ini, Silvana Herman memang masih lajang. Usianya nyaris 40 tahun. Dalam tayangan infotainmen, setiap ditanya statusnya, Silvana tak pernah merasa risau. "Jodoh itu di tangan Tuhan. Nanti juga datang," ucapnya rileks.
Panggung Nilai
Kemampuan memerankan "sebuah" karakter adalah tuntutan utama untuk menjadi aktris. Seorang aktris, dapat menjadi apa saja ketika berlakon, termasuk menjadi sosok yang dia benci di dalam kehidupan nyata. "Akan menjadi tantangan yang hebat," demikian biasanya sang pelakon menggambarkan kegembiraan ketika mendapat peran yang berbeda dari karakter aslinya. Itulah sebabnya, setiap aktris riang gembira saja memerankan tokoh apa pun, dalam cerita apa pun, dan dengan kemuskilan apa pun. Yang penting berakting. "Karena berakting aku ada".
Karena akting hanya peranan, karakter apa pun yang dimainkan dipahami oleh mereka bukan sebagai cerminan dari watak pribadi sang pelakon. Itulah sebabnya, Silvana mau menjadi sosok perawan tua dan jahat. Silvana tahu, itu hanya akting. Meski menyandang status yang sama di kehidupan nyata, dia tahu penonton tak akan mempersepsikannya dengan kejahatan yang sama. Itu juga sebabnya, Inul riang gembira menjadi Nila, yang bertobat dari jalan ngebor. Inul tahu, karakter itu hanya rekaan, bagian dari akting. Hanya sandiwara. Tak ada korelasi antara Inul dan Nila.
Sebagai dua karakter, memang tak ada korelasi antara watak di dalam sinetron dan watak asali di dalam kenyataan. Tapi sebagai "pembawa" nilai, seharusnya Inul menyadari "makna" yang lebih daripada sekadar pemeranan. Inul adalah ikon yang mencoba meletakkan sebuah perspektif baru di dalam memandang panggung dangdut. Bersama beberapa aktivis perempuan, Inul mencoba melawan dominasi nilai bahwa dangdut adalah medium dakwah, yang sebagai hiburan seharusnya mengajak orang dekat pada sang pencipta. Karena itu, goyangan yang dianggap menabuh syahwat bukan bagian dari dangdut. Goyangan sejenis itu membawa dangdut ke gerbang comberan. Inul mencoba "memetakan" posisi persepsi dan fakta, harapan dan kenyataan. Bagi Inul, goyangan adalah wilayah terbuka yang bisa dimaknai apa pun, dalam konteks apa pun. Tidak bermakna tunggal, dan harus dilihat dari persepektif hiburan, permintaan dan penawaran, bukan agama. Inul mencoba membebaskan seni dari beban moral, membebaskan dangdut dari kepemilikan satu orang.
Nah, nilai "kenyataan" Inul ini yang justru ditampik Nila. Padahal, sebagai nilai, korelasi keduanya amat jelas. Ada hubungan kausatif antara sinetron dan kenyataan dalam tautan nilai. Sinetron, film, pementasan drama, bahkan opera pun, bukan produk yang lepas nilai. Itulah sebabnya, tak boleh ada sinetron yang menghina agama. Tak ada satu karakter cerita yang boleh menghina agama orang lain, suku, atau personalitas seseorang. Seluruh cerita sebuah film atau sinetron, mungkin tidak berangkat dari dunia nyata. Tapi "ketidaknyataan" itu tetap saja digayuti nilai-nilai yang justru datang dari dunia nyata. Dalam tataran nilai itu juga, seorang pelakon terhubung dengan kenyataan kesehariannya. Seorang pelakon, seharusnya tidak "memperlawankan" karakter yang dia mainkan dengan sikap moral pribadi. Leonardo DiCaprio misalnya, selalu menolak memerankan sosok yang merusak lingkungan. Dia bahkan berusaha memerankan karakter yang mengampanyekan lingkungan, misalnya dalam film Blood Diamond. Sebagai aktivis lingkungan, Leo bahkan berusaha mengampanyekan "moral pribadi" tersebut di dalam film-filmnya. Saat ini, dia sedang membuat film The 11th Hour, yang bercerita tentang kehancuran bumi akibat pemanasan global. Leo melihat film adalah medium untuk menyampaikan sikap "politiknya". Jika boleh, cerita yang dia mainkan sedapat mungkin mengekspresikan "sikap moral yang dia pilih".
Kesadaran semacam inilah yang tidak dipunyai Inul, dan juga aktris Indonesia lainnya. Panggung bagi mereka adalah sesuatu yang bebas nilai dan pasti terpisah dari kehidupan nyata. Begitu memasuki panggung, mereka merasa telah keluar dari batas kenyataan, terlepas dari sikap moral pribadi. Yang mereka mainkan adalah "cerita" khayalan. Nilai di dalamnya pun khayalan. "Saya tidak seperti itu lho...." begitulah ucapan mereka. Panggung adalah pemanggungan, tempat "identitas" di pertukarkan, saling menegasi, dan absurd. Panggung adalah sebuah teritorial yang memutus sejarah hidup sang aktris dari kenyataan.
Sinetron dan atau film bagi aktris kita bukanlah wadah ekspresi sikap moral pribadi melainkan "cara berada". Sebagai "cara berada", yang utama adalah imbal balik dari pemeranan karakter itu: materi. Panggung dengan demikian adalah wadah untuk semata-mata mendapatkan materi, dan persetan dengan nilai! Dengan cara yang sama, dapat juga dibaca bahwa "perjuangan" Inul dulu untuk "memetakan" posisi dangdut bukanlah bicara tentang nilai, tapi peluang materi yang dia dapatkan. Perlawanan Inul adalah perlawanan materi, pemosisian ladang nafkah. Jika pun bicara nilai, pastilah itu "nilai" yang dapat dimasukkan ke dalam kantong!
Sayang, sikap anutan semacam itu ternyata tidak hanya dihinggapi para aktris kita. Wakil rakyat di DPR sana, pun menghayati panggung politik tak berbeda dari panggung sinetron, sebuah dunia yang terpisah dari kenyataan, sebuah panggung yang tak harus mengekspresikan sikap moral yang mereka pilih. Karena itu, ketika memasuki panggung politik, mereka rileks berkolusi, korupsi, berzina, dan jutaan kali cidera janji. Mereka tahu, panggung selalu berbeda dari kenyataan. Di panggung politik, mereka boleh jadi jahat, boleh korup, karena itu hanya peranan, hanya lakon yang harus mereka mainkan. Dan rakyat, hmmm.. tentu mereka anggap hanya penonton....
[Dalam versi yang lebih ringkas, artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 13 Mei 2007]
( t.i.l.i.k ! )
Sunday, May 06, 2007
Citra dan Teror Para Pengacara
Bagi pengacara para artis, kebenaran harus diperjuangkan, terutama, di depan kamera.

"Dalam rekaman itu, Maia bilang kepada teman laki-lakinya seperti ini, 'Demi Allah, demi Allah, saya sudah making love dengan Bang.... Sampeyan jangan bilang siapa-siapa.' Begitu kata Maia. Rekaman itu sangat menyakitkan Dhani," jelas Syamsul Huda, pengacara Dhani, sambil mengacungkan DVD rekaman itu.
Itulah kalimat yang semingguan ini meramaikan infotainmen. Huda tampil mewakili Dhani untuk menangkis "serangan" Sheila Salomo, pengacara Maia. Tuduhan kekerasan dalam rumah tangga dibalas dengan bukti selingkuh. Keduanya siap bertarung membela klien masing-masing. Di teve, seperti bersahutan, mereka berpukul kata dan yakin memiliki data lebih meyakinkan.
Perdebatan seperti Sheila dan Huda bukan hal baru di infotainmen. Nyaris setiap ada permasalahan hukum, pengacara seorang artis akan bersuara di infotainmen. Pengacara Tommy Soeharto dan Tata, juga berperang kata. Tuduhan selingkuh dan memiliki anak di luar pernikahan selalu diungkapkan pencara Tommy untuk menjatuhkan citra Tata. Pengacara Tommy lupa, bahwa ketika di dalam penjara pun, kliennyalah yang telah terbukti menikahi perempuan lain.
Kadang, perdebatan para pengacara itu memasuki hal-hal di luar hukum, menyerang integritas pribadi, bahkan menyinggung SARA. Kasus perseteruan Hotman Paris Hutapea dan Hotma Sitompoel, contohnya. Kedua pengacara ini berseteru pribadi saat berhadapan dalam kasus pembunuhan Naek Gomgom yang melibatkan artis Lidya Pratiwi. Karena bersedia membela Lidya, Hotman Paris dinilai telah mengewakan orang Batak. Hotma bahkan mengecam pembelaan itu sebagai tindakan untuk mencari popularitas semata.
Hotman Paris tidak tinggal diam. Dia pun menyangsikan integritas Hotma karena masih membawa kesukuan dalam sikap profesionalitasnya. Hotman menilai tindakan kesukuan itu yang justru memperhinakan orang Batak. Perdebatan terus meruncing, saling membeberkan bukti-bukti yang meringankan kliennya, sekaligus tak lupa saling mengecam. Terakhir, keduanya saling melemparkan tuduhan tentang "pengacara hitam." Dalam "perang" itu, Ruhut Sitompul pun masuk gelanggang, dan ikut menyerang Hotman Paris. Namun, dengan senyum, Hotman Paris menilai Ruhut, "Bukan pengacara yang pantas saya layani. Dia bukan level saya."
Banyak yang mengira, setelah kasus Lidya Pratiwi mereda, "perang" antara dua pengacara ini akan berakhir. Nyatanya, mereka bertemu lagi dalam kasus Maia dan Mulan. Hotman membela Mulan, Hotma mewakili Maia. Keduanya perang bukti, saling yakin menang. Dan ketika Maia menandatangani kesepakatan yang diinginkan Mulan, Hotman pun tertawa. "Ini bukti mereka telah mengaku kalah. Bertekuk lutut menghadapi Hotman Paris."
Selasa kemarin, Dhani mendatangi Hotman Paris, minta nasihat tentang kasusnya. Usai dari kantor pengacara itu, Dhani mengatakan siap menggelar perang Badar jika Maia menginginkan hal itu. Mengapa Dhani mendatangi Hotman? Ternyata Sheila Salomo, pengacara Maia itu, adalah rekanan Hotma Sitompoel and Partners. Olala....
Dua Teror
Pengacara seharusnya beracara di ruang pengadilan. Di depan jaksa dan hakimlah mereka wajib membeberkan bukti, memanggil saksi, dan menunjukkan kepiawaian berargumentasi. Namun, kini semua proses itu sudah mereka lakukan di depan kamera. Hotman Paris misalnya, dengan lantang menunjukkan tiada bukti bahwa Lidya benar melakukan tindakan pembunuhan berencana. Ia juga meyakinkan pemirsa bahwa Lidya pasti bebas dari tuduhan itu, dan hanya tersangkut pembunuhan biasa. Farhat Abbas juga melakukan hal yang sama ketika membela Alda. Dia jelaskan kronologis pembunuhan itu, sampai kecurigaan ada "yang bermain" dan "orang kuat" yang melindungi Ferry.
Keyakinan, bukti, ataupun saksi yang pengacara tunjukkan kepada infotainmen sebenarnya adalah teror dengan dua arah. Pertama, mereka membidik lawan. Dengan paparan itu, mereka berharap "lawan" sudah kalah sebelum maju ke persidangan. Itulah yang terjadi dengan Maia, akhirnya menuruti kehendak Mulan. Teror Hotman Paris bahwa mereka punya banyak bukti dan pasti menang, berhasil.
Kedua, teror kepada hakim dan jaksa di peradilan. Keyakinan yang mereka ucapkan bahwa kliennya tidak bersalah dan pasti menang, dan tayang berulang-ulang di teve, diharapkan bergema juga dalam nalar para jaksa dan hakim. Itu semacam "pukulan yang tak kelihatan". Jadi, perang bukti dan pertengkaran di infotainmen itu mirip psy-war para pelatih di Liga Inggris sebelum bertanding. Mereka sangat yakin pertengkaran yang disorot media akan memengaruhi hasil di lapangan sepakbola, di ruang persidangan. Hotman Paris sukses juga melakukan hal ini ketika Lidya Pratiwi ternyata hanya dihukum 10 tahun penjara.
Namun, dengan menjadikan kamera sebagai "ruang sidang", dan penonton sebagai hakim dan jaksa, para pengacara sebenarnya telah melakukan "penghinaan" pada peradilan. Itu adalah wujud ketidakpercayaan mereka atau klien mereka kepada lembaga peradilan. Jadi, "persidangan kamera" itu bukan untuk mencari putusan, melainkan semacam unjuk-kuasa, bahwa peradilan pasti tidak akan dapat melihat fakta-fakta kebenaran lebih daripada infotainmen. Bahwa peradilan justru telah menjadi pusat ketidakadilan.
Hakim Kamera
Yatie Oktavia dan Pangki Suwito adalah contoh mereka yang "tidak percaya" pada peradilan. Mereka merasa lebih dapat mengasuh cucu mereka dibandingkan mantan menantunya, sebagaimana yang diputuskan pengadilan. Di infotainmen, melalui pengacara, mereka paparkan bukti, juga saksi. Sebuah paparan yang seakan berkata, "Inilah hal-hal yang tidak dilihat hakim." Akibatnya, mereka tidak patuh pada putusan hakim, membangkang. Dan sampai kini, kekuasaan peradilan tidak dapat menembus "pembangkangan" itu.
Tamara Bleszynski juga merasa keputusan Mahkamah Agung menyangkut hal asuh Rasya tidak adil. Elsya Syarif menyuarakan hal itu. Di infotainmen, mereka ragukan penilaian para psikolog menyangkut psikologis Rasya, yang merasa tak nyaman dengan Tamara, dan menjadi salah satu unsur penilaian mengapa Rafly yang berhak mengasuk anak mereka. Di depan kamera, mereka paparkan "bukti" manipulasi penilaian psikologis itu.
Jadi, sebenarnya, kamera dan penontonlah jaksa dan hakim di mata mereka. Dengan demikian, putusan pengadilan bukanlah tujuan utama. Sering sekali, para pengacara saling gugat, saling klaim kebenaran, namun akhirnya tidak sampai beracara di ruang pengadilan. Mereka "cukupkan" semua itu hanya sebagai persidangan di depan kamera, jika "putusan" yang mereka harapkan telah didapatkan, yakni pemihakan dari para penonton. Jika mereka yakin penonton telah dapat melihat semua "kebenaran", maka hasil apa pun di persidangan bukan sesuatu yang perlu dan penting.
Gusti Randa misalnya, hanya ramai ketika bersidang di depan kamera. Dia paparkan semua kronologis perselingkuhan istrinya, dia jelaskan karakter selingkuhan itu, dan menyebut mereka dengan Mr X dan Y. Dia ungkapkan kekuatan politik mereka, dia yakinkan penonton, bahwa yang dia lawan adalah orang yang sangat berkuasa. Gusti memegang bukti, dia pasti menang, jika akses politik sang lawan tidak menembus ruang pengadilan.
Dan begitulah, Gusti Randa hanya ramai di depan kamera. Dia dengan pengacaranya, telah melakukan persidangan "in absentia", tanpa kehadiran terdakwa. Dan ketika argumentasinya telah menjadi "kebenaran" di benak penonton, Gusti merasa cukup. Apalagi ketika mantan istrinya, Nia Paramitha, membenarkan perselingkuhan itu dengan mau membintangi sinetron "Selebriti Juga Manusia" berdasarkan versi Gusti. Akibatnya, Gusti tidak harus memperjuangkan "kebenaran" itu ke meja hijau. Sampai kini kasus itu tak jelas akhirnya.
Persidangan di depan kamera yang ditempuh para artis adalah suatu jalan untuk tetap mengukuhkan citra. Pengacara adalah penjaga gawang dan pemoles citra mereka. Jika citra berhasil ditegakkan, apa pun hasil pengadilan bukan sesuatu yang pantas dihiraukan. Meski citra adalah bayangan, dan persidangan di depan kamera adalah kesemuan, para artis sadar, dari situlah mereka dapat terus menjalani kehidupan. Hidup dalam citra, dalam bayangan, yang mereka maknai sebagai kebenaran....
[Artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 6 Mei 2007]
( t.i.l.i.k ! )

"Dalam rekaman itu, Maia bilang kepada teman laki-lakinya seperti ini, 'Demi Allah, demi Allah, saya sudah making love dengan Bang.... Sampeyan jangan bilang siapa-siapa.' Begitu kata Maia. Rekaman itu sangat menyakitkan Dhani," jelas Syamsul Huda, pengacara Dhani, sambil mengacungkan DVD rekaman itu.
Itulah kalimat yang semingguan ini meramaikan infotainmen. Huda tampil mewakili Dhani untuk menangkis "serangan" Sheila Salomo, pengacara Maia. Tuduhan kekerasan dalam rumah tangga dibalas dengan bukti selingkuh. Keduanya siap bertarung membela klien masing-masing. Di teve, seperti bersahutan, mereka berpukul kata dan yakin memiliki data lebih meyakinkan.
Perdebatan seperti Sheila dan Huda bukan hal baru di infotainmen. Nyaris setiap ada permasalahan hukum, pengacara seorang artis akan bersuara di infotainmen. Pengacara Tommy Soeharto dan Tata, juga berperang kata. Tuduhan selingkuh dan memiliki anak di luar pernikahan selalu diungkapkan pencara Tommy untuk menjatuhkan citra Tata. Pengacara Tommy lupa, bahwa ketika di dalam penjara pun, kliennyalah yang telah terbukti menikahi perempuan lain.
Kadang, perdebatan para pengacara itu memasuki hal-hal di luar hukum, menyerang integritas pribadi, bahkan menyinggung SARA. Kasus perseteruan Hotman Paris Hutapea dan Hotma Sitompoel, contohnya. Kedua pengacara ini berseteru pribadi saat berhadapan dalam kasus pembunuhan Naek Gomgom yang melibatkan artis Lidya Pratiwi. Karena bersedia membela Lidya, Hotman Paris dinilai telah mengewakan orang Batak. Hotma bahkan mengecam pembelaan itu sebagai tindakan untuk mencari popularitas semata.
Hotman Paris tidak tinggal diam. Dia pun menyangsikan integritas Hotma karena masih membawa kesukuan dalam sikap profesionalitasnya. Hotman menilai tindakan kesukuan itu yang justru memperhinakan orang Batak. Perdebatan terus meruncing, saling membeberkan bukti-bukti yang meringankan kliennya, sekaligus tak lupa saling mengecam. Terakhir, keduanya saling melemparkan tuduhan tentang "pengacara hitam." Dalam "perang" itu, Ruhut Sitompul pun masuk gelanggang, dan ikut menyerang Hotman Paris. Namun, dengan senyum, Hotman Paris menilai Ruhut, "Bukan pengacara yang pantas saya layani. Dia bukan level saya."
Banyak yang mengira, setelah kasus Lidya Pratiwi mereda, "perang" antara dua pengacara ini akan berakhir. Nyatanya, mereka bertemu lagi dalam kasus Maia dan Mulan. Hotman membela Mulan, Hotma mewakili Maia. Keduanya perang bukti, saling yakin menang. Dan ketika Maia menandatangani kesepakatan yang diinginkan Mulan, Hotman pun tertawa. "Ini bukti mereka telah mengaku kalah. Bertekuk lutut menghadapi Hotman Paris."
Selasa kemarin, Dhani mendatangi Hotman Paris, minta nasihat tentang kasusnya. Usai dari kantor pengacara itu, Dhani mengatakan siap menggelar perang Badar jika Maia menginginkan hal itu. Mengapa Dhani mendatangi Hotman? Ternyata Sheila Salomo, pengacara Maia itu, adalah rekanan Hotma Sitompoel and Partners. Olala....
Dua Teror
Pengacara seharusnya beracara di ruang pengadilan. Di depan jaksa dan hakimlah mereka wajib membeberkan bukti, memanggil saksi, dan menunjukkan kepiawaian berargumentasi. Namun, kini semua proses itu sudah mereka lakukan di depan kamera. Hotman Paris misalnya, dengan lantang menunjukkan tiada bukti bahwa Lidya benar melakukan tindakan pembunuhan berencana. Ia juga meyakinkan pemirsa bahwa Lidya pasti bebas dari tuduhan itu, dan hanya tersangkut pembunuhan biasa. Farhat Abbas juga melakukan hal yang sama ketika membela Alda. Dia jelaskan kronologis pembunuhan itu, sampai kecurigaan ada "yang bermain" dan "orang kuat" yang melindungi Ferry.
Keyakinan, bukti, ataupun saksi yang pengacara tunjukkan kepada infotainmen sebenarnya adalah teror dengan dua arah. Pertama, mereka membidik lawan. Dengan paparan itu, mereka berharap "lawan" sudah kalah sebelum maju ke persidangan. Itulah yang terjadi dengan Maia, akhirnya menuruti kehendak Mulan. Teror Hotman Paris bahwa mereka punya banyak bukti dan pasti menang, berhasil.
Kedua, teror kepada hakim dan jaksa di peradilan. Keyakinan yang mereka ucapkan bahwa kliennya tidak bersalah dan pasti menang, dan tayang berulang-ulang di teve, diharapkan bergema juga dalam nalar para jaksa dan hakim. Itu semacam "pukulan yang tak kelihatan". Jadi, perang bukti dan pertengkaran di infotainmen itu mirip psy-war para pelatih di Liga Inggris sebelum bertanding. Mereka sangat yakin pertengkaran yang disorot media akan memengaruhi hasil di lapangan sepakbola, di ruang persidangan. Hotman Paris sukses juga melakukan hal ini ketika Lidya Pratiwi ternyata hanya dihukum 10 tahun penjara.
Namun, dengan menjadikan kamera sebagai "ruang sidang", dan penonton sebagai hakim dan jaksa, para pengacara sebenarnya telah melakukan "penghinaan" pada peradilan. Itu adalah wujud ketidakpercayaan mereka atau klien mereka kepada lembaga peradilan. Jadi, "persidangan kamera" itu bukan untuk mencari putusan, melainkan semacam unjuk-kuasa, bahwa peradilan pasti tidak akan dapat melihat fakta-fakta kebenaran lebih daripada infotainmen. Bahwa peradilan justru telah menjadi pusat ketidakadilan.
Hakim Kamera
Yatie Oktavia dan Pangki Suwito adalah contoh mereka yang "tidak percaya" pada peradilan. Mereka merasa lebih dapat mengasuh cucu mereka dibandingkan mantan menantunya, sebagaimana yang diputuskan pengadilan. Di infotainmen, melalui pengacara, mereka paparkan bukti, juga saksi. Sebuah paparan yang seakan berkata, "Inilah hal-hal yang tidak dilihat hakim." Akibatnya, mereka tidak patuh pada putusan hakim, membangkang. Dan sampai kini, kekuasaan peradilan tidak dapat menembus "pembangkangan" itu.
Tamara Bleszynski juga merasa keputusan Mahkamah Agung menyangkut hal asuh Rasya tidak adil. Elsya Syarif menyuarakan hal itu. Di infotainmen, mereka ragukan penilaian para psikolog menyangkut psikologis Rasya, yang merasa tak nyaman dengan Tamara, dan menjadi salah satu unsur penilaian mengapa Rafly yang berhak mengasuk anak mereka. Di depan kamera, mereka paparkan "bukti" manipulasi penilaian psikologis itu.
Jadi, sebenarnya, kamera dan penontonlah jaksa dan hakim di mata mereka. Dengan demikian, putusan pengadilan bukanlah tujuan utama. Sering sekali, para pengacara saling gugat, saling klaim kebenaran, namun akhirnya tidak sampai beracara di ruang pengadilan. Mereka "cukupkan" semua itu hanya sebagai persidangan di depan kamera, jika "putusan" yang mereka harapkan telah didapatkan, yakni pemihakan dari para penonton. Jika mereka yakin penonton telah dapat melihat semua "kebenaran", maka hasil apa pun di persidangan bukan sesuatu yang perlu dan penting.
Gusti Randa misalnya, hanya ramai ketika bersidang di depan kamera. Dia paparkan semua kronologis perselingkuhan istrinya, dia jelaskan karakter selingkuhan itu, dan menyebut mereka dengan Mr X dan Y. Dia ungkapkan kekuatan politik mereka, dia yakinkan penonton, bahwa yang dia lawan adalah orang yang sangat berkuasa. Gusti memegang bukti, dia pasti menang, jika akses politik sang lawan tidak menembus ruang pengadilan.
Dan begitulah, Gusti Randa hanya ramai di depan kamera. Dia dengan pengacaranya, telah melakukan persidangan "in absentia", tanpa kehadiran terdakwa. Dan ketika argumentasinya telah menjadi "kebenaran" di benak penonton, Gusti merasa cukup. Apalagi ketika mantan istrinya, Nia Paramitha, membenarkan perselingkuhan itu dengan mau membintangi sinetron "Selebriti Juga Manusia" berdasarkan versi Gusti. Akibatnya, Gusti tidak harus memperjuangkan "kebenaran" itu ke meja hijau. Sampai kini kasus itu tak jelas akhirnya.
Persidangan di depan kamera yang ditempuh para artis adalah suatu jalan untuk tetap mengukuhkan citra. Pengacara adalah penjaga gawang dan pemoles citra mereka. Jika citra berhasil ditegakkan, apa pun hasil pengadilan bukan sesuatu yang pantas dihiraukan. Meski citra adalah bayangan, dan persidangan di depan kamera adalah kesemuan, para artis sadar, dari situlah mereka dapat terus menjalani kehidupan. Hidup dalam citra, dalam bayangan, yang mereka maknai sebagai kebenaran....
[Artikel ini telah dimuat di Harian Suara Merdeka, Minggu 6 Mei 2007]
( t.i.l.i.k ! )